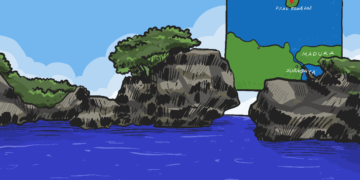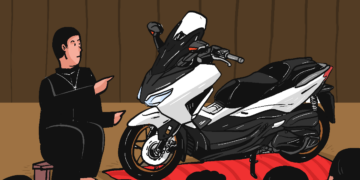Penggunaan bahasa Jawa makin tergerus seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya budaya asing, khususnya di kalangan Gen Z. Padahal, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Hendrokumoro pernah mengungkap bahwa jumlah penutur bahasa Jawa diperkirakan hanya mencapai lebih dari 80 juta jiwa.
Tapi penggunaannya terbatas pada konteks tertentu, misalnya hanya di lingkup keluarga yang kental dengan budaya Jawa atau komunitas tradisional. Artinya, jarang digunakan dalam kalimat sehari-hari. Berdasarkan penelusuran Mojok, bahkan terdapat juga istilah Jawindo.
Di Jakarta Selatan kita sering menemui kalimat campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Namun di Jawa, campuran bahasa ini lebih kompleks lagi. Di mana, bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia maupun bahasa slang. Misalnya begini:
“Eh, lu mau ngetan (ke arah timur), aku ngidul (arah Selatan).”
“Gue orang jogsel (Jogja selatan alias Bantul) Bre, walaupun mangane nganggo sego tok (makannya cuman pakai nasi saja) nggak masalah”.
“Maafin abang ya Dek kalau malam minggu nggak pernah bisa diajak keluar, soalnya abang lagi srawung (bersosialisasi)”.
“Bjir, reget banget bjir,”.
Meski terdengar lucu, campuran bahasa di atas justru menjadi concern bagi akademisi seperti Rendra Agusta, seorang filolog sekaligus praktisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Rendra mengungkap perkembangan zaman membuat pergeseran makna dalam bahasa, terutama bahasa Jawa kuno.
Pergeseran makna bahasa Jawa
Filolog Rendra menjelaskan, sebetulnya pergeseran makna dalam bahasa Jawa kuno tidak menjadi masalah di era sekarang, tapi harus tetap dilestarikan sebagaimana mestinya. Artinya, Rendra ingin masyarakat yang berasal dari Jawa tetap paham penggunaan katanya dengan konteks kalimat yang benar, khususnya Gen Z.
“Bahasa Jawa kuno bisa diajarkan dan dipakai untuk disiplin tertentu, misal pendidikan di kampus. Perkara di luar nanti dipakai atau tidak, terserah tapi dia harus sudah tahu pakemnya,” kata Rendra dikutip dari YouTube mojokdotco berjudul “Rendra: Aksara Jawa itu Mantra” yang tayang pada Selasa (21/10/2025).
Misalnya kata “kita” atau dalam bahasa Jawa adalah “kito”. Dalam bahasa Jawa kuno kata ‘kito’ sebenarnya berarti “kamu” bukan “semua orang”, seperti yang kerap dimaknai dalam bahasa Indonesia.
“Kalau ingin menyebut ‘kita’ harusnya memang menggunakan kulo dan panjenengan alias dua subjek, karena di Jawa tidak mengenal kata ganti orang ketiga jamak. Tapi hal itu sekarang kan sudah lazim,” ujar Rendra.
Oleh karena itu, terutama sebagai filolog, tafsiran bahasa Jawa harus dilihat sesuai zamannya. Seperti yang disampaikan falsafat Jawa, yakni nut jaman kelakone. Karena pada dasarnya, ungkapan dalam bahasa Jawa punya makna yang mendalam dan relevan dalam pembentukan karakter, serta sarat nilai untuk kehidupan bermasyarakat.
Cara menjadi Jawa sepenuhnya
Peran bahasa Jawa sebagai nilai kehidupan bermasyarakat terlihat dari kategorisasi cara penyampaiannya. Empat gaya komunikasi itu terdiri dari:
#1 Dhupak bujang atau kuli
Secara harfiah dhupak artinya menendang tapi itu hanya pengistilahan orang Jawa yang menyampaikan kritik atau kekesalannya secara langsung. Biasanya, dilakukan terang-terangan ke orang yang memiliki derajat sosial lebih rendah.
“Misalnya saat kita memerintahkan orang begini, ‘Eh, jupukno wedang (ambilkan air)’ si lawan bicara akan langsung tahu kan maksud perkataan kita. Nah, saya rasa semua komunikasi di masyarakat sedang berada di level ini,” kata Rendra.
#2 Semu mantri
Tingkat ini kesopanan gaya komunikasinya lebih baik ketimbang dhupak bujang atau kuli. Biasanya, komunikan akan menggunakan istilah-istilah guna menyindir perilaku lawan bicaranya. Misalnya, “kok polahmu koyo gabah diinteri”. Artinya secara harfiah begini, kok tingkah lakumu seperti gabah yang dipisah di atas tampah.
“Kalau maksud orang Jawa dulu, sebetulnya kita sedang disimbolkan oleh gabah itu atau sedang diperingatkan untuk berperilaku anteng (tenang), tapi dengan bahasa yang halus,” ujar Rendra.
#3 Esem bupati
Esem bupati adalah gaya komunikasi yang mencontoh perilaku bupati yang bersikap halus, ramah, dan murah senyum. Bupati sendiri sebagai simbol orang yang memiliki status lebih tinggi atau orang yang ingin dihormati.
Contoh sederhana, saat seorang pemuda hendak ke rumah sang pacar dan meminta izin orang tuanya. Namun, di sela menunggu itu, ayah sang pacar tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Bahkan sudah satu jam berlalu, ia tidak disuguhi minum sama sekali.
Kemudian, ayah sang pacar pun memberi tanda dengan tersenyum. Lalu menggunakan gestur seperti sedekap atau berkacak pinggang.
“Nah, kalau sudah begitu kita mesti tahu tandanya kita disuruh pulang,” kata Rendra.
#4 Sasmito ratu
Gaya komunikasi ini adalah puncak tertinggi dalam bahasa Jawa yang hanya menggunakan simbol, tapi punya makna mendalam. Misalkan, ada seorang presiden yang bertemu dengan sultan. Kalau dilihat, keduanya sama-sama punya kedudukan tertinggi.
Namun dalam pertemuan itu, sultan memberikan jamuan berupa sayur lodeh dan mengenakan baju batik parang. Padahal, sebagaimana orang Jawa biasanya, mereka lebih suka menyuguhkan makanan manis ketimbang sayur lodeh yang pedas.
Sedangkan, batik parang punya filosofis mendalam seperti menunjukkan kekuatan atau keberanian. Bahkan dalam konteks tertentu bisa berarti siap “perang”.
Tantangan Gen Z melestarikan bahasa Jawa
Selain gaya komunikasi di atas, Rendra juga mengingatkan bahwa di Jawa juga ada ungkapan yang terdiri atas paribasan, bebasan, wangsalan, hingga cangkriman. Dan semuanya itu bersifat simbolis.
Contoh, mlaku e koyok macan luwe (berjalannya seperti harimau yang lapar). Atau lambehane mblarak sempal (lambaian tangan yang mirip daun kelapa, tampak anggun).
“Nah, kegagalan Gen Z untuk membaca itu adalah mereka tidak tahu macan luwe bentuknya seperti apa? Sulit juga untuk masyarakat kota yang hidup secara urban lalu membayangkan daun kelapa. Maka caranya harus outing, di mana yang kota ke desa, kalau yang desa ke kota untuk membaca simbol-simbol itu,” tegas Rendra.
Dengan belajar gaya komunikasi itu saja, kata dia, orang Jawa bisa menjadi Jawa yang seutuhnya. Tak hanya mempelajari, tapi juga membiasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Mahasiswa Jakarta Terpaksa Belajar Bahasa Jawa biar Nggak Diketawain Orang Surabaya, Malah Geli Sendiri Pakai “Aku-Kamu” atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan