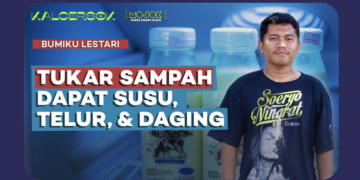Ada misi khusus dalam perjalanan saya ke Bali selama kurang lebih satu pekan. Saya ingin membuktikan klaim dari salah satu lembaga riset perjalanan, yang menyebut Pulau Dewata tak layak lagi dikunjungi pada 2025 mendatang. Lantas, apa yang saya temukan?
***
Saya memulai perjalanan dari Jogja menuju Bali pada Senin (16/12/2024) sore. Sebelum berangkat, berhari-hari sebelumnya saya membaca satu hasil riset dari Fodor’s. Ia merupakan penerbit panduan perjalanan dan penyedia informasi pariwisata online asal Amerika Serikat. Di dalamnya, terdapat informasi terkini untuk lebih dari 7.500 destinasi wisata di seluruh dunia.
Pada November 2024, Fodor’s merilis buku tahunan berjudul “Fodor’s No List 2025”. Isinya adalah daftar tempat yang tak layak lagi dikunjungi di tahun 2025.
Alasannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena lingkungan sudah rusak, sampah, ancaman keamanan, sampai peliknya birokrasi. Dan, yang membuat saya terkejut, Bali berada di urutan pertama.
Membaca temuan itu, saya agak bingung. Memang, kunjungan saya ke Bali bisa dihitung jari. Terakhir saya mendatangi pulau ini juga sudah sekitar empat tahun lalu. Saya pun melihat Bali melalui video dan foto di media sosial, yang mau diakui atau tidak, cuma menggambarkan bagus-bagusnya saja.
Memang, di media sosial juga kerap ditemui kelakuan turis-turis mancanegara yang begitu random yang mengganggu kenyamanan. Namun, kalau sampai pada kesimpulan Bali tak layak lagi dikunjungi karena hal-hal tadi, menurut saya cukup berlebihan.
Kiamat plastik di Bali
Salah satu klaim yang saya ingat betul dari temuan Fodor’s adalah “Bali mengalami kiamat plastik”. Masalah sampah amat disorot. Hal inilah yang, menurut mereka, membuat tempat ini tak lagi layak dikunjungi.
Membayangkan kiamat plastik atau krisis sampah, di kepala saya langsung terbayang Jogja. Saya lebih relate dengan masalah sampah di Jogja karena tengah mengalaminya sendiri. Sementara di Bali, saya belum bisa membuktikannya langsung.
Perjalanan saya dan rombongan ke Bali cukup memakan waktu. Apalagi, ada beberapa kendala selama perjalanan. Kira-kira 24 jam kami habiskan di dalam bus sebelum sampai di tempat penginapan.
Tempat penginapan kami tepat berada di jantung Pulau Bali. Lokasinya hanya beberapa jengkal dari bibir Pantai Kuta yang terkenal tak pernah mati itu.
Sayangnya, kami datang ketika musim hujan. Angin sedang kencang-kencangnya. Siang sampai malam hujan juga terus mengguyur. Tak ada waktu bagi kami untuk menikmati pantai.
Namun, dari sela-sela waktu luang di sini, saya pada akhirnya bisa mengamini klaim Fodor’s soal kiamat plastik di Bali. Pasalnya, secara langsung saya menyaksikan tumpukan sampah di banyak titik Pantai Kuta. Kebanyakan sampah yang sudah menggunung ini adalah plastik.

“Sudah berhari-hari sampahnya di situ. Karena kalau diangkut, nanti datang lagi ke situ,” kata seorang penjual Bakso Malang yang tiap malam berdagang di dekat Pantai Kuta.
Penanganan sampah medioker
“Siapa yang harus disalahkan atas kondisi ini?” Kira-kira demikian tanya saya dalam hati. Kalau berdasarkan obrolan saya dengan masyarakat sekitar dan para tour guide, mereka menyebut ini kondisi yang “alami”. Sebab, kata mereka, sampah-sampah ini terbawa dari tempat lain–bukan dari Pantai Kuta.
Jika pun klaim ini benar, tetap saja itu tak menutup fakta bahwa krisis sampah di Bali memang sudah separah itu. Setidaknya ini jauh jika dibandingkan dengan pantai-pantai di Vietnam, Thailand, atau Maldives yang lebih bersih.
Kalau kata Fodor’s, sih, ini karena penanganan sampah yang amat medioker. Pemerintah setempat gagap dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Sejak pandemi Covid-19 berakhir, kunjungan wisata di Bali meningkat 22 persen.
“Hal itu juga memberi tekanan luar biasa pada infrastruktur Bali. Pantai-pantai yang dulunya bersih, kini terkubur di bawah tumpukan sampah,” tulis Fodor’s melalui laman resminya, dikutip Kamis (26/12/2024).
Sebuah koalisi akademisi dan LSM bernama Bali Partnership, memperkirakan Pulau Dewata menghasilkan 1,6 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sampah plastik mencapai hampir 303.000 ton.

Sayangnya, menurut temuan mereka, hanya 48 persen dari sampah-sampah ini yang dikelola secara bertanggung jawab. Bahkan, cuma 7 persen sampah plastik yang didaur ulang.
Alhasil, kondisi ini mengakibatkan 33 ribu ton plastik masuk ke sungai, pantai, dan laut Bali setiap tahun, dan menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem di pulau ini.
Destinasi wisata di Bali yang semakin menjengkelkan
Selain sampah, ada masalah lain yang menurut saya bikin Bali semakin menjengkelkan: toilet umum. Selama di Bali, amat jarang saya menjumpai toilet umum yang bersih–khususnya di SPBU.
Bahkan, salah satu toilet umum di dekat Pasar Seni Ubud, kondisinya memprihatinkan: kotor, pesing, tak terawat, peralatan seperti flush closet dan bidet tak berfungsi. Bahkan saya “beruntung” karena menjumpai “sisa-sisa” pengguna toilet sebelum saya.
Sebenarnya hal ini juga sudah ditulis oleh Fodor’s. Menurut mereka, pemerintah setempat lebih memprioritaskan pengalaman turis-turis asing ketimbang wisatawan dalam negeri dan masyarakat lokal.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur besar diutamakan tapi melupakan hal-hal kecil, seperti toilet umum, misalnya. Hal ini juga, yang menurut Fodor’s, mendorong sikap cuek masyarakat Bali terhadap wisatawan.
“Menjelajahi kota-kota yang penuh dengan wisatawan membuat frustrasi; bertamasya di kota-kota yang penduduk setempatnya tidak suka dengan kehadiran Anda membuat kesal,” tulisnya.
Di Bali, Mojok sendiri juga menemui Putu Ardana, aktivis lingkungan yang mewakili Bali dalam acara COP29 di Baku, Azerbaijan. Sudah sejak lama Putu menilai pariwisata di Bali telah kehilangan arahnya.

Pariwisata dieksploitasi secara berlebihan atas nama profit. Kunjungan wisata, yang awalnya dia lihat sebagai “bonus”, kini malah ditempatkan sebagai hal utama. Pendeknya, selama hal itu mendatangkan keuntungan, maka eksploitasi pun seolah dibenarkan–meski ada banyak hal yang kudu dikorbankan termasuk kelangsungan alam dan budaya.
“Orang Bali tanpa kunjungan wisatawan itu tetap bisa bertahan hidup, makanya pariwisata itu sebenarnya hanya bonus. Tapi sekarang beda, alam dan budaya dieksploitasi demi keuntungan sebesar-besarnya,” kata alumnus UGM ini, Kamis (19/12/2024).
“Makanya, budaya di sini makin terkikis eksistensi dan esensinya, karena dijual demi kepentingan pariwisata,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA Pengalaman Saya Menyusuri Kios-kios Pasar Seni Ubud di Momen yang Kurang Tepat
Ikuti artikel dan berita Mojok lainnya di Google News