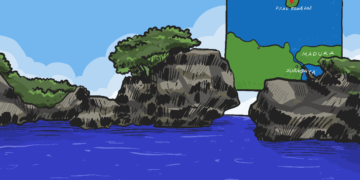Beberapa orang—terutama para perantau—sepakat bahwa Surabaya after rain itu indah dan romantis. Saya sendiri, jujur saja, termasuk salah satu yang berpandangan demikian. Saat masih merantau di sana, saya kerap memacu pelan motor menyusuri jalanan Kota Pahlawan tak lama setelah hujan mereda.
Usai pindah perantauan, saya masih sering kangen dengan suasana hujan atau setelahnya di Surabaya. Aroma jalanan yang masih basah, entah bagaimana, begitu khas di hidung saya. Istri saya dan beberapa teman juga berpendapat serupa.
Belum lagi suasananya. Pendar lampu-lampu kota yang tersiram air langit menjadi visual puitis. Kalau kata teman saya, memutari Surabaya sehabis hujan menjadi lebih puitis sembari mendengar playlist yang terputar melalui audio kecil nirkabel yang tersumpal di dua telinga. Sembari meratapi patah hati, menyelami kesedihan, merayakan cinta yang tengah rekah di hati, atau sekadar meromantisasi nasib dan kesendirian.
Menatap Surabaya after rain dari jendela kamar
Pada penghujung November 2025 lalu, kantor mengutus saya ke Surabaya untuk satu-dua pekerjaan. Ah, saya selalu antusias mendatangi kota itu. Surabaya sedang “puitis-puitisnya” karena hujan.
Saya menginap di sekitaran Gubeng, terhitung masih dalam wilayah jantung kota. Hujan yang turun saban sore hingga malam membuat suasana sekitar amat indah, sebagaimana deskripsi di atas.
Saya menikmatinya dari jendela kamar di lantai 3. Itu kebiasaan saya juga saat dulu masih ngekos di Wonocolo: Memandangi rumah-rumah dan jalanan kampung yang diguyur hujan dari jendela kamar di lantai 2 indekos.
Setelah reda, saya beranjak keluar, menikmati Surabaya after rain, lalu bertemu dengan teman-teman lama. Dan saat itulah saya menyadari sesuatu yang sebenarnya selama ini amat dekat: Sisi lain hujan Kota Pahlawan, ada air mata yang luruh dan tak terlihat tersapu hujan.
Air mata yang tersapu hujan Surabaya
Saya sedang memandangi setiap jengkal jalanan yang saya lalui—untuk nostalgia—ketika tiba-tiba driver ojek online (ojol) yang mengantarkan saya mengumpat. Belum lama hujan reda, belum separuh jalan menuju lokasi tujuan, tiba-tiba hujan mengguyur lagi.
“Kita neduh dulu, Mas, ini deres,” ujar si driver ojol, saya mengiayakan.
“Saya cuma punya mantel satu, mantel plastik, kalau masnya mau terabas, pakai itu,” ucap si driver usai kami berteduh asal di bawah pepohonan rindang.
Saya mengenakan mantel plastik itu. Sementara si driver ojol usia 40-an tahun hanya membungkus ponselnya dengan plastik bening, agar ia tetap bisa memantau rute dari Google Maps.
“Sedih, kesel, diam-diam nangis kalau hujan begini,” ucap si driver ojol tiba-tiba bercerita. “Tapi ya mau gimana lagi, masa kesel sama Tuhan yang menciptakan hujan.”
Katanya, pagi, sore, dan malam adalah jam-jam peak untuk mendapat penumpang. Itu adalah jam-jam orang berangkat kerja, pulang kerja, dan anak berangkat sekolah, pulang sekolah.
Di atas pukul 08.00 pagi sampai menjelang Asar, orderan yang masuk tidak terlalu ramai. Di jam-jam tersebut, driver lebih banyak menunggu di warung-warung kopi, bahkan parkir sembarang untuk sekadar tiduran.
“Kalau hujannya siang nggak masalah, tapi kalau sore sampai malam, itu kan awet. Jadinya sedih, banyak kesempatan narik yang hilang karena hujan,” tuturnya.
Menerjang hujan demi uang tambahan
Di sebuah kedai kopi bernuansa vintage, seorang teman lama datang menyibak hujan dengan mantel kelelawar. Wajahnya kuyup.
Ia bekerja sampingan sebagai kurir pesan antar makanan. Sepulang kerja kantor pada pukul 17.00, ia akan mengenakan jaket oranye, lalu siap mengantar pesanan-pesanan makanan yang masuk. Biasanya menjelang tengah malam ia baru pulang.
“Surabaya kalau musim hujan seperti ini bisa tertebak. Pagi-siang panas menyengat, tapi sore-malamnya hujannya awet,” ujarnya usai memesan secangkir kopi susu hangat dan duduk berhadapan dengan saya.
Masalahnya, orderan lebih banyak masuk ke akunnya ketika hujan sedang deras-derasnya. Beberapa kali ia tak mengambil. Tapi lebih sering mengambil karena daripada rezekinya tersendat.
Alhasil, ia harus menerjang hujan. Berdingin-dinginan. Sesekali juga harus melewati titik-titik jalan yang tergenang air. “Beberapa titik masih sama seperti dulu: Kalau hujan deras, pasti menggenang di atas mata kaki,” jelas teman saya itu.
Tapi mau bagaimana lagi. Ia memilih bekerja sampingan bukan karena iseng atau sekadar mengisi waktu. Tapi ia butuh uang tambahan untuk tambahan biaya hidup. Gajinya dari perusahaan di bawah UMR Surabaya, ternyata cukup tak cukup untuk sebulan. Apalagi, meski masih bujang, ia harus ikut membantu mengurus biaya-biaya rumah: Listrik dan lain-lain.
Menertawakan (getir) after rain
Di ujung pertemuan, kami sama-sama menertawakan masa lalu, saat kami sama-sama suka meromantisasi Surabaya after rain. Kata teman saya, memang romantis dan puitis bagi orang-orang yang sekadar memandangnya.
Namun, bagi orang-orang seperti teman saya atau driver ojol yang sebelumnya mengantar—yang berada persis dalam guyuran hujan—ada rekaman nelangsa yang mereka saksikan dari teman-teman serupa: Yang sama-sama menyambung hidup dari jalanan.
Hujan reda lebih sering ketika menjelang tengah malam. Telah lewat jam-jam peak penumpang. Itu tentu mengurangi potensi pendapatan driver ojol jika beroperasi lancar di jam-jam peak tersebut.
Sementara bagi teman saya yang seorang kurir pesan antar makanan, after rain (selepas hujan) di Surabaya menjelang tengah malam, ia akan pulang dengan tubuh terasa remuk. Lelah. Juga menggigil.
“Tapi kan begini. Dulu kita bisa pura-pura sakit biar nggak sekolah. Tapi sekarang, sakit pun kita harus pura-pura sehat biar bisa tetap kerja. Nggak kerja, nggak memeras tenaga, nggak hidup kita,” tutup teman saya.
Lalu kami sama-sama tertawa getir mengenang masa lalu: Menyimpulkan hujan dan suasana after rain di Surabaya begitu indah dinikmati. Ternyata dulu terasa indah hanya karena belum digebuk realita saja.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Di Surabaya, Kaos Oblong dan Sendal Japit adalah Simbol Kekayaan: Isi Dompet Cukup untuk Beli Mall dan Segala Isinya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan