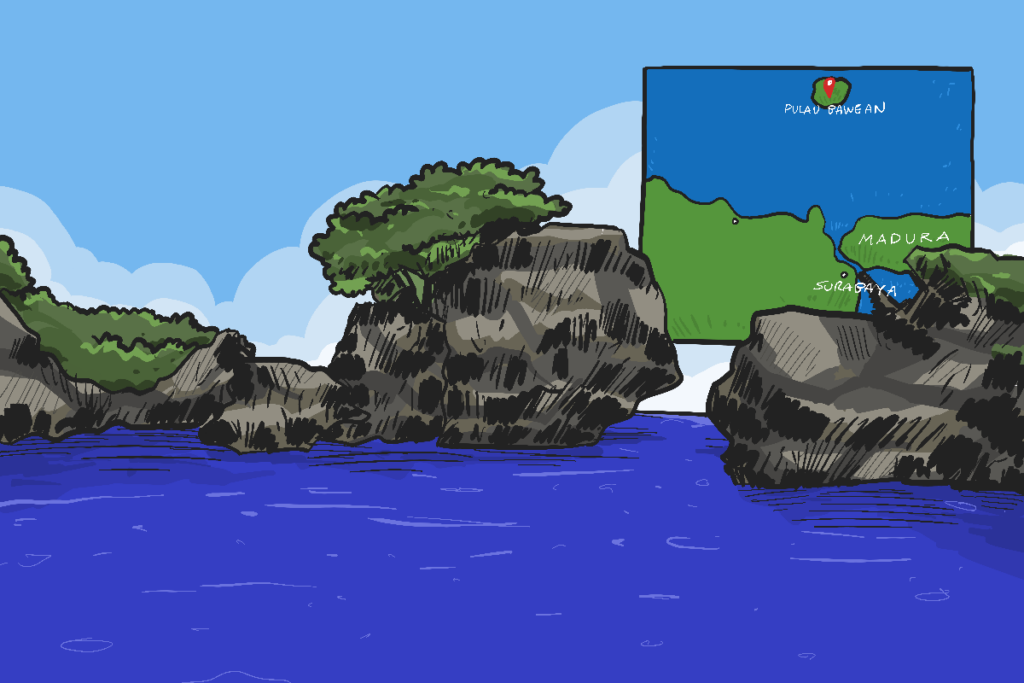MOJOK.CO – Selama enam bulan tinggal di Pulau Bawean, saya merasa menjadi anak tiri di negeri sendiri. Padahal masih bagian dari Pulau Jawa.
Ombak besar dan angin kencang membuat Kapal Roro Gili Iyang yang saya tumpangi tak bisa berlayar dengan tenang. Perjalanan selama delapan jam di atas kapal menggembosi nyali saya yang tidak bisa berenang.
Perut terasa dikocok dan kepala kliyengan tidak keruan. Beruntung, badan saya mudah beradaptasi sehingga tubuh bisa kembali bugar setelah kapal mulai bersandar di tujuan yaitu Pulau Bawean.
Saya datang dari Surabaya ke Pulau Bawean untuk bekerja. Ada proyek pembangunan dermaga yang lokasinya tidak jauh dari tempat para nelayan parkir kapal.
Setiap malam, saya melihat nelayan berangkat melaut dengan membawa perbekalan makanan. Esok, di siang harinya, mereka akan kembali dengan tangkapan ikan yang melimpah, satu ember tongkol berukuran besar hanya dijual Rp50 ribu.
Pulau Bawean berada di Jawa, tapi terasa seperti di Malaysia
Di Pulau Bawean, tidak ada Indomaret, Alfamart, apalagi kedai kopi kekinian. Pom bensinnya saja hanya buka tak lebih dari satu jam, kemudian tutup lagi karena stok bahan bakar habis. Kondisi seperti ini membuat kehidupan di Bawean terasa serba tradisional, namun tetap bersahaja.
Motor dan mobil parkir di pinggir jalan raya dengan kunci yang masih menempel adalah pemandangan sehari-hari. Warga Pulau Bawean hidup saling mengenal satu sama lain sehingga lingkungan aman dan minim pencurian.
Secara administrasi, Bawean masuk dalam Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Namun, kultur warganya sangat jauh berbeda dengan yang biasa saya lihat di Jawa.
Budaya Pulau Bawean lebih dekat dengan Melayu. Banyak warga yang berbicara dengan aksen Melayu, bukan Jawa. Kalau sedang berbelanja di Pasar Sangkapura, saya merasa seperti di Malaysia karena banyak orang berbicara dengan aksen khas serial Upin dan Ipin.
Bahkan, warga di sana kurang suka belanja emas dari Indonesia (Antam dan UBS). Mereka lebih suka membeli perhiasan emas Singapura, Malaysia, Dubai, atau negara Timur Tengah lainnya.
Bagi warga Pulau Bawean, mereka lebih familiar mendengar tetangganya liburan ke Singapura dan Malaysia ketimbang ke Jogja. Banyaknya warga yang merantau ke Singapore dan Malaysia ditengarai menjadi penyebab akulturasi budaya Melayu di pulau ini.
Baca halaman selanjutnya: Ketika masyarakat dipaksa untuk mandiri.
Infrastruktur pembangunan tidak memadai, warganya hidup mandiri
Infrastruktur di Pulau Bawean sangat tidak memadai. Misalnya, fasilitas umum terasa sangat kurang, transportasi minim, dan pasokan listrik tidak maksimal. Ini membuat lapangan pekerjaan di sana sangat terbatas sehingga mendorong penduduknya untuk merantau ke luar negeri.
“Kalau pun Mbak Uci (nama panggilan saya) kaya raya, tidak akan bisa membangun pabrik di Bawean sini karena unit pembangkit listriknya tidak kuat,” kata Pak Imran, Sekdes di Pulau Bawean.
Boro-boro dipakai untuk membuat pabrik yang memerlukan daya besar. Para nelayan ingin membuat cool storage agar hasil tangkapan ikannya tidak cepat membusuk saja listriknya tidak kuat.
Hidup di Bawean selama enam bulan saja sudah cukup untuk membuat saya merasa seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri. Bagaimana tidak, negeri ini sudah merdeka selama 88 tahun, tapi transportasi menuju Bawean masih terbatas sekali.
Kapal untuk mengangkut barang dari Jawa ke Pulau Bawean hanya beroperasi seminggu dua kali. Kalau cuaca buruk dan kapal dilarang berlayar, otomatis harga barang (termasuk kebutuhan pokok) meroket tinggi.
Pembangunan berjalan lambat
Transportasi yang kurang memadai ini membuat pembangunan di Pulau Bawean berjalan lambat. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang dari perusahaan konstruksi yang memilih undur diri saat mendapatkan tender (proyek) karena harga material bangunan di pulau ini kelewat mahal.
Di sisi lain, jika kontraktor tersebut mendatangkan material dari Jawa, akan terkendala transportasi. Slot kapal pengangkutan dari Jawa (Pelabuhan Paciran menuju Pelabuhan Bawean) sedikit dan kerap dimonopoli oknum penguasa setempat. Makanya, hitung-hitungan bisnisnya tidak menguntungkan.
Uniknya, meskipun kurang diperhatikan oleh pemerintah dan pembangunannya terbilang lambat, warga Bawean nampaknya hidup berkecukupan. Hal tersebut terlihat dari bangunan rumahnya yang luas dan desainnya cukup modern. Di pulau ini tidak ada rumah subsidi tipe 36 yang sempitnya saingan sama kandang ayam itu.
Warga Pulau Bawean yang (terpaksa) mandiri
Hidup dengan fasilitas umum yang kurang dan “dicuekin” pemerintah membuat warga Pulau Bawean mandiri. Mereka memilih kabur saja dulu, pergi merantau ke luar negeri, dan mencari penghidupan di sana.
Bahkan, jejaring warga Bawean di Singapura dan Malaysia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jika pembaca Mojok berkunjung ke Malaysia, carilah Kampung Boyan. Kampung ini dihuni oleh orang-orang asli Bawean yang menetap di Malaysia.
Warga yang merantau ke luar negeri tidak melupakan akarnya, tanah air leluhurnya. Mereka mengajak orang-orang di Bawean (utamanya laki-laki usia produktif) untuk bekerja di Malaysia ataupun Singapura.
Hal itulah yang kemudian membuat Pulau Bawean dijuluki sebagai Pulau Putri. Sebuah pulau yang mayoritas penghuninya perempuan karena penduduk laki-lakinya merantau ke luar negeri.
Meskipun terlalu dini menyebut warga sudah sejahtera hanya dari rumahnya, tapi saya yakin warga di Pulau Bawean tidak kelaparan karena kemandirian usahanya sendiri. Sebab, saya sering mendengar warga sana mengeluh tentang pemerintah yang abai dengan masalah warga (terutama nelayan).
Salah satu masalah yang sering dihadapi nelayan lokal adalah banyaknya kapal cantrang yang beroperasi di sana. Kapal-kapal tersebut datang dari Tuban dan daerah lainnya, mengambil ikan dengan cara merusak terumbu karang.
Para nelayan di sana sudah sering melaporkan kehadiran kapal cantrang pada pihak berwajib. Namun, pihak berwajib tidak pernah menanggapinya dengan serius.
Kalau nelayan berhasil menangkap kapal cantrang sendiri, setelah dibawa ke pihak berwajib, pemilik kapal justru dengan mudah lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut tentu saja membuat para nelayan lelah sendiri dan merasa dicuekin pejabatnya.
Jika masalah mayoritas warga (nelayan) saja diabaikan oleh pemangku kebijakan, apalagi masalah-masalah lain? Misalnya seperti minimnya lapangan kerja dan carut marut transportasi?
Pawang hujan dan hal-hal tidak masuk akal lainnya
Sebagai Homo Sapiens modern, sesungguhnya saya kurang percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Kalau di rumah sendirian misalnya, saya lebih takut ditikam maling ketimbang bertemu demit. Namun, selama di Pulau Bawean, saya menemui banyak kejadian aneh dan ganjil.
Kejadian pertama berhubungan dengan cuaca dan alam. Dalam proyek pembangunan dermaga, cuaca menjadi faktor yang mempengaruhi progres pekerjaan.
Masalahnya, satu minggu sebelum proses pengecoran pondasi, hujan deras turun setiap hari. Meski BMKG merilis perkiraan cuaca cerah, fakta di lapangan selalu hujan. Saya pun mulai khawatir dan mencari solusi supaya pengecoran tetap bisa dilakukan.
“Pakai jasa pawang hujan saja, Bu.” Kata Saiful, seorang guru di Pulau Bawean yang saya dapuk menjadi humas selama proyek berlangsung. Dia membantu saya berkomunikasi dengan warga dan nelayan setempat yang tidak semuanya mahir berbahasa Indonesia.
“Hanya Rp300 ribu saja per harinya. Ibu tahu beres saja. Saya yang mencarikan,” masih kata Saiful.
Sejujurnya, selama 15 tahun bekerja di proyek yang lokasinya bergonta-ganti; dari Bali, Sulawesi, hingga Morotai, saya tidak pernah menggunakan jasa pawang hujan. Apalagi mendatangkan “orang pintar”.
Namun, saya percaya dengan pepatah lama. “Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.” Jadi ya, saya iyakan saran dari warga lokal sebagai bentuk menghargai kultur setempat.
Yang “tidak masuk akal” lainnya
Satu hari menjelang pengecoran, Pak Saiful menemui Sang Pawang. Setelahnya, dia membawa cabai, bawang, dan lidi. Benda-benda yang umum saya temui di dapur. Ketiganya diberi doa atau mantra oleh Sang Pawang, kemudian diletakkan di site (lokasi proyek).
Entah kebetulan atau tidak, selama pekerjaan pengecoran yang berlangsung tiga hari tersebut, hujan tidak turun sama sekali. Bahkan, sampai lima hari kedepan hujannya tidak turun.
“Bu, maaf, saya lupa mencabut lidinya,” kata Saiful suatu malam saat saya mengeluh kenapa tidak ada hujan sama sekali. Padahal, proses pengecoran telah usai.
Awalnya, saya masih menganggap keberhasilan pawang hujan murni kebetulan. Namun, setelahnya saya mengalami kejadian yang tak kalah ganjilnya.
Tidak masuk logika
Suatu kali, saya pergi ke pemandian air hangat yang lokasinya tidak jauh dari makam Sunan Bonang. Iya, kalian tidak salah dengar.
Sunan Bonang juga memiliki makam di Pulau Bawean. Warga percaya jika makam asli Sunan Bonang justru yang berlokasi di sini, bukan di Tuban.
Kembali soal pemandian air panas. Setelah berendam di air panas dan hendak pulang, saya kesulitan menemukan jalan pulang. Saya berputar-putar terus di lokasi tersebut. Padahal saat datang, saya bisa menemukan jalannya dengan mudah.
Merasa ada yang janggal, saya duduk sebentar, berusaha mencerna kejadian dengan akal sehat. Sampai kemudian ada anak kecil yang membawa seperangkat alat pancing lewat. Saya bertanya ke anak itu tentang akses menuju jalan raya. Anak kecil ini kemudian menunjuk ke area yang sudah saya putari berkali-kali, tapi buntu.
Tanpa ragu, saya meminta anak tersebut mengantar saya ke jalan yang dia tunjuk. Dan betapa terkejutnya saya saat tahu jalannya tidak buntu. Saya pulang dengan perasaan campur aduk, berperang antara logika dan pengalaman empiris yang tidak bisa diterima pikiran di kepala.
Sebagai orang yang pernah bekerja di berbagai pulau kecil di Indonesia, Pulau Bawean menjadi salah satu yang paling berkesan. Bukan hanya karena proyek pembangunan dermaga yang berjalan lancar, tapi juga pengalaman mistisnya.
Jika pembaca Mojok ingin merasakan aura mistis bercampur keindahan alam, Bawean adalah tempat yang wajib didatangi.
Penulis: Tiara Uci
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA 4 Hal yang Saya Rasakan Saat Tinggal di Pulau Terluar Indonesia dan pengalaman seru lainnya di rubrik ESAI.