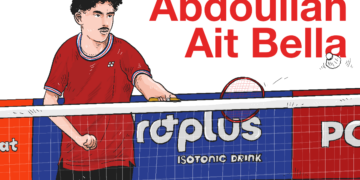Saking derasnya banjir informasi di linimasa, mulai dari tragedi kemanusiaan, bencana alam, temuan teknologi, sensasi selebritas, hingga gosip esek-esek habib junjungan itu, barangkali hanya sedikit yang mengingat cerita-cerita ini. Cerita yang membuat kita sedikit terketuk dan merasa penting untuk membicarakan peristiwa yang terjadi jauh di Amerika sana.
Pada akhir tahun 2015, kata kunci “Chapel Hill Shooting” sempat riuh di mesin pencari Google. Bersamaan dengan itu, di beranda sosial media muncul foto wajah tiga anak muda muslim yang menjadi korban peristiwa itu. Mereka adalah sepasang suami istri Deah dan Yusor, serta Razan, adik perempuan mereka.
Deah, 23 tahun, adalah siswa berprestasi di sebuah kampus kedokteran gigi. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan sosial tingkat lokal maupun internasional lewat berbagai proyek yang didedikasikan untuk orang miskin dan pengungsi Suriah di Turki. Adik iparnya, Razan, pada usia 19 tahun telah menjadi seorang arsitek yang membantu para tunawisma memiliki tempat tinggal alternatif lewat proyek-proyeknya.
Deah, Yusor, dan Razan, tiga anak muda muslim itu ditembak tepat pada otak di kepala belakang oleh seorang tetangganya lelaki ateis kulit putih, di tempat paling aman yakni di dalam rumah mereka sendiri. Selama berbulan-bulan sebelumnya, lelaki itu kerap mengetuk rumah mereka, mengacungkan senjata, dan mem-posting ujaran-ujaran kebencian anti-agama. Yusor sempat merasa terancam, namun Ibu mereka berujar, “Berbuat baik saja dan berikan wajah yang manis. Orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan akhlak yang kita beri.” Sang Ibu, hingga kini, barangkali tidak pernah mendapat jawaban mengapa seseorang dapat membunuh orang lain hanya karena pakaian yang mereka kenakan dan ajaran yang mereka percayai, bahkan ketika ajaran itu tidak mengganggu kehidupan pribadi mereka.
Saat ini di Amerika terdapat 3 juta lebih warga muslim, tidak mencapai satu persen dari total penduduk. Saya, di negeri dengan penduduk muslim paling banyak di dunia ini kini selalu membayangkan betapa tiap detik yang mereka lalui menjadi begitu menegangkan di bawah kendali seorang Donald Trump.
Presiden yang pada tiap orasinya penuh dengan makian dan seruan rasis, bias gender, dan kebencian anti-Islam itu langsung menerapkan kebijakan #MuslimBan yang bermaksud membatasi hak-hak warga muslim dan menolak masuknya imigran dan pengungsi muslim.
Ketika aksi 212, yang bermaksud mengkriminalisasi Ahok berlangsung dan berhasil menggerakkan jutaan muslim, berlangsung di Indonesia, saya kerap teringat kisah Deah, Yusor, dan Razan ini. Bagi saya, peristiwa tersebut lebih dari sekadar urusan politik atau bela-membela agama. Dari perspektif lain, ia menunjukkan bagaimana manusia bisa bergerak dan menuntut pihak yang berseberangan dengan mereka, kali ini dalam hal agama. Memang betul bahwa aksi itu berlangsung dengan begitu damai, toh tetap saja media Internasional menggunakan istilah hardline untuk para pesertanya. Sebuah penanda bahwa efek 9/11 tidak akan pernah habis dalam menahbiskan islamofobia yang menyebabkan saudara-saudara muslim di negara Barat sering mendapat tatapan curiga, serangan fisik kecil tanpa alasan, hingga pemeriksaan acak yang tak sewajarnya di bandara.
Celakanya, hari-hari ini di Indonesia, kita justru makin sering disuguhi video-video para agamawan yang isi ceramahnya begitu galak dan panas. Sama seperti mayoritas mana pun di seluruh dunia, jumlah yang besar ini juga dianggap sebagai kebanggaan dan privilese untuk menganggap minoritas tidak setara.
Beberapa bulan setelah tragedi penembakan tiga pemuda di Chapel Hill, Khalid Jabara, seorang Kristen Lebanon-Amerika bahkan dibunuh di Oklahoma hanya gara-gara namanya yang kearab-araban. Dan betapa menyedihkan, pekan lalu, muncul video viral yang mempertontonkan seorang laki-laki Amerika berteriak-teriak sambil melancarkan ujaran kebencian anti-muslim pada seorang perempuan di depan sebuah bangunan lembaga persaudaraan muslim di Amerika. Ironinya, di akhir video, perempuan yang ia tunjuk-tunjuk tepat di depan mukanya itu ternyata non-muslim. Propaganda dan contoh buruk Donald Trump lewat ujaran-ujarannya ternyata membuat warganya merasa memiliki hak untuk melakukan hal yang serupa.
Tenang, bumi Amerika juga seimbang dengan sedikit manusia yang berbicara atas nama hak minoritas. Larycia Hawkins, seorang keturunan Afrika-Amerika yang bekerja sebagai profesor di Universitas Wheaton, pernah mempromosikan platform solidaritas untuk perempuan muslim berhijab di Amerika yang mengalami diskriminasi setiap hari. Sikapnya membuat Larycia dipecat kampus. Ia kini bekerja di Universitas Virginia pada lembaga yang menyuarakan pluralisme, keberagaman ras, keimanan, dan budaya.
Salah satu pendiri situs web reddit, Alexis Ohanian, bahkan melakukan kerja serius yang justru dianggap lelucon oleh banyak orang ketika ia mendukung gadis muslim cilik yang menuntut kehadiran emoji hijab pada aplikasi pesan instan.
Seorang pemimpin redaksi sebuah majalah wanita di Amerika Serikat bahkan juga repot-repot memperjuangkan lewat desk redaksi agar foto muslimah berhijab bisa muncul pada cover majalah kebugaran.
Serangkaian cerita itu semata-mata adalah usaha untuk membuat Amerika “terbiasa” dengan perbedaan. Serangkaian cerita itu pula yang mengingatkan kita kepada ungkapan Marthin Luther, “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”
Ketika kawan-kawan non-muslim di Amerika mendeklarasikan diri siap menjadi muslim jika kebijakan #MuslimBan benar-benar diterapkan, terkadang saya membayangkan umat Muslim di Indonesia memberikan dukungan aksi serupa dengan mendeklarasikan diri siap membela hak-hak kaum minoritas di Indonesia.