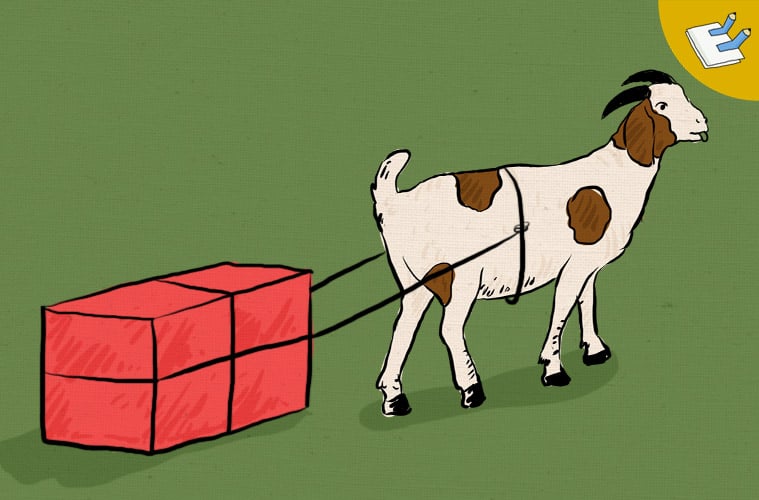Hari raya kurban telah tiba. Musim pemotongan hewan ternak oleh jagal partikelir mendapatkan momentumnya. Tapi seberapa paham kita Nilai Ekonomi Total dari perayaan idul adha? Bisa jadi nilainya jauh lebih besar dari yang dapat kita hitung. Itu di luar ruang udara kita yang akhir-akhir ini mendadak jadi paling pesing se-Asia Tenggara, mengingat satu dua hewan ternak di sekitar kita dari jutaan yang akan dikurbankan belum mendapatkan toilet training sebelumnya.
Semisal ada fatwa MUI: tahun ini rakyat Indonesia jangan memotong hewan ternak, tapi menyumbang pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, bagaimana? Relakah saudara? Sudikah umat mendengarkan himbauan dari lembaga pemuka agama tersebut?
“Wah … sepertinya itu ide bagus dan kekinian, Bro. Tapi jika itu yang terjadi, di fatwa berikutnya MUI akan jalan sendiri. Kami tidak akan sudi kawal lagi. #Eaaa. Ttd alumni 501.”
Lagi pula, yang akan mangkel bukan cuma mereka saja. Kepala Suku Mojok, yang tiap menjelang kurban sehari menengoki sampai tiga kali sehari, akan menjadi pihak yang tidak hanya mangkel, tapi juga murka. Tapi, ya, murkanya seorang penulis itu tetap tidak destruktif. Dia dia hanya akan merasa perlu menulis novel, Kurban Tak Pernah Tepat Waktu.
Dari berbagai sumber berita, hewan ternak yang dipotong untuk hari raya kurban tahun ini lebih kurang 1,1 juta ekor. Naik 10 persen dari data tahun sebelumnya. Rinciannya, 307.143 sapi, 8.289 kerbau, 715.641 kambing dan 90.682 domba. Itu angka perkiraan yang didasarkan pada jumlah kurban (resmi) tahun lalu. Resmi artinya tercatat dan dilaporkan.
Angkanya akan membengkak kalau ada peneliti yang rela blusukan dari kampung ke kampung. Karakter orang Indonesia itu seringkali memang istimewa, kalau tidak boleh dibilang eksentrik. Dari semula tidak ada rencana memotong hewan korban, pulang dari jalan-jalan sore tahu-tahu sudah memboncengi kambing. Hanya karena anaknya nangis minta dibelikan kambing untuk dipotong, akhirnya membeli. Hanya karena tetangganya menuntun kambing ke Masjid, langsung ikutan beli kambing. Demi jaga gengsi.
Kejadian-kejadian insidentil seperti itu rasanya naïf, tapi sangat kerap terjadi.
Padahal sangat baik kalau para sahibul kurban melaporkan kurbannya. Pertanyaannya tentu melaporkan kepada siapa? Kalau sudah dilaporkan ke RT, misalnya, apakah data tersebut akan direkap dengan baik? Itu memang masalah paling mendasar kita. Sementara orang yang berkurban pun, kalau ditanya mengapa tidak lapor, “Ah, nggak usah, nanti saya malah kawatir jadi riya.”
Lah, ikhlas dan lapor untuk pendataan yang baik itu dua hal yang lain sama sekali. Data yang dikelola dengan baik, pada penyelenggaraan selanjutnya dapat digunakan untuk memetakan distribusi daging kurban. Daerah mana saja yang “biasanya” surplus jumlah kurbannya dan daerah mana saja yang masih minus.
Kemudian, dengan angka yang ada (sebisa mungkin tidak melebih-lebihkan), kita bisa perkirakan nilai hewan ternak yang dikorbankan masyarakat.
Jika tiap ekor sapi dan kerbau berat per ekornya 400kg dan kambing 40kg. Paling tidak nilai keseluruhannya mencapai 8,2 triliun. Sekali lagi itu angka moderat. Sapinya Pak Jokowi, berjenis berangus yang rencananya akan disembelih di Palembang itu beratnya 1,2 ton. Harganya 85 juta, 4-5 kali lipat dari harga sapi dewasa standar kurban. Tidak sedikit juga orang yang menyumbangkan sapi jenis limosin yang hargaya bisa di atas 100 juta.
Itu belum memasukkan jamaah haji Indonesia yang berjumlah 200.000 berkurban di Saudi. Juga belum memasukkan pengurban lintas benua yang dikomandani diaspora Bantul, Ustadz Abu Latif alias Iqbal Aji Darsono. Bukan Daryono, ya … kalau itu lain lagi. Angkanya tentu akan fantastis.
Melihat animo masyarakat dalam berkurban yang tercermin dari banyaknya jumlah hewan kurban, Setya Novanto, dalam kapasitasnya sebagai Ketum Partai Golkar, pernah mengatakan, “Golkar ingin berbagi, untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat”.
Pernyataan itu kalau dibaca sekilas tidak ada yang luput. Wajar saja. Apa lagi dalam bingkai semangat beribadah. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi makro, pernyataan itu bermasalah dan cacat logika. Apa mungkin kemiskinan dan ketimpangan diselesaikan hanya dengan membagi daging kurban saja? Satu hari pula.
Di masa lalu, jargon-jargon yang ditiupkan pada setiap kegiatan memang sangat nyata dan membumi. Jangankan perayaan kemerdekaan Indonesia, spanduk idul adha sering memunculkan visi dan misi. “Dengan Semangat Kurban, Kita Perangi Kemiskinan dan Ketimpangan”.
Mungkin saat memberikan pernyataan, bapak yang disebut di atas sedang teringat masa mudanya.
Untuk sejenak melupakan tekanan hidup dan merayakan kegembiraan, tentu orang-orang miskin sudah sangat terbiasa dan terlatih. Mereka terbiasa menjadi vegetarian “terpaksa”, mengingat mahalnya protein hewani hingga sering tak terbeli. Melihat data konsumsi daging per kapita pun sepertinya mendukung fakta itu. Angkanya sangat rendah, 2,9 kg per tahun.
Padahal, di hari raya kurban, sering terjadi orang mendapatkan lebih dari 3 kg. Angka konsumsi daging per kapita bisa saja salah. Ada kemungkinan juga benar.
Sering terjadi, sahibul kurban dan panitia tidak mau terlalu pusing dalam mendistribusikan. Walhasil orang yang mendapatkan daging kurban hanya orang-orang di sekitarnya saja yang relatif mampu.
Tidak sedikit yang pemikirannya canggih mengemas dan mengawetkan daging kurbannya ke dalam kaleng agar dapat menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Tetapi itu bukan kecenderungan umum. Praktik yang lebih umum memang yang sudah sering kita lihat selama ini: beli, potong, dan bagikan ke tetangga. Asal secara agama sudah sah pemotongannya, pendistribusiannya dipilih cara yang paling sederhana.
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, angkanya akan lebih besar dari 8,2 triliun seperti angka di atas. Dampak ikutan atau efek pengganda yang mengikuti ibadah ini memang dahsyat. Petani/peternak dapat menjual hewan ternaknya, pemilik angkutan yang mendistribusikan hewan mendapatkan sewa, pengusaha SPBU mengisikan bbm ke angkutan hewan ternak, orang yang tidak mempunyai skil dapat menjaga dan mengurus hewan di temat penampungan.
Cukup? Belum.
Industri kulit bisa mendapatkan bahan baku relatif murah, jagal amatiran mendapatkan kepercayaan menyembelih, permintaan tali tambang meningkat, pedagang bumbu omsetnya melonjak, pengusaha arang kayu tersenyum cerah di antara jelaga, pengusaha tusuk sate semakin cepat meruncingi bambu, pedagang selongsong ketupat musiman menyerbu kota-kota di sekitar mereka tinggal.
Cukup? Masih banyak sebenarnya. Efek pengganda dari perayaan keagamaan memang secara ekonomi sangat besar. 9 sektor perekonomian Indonesia jelas aktif bergerak meresponsnya.
Kita bisa saja mengatakan bahwa praktek penjagalan yang dilakukan kurang berprikehewanan dan limbahnya mencemari lingkungan. Kondisi itu bukan berarti tidak dapat diperbaiki. Selalu ada rung untuk berkomunikasi dengan masayarakat. Lagi pula, itu gunanya orang yang mempunyai pengetahuan cukup tentang kurban dan pelaksanaannya. Dari tahun ke tahun mereka juga menunjukkan kecenderungan mau maju.
Tetapi kalau mengatakan kurban itu pemborosan. Itu artinya harus istigfar, ingat adanya efek pengganda. Nilai ekonominya tidak hanya mati di angka 8,2 triliun. Bisa jadi nilainya menggelembung hingga angka 50 triliun. Lebih besar dari laba yang dibukukan Freeport Indonesia di tahun 2016. Freeport sedikit saja memberikan manfaat, sedangkan perayaan kurban memberikan manfaat kepada umat.
Dimensi sosial kurban juga sangatlah besar, jauh melebihi nilai ibadah untuk individu. Kurban bukan sekadar napak tilas apa yang telah dilakukan Ibrahim, lebih dari itu, ia kesanggupan untuk menyingkirkan egoisme yang sudah sering berkarat.
Soal imbauan untuk mengalihkan kurban ke sumbangan dana untuk infrastruktur, itu hanya bualan saja. Ya sudah, tidak perlu baper. Mana kambingmu? Jangan katakan, “Aku sudah kurban perasaan”. Kuno! Cukup siapkan bumbu, tusuk sate, dan tentu saja nasi. Itu pun sudah menggerakkan roda ekonomi rakyat.