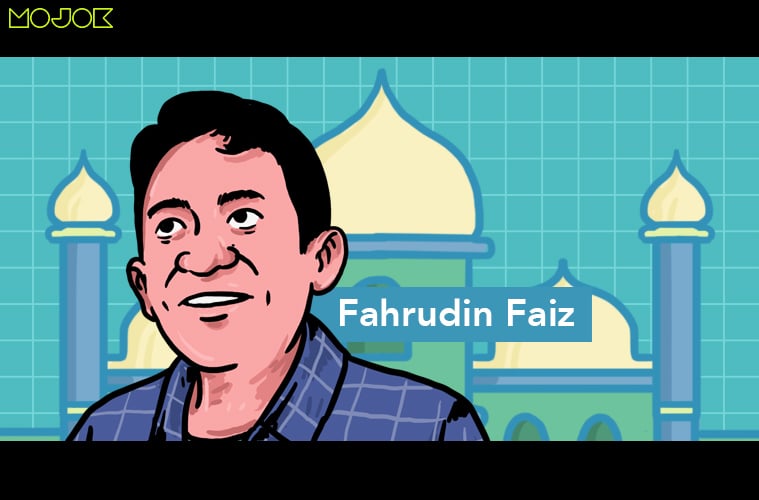“Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan sepuluh jari, ucapkan salah setulus hati, mari kita bersama berbenah diri, di bulan Ramadan yang suci. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.”
Kalimat indah seperti ini biasanya membanjiri lini masa media-sosial kita dengan berbagai bentuk, pola dan variasinya pada awal Ramadan kemarin-kemarin. Itulah salah satu budaya yang hidup di antara kita masa kini.
Menyikapi hal ini, apa komentar kita? Menarik, unik, efektif, atau genit?
Tak perlu nyinyir dengan mengatakan budaya semacam ini adalah sejenis “kehilangan jati diri”, “kepalsuan ekspresi”, “runtuhnya keintiman sosial”, “lenyapnya kedalaman” “kedangkalan penghayatan”, “sekadar citra, bukan ketulusan”, dan lain sebagainya.
Kita akui saja bahwa syarat dan rukun zaman ini dengan dukungan teknologi informasinya memang secara tak terelakkan akan membawa kita ke titik sebagaimana kita alami hari ini.
Justru penting saat ini untuk kita membuka mata dan pikiran, mencerna yang sedang terjadi tanpa terelakkan itu, kemudian merumuskan strategi-strategi sosial-budaya untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan dan mode hidup semacam itu.
Semoga revolusi gaya hidup yang lahir mengiring dahsyat-canggihnya teknologi informasi ini tidak menggerus jati diri atau mengikis nilai-nilai. “Angeli ananging ora keli” (Turut Mengalir namun tidak tenggelam), demikian dhawuh Sunan Kalijaga.
Kalau mau jujur, problem utama kita dalam hal ini sebenarnya terletak pada kesiapan dan keseriusan kita mengelola dan menyikapi perubahan zaman.
Selama ini kita lebih banyak larut dalam euforia dan ekstase meledaknya teknologi informasi, dan agak abai dengan strategi sosial-budaya untuk mengantisipasi efek dan dampak yang dapat muncul dan terjadi mengiring perkembangan teknologi tersebut.
Tampak sekali kita, khususnya para pemangku ilmu dan wawasan, juga pemegang kunci keputusan dan kebijakan, belum terlalu serius melakukan ideasi dan idealisasi, secara terstruktur dan terukur, untuk menyikapi perubahan-perubahan budaya, juga merancang tata nilai, tertib hidup logis-etis-estetis, di segala level hidup yang mungkin terjamah oleh perkembangan teknologi itu.
Kita seperti panitia kegiatan yang malas merancang kegiatannya sampai detil, lalu hanya menyatakan… “ya, nanti kalau ada kasus kita bersama mencari solusinya.”
Kembali kepada banjir dan perang ucapan di media sosial tadi. Perang ucapan itu bagi saya secara persis menggambarkan pola budaya dan relasi sosial baru dalam kehidupan manusia masa kini.
Setidaknya ada empat makna yang dapat kita tangkap dari fenomena adu ucapan ini, yaitu hidup yang terfokus kepada kompetisi, kehebohan, pertahanan nilai-nilai, dan penegasan eksistensi.
Saat mendapat kiriman, biasanya kemudian kita merasa tertantang, bukan karena tersentuh oleh isi ucapan, namun karena dorongan untuk segera melakukan hal yang sama. Ucapan-ucapan itu seakan menantang kita “Ini ucapanku, mana ucapanmu?”, “Apakah engkau masih ada, masih aktif, masih peduli?”
Kita pun merasa kecolongan, karena harusnya kita yang mengirim dulu, ternyata malah keduluan. Kita pun merasa harus segera mengirim ucapan yang senada, bahkan kalau bisa “lebih dahsyat” dari yang dikirimkan orang lain. Inilah logika kompetisi.
Dalam mode kompetisi ini, tidak hanya semangat peduli dan berbagi informasi yang ada di baliknya, namun juga gairah untuk adu cepat dan adu viral sebagai penegasan status diri. Siapa yang lebih cepat mengirim, dialah yang paling kompeten.
Dalam kasus ucapan selamat Ramadan tadi misalnya, mereka yang berlomba mengirimkannya “seakan” sedang menunjukkan citra dirinya sebagai yang sangat serius dan perhatian terhadap pesan-pesan agama, setidaknya seperti itulah kehadiran pesan tersebut terbaca.
Dalam kasus lain, misalnya ucapan semoga lekas sembuh kepada teman yang sakit atau belasungkawa kepada yang meninggal, siapa yang lebih dahulu tahu berita lelu mengirim ucapan yang pertama akan menggondol citra sebagai yang memiliki tingkat kepedulian dan kemanusiaan tinggi.
Siapa yang cepat, dia yang menang. Siapa yang cepat, dialah trend-setter; yang lain sekadar follower.
Lebih lanjut, seandainya kita bukan orang yang paling dulu mengirim ucapan, masih ada kesempatan untuk meraih status trend-setter ini, yaitu melalui jalur kehebohan atau keviralan. Hal ini dapat diraih misalnya dengan membuat kalimat yang sangat indah, unik, atau menyisipkan emoji stau stiker yang menarik perhatian, atau gambar dan video yang menimbulkan kesan mendalam.
Ukuran kemenangan di sini bisa dilihat dari berapa banyak ucapan kita di-like atau dikomentari, apalagi jika di-copy atau di-forward ulang berkali-kali. Inilah logika kehebohan.
Meskipun demikian, tentu masih banyak pula orang masih memegangi idealisme nilai dan norma kemanusiaannya, dan tidak terlalu peduli dengan situasi perlombaan atau kehebohan.
Mereka ini lebih ingin menjaga dan mengekspresikan nilai hidup yang diyakininya lewat ucapan. Mereka ini mungkin bukan yang pertama mengirim, juga tidak mengirim ucapan yang istimewa, bahkan mungkin hanya meng-copy saja kiriman orang.
Prinsip mereka seperti ini: “Tidak penting siapa pengirimnya yang pertama, tidak harus selalu istimewa, yang penting bukankah kita saling peduli dan saling menyebarkan sesuatu yang baik?” Inilah logika para agen penegak nilai-nilai.
Pada akhirnya, saat aspek kompetisi, kehebohan dan nilai juga tidak terjangkau sebagai dasar tindakan, berbagi ucapan ini dapat pula sebagai penanda eksistensi.
Mereka yang berada di ranah ini menggunakan logika: “Yang penting aku menunjukkan keberadaanku, bahwa aku masih ada, masih aktif, masih sadar menjalin interaksi dengan yang lain. Aku posting, mengirim sesuatu ucapan, maka aku ada.”
Inilah pola penegasan eksistensi.
Tentu saja setiap mode memiliki logika, urgensi, signifikasi, dan relevansinya sendiri, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta visi manusia yang menjalankannya.
Menghadapi situasi yang sedemikian kompleks ini, manusia tidak hanya dituntut mampu berpikir cerdas dan bekerja keras, namun juga harus mau menarik diri sesaat, merenung dan menelaah kembali ketepatan segala perilaku sosial-budaya dan teknologinya.
Momen Ramadan semoga setidaknya dapat membawa kita minggir sebentar, sekadar mengkalkulasi ulang, segala tingkah dan perilaku kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik dalam aspek ketepatan dan relevansinya dengan ideal-ideal dan nilai-nilai hidup yang kita yakini, juga manfaat-maslahatnya untuk diri kita sendiri dan juga yang lain.
Keluasan wawasan, kepekaan, kepedulian, serta kesadaran kemanusiaan, menjadi prasyarat agar manusia masih kuat bertahan menghadapi gempuran teknologi ciptaannya sendiri.
Untuk sementara, sebelum nanti lahir struktur serta tatanan ideal baru yang di lebih sistemik menyikapi gempita dan arus deras budaya baru teknologi informasi, semoga kita mampu “menguatkan” diri kita, baik secara mental, moral maupun spiritual.
Kembali ke semboyan dari Kanjeng Sunan Kalijaga tadi: Angeli Ananging Ora Keli. Mengikuti aliran, namun tidak tenggelam.
Sepanjang Ramadan, MOJOK menerbitkan KOLOM RAMADAN yang diisi bergiliran oleh Fahruddin Faiz, Muh. Zaid Su’di, dan Husein Ja’far Al-Hadar. Tayang setiap hari.