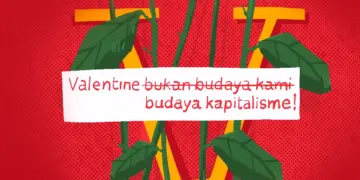MOJOK.CO – Penolakan atas Permendikbud 30 muncul karena prasangka. Padahal, melawan kekerasan seksual tak bisa pakai prasangka semata.
Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis jika kemampuan membaca bukan sekadar bisa mengeja kalimat, melafalkan kata, membunyikan konsonan atau vokal, tapi juga memahami yang tersirat. Menafsirkan apa yang nggak dijelaskan kayaknya susah buat beberapa orang dan itu tak apa. Mereka hanya perlu dibantu.
Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya penganjur poligami yang mendasarkan diri pada Surat An-Nisa ayat ke-3:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa lelaki boleh, kok, menikah dengan satu, dua, tiga, hingga empat. Syaratnya, dia harus adil. Kalau takut nggak adil, ya istri satu saja. Kalau ada yang memaksa, menikahi perempuan lebih dari satu tapi nggak adil, maka dia sudah berbuat aniaya.
Tapi pada praktiknya, penganjur poligami hanya memaknai kalimat “… maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat,” tapi tidak “… jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”
Mereka ini, saya kira, adalah kaum yang enggan membaca serius ajaran agamanya sendiri. Ini problem universal, lho.
Banyak orang membaca sebuah aturan hanya berdasarkan bias kognisi yang dia miliki. Sebagai pelaku poligami, banyak hanya berhenti pada empat istri, tapi enggan membahas serius definisi adil atau bahkan larangan poligami jika tidak adil.
Hal serupa juga terjadi di berbagai aturan. Mereka merespons aturan yang merugikan/menguntungkan si individu. Salah satunya soal Permendikbud 30 yang dibuat untuk menghentikan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan dunia pendidikan.
Dua hari ini saya mengikuti perdebatan orang-orang mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Saya lalu sadar, bahwa kita jauh dari level membaca sebagai usaha memahami.
Muhammadiyah dan PKS menolak Permendikbud ini karena dianggap melegalkan dan mengizinkan zina. Di dalamnya ada bagian yang berbunyi: “Atas persetujuan korban”. Misalnya, “Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.”
Mereka berkelakar, “Jadi kalau korban setuju, bukan pelecehan?” Fokusnya selalu pada boleh atau tidak. Sementara perlindungan kepada korban kekerasan seksual, pemulihan hak korban, dan bagaimana korban harus diperlakukan diabaikan. Muhammadiyah malah ngotot kalau mereka ini fokus pada substansi.
Logika bahwa “persetujuan korban berarti memperbolehkan zina” itu nyaris sama bodohnya dengan “menggunakan helm berarti boleh kebut-kebutan”. Lho, kok ke helm? Kan nggak nyambung?
Salah satu alasan muncul peraturan menggunakan helm adalah banyaknya korban kecelakaan terluka di kepala. Untuk mencegah dan mengurangi angka kematian atau cedera kepala karena kecelakaan bermotor, aturan wajib pakai helm dibuat.
Contoh kebijakan lain adalah peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Pasal 15 tentang batas minimum usia konsumsi alkohol. Aturan tersebut menyebutkan bahwa mereka yang berusia 21 baru boleh minum alkohol. Apakah ini berarti mereka yang berusia 21 tahun harus minum alkohol? Kan tidak.
Penolakan terhadap Permendikbud 30 ini melahirkan pertanyaan. Jangan-jangan, mereka sudah salah memperlakukan pasangannya? Jangan-jangan, saat melakukan kegiatan seks, mereka selalu memaksa? Langsung buka celana tanpa tahu apakah pasangan kalian mau atau tidak? Sukanya langsung sosor saja tanpa ada persetujuan pasangan padahal jatuhnya menjadi kekerasan seksual?
Beberapa teman di Twitter meledek. Orang-orang yang kaget soal persetujuan ini mungkin selama ini berpikir perempuan adalah objek pasif yang kita nggak perlu izin saat melakukan apa pun kepadanya. Sehingga jika mereka meminta kalian untuk menghormati hak tubuh melalui consent, jadi kaget dan marah-marah.
Lalu bagaimana sih persetujuan korban yang dimaksud? Dalam permendikbud 30 itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa, persetujuan korban dianggap tidak sah apabila dia berusia di bawah umur sesuai peraturan Undang-Undang, mengalami situasi di mana pelaku mengancam dan menyalahkan kedudukannya, di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, sakit, tidak sadar, atau tertidur.
Jangan-jangan, mereka yang menolak Permendikbud 30 ini melakukan seks dengan paksaan, melakukan seks bersama anak di bawah umur, atau menggunakan alkohol atau narkoba untuk melakukan kekerasan seksual?
Astagfirullah, tentu saja saya percaya Muhammadiyah sebagai lembaga Islam berkemajuan tidak akan melakukan ini. Bagaimana dengan yang lain? Mereka yang terbiasa menikahi anak di bawah umur? Mereka yang terbiasa melakukan kekerasan seksual tapi nggak sadar? Ini tentu sangat berbahaya dan mengancam eksistensi mereka.
Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Defirentia One Muharomah, mengatakan bahwa kontroversi yang muncul saat ini hanya karena adanya perbedaan pendapat yang didasarkan pada prasangka. Menurutnya, muatan dalam permen tersebut tidak ada yang dimaksudkan untuk melegalkan seks bebas.
Nomenklatur “persetujuan korban” yang dipermasalahkan itu, bukan untuk melegalisasi seks bebas, namun untuk menekankan bahwa selama ini banyak kasus kekerasan seksual yang dianggap sebagai kejadian suka sama suka sehingga lolos dan tidak ditindak sebagaimana mestinya.
Nah, kalau sudah begini, apalagi yang mau ditolak?
BACA JUGA RUU PKS Adalah RUU yang Islami dan ulasan menarik lainnya di rubrik ESAI.