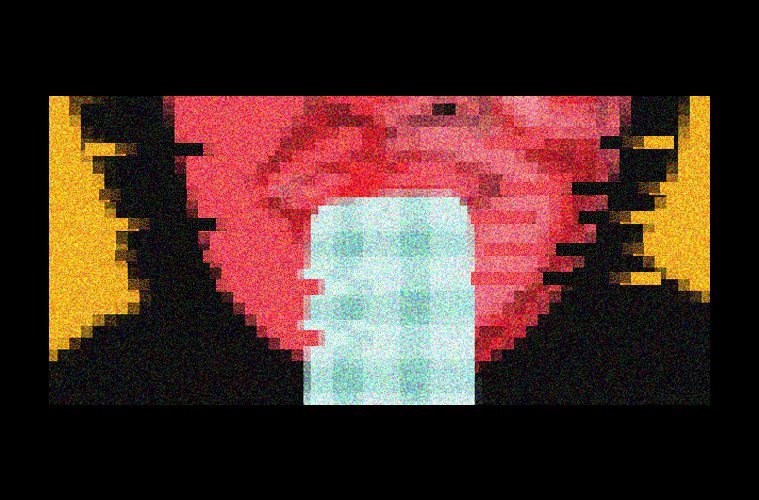MOJOK.CO – Es krim dan kemaluan. Publik marah karena Oklin Fia dianggap menodai kesucian jilbab atau hijab sebagai bagian dari agama Islam. Apakah kita perlu memenjarakannya?
Seorang perempuan berfollowers ratusan ribu di Instagram dan TikTok, yang lalu digelari sebagai selebgram bernama Oklin Fia sedang ramai dibicarakan. Dalam konten media sosialnya, Oklin menampilkan diri dengan gaya yang cukup menonjol. Dia memakai penutup kepala semacam hijab pasmina dan baju serta celana yang selalu ketat, hingga menampilkan bentuk payudara dan pantatnya.
Lalu, yang paling mutakhir, konten Oklin Fia adalah mengajak seorang laki-laki untuk meletakkan sebatang es krim di depan area penis, yang disambut Oklin dengan membungkukkan badan lalu menjilati es krim tersebut.
Publik kemudian tersinggung. Publik marah karena Oklin Fia dianggap menodai kesucian jilbab atau hijab sebagai bagian dari agama Islam. Definisi “bagian” ini kurang jelas didefinisikan bobotnya. Pokoknya, jilbab atau hijab adalah bagian dari agama Islam, sehingga menghina kain penutup kepala ini sama dengan menista agama.
Baca halaman selanjutnya: Logika yang mengganggu di kasus Oklin dan tuduhan menista Islam.
Oklin Fia dan menista Islam: Nalar publik yang lumayan membuat saya tidak tenang
Pertama, mengapa publik lebih mengkhawatirkan bobot nilai sebuah barang dibanding mengkhawatirkan perilaku manusianya? Dengan atau tanpa hijab, ide konten Oklin Fia adalah normalisasi pelecehan seksual kepada laki-laki. Konten Oklin seharusnya melukai nalar laki-laki secara umum. Ilustrasi laki-laki yang tidak keberatan untuk seolah “dijilati” alat kelaminnya di ruang terbuka adalah objek seksualisasi.
Bayangkan jika perempuan menggantikan posisi laki-laki yang “dijilati” bagian tubuh tertentunya. Para perempuan di Indonesia akan dengan segera bersolidaritas untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah pelecehan seksual.
Tapi, saat posisi objek konten ini adalah seorang laki-laki, entah kenapa logika ini tidak muncul. Sebagian menganggap konten ini lucu. Yang lain justru seolah mengafirmasi bahwa begitulah laki-laki, yang malah senang jika menjadi objek seksualisasi perempuan.
Publik yang terbelokkan fokusnya lebih membela sebuah kain. Mereka malah tidak mempersoalkan perbuatan manusianya, dalam hal ini Oklin Fia. Sikap ini mirip dengan wujud permisif. Khususnya kepada perbuatan koruptor, asalkan pelakunya tidak tampil mengenakan baju koko dan peci.
Terbiasa mempermasalahkan tampilan luar, asal teriak menista Islam
Sekarang ini, kita memang terbiasa puas dengan mendisiplinkan tampilan-tampilan luar. Kita tidak tertib mendisiplinkan perilaku yang memberikan dampak merusak hajat hidup masyarakat jamak. Alasannya? Tentu saja karena yang kedua perlu proses dan ketelatenan jangka panjang. Bukan sekadar dapat ditertibkan dengan cara berbisik-bisik dari belakang, menstigma, atau menghukum fisik seseorang.
Logika lain yang saya baca di berbagai platform media sosial terkait Oklin Fia dan menista Islam malah lebih buruk lagi. Misalnya:
“Kalau nggak pakai jilbab sih terserah ya mau ngapain aja.”
“Copot dulu jilbabnya, silakan deh mau bebas berperilaku seperti apa.”
Logika yang sangat mengganggu
Logika ini mengganggu sekali. Jilbab, atau manusia dengan jilbab, dalam logika ini dianggap sebagai subjek yang tidak bisa atau tidak boleh berperilaku menyimpang. Pertama, hukum moral ini lagi-lagi bias gender.
Sebab, yang bisa secara spontan menanggung beban hukum ini adalah manusia perempuan saja. Khususnya untuk tindakan-tindakan amoral yang berkaitan dengan seksualitas. Sedangkan, laki-laki pelaku pelecehan seksual dan kekerasan seksual bisa bebas melenggang begitu saja. Penampilan mereka lebih tidak mudah diidentifikasi.
Kedua, hukum moral ini juga sangat diskriminatif kepada perempuan tanpa jilbab. Seolah, hasrat seksualitas yang diasosiasikan dengan liar atau tak senonoh layak diatribusikan kepada perempuan yang tidak memakai jilbab.
Seolah, perempuan yang tidak memakai jilbab tidak memiliki kontrol dan martabat diri. Pandangan ini sangat tidak adil sejak dalam pikiran. Sebab, diam-diam di dalam kepala, kita kembali mengobjektifikasi, bahkan mendehumanisasi perempuan (tanpa jilbab). Seolah mereka itu tanpa kesadaran, kehendak, dan intelektualitas.
Padahal, di Indonesia, tidak semua perempuan beragama Islam memakai jilbab. Dan, ada perempuan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga penghayat kepercayaan yang tidak memakai jilbab.
Memelihara pikiran merendahkan perempuan tanpa jilbab di Indonesia sama dengan merendahkan jutaan perempuan bermartabat. Saya satu barisan jika para perempuan ini ingin tersinggung terhadap pandangan publik yang misoginis begini.
Pemakaian jilbab dalam teks Islam
Benar, bahwa sejak awal peradaban, manusia mulai memaknai segala hal. Misalnya pakaian sebagai sebuah simbol. Baik didefinisikan oleh sosiologi, antropologi, filsafat, maupun psikologi.
Sebab-sebab perintah pemakaian jilbab dalam teks Islam juga terkait dua hal paling umum. Pertama, karena fungsi, misalnya agar tidak dilecehkan. Fungsi ini terkait erat dengan kondisi kebutuhan akan toilet dan jalanan publik yang aman berabad lampau. Yang kedua, sebagai simbol status sosial. Contohnya agar dikenali dan menjadi perbedaan dengan perempuan budak pada masa itu.
Lalu, belasan abad kemudian, di Indonesia hari ini, jilbab bisa menjadi daya jual lebih. Misalnya untuk mereka yang menyediakan jasa seks dan perempuan di panggung politik elektoral. Setara dengan gelar mendadak haji pada calon legislatif laki-laki beragama Islam. Kalau seperti ini, bagaimana saya, sebagai perempuan muslim Indonesia yang mengenakan jilbab, menempatkan diri?
Membebaskan diri dari kungkungan
Saya sih telah lama membebaskan diri dari kungkungan makna dianggap mulia dan suci hanya karena kain penutup kepala. Simbol perempuan mulia dan suci itu, untuk masa ini, jelas bukan pada pakaian. Belasan abad lalu, status sosial perempuan perlu ditolong dengan “pakaian”.
Tapi hari ini, saya memilih mendefinisikan kemuliaan perempuan Islam dan pada umumnya, kepada kemampuan menalar. Hal ini membuat perempuan mampu melakukan dua hal yang saling terkait. Pertama, mengambil keputusan optimal dalam hidupnya. Lalu, kedua, termanifestasi dalam perilaku yang menghadirkan dampak baik untuk diri sendiri maupun masyarakatnya.
Dengan prinsip ini, saya sama sekali tidak perlu membela kain di kepala Oklin Fia. Saya, sebagai perempuan beragama Islam, juga tidak merasa ingin memenjarakan Oklin.
Oklin Fia tidak mempermalukan sebuah barang, melainkan mempermalukan dirinya sendiri sebagai individu beragama Islam. Dan, setiap tindakan individu yang memiliki dampak sulit diukur seperti “rasa malu” atau “rasa jijik”, memang tidak perlu dipidana.
Dia hanya perlu dikompetisikan dengan dampak-dampak lain yang dianggap tidak memalukan atau tidak menjijikkan. Setelah itu, berebut ruang budaya yang dimiliki masyarakat. Pertanyaannya, jika konten penalaran dan pengetahuan gagal merebut ruang-ruang kebudayaan baru ini, bagaimana sikap kita?
Jangan-jangan, ketersinggungan kepada konten Oklin Fia, lagi-lagi hanya wujud denial akan kekalahan kita merebut ruang kebudayaan baru ini? Kita menyerah di hadapan Oklin Fia dan memilih paksaan untuk menundukkannya.
Penulis: Kalis Mardiasih
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Apa Salah dan Dosa Perempuan Edgy dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.