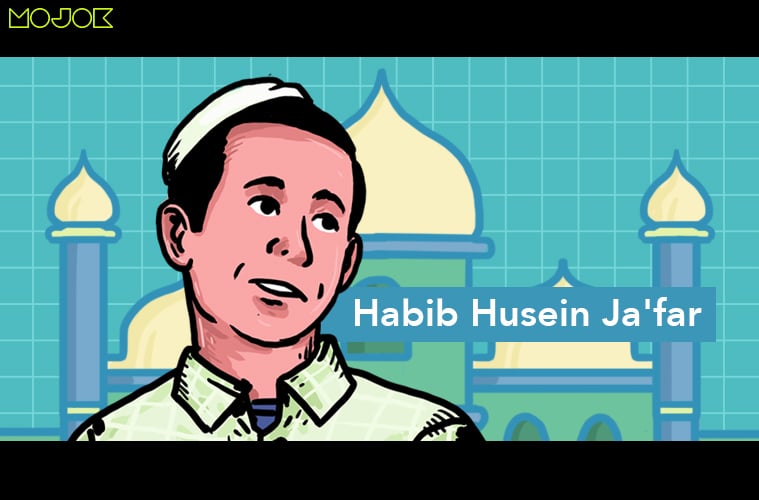MOJOK.CO – Mengelak dari pertanyaan “kapan nikah” memang butuh keterampilan khusus. Mungkin pembelaan syar’i ini, bisa dijadikan sebagai salah satu solusi.
Apa jawaban kalian ketika mudik kemarin saat ditanya sama kerabat, sahabat, dan tetangga ihwal: mana pasangannya? Kapan nikah, nih? Kok nggak disegerain aja? Nunggu apa lagi, sih?
Apakah merengut? Melengos? Tersenyum kecut? Menyahut sekenanya? Segera menghindarinya? Ataukah nyerocos ala-ala SJW gitu hingga memicu ketidaknyamanan baru dengan sejumlah orang?
Btw, kini kalian saya bela. Tak main-main, pembelaan dari pertanyaan “kapan nikah” saya ini berdasar mutu syar’i yang luar biasa, salafus shalih, generasi kedua pasca Nabi saw., alias sahabat. Kurang syar’i apa lagi coba? Biar kalian makin yakin pada mutu unggulan kesyar’ian berdasar generasi sahabat, saya simak dulu bagian yak-yako ini.
Di antara empat imam mazhab yang paling terkemuka popularitasnya hingga kini, tersebutlah sosok Imam Malik. Beliau adalah murid tak langsung dari Abu Hanifah—sebab Imam Malik berguru kepada salah satu murid utama Abu Hanifah. Beliau adalah guru langsung Imam Syafii.
Beliau membangun mazhabnya dengan karakter yang khas, yakni menjadikan tradisi para sahabat Nabi saw. di Madinah sebagai sumber rujukan hukum yang utama—setelah Alquran. Ini berbeda dengan karakter mazhab lainnya. Alasan beliau sangat masuk akal: bahwa generasi dan tradisinya yang paling dekat dengan keontetikan Rasulullah saw. adalah para sahabat. Tradisi Madinah masa itu wajar disebut sebagai representasi utama tata cara hidup Rasulullah saw.
Jelas kan kini bahwa mendasarkan suatu pandangan hukum pada para sahabat adalah sangat otoritatif. Dalam tradisi Syafiiyah pun, Qaul Shahabah dijadikan salah satu sumber rujukan hukum. Mashoook….
Kini, simak dan hafalkanlah dengan saksama nukilan syar’i dari generasi sahabat buat kalian yang tak kunjung menikah dan bosan dengan pertanyaan “kapan nikah”. Semoga kalian menjadi bahagia–entah sekadar wacana ataupun ya wacana. Bhaa….
Tersebutlah sahabat terkemuka yang masuk dalam golongan sahabat Nabi saw. yang dijamin masuk surga, yakni Abdurrahman bin ‘Auf. Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah—bukan ke Instastory—Abdurrahman bin ‘Auf dipaksa oleh kaum Quraisy Mekkah untuk meninggalkan semua hartanya. Hanya baju yang melekat di badannya saja yang boleh dibawa.
Padahal saat itu ia telah sangat kaya luar biasa! Ditinggalkanlah semua harta kekayaan itu olehnya. Demi membela iman, Islam, dan hijrah ke Madinah.
Setiba di Madinah, ia disambut oleh para anshar, salah satunya adalah saudagar kaya raya Madinah—duh, maaf, saya lupa nama tokoh anshar ini. Tokoh anshar ini menjamu Abdurrahman bin ‘Auf dengan mewah—entah itu sate klathak, tongseng terpedo, atau kambing guling. Sembari menikmati suguhan, tokoh anshar itu berkata,
“Kang, nuwun sewu, kulo mireng leh njenengan niku ten Mekkah sak sugeh-sugehe juragan njeh?” (“Kang, maaf, saya dengar Anda di Mekkah adalah juragan yang sangat kaya, ya?”)
Abdurrahman bin ‘Auf mesem-mesem tamvan gitu, macam Ivan Lanin. Mengangguk-angguk. “Njeh, njeh, alhamdulillah, pangestunipun….”
Dasar orang anshar ini baik banget, ia menyodorkan tawaran kepada Abdurrahman bin ‘Auf yang hari ini mustahil ditolak oleh Nikita Mirzani—kita juga, ding.
“Kang, menawi ngoten, monggo panjenengan pendet mawon harta kulo sepaleh njeh. Saget njenengan kagem merintis usaha nopo mawon ten mriki. Menowo dagangan onta, wedhus, kurmo, nopo mawon. Damel penerbit indie njeh kadose sae mawon….”
(“Kalau memang begitu, silakan Anda ambil saja harta saya separuh. Dapat Anda gunakan untuk merintis usaha apa pun di sini. Misalnya berdagang onta, kambing, kurma, apa saja. Untuk bikin penerbit indie sepertinya juga baik….”)
Abdurrahman bin ‘Auf mesem-mesem tamvan gitu, macam Ivan Lanin lagi. Kali ini menggeleng-geleng. “Sampun, Kang, sampun, saestu matur nuwun….” (“Sudah, Kang. Sudah, terima kasih sangat…”)
“Kang, kulo njeh tenanan lho niki, saestu tenanan. Mboten kok yak-yako tenanan kados piyantun Solo-Jogja padahal asline njeh merengut niku….” (“Kang, saya juga beneran ini, sungguh. Tidak seperti benerannya orang Solo-Jogja padahal sebetulnya cemberut.”)
“Mpun, saestu, kulo matur nuwun….”
Orang anshar yang baiknya sangat anarkis ini, masih berusaha membujuk Abdurrahman bin ‘Auf. Kali ini, ia berkata dengan sedikit menggoda, “Anu, Kang, kulo niki kan gadah istri katah, heee….biasalah, Kang, njeh, heee… Ngeten mawon, panjenengan kulo aturi mendet sepaleh harta kulo plus milih bojo kulo sek pundi mawon sek njenengan remeni. Ngapunten lho, Kang, niki ampun njenengan artikke kulo adol-adol garwo, lho. Saestu mboten. Niki ming saking estune kulo ten panjenengan….”
(“Anu, Kang, saya ini kan punya istri banyak. Begini saja, Anda saya persilakan mengambil separuh harta saya plus memilih istri saya yang mana saja yang Anda sukai. Maaf loh, Kang, ini jangan Anda artikan saya jual-jual istri, loh. Sungguh bukan. Ini hanya saking hormatnya saya ke Anda….”)
Abdurrahman bin ‘Auf lagi-lagi hanya mesem-mesem tamvan gitu, lagi-lagi macam Ivan Lanin—ha, masak macam Marno Blewah yang cah-mandiri-manualan itu.
“Estu kulo matur nuwun, Kang. Matur nuwun. Sampun cekap. Sakniki nyuwun tulung kulo diparingi weruh ten pundi nggeh pasar niku?” (“Sungguh saya berterima kasih, Kang. Terima kasih. Sudah cukup. Sekarang saya minta tolong dikasih tahu, pasarnya di mana, ya?”)
“Pasar, Kang?”
“Njeh. Pasar ageng kados Bringharjo nopo Klewer niku. Sanes kados Amplaz nopo Paragon nopo Hartono Mall njeh….” (“Iya. Pasar besar seperti Bringharjo atau Klewer gitu. Bukan seperti Amplaz, Paragon, atau Hartono Mall, ya…”)
Ditunjukilah Abdurrahman bin ‘Auf lokasi pasar Madinah. Dengan bekal kecerdasan dan pengalamannya berbisnis selama di Mekkah, ia merintis usahnya dari nol. Tanpa modal! Hanya pakai dengkul, itu pun dengkul orang. Orang-orang Madinah pula. Jal, kurang syar’i apa lagi?
Dedikasi, perjuangan, komitmen, dan keamanahannya yang luar biasa dalam berdagang menjadi sangat kondang. Hanya dalam waktu setahun, ia telah melesat jadi saudagar kaya di Madinah. Beberapa waktu kemudian, sampai digambarkan oleh Aisyah ra. bahwa bila kafilah dagang Abdurrahman bin ‘Auf melintas, terdengarlah suara gemuruh derap kaki unta dan kuda yang mengangkut dagangan Abdurrahman bin ‘Auf. Sebagiannya dikirim langsung, sebagiannya buat COD-an.
Dalam keadaan giat berdagang begitu, mengembangkan bisnis-bisnisnya dengan akselerasi tinggi, tentu saja Abdurrahman bin ‘Auf mendengar tuturan Rasulullah saw. perihal “menyegerakan” menikah (ya ma’syaras syabab…) serta menyudahi pertanyaan “kapan nikah” yang ditujukan kepadanya. Bentar ya, kata “menyegerakan” sengaja saya kasih tanpa petik, supaya terbedakan dengan takwil Felix Siauw yang getol mendorong anak-anak abegeh untuk udah putusin aja dan nikah aja segera, sekarang juga. Ini beda!
Pun tidak mungkinlah Abdurrahman bin ‘Auf sebagai orang dekat Rasul saw. tidak bersungguh-sungguh dalam memperhatikan, memahami, dan mengamalkan tuturan-tuturan Rasulullah saw.
Saad bin Abi Waqash, sobat kentel Abdurrahman bin ‘Auf, suatu hari berkata kepadanya.
“Kang, kowe ki ngenteni opo meneh je, kok ra gek ndang rabi to?” (“Kang, kamu ini nunggu apa lagi, sih, kok nggak segera menikah?”)
“Sik, aku sik karep mempeng dagangan je….” (“Bentar, aku masih pengin serius berdagang.”)
“Wolah, Kang, Kang. Tok kiro rabi ki ra penak? Yo penuk pol-polan je….” (“Alah, Kang. Kamu kira menikah itu nggak enak? Ya, enak pol-polan.”)
Abdurrahman bin ‘Auf hanya mesem-mesem tamvan gitu, serupa lagi sama Ivan Lanin.
“Ngene wae, Kang,” lanjut Saad bin Abi Waqash. “Aku ki nduwe bojo loro, to. Kowe reti dewe. Saiki kowe pilihen sek endi sek kowe senengi, tak pegat, rabinen….” (“Aku ini kan punya istri dua. Kamu ngerti sendiri. Sekarang kamu pilih saja yang kamu senengi, saya cerai, silakan dinikahi.”)
Lagi-lagi, Abdurrahman bin ‘Auf mesem-mesem tamvan ala-ala Ivan Lanin itu dan menggeleng. “Wes to, Kang, mengko leh wes wayahe rakyo rabi. Wayahe… wayahe…. wayahe….” (Udah, Kang. Nanti saja kalau sudah waktunya pasti kan menikah.”)
Kini dari catatan sejarah kita mengenal sosok Abdurrahman bin ‘Auf sebagai salah satu sahabat kaya raya yang luar biasa sumbangan hartanya kepada perjuangan Rasul saw. di awal-awal penyebaran Islam—selain sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan tentu pula Ustman bin Affan. Lantas, jelas saja, Abdurrahman bin ‘Auf pun kemudian menikah.
Nah, gimana, sudah lega kini? Sudah jos kan, pembelaan syar’i ini buat kalian jadikan senjata bila masih saja ditanya-tanya ihwal: Mana pasangannya? Kapan nikah, nih? Kok nggak disegerain aja? Nunggu apa lagi sih?
Jawab saja seyes-yeso gini: “Nanti aku akan menikah kalau sudah wayahe… wayahe… wayahe. Sekarang aku mau berbisnis dulu, biar kaya raya, macam Abdurrahman bin ‘Auf!”
Lalu, malamnya, kembali ndermimis di pojokan kos. Duh Gusti, kulo niki saestu pengin sugeh, tapi arep dagangan nopo? Hawong utang-utang mawon do mboten kiat kulo bayar sampe diuber-uber khalayak ngeten je? Nek fuqara’ terus, njuk kapan kulo leh rabi, Gusti? Hamosok ajeng mandiri-manualan terus ngeten?
(Duh, Gusti, saya betul-betul pengin kaya, tapi mau dagang apa? Wong, hutang-hutang saja, saya nggak kuat bayar sampai dikejar-kejar gini? Kalau fuqara’ terus, saya kapan nikah, Gusti? Masak mau sendirian terus gini?)