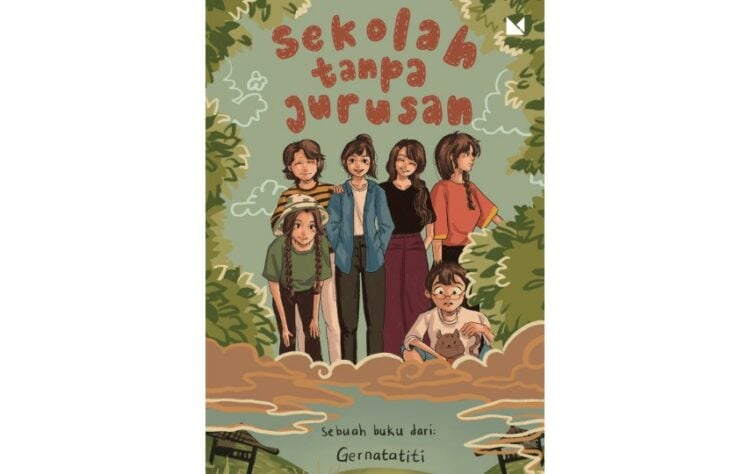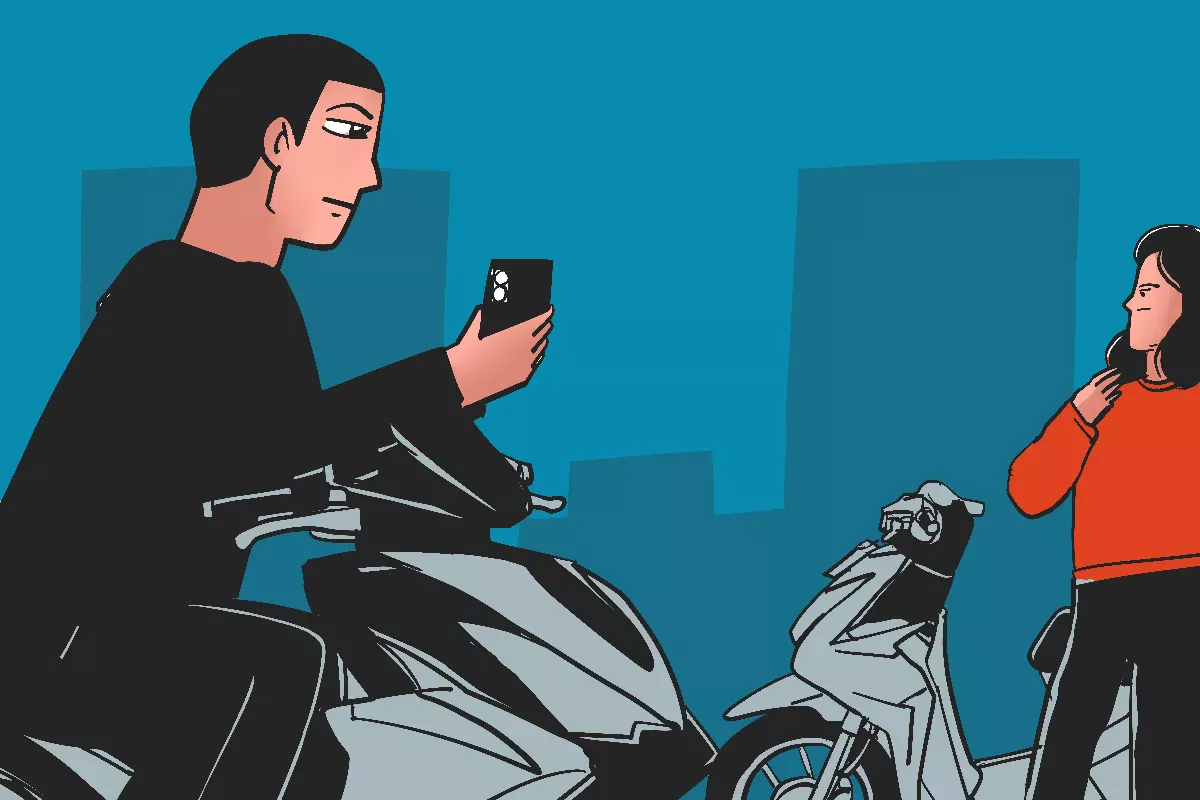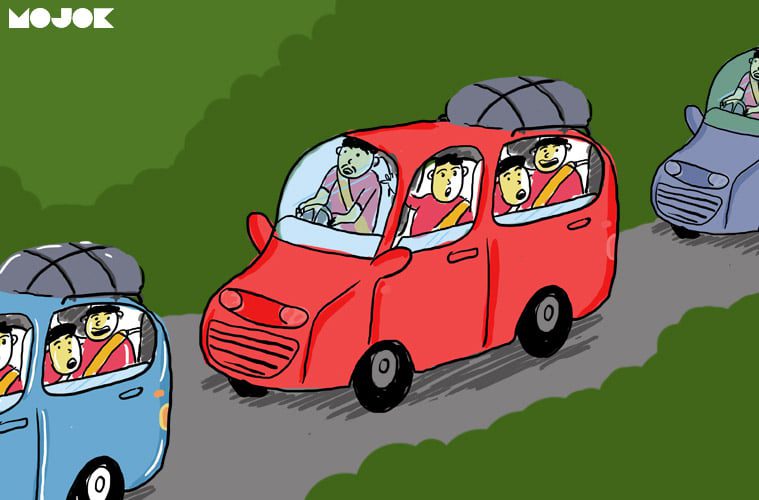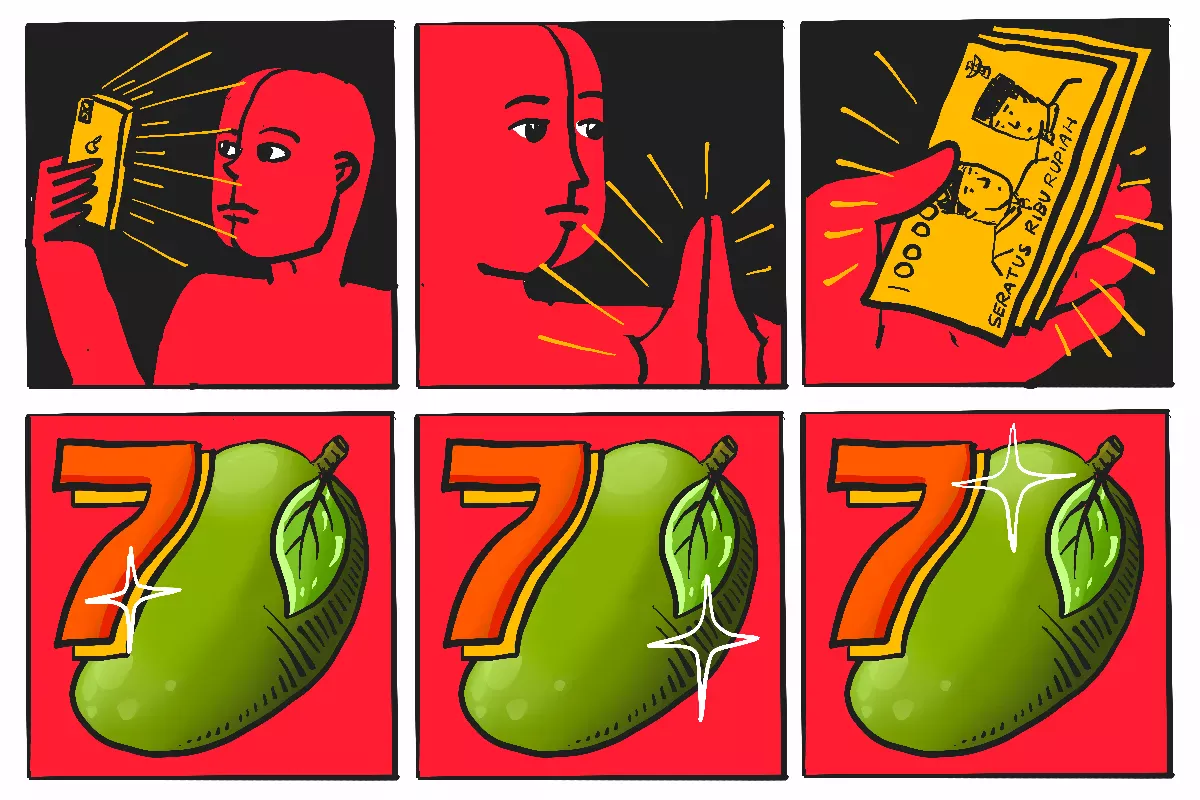Judul: Sekolah Tanpa Jurusan
Penulis: Gernatatiti
Penerbit: Buku Mojok
Ketebalan: 170 halaman
Tahun Terbit: 2022
Buku Sekolah Tanpa Jurusan adalah catatan harian dari seorang fasilitator Sanggar Anak Alam (SALAM) untuk jenjang setara SMA, Gernatatiti. Dalam buku ini, ia bercerita banyak hal tentang SMA SALAM tersebut mulai dari persiapan awal pembentukan, penyusunan kurikulum, hingga tahap pengimplementasian di kelas.
Sekolah Tanpa Jurusan yang diterbitkan oleh Buku Mojok ini dibuka dengan kata pengantar yang bernas dari Roem Topatimasang. Melalui kata pengantar tersebut, kita diajak untuk melihat betapa banyak sejarah peradaban manusia yang tercatat, bermula, atau bahkan berubah secara signifikan berkat keberadaan catatan harian. Salah satunya adalah catatan harian Wallace dan Charles Darwin yang di kemudian hari melahirkan teori yang menggemparkan dunia, dan bahkan masih menjadi topik diskusi hingga hari ini, yaitu penyaringan alami dan daya bertahan pihak terkuat.
Hal tersebut mengingatkan saya pada sebuah nasihat lawas tentang menulis. Bahwa satu-satunya cara untuk bisa menulis adalah dengan berlatih menulis, seburuk apa pun dan sesederhana apa pun tulisan tersebut. Mungkin catatan harian yang kerap kita sepelekan itu, di kemudian hari akan menjadi modal besar dalam membangun kemampuan kita menulis. Atau dalam skala lebih luas, seperti yang dikatakan oleh Roem Topatimasang dalam kata pengantarnya, barangkali catatan harian tersebut dapat menjadi tonggak peradaban dengan caranya sendiri.
Melalui buku Sekolah Tanpa Jurusan, kita akan banyak belajar tentang hal-hal yang mungkin tidak akan kita dapat sekalipun kita sudah mengikuti program wajib belajar 12 tahun yang digaungkan pemerintah. Seperti misalnya pengetahuan sederhana bahwa silabus dan modul sebenarnya adalah sekumpulan cara belajar yang disusun untuk dipraktikkan di kelas oleh pengajar.
Sebagian dari kita hanya tahu bahwa silabus adalah setumpuk kertas tebal yang kerap dikeluhkan oleh para guru, akibat penyusunannya yang rumit dan membutuhkan banyak waktu.
Saya besar di lingkungan pengajar sekolah konvensional. Jadi, saya hafal betul keluhan-keluhan yang ibu saya ucapkan tatkala harus menyusun sejumlah instrumen pengajaran termasuk silabus tersebut. Sekalipun begitu, sebelum membaca buku ini, saya tidak pernah benar-benar memahami bahwa silabus sejatinya adalah cara belajar yang perlu disusun dan diimplementasikan oleh pengajar. Yang saya ingat tentang silabus hanyalah tumpukan kertas yang jadi bahan gerutu ibu saya.
Dari buku ini kita juga akan dibekali pengetahuan tentang bagaimana sebuah kurikulum dirancang. Ia tidak datang dari ruang hampa, melainkan datang dari riset serta konteks yang melatarbelakangi.
Saya tidak tahu riset seperti apa yang dulu digunakan oleh Kemendikbud untuk merancang kurikulum pendidikan formal, tapi rasa-rasanya jika melibatkan siswa, hanya sedikit sekali porsinya. Terlihat dari banyaknya protes yang datang dari siswa maupun orang tua siswa tentang betapa tidak relevannya kurikulum yang sering gonta-ganti nama itu.
Akan tetapi, penyusunan kurikulum untuk SMA SALAM dilakukan dengan menjadikan keingintahuan siswa sebagai fondasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa sejak penyusunannya kurikulum tersebut bersifat partisipatif. Kita juga akan diajari bagaimana melakukan risetnya, cara penyusunan kurikulum, hingga evaluasinya.
Mengingat riset yang dilakukan oleh Gernatatiti dan kawan-kawan dalam penyusunan kurikulum tersebut dilakukan secara mandiri, maka bukan hal yang mustahil jika hal tersebut kita lakukan sendiri untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah untuk apa pun yang kita perlukan.
Salah satu ciri pembeda antara SALAM dengan dengan sekolah konvensional adalah pemberdayaan dan pembentukan nalar kritis. Dalam salah satu esai di bab akhir yang berjudul Merayakan Keberagaman Pengetahuan, Gernatatiti bercerita tentang riset mandiri yang dilakukan oleh anak kelas 5 SD tentang kebiasaan perokok. Dari perjalanan risetnya, ia mampu menyimpulkan bahwa kebanyakan orang menjadi perokok berawal dari rasa penasaran dan iseng untu mencoba. Lalu, ia menyarankan kepada para orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya mencoba rokok, jika tak ingin anaknya tumbuh menjadi perokok.
Sesuatu yang sederhana, tapi nampaknya akan sulit didapat di sekolah konvensional yang gurunya lebih banyak disibukkan dengan perkara administratif.
Ada juga cerita tentang penyusunan rapor yang dilakukan bersama dengan para pelajar. Mereka dapat terlibat aktif dalam penilaian dan evaluasi serta turut memberi sudut pandang terhadap sistem pembelajaran di SALAM.
Setelah membaca buku Sekolah Tanpa Jurusan dan mempelajari perspektif sang fasilitator, saya jadi penasaran, kira-kira seperti apa ya perspektif para pelajar? Apakah mereka kesulitan beradaptasi dengan sistem yang barangkali sangat berbeda dengan sistem sekolah kawan-kawan di lingkungannya? Serta apa yang mereka rasakan, dapatkan, dan mungkin mereka sayangkan dari SALAM?
Meskipun buku ini sangat menarik untuk dibaca, namun tetap ada beberapa hal yang membuat saya tidak nyaman membaca buku ini.
Yang saya rasakan sebagai awam—sebagai produk sekolah konvensional—saat membaca buku ini adalah seperti disalahkan dan dibandingkan. Narasi dalam buku ini seolah benar-benar ingin menegaskan bahwa sistem sekolah egalitarian semacam ini adalah sistem terbaik. Sebagai contoh, banyak penggunaan diksi “berbeda dengan sekolah pada umumnya” dan sejenisnya yang mengawali sejumlah paragraf dalam buku ini.
Saya juga menangkap tendensi Gernatatiti untuk mengkritisi sistem pendidikan di Indonesia yang dalam banyak hal memukul rata karakteristik para siswa, sehingga banyak yang tak mampu tumbuh sesuai panggilan jiwanya. Tentu hal tersebut adalah hal baik, mengingat masih banyak lubang pada sistem pendidikan kita.
Akan tetapi, satu hal yang seolah dilupakan, bahwa dalam beberapa situasi, tidak mungkin mengakomodir semua isi kepala. Apalagi jika kaitannya adalah dengan membangun sistem untuk sebuah bangsa sebesar Indonesia.
Bahkan, dalam buku ini pun, Gernatatiti mengamini hal serupa. Dalam artikel berjudul Membangun Kesepakatan, ia menceritakan tentang menu makan yang tak mungkin menuruti satu per satu selera siswa. Akhirnya, beberapa kali siswa kemudian diminta mengerti dan menghargai makanan apa pun yang tersaji di hadapannya.
Secara keseluruhan, buku ini cukup menarik untuk dibaca khususnya bagi para tenaga pendidik atau inisiator sistem pendidikan. Isinya yang detail dan berupa catatan harian membuat buku ini terasa “nyata” dan dekat dengan keseharian para pendidik.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Kehidupan Setelah Jam 5 Sore, Buku yang Mampu Berikan Pelukan dan Berbagi Beban Kehidupan.