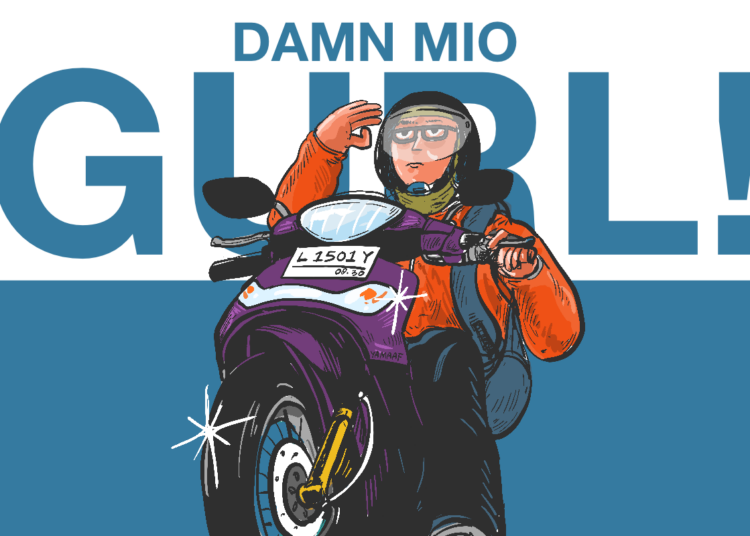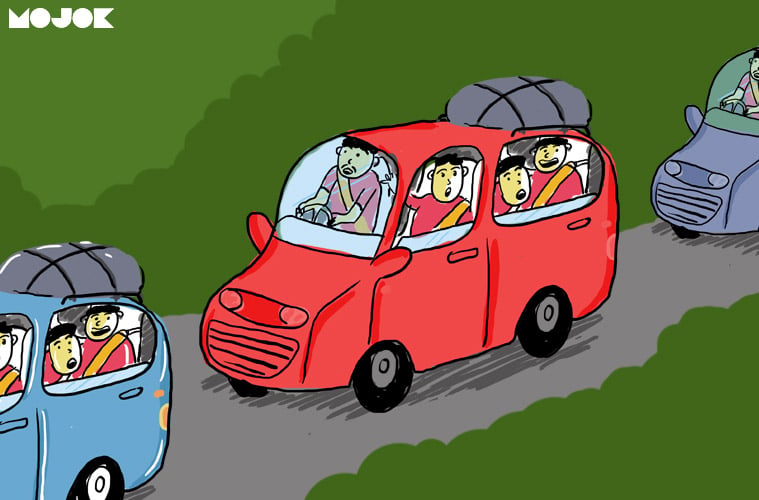Di atas kertas, mungkin rumah subsidi adalah jawaban negara terhadap keresahan kaum urban dan semi-urban: harga tanah melambung, biaya hidup naik, dan gaji masih stagnan. Maka hadirlah solusi berupa hunian murah, katanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi di lapangan, yang terlihat bukan impian yang terwujud, melainkan jebakan yang dirancang rapi.
Saya pernah menyebut rumah subsidi sebagai “penjara waktu”, dan saya masih percaya itu. Sebab ketika seseorang memutuskan untuk membeli rumah subsidi, ia tak hanya membeli bangunan, tapi juga berkomitmen terhadap lokasi, kualitas hidup, dan risiko jangka panjang yang mungkin tidak terbayangkan saat awal akad kredit.
Mimpi murah yang tak murah
Mari kita coba buka tabir kenyataan: banyak perumahan subsidi yang dibangun asal jadi. Tak sedikit yang didirikan di wilayah banjir rutin, bahkan ada yang dalam setahun bisa tiga kali terendam. Lucunya, pengembang tetap bisa menyulap kawasan seperti itu menjadi komplek hunian dengan brosur bertuliskan “asri dan strategis”.
Di sisi lain, ada yang malah dibangun di zona rawan longsor. Jangan tanya kenapa izinnya bisa keluar, kalian tahu sendiri jawabannya.
Tapi, coba bayangkan, rumah dibangun tanpa amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang layak, tapi dipasarkan secara masif ke masyarakat yang tak punya banyak pilihan. Bahkan, ada yang meyakinkan pembeli bahwa longsor itu “jarang terjadi”, seperti menyamakan tanah geser dengan gerhana matahari.
Soal kualitas bangunan? Jangan berharap banyak. Ada rumah subsidi yang tak punya pondasi yang layak. Dindingnya bisa diketuk dan bunyinya lebih mirip kardus daripada bata ringan.
Genteng bocor, septic tank dangkal, bahkan ada yang setelah dua bulan ditinggali, keramiknya mulai copot satu per satu seperti undangan pernikahan yang dibuka paksa.
Dosa kolektif: antara pengembang, negara, dan pembeli yang terdesak
Masalah ini tentu tidak muncul dari satu sisi saja. Ini dosa kolektif. Para pengembang kerap tergiur margin besar dengan cara memangkas biaya pembangunan. Negara, melalui institusi dan bank pelat merah, kadang tutup mata karena proyek perumahan subsidi dianggap “jalan mulia”. Yang penting bisa menggugurkan target.
Sementara itu, calon pembeli juga berada dalam posisi sulit. Dengan gaji pas-pasan dan tekanan sosial untuk “punya rumah sendiri sebelum usia 30”, banyak yang terpaksa ambil rumah subsidi meski sebenarnya belum yakin.
Belum sempat menikmati ruang tamu, mereka sudah pusing atap bocor, pagar miring, atau dinding yang rembes, dinding retak.
Survey bukan formalitas: ini panduan bertahan dari perumahan zonk
Lalu, bagaimana jika kita—seperti jutaan orang lainnya—memang sedang mempertimbangkan rumah subsidi? Apakah semua rumah subsidi jelek? Tidak. Tapi tetap harus waspada.
Survey itu bukan formalitas, melainkan investigasi kecil-kecilan. Nah berikut mungkin beberapa tips biar nggak kejebak. Sila cek halaman selanjutnya.
Baca halaman selanjutnya
Cek riwayat lokasi, infrastruktur, konstruksi, dan legalitas