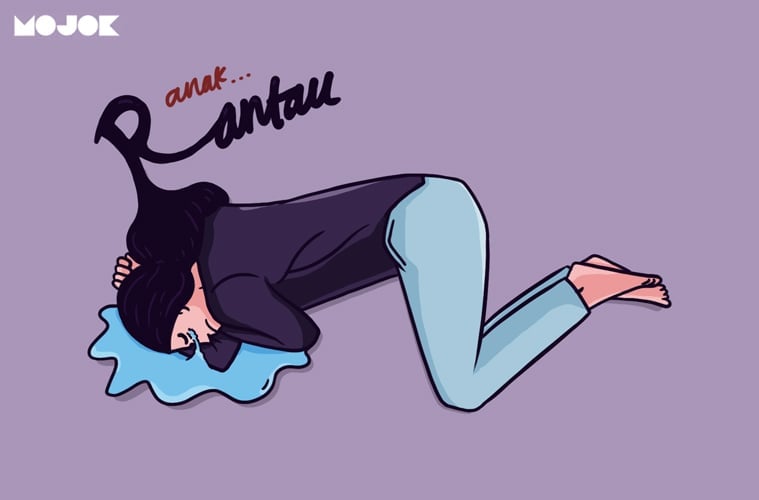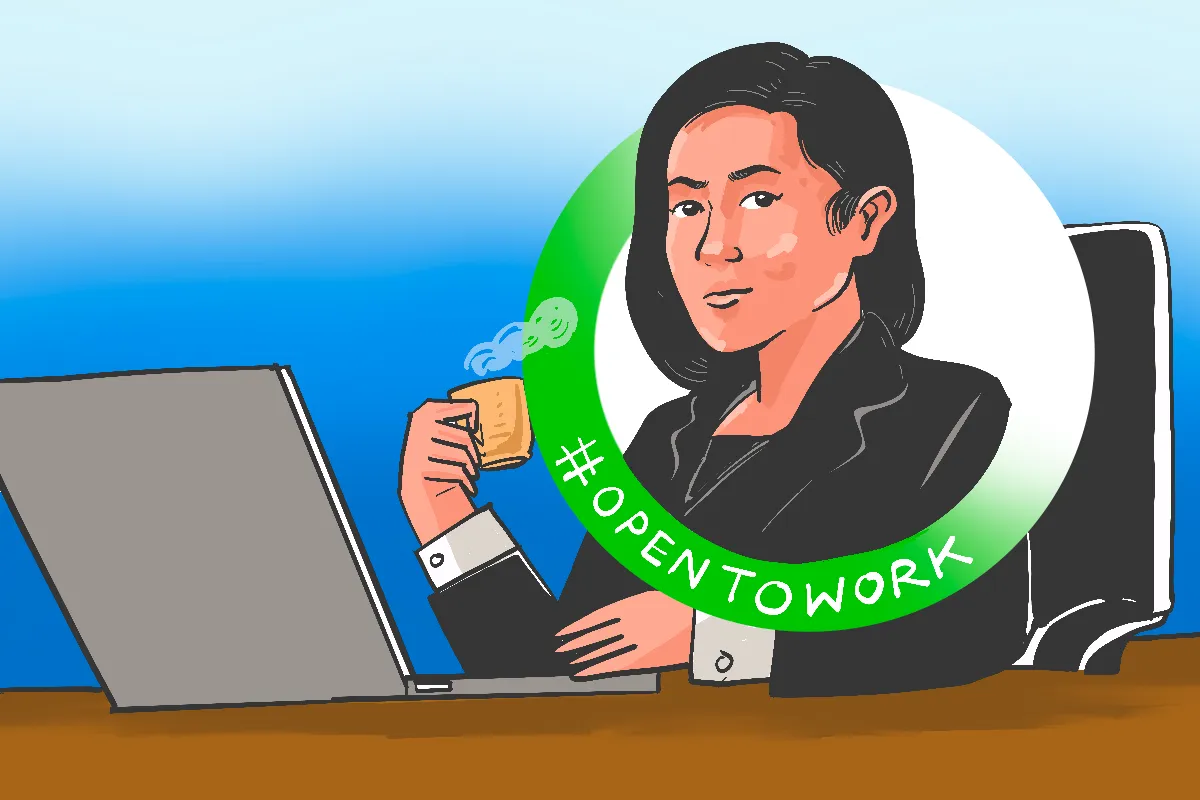Pertama-tama, saya ingin mengawali tulisan ini dengan cerita mengenai hari-hari tenang dan menyenangkan saya sebagai seorang mahasiswa di salah-satu kampus yang ada di Yogyakarta. Hari-hari perkuliahan saya jalani seperti halnya banyak mahasiswa lain; pergi ke kampus di pagi hari, mengerjakan tugas di perpustakaan fakultas, hingga lontang-lantung nggak jelas bersama teman-teman di kantin kampus. Semuanya berjalan indah, damai, dan tentram sebelum datangnya berita menyesakkan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) kilat yang dikebut jadi oleh DPR untuk mengamputasi kewenangan KPK.
Awalnya saat itu saya masih berfikir bahwa semuanya akan tetap berakhir baik. Dengan logika waras paling sederhana sekalipun. Rancangan Undang-Undang non-sense yang dikebut hanya dalam waktu tiga minggu tersebut akan ditolak persetujuannya oleh Presiden Jokowi. Saya yakini betul pada waktu itu, bahwa itulah yang akan dilakukan oleh beliau. Akan tetapi apa boleh dikata, harapan selamanya tetaplah harapan. Apalagi harapan tinggi yang dilekatkan pada pundak seorang politikus. Ia pupus, menyumblim jadi abu di udara dalam ruang panas lobi-lobi politik dan kekuasaan.
RUU sampah yang mengamputasi kewenangan KPK tersebut pun—satu-satunya lembaga produk reformasi yang paling dipercaya publik—akhirnya pengesahannya disetujui juga oleh sang presiden yang saya percaya dan banyak orang lainnya sebagai “orang baik”. Mulai dari situ lah benih-benih kekesalan, kekecewaan, dan merasa dikhianati muncul dalam diri saya.
Saya yang sebelumnya adalah seorang mahasiswa yang cenderung apatis terhadap aksi massa dan demonstrasi. Akhirnya untuk pertama kalinya menutuskan ikut turun ke gelanggang aksi. Menyatakan sikap, penolakan, dan protes keras bersama teman dan banyak civitas akademika lain di balairung kampus. Serta tak lupa, beberapa saat setelahnya juga turut melakukan aksi turun ke jalan bersama organisasi kemasyarakatan anti-korupsi lain.
Kenyataan yang menyakitkan itu ternyata baru awal. Rentetan remuk redam dan kekecewaan lain ternyata sedang menunggu di belakang sana. Mulai dari pengesahan RUU Pemasyarakatan yang bikin geleng-geleng kepala dan koruptor bersorak senang. Tak kunjung diselesaikannya RUU urgen seperti RUU PKS, hingga rencana pengesahan RUU KUHP baru yang banyak pasal di dalamnya dipercaya akan mengebiri kekebasan demokrasi dan berekspresi setiap individu warga negara.
Lengkap sudah sekarang perasaan antara marah, kecewa dan merasa dikhianati beramai-ramai oleh para elite politik. Dalam hati sampai-sampai saya berfikir, elite-elite politik dan para bedebah oligark itu sudah semakin berani dan kurang ajar ingin merampas hak-hak publik dan warga negara. Dan ini tak bisa lagi didiamkan terus menerus. Ini wajib dilawan, pikir saya dalam hati.
Layar pun bersambut, sejak hari itu juga saya putuskan untuk total turun ke gelanggang perjuangan untuk menolak pengesahan UU dan RUU bermasalah tersebut. Saya gencar betul koar-koar di media sosial, menulis artikel untuk mengkritik kebijakan tersebut, mengajak banyak teman untuk ikut turun ke jalan. Dan dari situ lah awal mula munculnya masalah baru yang menimpa diri saya yang ternyata juga tak kalah menyesakkan dengan masalah-masalah yang sudah saya sebut di atas tadi, yakni amuk amarah dan renggangnya hubungan baik saya dengan kakak.
Renggangnya hubungan baik dengan kakak
Kakak saya seorang anggota Brimob, ia seorang polisi. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja mengirim pesan WhatsApp kepada saya. Isi pesannya tak seperti biasanya, pesannya kali ini tidak berisi pertanyaan-pertanyaan macam, “bagaimana kabar saya?” ataupun “bagaimana kabar kuliah saya?”. Pesannya kali ini berisi tentang maklumat larangan pada saya untuk tak usah ikut-ikut aksi demonstrasi lagi.
Baginya, demo yang sedang banyak dilangsungkan oleh mahasiswa dan banyak elemen masyarakat sekarang lebih banyak bersifat merusak dan anarkistis. Tak lupa ia juga mengirimkan video yang menunjukan perilaku pengrusakan dan penyerangan kepada para petugas kepolisian yang ada.
Saya, yang kebetulan memang mengikuti aksi demonstrasi #GejayanMemanggil yang dilangsungkan di Jogja kemarin. Dan senantiasa mengupdate perkembangan situasi yang ada di Jakarta pun membalasnya dengan argumen bahwa pihak kepolisian terkadang juga sudah berperilaku represif kelewat batas dalam hal menangani demonstrasi yang ada.
Sebagai seorang kakak, tentu saja ia marah melihat bantahan argumen dari adiknya. Barangkali egonya terkoyak pada waktu itu, barangkali hati kecilnya sakit melihat begitu banyak media dan orang yang mendiskreditkan instiusi yang ia cintai atau barangkali juga ia khawatir dengan keselamatan saya sendiri. Intinya saya tahu kalau hati kecilnya sedang kacau balau waktu itu.
Ia lalu mengirimkan lagi beberapa video dan laporan lagi dari teman-temannya yang sedang bertugas di Jakarta sana. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kakak saya kebetulan tidak sedang bertugas di sana. Yang lalu diikuti dengan berbagai rentetan ceramah dan argumen bantahan yang tak henti-hentinya.
Awalnya saya masih berupaya menahan diri untuk tak meladeni tudingan-tudingannya tersebut. Saya tahu betul posisi kakak, tahu betul posisi teman-temannya yang sedang bertugas. Mereka hanyalah polisi dengan pangkat rendah yang bergerak karena melaksanakan perintah atasan.
Doktrin yang ditanamkan dalam otak dan benaknya jelas. Kepentingan negara, negara, dan negara adalah yang utama. Sedangkan bagi saya sendiri, menjadi tergerak dan bergerak karena panggilan nurani kecil sebagai seorang terpelajar. Panggilan yang bagi saya adalah panggilan kemanusiaan dan keadilan yang sudah tak mungkin lagi bagi saya untuk pura-pura tak dengar, masa bodoh, dan terus bungkam.
Intinya, saya sadar betul bahwa sejak awal ia dan teman-temannya memang dididik untuk berperilaku, berfikir, dan bertindak secara taktis dan siap menerima perintah dari garis komando yang ada. Tanpa bantahan dan sanggahan.
Saya paham sebab-sebab yang mendasari itu semua. Dan oleh karena itu pula, saya dalam posisi dilema betul sekarang. Dulu, waktu kecil kami memang sering bertengkar sebagai dua orang bocah. Tapi kali ini pertengkaran kami lain, kami sekarang sudah sama-sama dewasa, dan rasa-rasanya tak pernah pertengkaran yang terjadi di masa kecil itu rasanya sesakit ini. Saya sadar, kini kami dipisahkan oleh daya nalar, latar belakang argumen, serta tugas dan visi yang amat berbeda dalam melihat kebenaran.
Saya berjuang untuk menyelamatkan ruang-ruang demokrasi yang hendak dikebiri, serta sekuat mungkin melawan oligarki politik meraja rela. Sedang ia, polisi yang melaksanakan tugas negara dengan mengikuti panggilan tugas dari apa-apa yang sudah ia sumpahkan.
Tak ada yang salah di sini. Yang jelas salah adalah, para bedebah-bedebah elite politik dan para penguasa oligarki yang ada di balik ini semua. Yang tertawa di kursi emas singgasananya. Yang mengharuskan kami, dua saudara sekandung untuk saling hantam di medan perjuangan yang amat berlawanan. Semoga saja doa tulus dari ibu bisa senantiasa menyelamatkan kami. Dari amukan api yang mungkin saja bisa membakar kami berdua menjadi abu dalam kemarahan. Semoga saja. (*)
BACA JUGA Apabila Widji Thukul Tiba-tiba Muncul dan Baca Puisi di Tengah Demo Mahasiswa atau tulisan Mustaqim Aji Negoro lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.