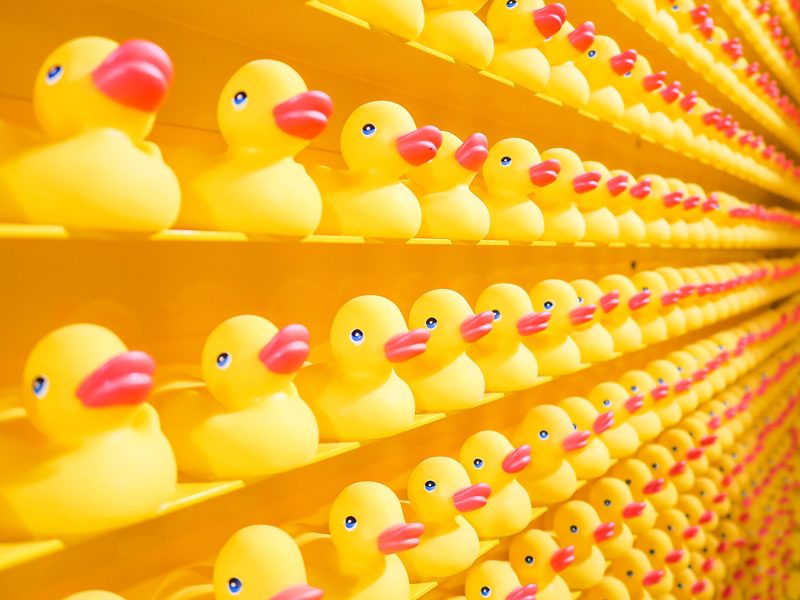Bicara soal masalah kesehatan mental, sering dapat membuat kita terlalu cepat menyimpulkan dan menggeneralisir. Misalnya, kita dengan cepat menyimpulkan bahwa ada pihak “sakit” yang perlu disembuhkan, dan ada pihak yang selalu dapat menjadi penyembuh. Contohnya dalam konteks bergereja. Sebagian besar orang beranggapan, pihak yang bermasalah pastilah jemaat, sedangkan sang pemecah masalah adalah pendeta. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.
Banyak pendeta yang bukan hanya berposisi sebagai konselor, namun juga di kesempatan lain menjadi konseli dalam suatu proses konseling. Sayangnya, permasalahan para pendeta memang kerap dianggap tabu untuk dibicarakan.
Alhasil, ada pendeta yang sampai memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan masalah yang dihadapi. Jarrid Wilson, misalnya. Ia adalah pendeta di sebuah gereja besar di Riverside, Amerika Serikat. Ia juga kerap menyuarakan isu kesehatan mental dalam pelayanan kesehariannya. Siapa sangka, Jarrid memutuskan untuk mengakhiri hidup di tahun 2019.
Hal tersebut tentu menjadi pelajaran mahal bagi para hamba Tuhan yang masih aktif dalam menjalankan tugasnya. Para hamba Tuhan ini sering abai mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental yang menjangkitinya. Mudah emosi, stres-stres kecil, pikiran tidak jernih, dan memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan matang, menjadi tanda yang patut diwaspadai. Pun demikian dengan pemicu-pemicu yang kerap membuat para pendeta mengalami gangguan kesehatan mental tadi.
Dengan berbekal pengalaman para pendahulu, setidaknya seorang pendeta dapat memetakan beberapa pemicu yang berpotensi menganggu kesehatan mental mereka.
#1 Panggilan hidup (life calling) yang tidak jelas
Sudah menjadi rahasia umum kalau ada orang yang masuk sekolah kependetaan bukan karena panggilan hidup. Mungkin dulunya masuk sekolah teologi karena gereja menyediakan beasiswa, atau mungkin juga karena tidak diterima di jurusan-jurusan umum universitas lain. Anggapannya, melanjutkan studi di sekolah teologi lebih mudah dan tidak ribet untuk dijalani.
Saat terjun langsung di dunia pelayanan, kenyataan tidak selalu sesuai dengan teori di bangku pendidikan. Akibatnya, ia akan berpikir ulang tentang jalan hidupnya dan bisa saja meninggalkan jalur kependetaan.
#2 Keinginan tampil sempurna
Nah, pemicu yang satu ini juga sering membuat seorang pendeta stres. Betapa tidak, seorang pendeta dituntut cakap mengajar, fasih berkotbah, perhatian kepada jemaat tanpa membedakan, dan menjadi personifikasi gereja bagi kalangan luar. Tuntutan-tuntutan itu memang wajar, dan seorang hamba Tuhan sudah paham mengenai hal tersebut.
Namun, tidak semua hal bisa berjalan sempurna. Contohnya saya. Ada kalanya saya kekurangan waktu untuk persiapan berkhotbah, sehingga jemaat merasa “kurang kenyang”. Ada kalanya saat jemaat datang meminta bantuan doa, saya justru tidak berada di pastori.
Hal-hal semacam itu bila tidak ditanggulangi, akan berujung pada rasa bersalah yang berkepanjangan.
#3 Permasalahan jemaat
Secara umum, jemaat terdiri dari bayi, balita, anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, keluarga, dan lansia. Walau dibantu oleh para majelis, penatua, diaken atau apa pun istilahnya, tetap saja seorang pendeta harus—setidaknya—mendengar dan tahu, bila terjadi masalah.
Dan yang sering bikin pusing justru adalah masalah antarjemaat. Misalnya, si A bermasalah dengan si B. Perkara yang personal ini kemudian bisa berkembang menjadi komunal, melibatkan keluarga A dan B, melibatkan pihak-pihak yang membela si A dan si B. Padahal permasalahan tersebut berawal dari hal sederhana, semisal tidak mendengar ketika disapa, atau terlewat saat bersalaman.
#4 Permasalahan organisasi/sinode
Pendeta suatu gereja tentu terikat dengan sinode tempat gereja tersebut bernaung. Meski tidak semua pendeta tergabung secara struktural dalam kepengurusan organisasi, namun ada saja potensi masalah yang bisa timbul gara-gara masalah organisasi.
Misalnya nih, saat ada pendeta di suatu daerah yang meninggal dunia, siapa yang akan menggantikannya? Mau tak mau, organisasi harus turun tangan.
Masalahnya, apakah pendeta pengganti langsung bisa cocok dengan jemaat yang dibina oleh pendeta terdahulu? Belum tentu. Bisa saja jemaat membuat laporan ke sinode dan hal tersebut menimbulkan ketegangan hubungan antara pendeta dan jemaat, maupun dengan sinode.
#5 Permasalahan keluarga
Inilah salah satu perbedaan antara pastor/romo dengan pendeta. Bila pastor/romo hidup selibat (tidak menikah), maka pendeta diperbolehkan untuk menikah.
Adanya keluarga tentu menjadi elemen pendukung dan penguat bagi kehidupan dan pelayanan seorang pendeta. Tapi jangan salah, ada juga hamba Tuhan yang justru stres karena masalah keluarga.
Misalnya, saat pendeta harus melayani jemaat, namun sang istri justru keluyuran ke tempat lain dan tidak mendampingi. Atau, saat ada anak pendeta yang nakal, dan kemudian menjadi bahan pergunjingan jemaat.
Tentu hal tersebut menjadi tekanan tersendiri dalam kehidupan seorang pendeta. Ibaratnya, orang akan berkata, “Keluarga sendiri saja tidak bisa dibina, lha kok mau membina jemaat?”
Itulah beberapa pemicu yang berpotensi menghadirkan gangguan kesehatan mental bagi seorang pendeta.
Keterbukaan terhadap masalah diri sendiri, berbicara dengan orang yang tepat, dan berdamai dengan kekurangan diri sendiri, dapat menjadi penolong bagi seorang pendeta, untuk menyelesaikan panggilan hidupnya sampai “garis akhir”.
Masalahnya, kita tidak pernah tahu garis akhir itu masih seberapa jauh. Yang pasti kita terus berjalan, dan bila lelah, tak ada salahnya beristirahat sejenak.
Penulis: Yesaya Sihombing
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Hal-hal yang Sering Dibicarakan para Pendeta Saat Kumpul Bareng.