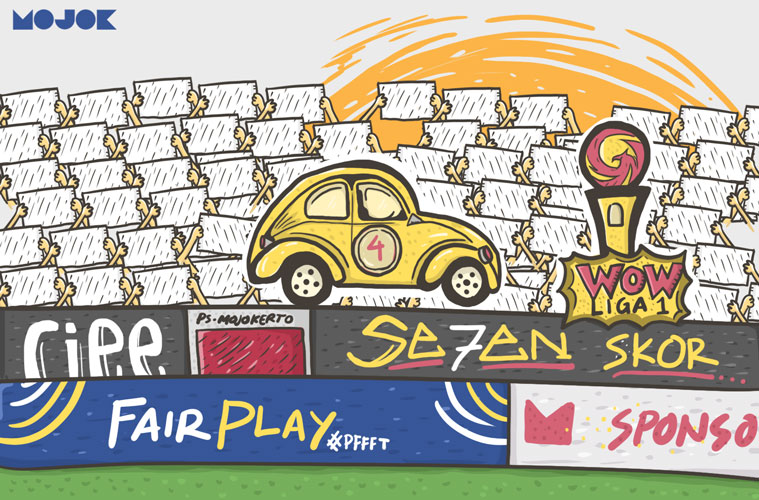Lebaran kemarin, saya —ehm, lebih tepatnya istri saya— membeli sebuah televisi dengan ukuran layar yang cukup besar dengan resolusi yang mumpuni.
“Ini tivinya mantep, Bos. Buat nonton dangdut bisa sampai kelihatan komedo penyanyinya,” canda petugas toko elektronik yang mengantar dan menginstall televisi tersebut di rumah saya.
Sejak punya televisi, tentu saja saya jadi lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi. Ini saya anggap sebagai semacam balas dendam masa lalu, sebab sebelumnya, saya belum pernah punya televisi sebesar ini.
Dengan televisi baru ini, saya jadi lebhih keranjingan menonton film-film Netflix. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini di mana gedong film semuanya libur tidak beroperasi.
Hanya saja, saya memang punya kebiasaan yang ganjil. Walau banyak film baru dan update di Netflix, namun tetap saja saya lebih suka menonton film yang sudah pernah saya tonton sebelumnya, berkali-kali.
Salah satu film yang sangat rutin saya tonton ulang berkali-kali adalah The Godfather. Film legendaris garapan Mario Puzzo dan Francis Ford Coppola benar-benar tak pernah membuat saya bosan untuk terus menontonnya.
Satu hal yang selalu membuat saya takjub pada film mafia tersebut tentu saja tentang drama kekeluargaan yang penuh dengan pembunuhan. Betapa para mafia, bisa sangat dekat dengan keluarga dan kawan-kawan serta musuhnya. Bisa berkumpul bersama saling tertawa dan saling peluk, namun dengan mudah berganti menjadi konflik untuk kemudian saling bunuh antar sesamanya.
Mereka bisa bertemu seseorang, berbincang selayaknya kawan lama, untuk kemudian membunuhnya sehari setelahnya.
Adalah sebuah fragmen yang sentimentil ketika seorang Michael Corleone tega membunuh Fredo, kakak kandungnya sendiri. Padahal tak terhitung berapa adegan yang memperlihatkan pesan betapa dalam keluarga Corleone, kekeluargaan adalah segalanya.
Di The Godfather, rasanya menjadi hal yang sangat biasa ketika seorang mafia membunuh mafia lainnya hanya karena perselisihan prinsip atau urusan bisnis yang tidak menemui jalan kesepakatan mufakat. Sungguh sangat tidak Pancasila.
“Kok bisa ya, Lis, mafia-mafia itu dengan entengnya membunuh rekan bisnisnya, padahal mereka sebelumnya kekancan erat lho,” kata saya suatu ketika kepada Kalis istri saya yang sedang asyik membaca buku di sebelah saya yang sedang asyik menonton film.
“Ya nggak tahu, mungkin sudah kebiasaan,” kata Kalis dengan nada yang malas. Jawaban basa-basi yang tentu saja tidak memuaskan saya.
Kelak, pertanyaan kecil namun menggelitik itu menemukan sedikit jawaban melalui raket nyamuk yang saya beli beberapa hari yang lewat.
Saya memang sudah sejak lama ingin membeli raket nyamuk sebab nyamuk-nyamuk di rumah saya semakin hari semakin brutal saja. Bunyi dengung mereka benar-benar menganggu waktu jenak saya saat menonton film.
Mereka, nyamuk-nyamuk tak tahu diuntung itu seakan memang sengaja menggoda dan menguji kesabaran saya dengan terus terbang di sekitar telinga saya.
Seminggu dua minggu, saya masih sanggup. Namun selebihnya, kesabaran saya pun mencapai batasnya. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli raket nyamuk dan menghajar mereka tiap kali mereka berulah dengan terbang rendah di dekat telinga saya.
“Pretak!… Pretak!… Pretak!…” Bunyi tersebut kini mulai akrab di telinga saya seiring dengan ayunan raket nyamuk saya. Ada semacam kepuasan tiap kali saya bisa menghajar para nyamuk itu.
Saking asyiknya, saya sampai sengaja mencari nyamuk di mana pun ia berada. Saya jadi rajin menyibakkan pakaian yang digantung di dekat lemari. Sesekali saya bergerilnya di sekitar dapur. Semata demi bisa men-smash para nyamuk tak tahu diuntung itu.
Terkadang, tak ada nyamuk, ngengat-ngengat kecil pun saya sikat pula.
Istri saya sampai dibikin heran dengan kebiaasaan saya tersebut, hingga pada suatu ketika, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat batin saya bergejolak. “Kok bisa tho, Mas, kamu suka banget bunuhin nyamuk-nyamuk itu?”
Pertanyaan tersebut tentu tak ada bedanya dengan pertanyaan saya tentang para mafia yang bisa dengan mudahnya membunuh kawan dan lawannya itu.
Pada akhirnya, pencerahan itu datang. Jawaban atas pertanyaan saya itu hadir di hadapan saya.
Saya dan para mafia itu kelihatannya punya satu kesamaan. Suka dan tega membunuh siapa saja yang kami anggap menganggu. Hanya beda tingkatan gangguannya saja.
Bagi para mafia, gangguan adalah mereka yang mengusik bisnis mereka. Sedangkan bagi saya, gangguan adalah mereka yang terus terbang sambil mendengung di sekitar telinga saya.
Para mafia mungkin menganggap aktivitas membunuh mafia lainnya itu adalah hal yang biasa saja, sama seperti saya yang menganggap membunuh nyamuk-nyamuk yang mengganggu hari-hari saya itu biasa juga.
Saya puas. Sebab pertanyaan saya sedikit mendapatkan pencerahan. Walau saya juga merasa sentimentil, sebab pada titik itulah, saya harus mengakui, bahwa saya adalah seorang pembunuh juga.