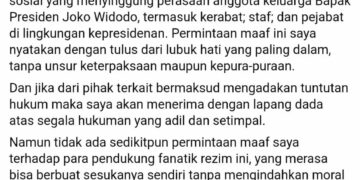MOJOK.CO – Kepercayaan soal setan yang menempel di berhala memang ada, dalam istilah Ustaz Abdul Somad disebut “jin kafir”. Iya, memang ada dasarnya.
Sebagai keluarga dengan latar belakang pesantren cukup kental, saya “beruntung” dimasukkan ibu saya ke sebuah SD negeri. Tidak seperti 9 kakak saya yang masuk ke sekolah Islam sedari SD, dari yang madrasah ibtidaiyah di pesantren sampai SD islam swasta. Cuma saya sendiri yang SD-nya sekolah negeri.
Dari sekolah negeri ini pula saya jadi punya banyak sekali sahabat beda agama. Dari Hindu, Kristen, dan Katolik. Dan—harus diakui—ketika pertama kali berkenalan seorang teman yang berbeda agama, ada perasaan heran (saat masih kelas 1 SD), oh jadi si A itu Kristen, oh si B itu Katolik, dan sebagainya.
Saya juga jadi terbiasa main ke rumah teman saya yang Kristen atau Katolik, lalu dan untuk pertama kalinya, menyaksikan hiasan patung salib di rumah, atau melihat gambar dan patung di rumah teman saya yang Hindu. Bahkan juga kadang diajak main petak umpet di gereja. Hal yang kalau muncul fotonya saat ini, bisa jadi saya akan dianggap sebagai korban kristenisasi.
Persinggungan sejak kecil kayak gini bikin saya tak pernah masalah ketika bertemu salib atau masuk gereja saat ini. Patung Yesus atau salib bagi saya biasa saja. Tapi jangan salah, hal ini berbeda dengan anggota keluarga saya yang lain.
Mau setoleran apa pun, ketika seseorang yang sejak kecil tak terbiasa menyaksikan patung Yesus atau lambang salib, wajar belaka kalau ia akan merasa agak risih. Alasannya sederhana: nggak terbiasa. Itu pengalaman yang jarang dialami. Melihat salib, masuk gereja, atau bahkan melihat patung Yesus adalah sesuatu yang aneh.
Maka ketika ada seorang jamaah bertanya ke Ustaz Abdul Somad. “Apa sebabnya Ustaz, kalau saya menengok salib lalu menggigil hati saya?” itu wajar belaka. Lumrah. Dugaan saya, sepanjang hidup si penanya nggak pernah akrab bersinggungan dengan simbol agama lain—terutama lambang salib.
Dugaan ini muncul karena pertanyaan dari jamaah ini juga pernah saya alami. Bukan dengan salib, melainkan ketika ikut malam Waisak di Candi Borobudur untuk liputan beberapa tahun lalu.
Saat itu suasana Borobudur begitu ramai dengan biksu, di telinga saya rapalan-rapalan doa dari para biksu yang datang dari penjuru dunia benar-benar mengintimidasi. Hati saya bergetar mendengarnya. Entah karena takut, entah karena takjub. Satu hal yang saya tahu, saya merasa tidak betah.
Ini jelas berbeda ketika saya mendengar nyanyian-nyanyian di gereja atau bertemu dengan para suster di dekat rumah teman saya ketika kecil. Karena sudah terbiasa, saya biasa saja. Betah-betah saja. Jadi kesimpulan sementara saya, saya tak betah ya karena saya tak terbiasa ketika mendengar doa rapalan para biksu yang menggetarkan itu.
Oleh karena itu, ketidakbetahan itu, tidak serta-merta saya sandarkan dengan model jawaban Ustaz Abdul Somad. Yang langsung menjawab, “itu setan,” tanpa memberi elaborasi terlebih dahulu kepada jamaah yang bertanya. Atau tanpa perlu mengaitkan perkara “berhala” itu pada agama tertentu di Indonesia.
Tapi pertanyaannya, apakah yang dikatakan Ustaz Abdul Somad itu memang ada dasarnya? Maksudnya memang pernah ada ulama terdahulu membicarakan ini?
Baiklah, saya tidak ingin memperkeruh suasana, melainkan hanya memberi pandangan bahwa apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad bisa dicek, misalnya, di kitab Minan Al-Kubro karya Imam As-Sya’roni.
Sebenarnya sih penjelasan di kitab itu justru lebih ekstrem lagi. Bahwa setan merupakan pihak yang menggoda manusia untuk menyembah berhala karena memang ia masuk ke sana (entah patung, entah simbol). Hanya saja—ini yang jadi masalah bagi Ustaz Abdul Somad—harusnya tak perlu diterangkan “berhala” tersebut adalah berhala dari agama apa, kepercayaan mana, dan dari penganut apa.
Saya pun, sedari ikut taman pendidikan Al-Quran (TPA) anak-anak sampai kemudian ngaji di pesantren, sudah tahu ada kepercayaan soal setan “menempel” di berhala (atau patung) seperti itu ada di agama saya. Bedanya, guru ngaji saya dulu tidak pernah secara spesifik menyebut berhala yang dimaksud itu merujuk pada agama apa. Sehingga sentimen terhadap agama lain tidak muncul.
Hal ini ditambah dengan pergaulan saya di SD. Sudahlah saya terbiasa melihat patung Yesus atau salib, main ke gereja pula—saya jelas tidak sebodoh itu bilang kalau di kepercayaan agama saya ada keyakinan bahwa berhala-berhala itu ada setan-nya ke teman saya. Sebab, meski itu keyakinan saya, tapi itu tak berarti memberi saya hak bicara seperti itu ke mereka.
Rasa sensitif atau tidak semacam ini bisa muncul karena sepele: pergaulan. Kalau saya hanya berteman dengan teman-teman yang seiman, kepekaan semacam itu tentu tak bakal ada. Bisa saja saya enteng menyebut apa yang saya percayai di hadapan mereka.
Beruntung sekali, sedari kecil saya sudah bergaul dengan teman-teman beda agama, jadi saya paham apa yang sensitif menurutnya dan apa yang tidak. Bahkan kami sering bercanda soal agama kami masing-masing, tapi tak pernah tuh sampai sakit hati—karena kami paham di bab apa saja teman saya bisa tersinggung dan di perkara apa saya bisa tersinggung.
Hal kayak gini sebenarnya tidak melulu persoalan agama, tapi juga kehidupan sosial. Misalnya, kamu cuma mau tinggal di rumah, tak pernah kenal tetangga-tetangga, hidup cuma di kamar doang, ya wajar kalau ketika ada ajakan gotong royong kamu merasa tak masalah tak ikut. Padahal bagi warga lain perilakumu kayak gitu bisa bikin sakit hati—meski kamu tak bermaksud bikin sakit hati. Inilah yang dinamakan matinya kepekaan.
Persoalan Ustaz Abdul Somad dan jamaah yang bertanya sebenarnya hanya pada: kurang gaul dengan sahabat-sahabat beda agama. Wajar kalau sensitivitas mereka jadi tidak ada. Karena rasa sensitif itu tidak ada, maka tak heran kalau masih ada saja pihak-pihak yang merasa Ustaz Abdul Somad tak perlu minta maaf.
Hal kayak gini jelas bukan persoalan apakah forum itu tertutup atau tidak, pengajiannya hanya terbatas atau tidak, tapi ini soal rasa menghormati kepercayaan umat agama lain. Mau itu di tempat tertutup atau terbuka, bicara secara spesifik ke agama tertentu jelas perkara yang tidak elok.
Malah, ketika itu diakui sebagai forum tertutup, justru lebih bikin sakit hati lagi. Ya iya dong, ini kan kayak kamu mergokin orang lain lagi bicara tentang kejelekanmu secara diam-diam.
Masa iya, begitu kamu kepergok kamu cuma bilang, “Ini forum tertutup kok. Kami membicarakan hal-hal jelek soal kamu, tapi kan tadi kamu tadi nggak tahu. Ya nggak apa-apa dong. Kan tadi waktu kita ngomong kamu nggak tahu.”
Lha kok enak?
BACA JUGA Benarkah Asap Sate Babi Najis?