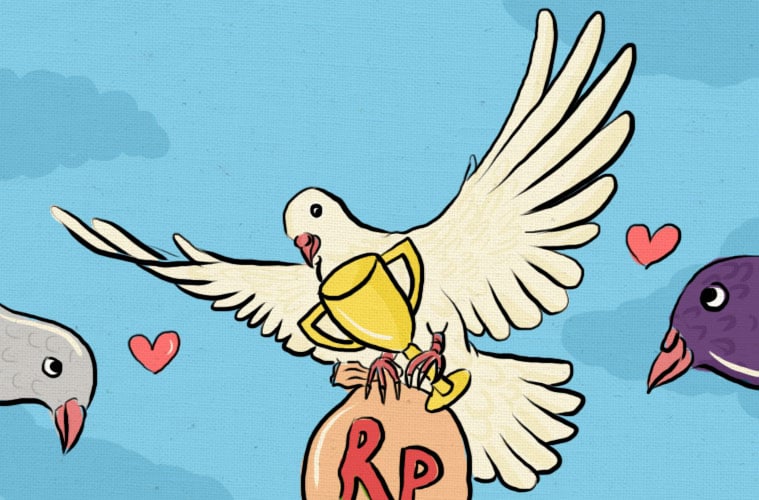Dulu di zaman kuliah—masa aktif-aktifnya di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM/Persma), Hari Pers Nasional selalu memberi suntikan energi besar bagi Delano, bukan nama asli, untuk meniti “jalan perjuangan jurnalisme”: menjadi seorang wartawan/jurnalis di media pers.
Bahkan, di awal kariernya menjadi seorang wartawan/jurnalis, semangat itu masih membara dalam dirinya. Entah kenapa, “wartawan/jurnalis” terasa menjadi atribut keren yang melekat dalam dirinya. Bahkan dia selalu bangga ketika menuliskan “wartawan” di kolom “profesi” KTP.
Namun, realitas hidup sering kali tidak sejalan dengan gambaran ideal di kepala seseorang. Termasuk bagi Delano. Di usianya yang menjelang 30-an tahun, dia toh tidak beranjak ke mana-kemana. Karier stuck, gaji stuck, hingga harus menahan sakit hati karena cap “gagal”, bahkan dari keluarga sendiri.
Bayangan keliru soal wartawan/jurnalis: profesi keren, pasti gaji tak main-main
Delano tidak menampik bahwa motifnya menjadi seorang jurnalis sebenarnya berkelindan antara dua hal: pengaruh ketokohan dan pelarian dari tujuan utama yang gagal tercapai.
Pengaruh ketokohan: ada sosok-sosok hebat dalam dunia jurnalisme kita. Sebut saja Najwa Shihab. Bekerja dengan nurani demi membela kepentingan publik, terdengar amat luhur dan keren bagi Delano.
Pelarian: Delano sebenarnya lebih ingin menjadi seorang kolomnis atau esais. Namun, berkali-kali tulisannya ditolak media massa, pada akhirnya menjadi wartawan/jurnalis adalah pilihan yang lebih masuk akal: karena basic-nya sama-sama menulis. Toh dia sudah terbiasa menulis berita bekal yang dia dapat dari gabung dengan LPM/Persma.
“Maka bayanganku, gaji yang bakal diterima juga nggak recehan. Karena di masaku itu wartawan dipandang sama aja kayak pekerja kantoran,” ungkap Delano, Senin (9/2/2026) malam.
Ditambah lagi, pemuda asal Jawa Tengah itu terpengaruh oleh film-film dengan tema “jurnalisme”. Digambarkan betapa kerennya profesi seorang pewarta itu, dan tampak tidak ada keluh kesah soal gaji rendah.
Realitas wartawan/jurnalis di media pers daerah, keren enggak gembel iya
Delano menelan ludah ketika memulai kariernya di sebuah media pers online kecil di Jawa Tengah pada awal 2019. Bagaimana tidak. Gambaran gaji yang bakal dia terima: Rp15 ribu perberita, dengan beban harian 4 berita dan waktu kerja Senin-Sabtu (6 hari kerja).
Namun, Delano sudah kepalang bingung. Sejak zaman kuliah terlanjur lebih fokus di LPM/Persma, tidak mengembangkan skill lain. Hanya skill menulis dan memberitakan saja yang dia punya.
“Rp15 ribu kali 4 berita Rp60 ribu. Jika dikali sebulan (pakai asumsi full kerja) itu saja cuma dapat Rp1,8 juta,” ungkap Delano.
“Nggak ada lah bayangan bisa kritis-kritis ala Najwa Shihab. Cuma memberitakan peristiwa. Nggak keren lah, apalagi gajinya,” sambungnya.
Dan mirisnya, di daerah kecil, wartawan/jurnalis itu tidak lebih dari “gembel” yang perlu ditolong. Setidaknya di mata para birokrat. Tidak ada harga dirinya.
Bahkan, amat mudah mulut wartawan disumpal atau dipesan untuk membranding birokrat, hanya dengan amplop berisi Rp50 ribu atau sekadar traktiran makan siang.
Delano awalnya sangsi dengan praktik semacam itu. Bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang dia pelajari. Namun, omongan sengak salah seorang rekannya menyadarkannya akan realitas yang dia hadapi.
“Nggak usah naif. Jurnalis sejahtera itu cuma ada di Pusat (media-media besar yang sudah mapan secara bisnis). Gajinya tetap. Mungkin juga dapat BPJS Ketenagakerjaan. Kamu? Kita? Gembel,” ucap rekan Delano.
Menyadari realitas tersebut, Delano pun pada akhirnya menjadi sering berburu amplop dari pejabat. Lumayan untuk bensin atau sekadar kopi dan rokok.
Batu loncatan, tapi ambles
Pada mulanya Delano hanya ingin menjadikan media pers online di daerah sebagai batu loncatan. Siapa tahu, jalan hidup dan sedikit keberuntungan menyeretnya ke Ibu Kota: ke media-media besar yang bisnisnya lebih mapan.
Namun, bukannya menjadi batu loncatan, batu tersebut justru semakin ambles. Tidak bisa melontarkan Delano ke mana-mana, berhenti di tempat.
“Ada lowongan kerja di media besar, kucoba ternyata gagal. Mungkin karena tempat kerja asalku adalah media yang nggak diperhitungkan. Wong emang media kecil daerah,” ucap Delano.
Hingga kini, dia sudah tiga kali pindah media. Setidaknya saat ini dia mendapat gaji tetap (di angka Rp2,2 juta). Lebih beruntung dari sejumlah temannya, wartawan/jurnalis daerah yang harus menerima gaji di bawah UMP. Walaupun memang masih pas-pasan untuk sewa kos dan kebutuhan. Jadi jangan harap bisa punya tabungan.
Jelas masih belum sejalan dengan cita-cita Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berharap gaji wartawan ada di angka Rp8 jutaan atau seminimal-minimalnya seangka UMP/UMK, atas risiko kerja dan peran vitalnya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Cap gagal dan tak berguna dari keluarga sendiri
Delano nyaris jarang pulang. Dia selalu takut tiap sesekali harus pulang ke rumahnya, kendati jarak rumah dengan tempat kerjanya hanya 2 jam. Karena kalau pulang, pasti dia akan kembali ke kos dengan dada sesak hingga cemas berlebihan.
Orang tua Delano memang sudah berkali-kali meminta Delano untuk mencari pekerjaan lain yang lebih pasti secara ekonomi. Setelah tahu honor perberita yang Delano terima sejak awal kariernya.
Masalahnya, seperti yang Delano singgung di awal, dia merasa tidak punya keahlian lain selain menulis berita. Alhasil, kalau tidak dibanding-bandingkan dengan anak tetangga atau saudara yang sudah mapan, ya orang tua pasti menjadikan Delano sebagai sasaran kekesalan.
“Umur 30 tahun sudah nikah, sudah bisa beli ini, beli itu. Sama orang tua bisa ngasih. Sementara aku, belum bisa ngasih apa-apa dan nggak jadi apa-apa,” ungkap Delano lesu.
“Dikuliahkan mahal-mahal. Kerja bertahun-tahun kok nggak ada hasilnya,” kalimat itu paling sering terlontar dari sang ibu. Perkaranya, tidak jarang Delano memang masih meminta bantuan uang dari orang tuanya. Misalnya, sesederhana bayar pajak motor, sementara uang Delano kurang. Mau tidak mau dia harus minta tambahan dari orang tua.
Nyaris tidak ada kebanggaan dari orang tua terhadap Delano. Sebab, Delano mendengar sendiri, betapa orang tuanya sering merendahkan Delano di hadapan orang lain: tetangga atau saudara. Disikapi seperti anak gagal dan tidak berguna.
“Sedih, sih. Tapi juga burem, entah sampai kapan kayak gini. Apalagi, makin banyak media pers bertumbangan kan, langsung badai PHK. Di titik ini, aku merasa wartawan/jurnalis ternyata bukan profesi yang recommended, bahkan untuk opsi pelarian sekalipun,” beber Delano.
“Aku juga bener-bener ngelarang adikku ngikuti jejakku. Walaupun dia juga suka menulis. Tapi aku arahkan dia buat pragmatis. Kita butuh uang. Bukan untuk sekadar hidup, tapi juga nggak direndahkan,” tutupnya nanar.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Media Online Tak Seharusnya Anxiety pada AI dan Algoritma atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan