Kita semua cuma serangga di dalam KRL ibu kota, yang bekerja keras hingga lupa dengan diri kita sendiri. Itulah yang ingin disampaikan Franz Kafka melalui novel Metamorphosis, yang ditulis 100 tahun lalu tapi relevansinya pada pekerja urban hari ini makin terasa.
***
Bayangkan, kamu terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa tubuhmu telah berubah menjadi serangga raksasa yang menjijikkan. Punggungmu mengeras laiknya memakai baju besi, perutmu melengkung, dan kakimu tiba-tiba menjadi banyak.
Namun, alih-alih berteriak histeris karena kehilangan kemanusiaanmu, hal pertama yang melintas di pikiranmu justru adalah: “Aduh, aku terlambat kerja! Bagaimana caraku mengejar kereta jam tujuh pagi?”
Adegan pembuka dalam novel Metamorphosis (1915) karya Franz Kafka ini bukan sekadar fantasi absurd. Ia adalah cermin bagi pekerja urban modern hari ini, yang hidup di bawah tekanan ekonomi, birokrasi semrawut, dan krisis identitas yang mendalam.
Gregor Samsa, sang tokoh utama, bukan berubah jadi serangga dan mati karena sihir, tetapi karena menjadi korban dari sistem yang menggerogoti kemanusiaannya.
Saya pertama kali membaca karya Kafka ini kira-kira tujuh tahun lalu, saat masih aktif kuliah. Saat itu, novel ini saya nikmati sebagai sastra absurd. Mungkin kebanyakan orang juga berpikir demikian.
Namun, ketika saya memasuki dunia kerja, Metamorphosis justru makin relevan. Menurut keyakinan saya, Kafka menulis novel ini bukan sebagai cerita fantasi tentang manusia yang berubah menjadi serangga.
Lebih dari itu. Ia adalah potret sunyi tentang bagaimana seseorang perlahan kehilangan nilai kemanusiaannya di mata orang-orang terdekatnya.
Perubahan fisik Gregor Samsa, menjadi seekor serangga mirip kecoa, hanyalah pintu masuk. Yang sesungguhnya menjadi pusat cerita adalah perubahan sikap keluarga, dunia kerja, dan akhirnya Gregor sendiri terhadap keberadaannya.
Keyakinan saya itu makin menguat setelah berbincang singkat dengan Dalang Sigit Susanto pada Selasa (13/1/2026) lalu. Penerjemah novel Metamorphosis ke dalam Bahasa Indonesia ini kondang setelah beberapa kali mementaskan wayang di Swiss dengan lakon diambil dari novel-novel Kafka, termasuk kisah Gregor Samsa.
Kita dianggap berguna selama mereka masih menghasilkan uang
Bagi Sigit, dalam realitas pekerja urban, relevansi kisah Gregor sangat terasa pada bagaimana harga diri seseorang seringkali dilihat “hanya sebatas angka di slip gaji”. Kamu dianggap berguna selama masih bisa menghasilkan uang.
Kafka menghidupkan kengerian ini melalui reaksi pertama Gregor saat terbangun sebagai serangga. Bukannya memikirkan bagaimana cara menggerakkan “banyak kaki kecilnya yang bergetar tak berdaya”, Gregor justru terpaku pada jam weker di atas laci.
Ia meratapi pekerjaannya dalam sebuah monolog batin yang sangat akrab di telinga pekerja modern kiwari.
“Oh, Tuhan… betapa melelahkannya pekerjaan yang telah kupilih! Masuk dan keluar dari kereta setiap hari… hubungan manusia yang selalu berubah, tidak pernah menetap, tidak pernah menjadi intim.”
Novel itu ditulis lebih dari seabad yang lalu. Namun, rintihan Gregor tadi lebih terdengar seperti keluhan pekerja di Jakarta yang harus berdesakan di dalam KRL demi pekerjaan yang melelahkan–dan mungkin tak mereka dambakan.
Menurut Sigit, di sini, Kafka ingin menunjukkan bahwa bahkan sebelum fisiknya berubah pun, jiwa Gregor sudah lebih dulu “mengkerdil” akibat rutinitas yang monoton dan menyiksa pikiran.
Detail yang paling menyayat hati adalah alasan di balik ketekunan bekerjanya. Gregor tidak bekerja untuk impian pribadinya, tetapi sebagai mesin pelunas utang keluarga. Ia pernah bergumam dalam hati:
“Begitu aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk melunasi utang orang tuaku kepada bos aku pasti akan melakukannya. Itu akan menjadi pemisah besar dalam hidupku”.
Kutipan ini menegaskan posisi Gregor sebagai “celengan” (piggy bank) bagi keluarganya. Ia rela tak punya mimpi. Mengubur dalam-dalam cita-citanya. Yang terpenting baginya, tetap bekerja–meski pekerjaan itu tak ia inginkan–demi keluarganya.
Bukankah para sandwich generation hari ini juga merasakannya?
Tubuh kita, para pekerja urban, adalah milik bos
Kalau kalian pikir relevansi kisah Metamorphosis terhadap pekerja urban hari ini cuma sampai di situ, kalian salah. Bagi saya, salah satu adegan paling mencekam–brutal sekaligus relevan– adalah sosok Chief Clerk, sang manajer kantor, datang ke rumahnya karena Gregor terlambat masuk kerja.
Kantor tak mau tahu. Ia tak peduli Gregor berubah menjadi kecoa sekalipun. Yang mereka tahu, Gregor terlambat kerja beberapa jam–untuk pertama kalinya dalam lima tahun.
Dan, jahatnya lagi, Chief Clerk sama sekali tak menanyakan kesehatan Gregor. Ia malah langsung menyerang karakternya. Gregor dituduh malas, tidak cakap, hingga tak mau mendengarkan penjelasan Gregor yang telah berubah menjadi kecoa.
Bagi pekerja urban di luar sana, apakah bos kalian seperti itu? Tidak mau tahu dengan kesehatan pekerjanya, serta cuma melihat kesalahan tanpa pernah mengapresiasi pencapaian. Jika iya, kalian adalah Gregor-Gregor masa kini.
Kalau meminjam teori Marxisme, Chief Clerk adalah kaum borjuis, representasi dari birokrasi yang cuma memandang pekerja bukan sebagai manusia, melainkan sebagai “benda” yang tenaganya harus dieksploitasi sampai habis.
Pekerja diharapkan untuk terus berfungsi seperti mesin. Dan, jika “mesin” itu rusak, maka ia harus segera disingkirkan karena dianggap tak berguna lagi.
Menurut cerita Sigit Susanto, Kafka menuliskan adegan ini berdasarkan pengalamannya sendiri saat bekerja di Institut Asuransi Kecelakaan Pekerja. Di sana, ia menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan birokrasi membatasi kebebasan individu.
Dalam Metamorphosis, Gregor digambarkan sebagai “creature of the boss” (makhluk milik bos), “alat” yang tidak boleh memiliki “punggung dan pikiran” sendiri. Ya, kira-kira sama seperti pekerja urban hari ini.
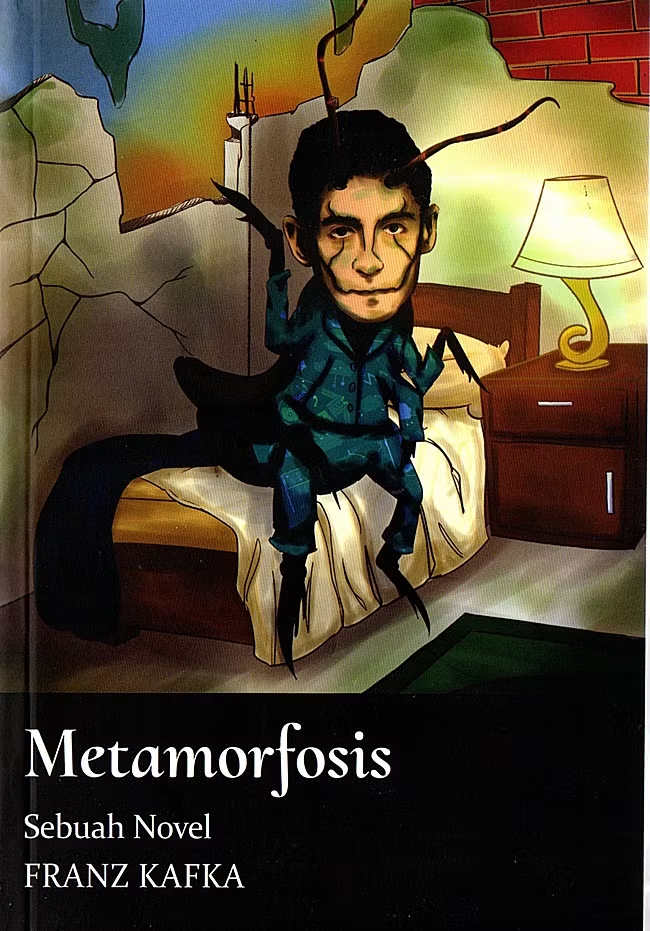
Kita bakal dibuang setelah dirasa tak berguna
Namun, cerita paling memilukan, bagi saya, justru datang dari perubahan sikap keluarga Gregor. Sebelum tubuh Gregor berubah jadi kecoa, ayahnya digambarkan sebagai pria tua yang lemah dan hanya bersantai di kursi sepanjang hari.
Baca halaman selanjutnya…
Bahkan, kita cuma dianggap angin lalu ketika sudah tiada.
Namun, begitu Gregor tidak lagi bisa bekerja, sang ayah mengalami perubahan perilaku yang drastis. Ia kembali bekerja sebagai penjaga bank, mengenakan seragam biru ketat dengan kancing emas, yang membuatnya terasa seperti bos di rumah.
Puncaknya, digambarkan dalam adegan serangan apel. Saat Gregor mencoba merayap keluar dari kamarnya, ayahnya–pria yang selama ini ia nafkahi–justru mengejarnya dengan kemarahan yang meluap-luap.
Ia mulai membombardir Gregor dengan apel dari meja makan. Salah satu apel tersebut bersarang di punggung Gregor, menembus kulit serangganya yang keras, dan dibiarkan membusuk di sana karena tidak ada anggota keluarga yang berani atau mau mencabutnya.
Membaca ulang adegan ini, rasanya nyesek. Membayangkan menjadi Gregor, semula tulang punggung yang menafkahi keluarga, tetapi cacat fisik membuatnya dipandang tak berharga.
Luka apel ini, bagi saya, adalah simbol fisik dari penolakan keluarga. Dalam dunia pekerja urban saat ini, mirip dengan orang tua atau pasangan yang perlahan-lahan berubah menjadi asing atau agresif ketika kita tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi finansial mereka.
Kasih sayang yang dulu ada, kini berubah menjadi rasa jijik karena kita dianggap sebagai “hama” yang menguras sumber daya mereka.
Jika sang ayah mewakili kemarahan, saudara perempuannya, Grete, mewakili kejijikan yang lebih halus tapi lebih mematikan. Awalnya, Grete adalah satu-satunya orang yang peduli; ia membawakan makanan sisa yang membusuk karena ia tahu Gregor menyukainya. Namun, seiring berjalannya waktu, kasih sayangnya terkikis oleh kelelahan dan ambisinya sendiri.
Adegan ikonik yang menandai berakhirnya kemanusiaan Gregor adalah saat Grete bermain biola untuk para penyewa kamar. Gregor, yang sangat mencintai adiknya dan bermimpi menyekolahkannya ke konservatori musik, merayap keluar karena terpesona oleh alunan musik itu.
Namun, alih-alih disambut dengan pelukan, kehadirannya justru memicu bencana bagi reputasi keluarga di depan para penyewa.
Di sinilah Grete mengucapkan kalimat yang nyelekit dan bikin Gregor kena mental–saya pun ikut nyesek membacanya.
“Ayah, Ibu, kita tidak boleh lagi berpikir bahwa ‘ini’ adalah Gregor. Kita harus mencoba menyingkirkannya… ‘itu’ akan menghancurkan kita semua”.
Grete, adik yang Gregor sayangi, berhenti menyebutnya “kakak” dan menggantinya dengan kata ganti “itu”. Transformasi Grete dari seorang gadis muda yang lembut menjadi orang yang dingin, bagi saya, mencerminkan bagaimana pekerja urban sering kali “dibuang” oleh lingkaran terdekatnya begitu mereka dianggap tidak lagi berguna bagi circle mereka.
Familiar, bukan?
Kita, para pekerja urban, dianggap angin lalu setelah tiada
Mungkin, adegan yang paling memuakkan adalah apa yang terjadi setelah Gregor mati karena kelaparan dan luka-lukanya. Begitu mayat Gregor ditemukan oleh pelayan dan dibuang seperti sampah, keluarga Samsa tidak meratap. Sebaliknya, mereka merasakan kelegaan yang luar biasa.
Mereka mengambil hari libur, naik trem ke luar kota, dan menikmati sinar matahari yang hangat. Sesuatu yang sangat kontras dengan kamar Gregor yang gelap dan berdebu.
Pesan Kafka sangat jelas: kematian Gregor bukan alasan untuk merasa kehilangan. Di realitas urban saat ini, adegan ini mengingatkan kita pada bagaimana roda korporasi dan bahkan struktur keluarga tertentu akan terus berputar dengan ceria setelah mereka “membuang” individu yang sudah habis diperas tenaganya.
Semakin relevan, bukan?
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Alfamart 24 Jam di Jakarta, Saksi Para Pekerja yang Menolak Tidur demi Bertahan Hidup di Ibu Kota atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan