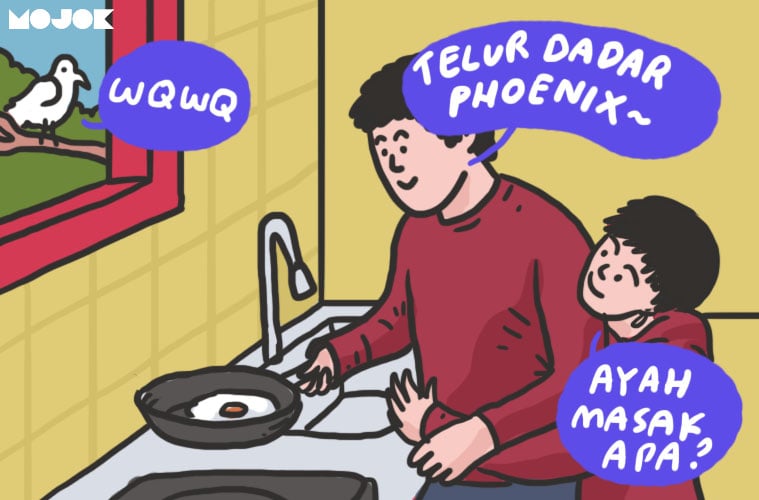Di ruang tamu kecilnya, aroma minyak kayu putih masih menempel di sandaran kursi panjang. Sejak ayah dia meninggal tiga bulan lalu, Adel (24) jarang duduk di sana.
Kursi itu dulu jadi tempat favorit ayahnya; untuk menonton berita dengan volume keras, sambil mengomentari semua hal. Dari skandal Pertamina, sampai Timnas Indonesia yang lagi bagusnya-bagusnya.
Sekarang, yang tersisa hanya ruang kosong dengan suara televisi yang channel-nya nyaris tak pernah diganti.
“Tiap kali nyalain TV di ruang tengah, rasanya ayahnya kayak masih nonton. Makanya aku nyalain terus, aku panjer di channel kesukaan beliau, nggak pernah kuganti,” katanya, Senin (3/11/2025).
Adel tahu betul, ayahnya bukan tipe yang pandai bicara ke anak-anaknya. Kalimat terpanjang yang diingatnya, bahkan hanya, “Kalau pulang main jangan malam-malam, ringroad selatan bahaya kalau udah jam 12 malam,” yang bahkan lebih terdengar seperti perintah daripada nasihat.
Tak pernah ada obrolan empat mata yang dari hati ke hati, apalagi pelukan hangat. Hubungan mereka berjalan dengan ritme yang kaku dan formal.
Namun, ketika ayahnya jatuh sakit, Adel–sebagai anak termuda–menjadi orang yang merawat. Waktu mereka semakin banyak, meski ayahnya sudah dalam keadaan tak berdaya.
Tapi dari situ Adel mulai menyadari banyak hal. Mengapa ayahnya jarang bicara, mengapa ayahnya selalu menitipkan uang saku ke ibunya–tidak langsung ke dirinya, atau mengapa ia selalu mengomel kalau pulang main terlalu malam.
“Dan ketika ayah akhirnya pergi, rumah mendadak terasa asing. Aku tiba-tiba rindu caranya marah kalau aku pulang malam. Bahkan aku rindu suara sandalnya, yang kalau berjalan sambil digesek ke lantai,” ucapnya.
“Lucu, ya. Dulu aku pikir kami cuma tidak cocok. Sekarang, setiap aku pulang, rasanya seperti ditinggal orang yang belum sempat aku kenal.”
Keheningan yang menjadi sumber kesedihan
Adel bukan satu-satunya yang merasakan kehilangan semacam itu. Dalam banyak keluarga, relasi ayah dan anak memang seringkali berjalan tanpa kedekatan emosional.
Hubungan tetap berjalan, tapi tanpa komunikasi yang hangat. Baru setelah sosok itu tiada, kesunyian di rumah terasa lebih nyata.
Sebuah studi berjudul “Relationship Quality Between Older Fathers and Middle-Aged Children” yang terbit di The Journals of Gerontology (2016), menemukan bahwa kualitas hubungan antara ayah lanjut usia dan anak dewasa punya pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan emosional keduanya.
Anak yang merasa hubungannya buruk dengan ayah cenderung memiliki tingkat depresi lebih tinggi dan kepuasan hidup lebih rendah. Hal serupa juga dialami para ayah yang merasa hubungannya dengan anak tak hangat.
Temuan itu memperlihatkan satu hal: jarak emosional bukan hanya soal “kurang akrab”, tapi bisa berdampak panjang. Ketika hubungan dibiarkan berjalan fungsional tanpa ruang ekspresi yang intim, keheningan itu bisa menjadi sumber kesedihan yang baru terasa saat salah satunya pergi.
Hal itulah yang dirasakan Adel. Ketika ayahnya sudah tiada, perasaan sedih yang sulit dijelaskan itu seketika muncul, meski mereka tak memiliki hubungan yang hangat.
“Bahkan aku nggak merasakan kesedihan kayak begini waktu putus dengan pacar yang sudah berhubungan 4 tahun,” ungkapnya.
Penelitian lain, yang dilakukan oleh Ohio State University (2022), menunjukkan bahwa pengalaman seperti ini ternyata cukup umum. Sekitar 26 persen anak dewasa di Amerika mengaku pernah merasa “terasing” dari ayahnya, sementara hanya 6 persen yang merasa hal serupa terhadap ibu.
Artinya, anak memang lebih sering memiliki jarak emosional dengan ayah dibanding ibu, meski hubungan mereka tetap berjalan secara sosial.
Emotional suppression, malu-malu mencurahkan rasa sayang
Di Indonesia, belum banyak riset yang secara khusus meneliti pola serupa. Namun, dalam banyak keluarga, terutama yang tumbuh di masa 1980–2000-an, pola ini terasa akrab: ayah bekerja keras, jarang di rumah, dan canggung menunjukkan kasih sayang.
Lelaki pada generasi itu dididik untuk tangguh dan hemat kata. Cinta bagi mereka bukan pelukan, melainkan kewajiban yang dijalankan dengan diam.
Dalam psikologi, ada istilah emotional suppression, yakni kecenderungan menahan ekspresi emosi karena norma sosial atau peran gender. Banyak laki-laki dewasa membawa beban ini ke dalam kehidupan keluarga. Mereka percaya bahwa menunjukkan kasih sayang terlalu terang bisa dianggap lemah, sehingga memilih diam dan bekerja sebagai bentuk cinta paling konkret.
Bagi anak, terutama yang tumbuh dalam budaya baru yang lebih terbuka secara emosional, pola ini sering salah dibaca sebagai ketidakpedulian. Hasilnya, adalah jarak yang makin melebar. Ayah merasa sudah memberi segalanya, tapi anak merasa tak pernah benar-benar dikenali.
Ketika figur ayah itu akhirnya tiada, yang tersisa adalah ruang kosong. Bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan kesempatan memahami cinta yang hadir dalam bentuk lain.
Itulah sebabnya banyak orang baru menangis setelah ayah mereka pergi, bukan karena kematian itu sendiri, tapi karena baru saat itu mereka belajar mendengar bahasa kasih yang selama ini dibungkam oleh waktu dan kebiasaan.
Laci tua bukti kasih sayang ayah
Cerita lain dialami Dimas (33). Sama seperti Adel, hubungan dengan ayahnya dulu terasa “seperti dua orang yang sekadar berbagi rumah”.
Ayahnya pensiunan pegawai negeri yang disiplin dan keras. Ia mengatur semuanya dengan ketat. Dimas pun tumbuh dengan rasa hormat bercampur takut. Tak pernah ada percakapan santai, obrolan hati ke hati, apalagi pelukan.
“Kalimat favorit beliau cuma ‘Jangan bikin malu keluarga,’” kata Dimas sambil tersenyum getir.
Setelah kuliah di luar kota, Dimas jarang pulang. Komunikasi mereka hanya lewat ibu atau pesan singkat berisi hal-hal “praktis”, seperti transferan uang.
Hingga, pada suatu hari, kabar duka datang. Ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Dimas yang saat itu sedang menjalani ujian tengah semester di kampusnya, pulang dengan perasaan campur aduk
“Antara sedih, tapi juga canggung karena tak tahu harus merespons bagaimana,” ungkapnya.
Setelah pemakaman, Dimas membantu ibunya membereskan kamar ayahnya. Di dalam laci kecil di meja kerja, ia menemukan amplop berisi kertas lusuh. Di atasnya tertulis: “Untuk Dimas.” Di dalamnya ada surat yang isinya bikin Dimas menangis saat itu juga.
Ia bercerita, isi surat itu nyaris tidak ada nasihat bijak atau harapan muluk seorang ayah kepada anaknya. Isinya hanya permintaan maaf kalau selama ini ayahnya terkesan cuek, keras, dan suka mengatur.
Ayahnya juga mengatakan bahwa dirinya ingin sekali memeluk sang anak dan mengobrol hal-hal kecil soal hari-harinya. Namun, ada perasaan malu dan sungkan.
“Waktu itu aku baru sadar, ayah cuma nggak tahu caranya bilang sayang.”
Bagi banyak orang, ayah adalah sosok yang sulit dijelaskan. Mereka jarang bicara, tapi kehadirannya kadang menenangkan. Di mata anak-anaknya, keheningan itu sering disalahartikan sebagai jarak, padahal mungkin di sanalah cinta paling jujur tinggal.
Adel dan Dimas hanyalah dua dari banyak orang yang menyadari hal itu terlambat. Mereka tumbuh bersama ayah yang keras kepala, kaku, dan pelit kata. Namun, pada akhirnya, kehilangan merekalah yang justru mengajarkan makna kasih sayang paling dalam.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Suara Ibu di Telepon Selalu bikin Tenang usai Hadapi Hal-hal Buruk dan Menyakitkan di Perantauan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan