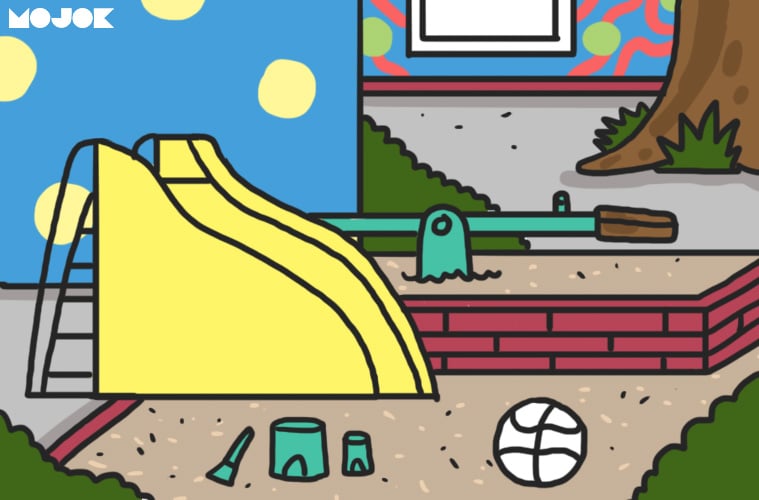Melalui sebuah eksperimen kecil, saya mengetahui bahwa penghasilan tukang parkir kafe estetik di Jogja mencapai Rp150-200 ribu sehari, atau Rp5 juta sebulan. Dua kali lipat gaji karyawan kafe itu sendiri.
***
Saya sering nongkrong di sebuah kafe estetik di Jogja. Kafe-nya nggak besar, cuma ada dua ruangan: indoor yang sempit dan outdoor yang kalau penuh sedikit saja sudah bikin kursi saling bersenggolan.
Dindingnya ala-ala industrial. Sementara musiknya indie-pop dan garage-rock kesukaan anak-anak skena.
Saya sering ke sana karena salah satu pengelolanya teman saya sendiri. Di sana, kadang ngetik kerjaan, atau cuma ngobrol ngalor-ngidul soal hidup susah sebagai WNI. Tapi saya menyukai tempat ini karena suasananya tenang, harga kopi masih rasional, dan pelayannya sudah akrab aja, sih.
Sampai suatu sore, saya tanpa sengaja memperhatikan seseorang yang selama ini mungkin luput dari radar: tukang parkir.
Kafe ini punya area parkir kecil, hanya muat sekitar 15-20 motor kalau ditata rapi. Tapi sore itu, saya lihat arus motor keluar-masuk cukup ramai. Dalam dua jam saya nongkrong, saya hitung kira-kira lebih dari 15 motor berganti posisi. Tarif parkirnya standar: Rp2 ribu per motor.
Artinya dalam dua jam saja, sesuai hitungan saya, tukang parkir itu sudah mengantongi Rp30 ribu.
Saya sempat berhitung dalam hati: “Kalau dua jam bisa 30 ribu, berarti kalau seharian? Wah, lumayan juga.” Tapi tentu itu baru kira-kira. Maka, saya memutuskan untuk bikin “eksperimen kecil” di kemudian hari.
Saat jam prime time, bisa dapat lebih banyak
Beberapa malam setelahnya, saya datang lagi. Kali ini di jam prime time–sekitar pukul tujuh sampai sepuluh malam–saat mahasiswa dan pekerja mulai menyerbu kafe dengan laptop dan keresahan masing-masing.
Saya duduk di pojokan outdoor. Kopi saya taruh di sebelah laptop yang saya biarkan menyala. Misi saya malam itu sederhana: menghitung jumlah motor yang masuk dan keluar.
Saya hitung satu per satu secara teliti dan presisi. Niat banget untuk melakukan riset. Hasilnya? Dalam tiga jam, total ada 40 motor keluar-masuk.
“Kalau satu motor dua ribu, berarti tukang parkir itu menghasilkan 80 ribu rupiah. Delapan puluh ribu dalam tiga jam,” kata saya dalam hati.
Itu belum termasuk uang recehan dari pelanggan yang “bayar lebih” atau yang keburu cabut tanpa ambil kembalian.
Penghasilan tukang parkir 2 kali lipat karyawan kafe
Saya coba bandingkan dengan gaji teman saya yang kerja di kafe itu. Katanya, dia digaji Rp2,3 juta per bulan. Kerjanya enam hari seminggu, delapan jam per hari. Kalau dibagi rata, berarti ia mendapatkan penghasilan Rp95 ribu per hari.
Artinya, si tukang parkir dalam tiga jam kerja sudah dapat hampir setara pendapatan harian karyawan kafe. Dan kalau malam-malam lain seramai itu, berarti dalam sehari ia bisa dapat lebih dari Rp100 ribu, bahkan mungkin Rp150-200 ribu rupiah.
Untuk memastikannya, saya tanya teman saya lagi.
“Tukang parkir itu bagi hasil nggak sama pengelola?” kira-kira demikian pertanyaan saya.
“Setahuku ya nggak. Parkir dipegang sendiri. Nggak ada sistem bagi hasil,” jawabnya.
Saya sempat bengong. Jadi selama ini, tiap malam si tukang parkir mungkin membawa pulang uang harian setara dua kali gaji karyawan yang kerja delapan jam di bawah AC.
Saya coba bayangkan perhitungan kasarnya:
Kalau rata-rata sehari Rp100 ribu (50 motor), sebulan (katakanlah kerja 26 hari) berarti Rp2,6 juta. Kalau Rp150 ribu per hari (75 motor), bisa Rp3,9 juta. Atau, pas bener-bener ramai, sehari Rp200 ribu (100 motor), tukang parkir bisa mendapatkan Rp5,2 juta.
Dan itu tanpa slip gaji, tanpa tunjangan, tanpa cuti tahunan. Tapi uangnya tunai. Langsung di tangan.
Margin of error
Namun, itu adalah eksperimen kecil yang saya lakukan atas dasar kepo saja. Perhitungannya bisa salah, bisa mendekati, dan bisa juga tepat. Nah, mungkin di sini letak margin of error-nya: bisa jadi tiap jam tingkat keramaian kafe beda-beda.
Bisa jadi, waktu saya melakukan eksperimen kecil itu, kebetulan kafe memang lagi ramai saja. Wallahualam.
Tapi yang jelas, eksperimen kecil ini bikin saya berpikir, bahwa dalam ekosistem ekonomi kota seperti Jogja—yang katanya murah—ada lapisan pekerjaan yang diam-diam jauh lebih “untung” dari yang terlihat.
Teman saya yang kerja di kafe itu harus melayani pelanggan, bersih-bersih, kadang lembur. Gajinya pas-pasan. Sementara tukang parkir “cuma” bermodal rompi dan peluit, bisa membawa pulang uang lebih banyak.
Bisa jadi, ini bukan cuma soal siapa kerja lebih keras, tapi siapa yang lebih “cerdik” dalam melihat peluang. Si tukang parkir tak menunggu tanggal muda, tak perlu menunggu transferan finance, tak kenal potongan BPJS. Semua langsung cair.
Malam itu, saya pulang dengan kepala penuh angka. Di satu sisi saya kagum–karena ternyata tukang parkir bisa “mengalahkan” sistem gaji karyawan formal. Tapi di sisi lain, ada semacam ironi yang susah saya cerna.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Eksperimen Seminggu Jadi Tukang Parkir Ilegal di Jogja, Penghasilannya Bisa Kebeli Apa Aja? atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan