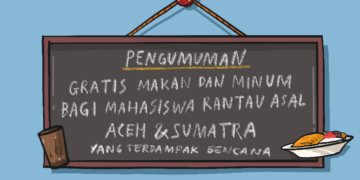Tergoda hingga kalap
Karena bingung, Gandika lantas melempar ke teman kerjanya agar dilayani terlebih dulu. Niat sebenarnya, ya biar Gandika tahu bagaimana cara temannya memesan.
Dan barulah Gandika tahu, ternyata cara pesannya adalah tinggal menunjuk saja lauk atau sayur sesuai selera.
Dari situ pula akhirnya Gandika tahu kenapa warteg kerap disebut sebagai warung makan touch screen (layar sentuh). Sebab, pembeli tinggal menyentuh layar kaca etalase, lalu jenis lauk atau sayur yang disentuh itu akan langsung berpindah ke piring.
“Aku lihat kan temanku itu pilah-pilih sesuka hati. Dicampur-campur. Jadi aku tiru,” ucap Gandika.
Dia lantas memilih beberapa varian sayur dan lauk. Tidak cukup satu lauk: telur ceplok balado, Gandika juga memilih lauk-lauk pelengkap seperti tahu hingga pentol.
Sensasi mewah untuk menebus keterbatasan menu di rumah
“Itu pengalaman pertama makan di warteg yang memberi lidahku pengalaman baru,” kata Gandika.
Sebab, selama ini, di rumah dia biasanya hanya makan dengan satu jenis sayur dan lauk. Misalnya tumis kangkung dan telur ceplok. Ya sudah, itu saja.
Itupun akan dimakan seharian (tidak ada istilah ganti menu tiap jam makan). Maklum orang desa, dan terlebih dari keluarga pas-pasan.
Maka, sensasi makan di warteg untuk pertama kali itu seperti menebus “keterbatasan” dalam hal makan. Karena dia bisa mencampur aneka lauk dan sayur dalam satu piring.
“Aku cocok-cocok saja dengan masakan warteg. Karena aku bukan tipe orang yang pilih-pilih kalau soal makan. Tapi yang paling penting, aku kenyang pol lah makan di warteg. Karena nasinya, kalau kata orang Rembang, munjung-munjung (menggunung atau melimpah ruah),” jelas Gandika. Sensasi merokok selepas makan di warteg pun terasa begitu nikmat.
Terbengong-bengong saat totalan
Tapi eh tapi, Gandika langsung terbengong-bengong saat totalan. Dia habis Rp30 ribu untuk sekali makan. Melihat itu, teman Gandika malah tertawa ngakak. Karena teman Gandika hanya habis belasan ribu saja.
“Lah kamu semua menu dipilih, ya jelas habisnya segitu lah,” kata teman Gandika.
“Bingung, Cok. Pas lihat kamu bisa memilih sesuka hati, aku ikut-ikut,” balas Gandika.
“Per item itu dihitung. Jadi harga menyesuaikan,” timpal Gandika.
“Lah aku nggak mbok kasih tahu e, Cok,” balas Gandika.
Bagi orang pas-pasan seperti Gandika, apalagi saat itu dia baru mulai bekerja, kehilangan uang Rp30 ribu untuk sekali makan tentu menimbulkan penyesalan. Sebab, uang segitu seharusnya bisa digunakan untuk makan dua kali—atau bahkan tiga kali—sehari.
“Tapi enak dan kenyang kan?” Goda teman Gandika.
“Ya iya, kenyangnya iya. Enaknya iya. Tapi dompetku bisa ludes kalau aku kalap seperti tadi,” balas Gandika.
Salah strategi itu menjadi pelajaran penting bagi Gandika. Setelahnya, Gandika akhirnya lebih sering makan di warteg saat kemudian berpindah-pindah daerah kerja. Karena dia tidak bisa memungkiri kalau lidahnya cocok dan perutnya kenyang kalau makan di warteg.
“Jadi milihnya dua jenis saja. Sayur satu jenis, lauk satu jenis. Asal nasinya banyak, itu sudah cukup. Bagiku pokoknya asal kenyang,” tutur Gandika.
Namun, jika sedang punya uang lebih, Gandika biasanya akan mengaktifkan mode kalap. Kebahagiaan menurutnya, tidak melulu misalnya makan di restoran mewah. Tapi bisa makan dengan menu dua lauk sekaligus dalam satu piring seperti di warteg sudah sangat cukup: Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sejak kecil.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Burjo di Sekitar UNY Menyelamatkan Hidup Mahasiswa Semester Tua yang Terancam DO dan Tak Sanggup Bayar UKT atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan