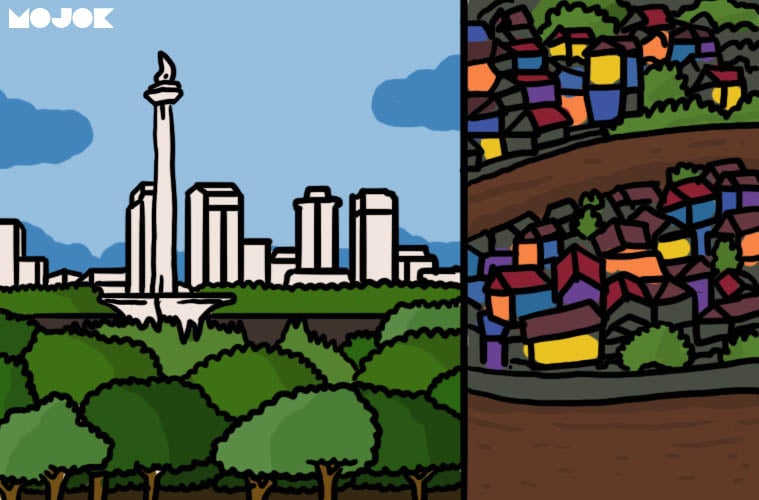MOJOK.CO – Ada hal lain yang menarik untuk didiskusikan tentang banjir Jakarta awal tahun ini, yaitu bagaimana ia “didepolitisasi” dan “direpolitisasi” warganet.
Saya akan ambil dua contoh. Pertama, cuitan aktivis HAM Haris Azhar yang saya sebut melakukan “depolitisasi” terhadap peristiwa banjir Jakarta, yang sebenarnya lebih tepat disebut banjir Jabodetabek. Lalu status Facebook sejarawan JJ Rizal saya anggap sebagai “repolitisasi” karena menyoal niat pengusaha dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) yang ingin menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta gara-gara banjir bikin operasi sejumlah mal di Jakarta terhenti.
Melihat luasan Banjir, apakah sebanding dengan luasan kerja Ahok atau Anies selama ini. Ini ulah kita semua.. bukan waktunya menyalahkan. Ini waktu bangun solidaritas. Sadar bersama ke depan bahwa masalah lingkungan hidup ada cara kita hidup sehari-hari.
— Jogging bukan joget (@haris_azhar) January 1, 2020
Adapun yang saya maksud dengan “politik” dalam konteks depolitisasi-repolitisasi adalah bagaimana ruang yang banjir di Jakarta diproduksi.
Cuitan Haris Azhar pada 1 Januari 2020 mengajak untuk menyadari bahwa banjir Jakarta terjadi karena “ulah kita semua” dan momen banjir ini “bukan waktunya menyalahkan”, melainkan “waktu bangun solidaritas”.
Saya berempati terhadap korban banjir dan sangat bisa menerima seruan bersolidaritas membantu korban banjir. Saya pikir itu penting. Ketika orang menghadapi musibah, maka solidaritas dari orang lain sangat dibutuhkan. Itu adalah suatu yang normal dalam kehidupan. Dan tampaknya kehidupan berjalan seperti itu.
Proses depolitisasi terjadi pada/melalui bagian “ulah kita semua” dan “bukan waktunya menyalahkan”.
Barangkali, maksud Haris Azhar dengan “ulah kita semua” adalah hubungan banjir dengan perubahan iklim yang menjadi narasi dominan di kalangan pemerhati lingkungan sekarang ini. Secara sederhana, yang saya pahami melalui sebuah pemodelan yang pernah saya kerjakan sekitar 8 tahun lalu, salah satu dampak perubahan iklim adalah memperparah momen-momen ekstrem hidrologi, yakni banjir dan kekeringan.
Lantas apa hubungannya dengan saya? Saya menjadi penting di sini karena Haris menyebut “ulah kita semua”. Kata yang dipakai adalah kita. Jadi saya adalah bagian dari “kita” itu.
Sampai di sini saya agak bisa menerima bahwa saya ikut bikin ulah yang menyebabkan banjir di Jakarta. Kontribusi saya, barangkali, dalam kerangka diskusi perubahan iklim, melalui jejak ekologi/karbon dalam memproduksi gas rumah kaca.
Seperti yang sudah saya sampaikan pada tulisan di Mojok sebelumnya, saya melihat terutama ada tiga jenis banjir di Jakarta:
(1) banjir kiriman dari Puncak,
(2) banjir karena hujan lokal, dan
(3) banjir dari laut, yang mana kenaikan muka air laut berkombinasi dengan penurunan muka tanah.
Model-model banjir ke-1, 2, dan 3 ini dapat saling berkombinasi. Penyebab-penyebab dari ketiga jenis banjir itu sudah saya uraikan sedikit dalam tulisan ini. Terutama yang berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan dan ekstraksi air tanah dalam.
Memang ada faktor-faktor penyebab lain yang skala sifatnya lebih luas, seperti perubahan iklim yang memengaruhi curah hujan. Saya menganggap faktor ini juga masih dapat dilihat sebagai bagian dari interaksi manusia dengan non-manusia.
Jadi, dengan menyebutnya memiliki skala lebih luas, bukan berarti saya menyebutnya sebagai faktor yang tidak memiliki sebab-akibat dengan manusia. Maksud saya, perubahan iklim dapat terjadi karena adanya kontribusi manusia, termasuk saya di dalamnya, melalui jejak ekologi/karbon dalam hal produksi gas rumah kaca. Meskipun kalau dilacak, saya sebagai orang Indonesia tidaklah termasuk penyumbang emisi karbon yang besar. Ada banyak orang lain yang menyumbang emisi karbon yang lebih besar, misalnya warga di negara-negara macam Eropa Barat dan Amerika Utara.
Sampai di sini cuitan Haris Azhar masih dapat dilihat sebagai otokritik terhadap apa yang disebut “peradaban manusia”.
Dalam perkembangan ilmu-ilmu, misalnya geografi manusia (human geography), ada satu istilah yang mendapatkan tempatnya dalam diskursus, yaitu anthropocene. Dalam pemahaman saya, anthropocene adalah suatu pendapat yang mengidentifikasi perubahan zaman di mana pengaruh manusia terhadap lingkungannya, misalnya iklim atau penggunaan lahan, semakin nyata. Otokritik yang muncul secara logis menempatkan manusia sebagai “perusak” non-manusia (udara, air, tanah, air tanah, dan sebagainya).
Saya mau memperdalam ini. Rasanya bukan manusia secara keseluruhan yang merusak non-manusia, tapi sebagian manusia.
Saya ambil contoh kasus Lumpur Lapindo. Perbuatan manusia menyebabkan tenggelamnya desa-desa, pindahnya orang, dan berubahnya bentang alam. Dari bentang alam yang fungsional (kampung, sawah, pabrik, dan/atau pemakaman) menjadi bentang alam yang mendatangkan masalah (danau lumpur dalam tanggul yang sewaktu-waktu bisa jebol).
Manusia penyebab dalam kasus Lumpur Lapindo adalah manusia yang sangat spesifik, yaitu manusia yang berafiliasi dengan perusahaan minyak dan gas yang memiliki dan mengoperasikan Sumur Banjar Panji #1, yang di situ, menurut salah satu versi pendapat yang berkembang, telah terjadi pelepasan tekanan dari dalam formasi batuan ke dalam lubang bor (underground blowout), dan kemudian muncrat ke permukaan menyemburkan lumpur.
Dalam kasus ini, manusia spesifik itu berhasrat mendapatkan keuntungan melalui perusahaan minyak dan gas. Corak produksi mencari keuntungan seperti ini disebut kapitalisme; pemilik kapital/modal atau pemilik perusahaan minyak dan gas itu disebut kapitalis/pemodal. Dalam pandangan ini, istilah anthropocene terlalu umum untuk mendeskripsikannya. Bukan aktivitas manusia secara umum yang menyebabkan peristiwa Lumpur Lapindo, tapi manusia yang sangat spesifik, yaitu kapitalis. Jadi, lebih pas rasanya zaman yang melingkupi peristiwa Lumpur Lapindo dideskripsikan sebagai capitalocene, alias zaman kapitalisme. Dan dengan demikian, kritiknya bukan terhadap manusia secara umum, tapi pada kapitalis.
Begitu pula dengan banjir Jakarta. Misalnya kita urai salah satu penyebab terjadinya banjir kiriman, yakni semakin berkurangnya kemampuan ekosistem Puncak untuk menyerap air hujan. Salah satu penyebab pengurangan ini adalah karena adanya konversi penggunaan lahan di Puncak. Pemberitaan-pemberitaan di media telah menunjukkan contoh-contoh kalangan yang memiliki rumah atau villa peristirahatan di Puncak.
Termasuk di antara mereka adalah golongan para pejabat. Yang pernah saya temukan muncul di media ialah Wiranto (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024), Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta 1997-2007), Oetojo Oesman (Menteri Kehakiman 1993-1998), H.B.L. Mantiri (Pangdam IX Udayana Januari-Juli 1992), (Alm.) Basofi Sudirman (Gubernur Jawa Timur 1993-8), Radinal Mochtar (Menteri PU 1998), Ginandjar Kartasasmita (Menteri Pertambangan dan Energi 1993-1998), Djaja Suparman (Pangkostrad 1999-2000), dan Probosutedjo (adik tiri Soeharto).
Banjir jenis kedua, banjir lokal, juga dapat dilihat seperti itu. Misalnya grup Ciputra yang pendirinya baru saja meninggal dan pada 2019 masuk jajaran 20 orang terkaya di Indonesia. Dalam hal banjir Jakarta, peran sentral Ciputra dapat saya lihat pada pembangunan Pantai Indah Kapuk.
Sebelum tahun 1980-an, kawasan ini adalah kawasan hutan bakau dengan kemampuan menampung air mencapai 16 juta meter kubik. Namun, hutan ini kemudian dikonversi menjadi lapangan golf (76,2 hektare), fasilitas olahraga dan rekreasi (20,43 hektare), taman (86,5 hektare), perumahan (368,34 hektare), pergudangan (17,48 hektare), area bisnis (88,18 hektare), dan lain-lain (57,5 hektare). Secara keseluruhan, konversi itu mengurangi/menghilangkan kemampuan lahan menampung air.
Konversi penggunaan lahan di Puncak dan Jakarta Utara yang mengubah kawasan hutan penampung dan penyerap air menjadi peruntukan lain adalah dua dari sekian penyebab banjir Jakarta. Air yang turun tidak tertampung dan terserap, tapi langsung masuk ke saluran air dan sungai-sungai.
Kalau saluran air dan sungai-sungai tidak terpelihara karena penuh sampah atau sedimen, permasalahan akan semakin kompleks. Di satu sisi air hujan yang turun menunjukkan kecenderungan semakin banyak (karena perubahan iklim memperparah momen ekstrem hidrologi). Di sisi lain saluran-saluran banyak yang tak terpelihara. Keduanya saling memperkuat, dan resultante yang sangat masuk akal adalah banjir.
Sekarang banjir jenis ketiga yang datang dari laut. Dalam kombinasi penyebab kenaikan muka air laut + penurunan tanah, kenaikan muka air laut menyumbang kecil, sedangkan penurunan tanah lebih besar sekitar 20 kali. Di beberapa lokasi, tanah turun lebih dari 10 cm/tahun, sementara angka kenaikan muka air laut yang sering saya temukan di berbagai publikasi sekitar 0,5 cm/tahun. Dengan besaran ini, perhatian lebih layak dialamatkan pada penurunan muka tanah.
Mengapa muka tanah di Jakarta turun? Para pakar mengidentifikasi penyebabnya meliputi: ekstraksi air tanah dalam, pembebanan bangunan, pengompakan material sedimen, dan aktivitas tektonik. Dari keempat faktor ini, sependek yang dapat saya amati, yang menjadi fokus penelitian (sekaligus perdebatan) adalah ekstraksi air tanah dalam dan pembebanan bangunan.
Diskusi/debat persisnya berada di seputar “Seberapa jauh keduanya menyumbang penurunan tanah di Jakarta?”. Ada pakar/praktisi yang menyatakan penyebab dominannya adalah ekstraksi air tanah dalam. Ada pakar/praktisi yang menyebut pembebanan bangunan. Ada juga pakar yang menyampaikan adanya variasi: di satu tempat penyebab dominannya adalah ekstraksi air tanah dalam, di tempat lain pembebanan bangunan.
Yang menyebabkan penurunan tanah adalah ekstraksi air tanah dalam, bukan air tanah secara umum. Di Jakarta, air tanah dengan kedalaman lebih dari 40 m biasanya disebut air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah dengan kedalaman kurang dari 40 m.
Model hidrogeologi ada yang menunjukkan bahwa aquifer (batuan sarang air tanah) di bagian utara Jakarta telah berubah dalam rentang waktu sekitar 1 abad. Pada 1900-an, di bawah tanah Jakarta Utara air tanah bergerak dari bawah (aquifer dalam) ke atas (aquifer dangkal). Di tahun 1990-an, yang terjadi adalah sebaliknya, air tanah bergerak dari atas (aquifer dangkal) ke bawah (aquifer dalam). Ini artinya air tanah di aquifer dalam semakin berkurang.
Faktor mana pun yang menjadi penyebab utama, ekstraksi air tanah dalam atau pembebanan bangunan, keduanya bisa diperas lagi menjadi satu hal: soal pembangunan yang masif di Jakarta. Beban-beban bangunan muncul dari gedung-gedung pencakar langit. Sementara mayoritas pengekstrak air tanah dalam adalah sektor bisnis dan industri (mal, hotel, apartemen, pabrik bir). Poinnya, ekstraksi air tanah dalam hanya berkemungkinan kecil bisa dilakukan warga dengan rumah biasa, apalagi warga miskin kota. Alasannya sederhana, membor air tanah dalam itu mahal.
Dari paparan mulajadi (genealogi) ketiga banjir di Jakarta ini, meski tentu saja banyak faktor-faktor lain yang belum didiskusikan, terlihat bahwa peran manusia (“ulah kita” dalam cuitan Haris) tidaklah sama. Saya tidak punya rumah atau vila di Puncak, tidak mengonversi penggunaan lahan secara masif di dalam kota, tidak mengekstrak air tanah dalam, juga tidak punya gedung besar/tinggi yang menyumbang beban ke tanah Jakarta. Haris tampaknya juga tidak.
Jadi, Haris dan saya (“kami”) memiliki “ulah” lebih kecil dalam memproduksi banjir di Jakarta. Yang memiliki ulah lebih besar adalah para pemilik vila di Puncak itu, orang-orang yang mengganti penggunaan lahan secara masif di dalam kota itu, dan para pengekstrak air tanah dalam yang kemungkinan besar adalah juga para pemilik/pemakai gedung-gedung tinggi/besar.
Kalau diringkas, hubungan produksi dan eskalasi dampaknya berjalan sebagai berikut.
Yang berperan besar dalam produksi banjir di Jakarta adalah kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, yang mana mayoritas mereka melakukannya untuk kesenangan (vila peristirahatan di Puncak) dan akumulasi kapital (oleh sektor bisnis di dalam kota ataupun persewaan vila di Puncak). Dalam studi-studi terhadap dampak bencana banjir perkotaan, sudah sangat lazim terlihat bahwa kelompok yang terdampak relatif paling parah adalah kelompok-kelompok rentan macam orang tua, anak-anak, perempuan, dan orang miskin.
Artinya satu. Kelompok rentan harus menanggung akibat dari kesenangan dan akumulasi kapital kelompok elite politik dan bisnis.
Solidaritas seperti yang dicuitkan oleh Haris Azhar memang perlu dan harus. Mungkin momen banjir seperti ini memang bukan momen yang tepat untuk menyalahkan. Dalam bahasa Haris Azhar “bukan waktunya menyalahkan”. Karena kan dilematis juga. Pada saat orang terkena musibah banjir, pada saat orang butuh bantuan berupa selimut atau bahan makanan dan obat-obatan, saya malah mengidentifikasi para pihak yang saya anggap sebagai menyumbang besar terhadap produksi ruang Jakarta yang banjir.
Saya bukannya tidak peduli dengan kondisi dilematis itu. Hanya saja saya berpendapat bahwa niat baik, kebutuhan bersolidaritas, dan pilihan momen untuk tidak menyalahkan jangan sampai membuat nalar kita tumpul; tidak tajam dalam menganalisis bagaimana ruang Jakarta yang banjir itu diproduksi, terutama oleh siapa dan dengan eskalasi dampak yang paling kuat terhadap kelompok mana.
Jangan sampai niat baik itu justru menjadi tempat/alat/kendaraan bagi para perusak ekosistem Puncak, kota, dan air tanah dalam Jakarta untuk bersembunyi dari perbuatan-perbuatannya yang sudah menyumbang kontribusi dalam bagaimana ruang Jakarta yang banjir diproduksi.
Dengan pemikiran seperti inilah maka saya menyebut cuitan Haris mendepolitisasi permasalahan banjir Jakarta. Saya sebut mendepolitisasi karena dapat diperlihatkan bagaimana proses-proses yang sangat politis (perubahan penggunaan lahan, pembangunan gedung-gedung raksasa yang masif, ekstraksi air tanah dalam) memproduksi ruang Jakarta yang banjir, namun cuitan seperti itu tidak mengkonfrontasi secara frontal peristiwa produksi yang sangat politis ini. Sebaliknya, melalui seruan solidaritas, malah menciptakan ruang untuk para pelaku buat bersembunyi.
Dan itu yang kemudian benar-benar terjadi. Lebih jauh, mereka bukan hanya bersembunyi, tapi berusaha mengkapitalisasi ruang tersebut. Seperti yang sudah disinggung sedikit di atas pada bagian status Facebook JJ Rizal, telah terarsip di media daring pada tanggal 11 Januari 2020, HPPBI berniat meminta ganti rugi atas peristiwa banjir.
Di sini, kebalikan dari cuitan Haris Azhar, status JJ Rizal melakukan konfrontasi frontal, merepolitisasi momen banjir. JJ Rizal menyoal pendirian mal seperti Mal Taman Anggrek yang menjadi contoh di media daring sebagai mal yang tidak beroperasi karena banjir. Bahwa Mal Taman Anggrek yang selesai dibangun pada 1996, justru didirikan pada area Hutan Kota Tomang yang menurut Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 merupakan “hutan kota” atau bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pendirian Mal Taman Anggrek telah mengkonversi “hutan kota” yang merupakan bagian dari eksositem kota fungsional yang bisa menahan dan menyerap air hujan menjadi “beton kota” yang cenderung akan mempercepat aliran permukaan yang akan berujung pada banjir. Selain karena beban/berat dari gedung mal itu sendiri, kalau Mal Taman Anggrek memakai sumur air tanah dalam (dugaan saya, iya), perannya sebagai penyebab banjir bisa disebut makin berlipat-lipat.
Dengan kata lain, status JJ Rizal menyoal, kok kelompok pengusaha mal yang justru adalah aktor penting dalam bagaimana ruang Jakarta yang banjir diproduksi sekarang berniat meminta ganti rugi? Alias: Penyebab/pelaku kok sekarang mengklaim sebagai korban?
Entah karena terpengaruh oleh repolitisasi warganet seperti yang dilakukan JJ Rizal atau tidak, yang jelas, secara kronologis, di media daring pada 13 Januari 2020 terbaca bahwa kelompok HPPBI melakukan klarifikasi. Mereka tidak menuntut ganti rugi atas dampak banjir, tapi meminta kompensasi pengurangan pajak.
Ke depan, dalam hemat saya, yang dibutuhkan adalah model-model repolitisasi frontal seperti yang dilakukan JJ Rizal. Secara lebih persis, yaitu membedakan manusia secara keseluruhan dengan kapitalis, serta membedakan penyebab/pelaku dengan korban.
BACA JUGA Membaca Peristiwa 1965 dari Perspektif Perebutan Sumberdaya atau esai BOSMAN BATUBARA lainnya.