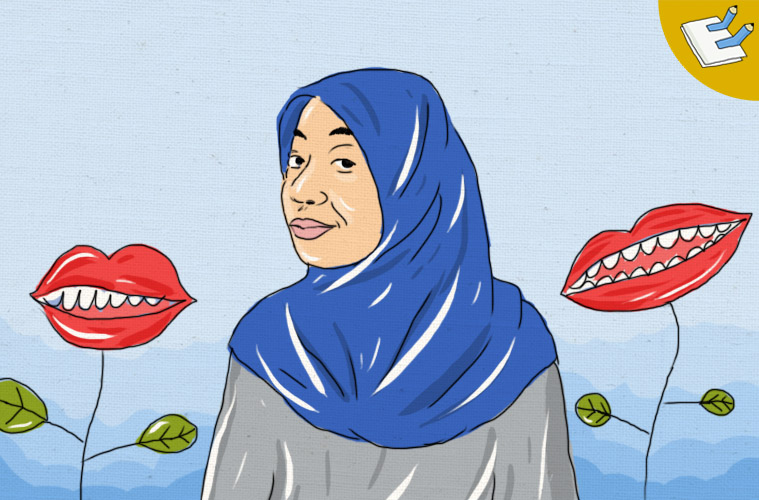Menjadi perempuan yang bebas bicara adalah kemewahan. Di Indonesia dan banyak bagian dunia lain, kemewahan itu masih terbatas pada forum-forum diskusi tertutup atau panggung pertunjukan. Di luar itu, bisa-bisa kita dicap perempuan nggak bener.
Mei lalu saya diundang ke acara stand–up comedy perempuan bertajuk #PerempuanBerHAK di Teater Bulungan, Jakarta Selatan. Penampil malam itu adalah Sakdiyah Ma’ruf, Alison Thackray, Jessica Farolan, Fathia Sari Puspita, dan Ligwina Hananto.
Publik mengenal Sakdiyah Ma’ruf sebagai seniman dan penerjemah. Saya membaca pengantar tesis masternya tentang comedy jihad. Tesis itu bercerita tentang bagaimana muslim di Amerika memulai pertunjukan-pertunjukan stand up comedy sebagai respons terhadap publik Amerika yang semakin antipati kepada Islam.
Situasi Amerika sesudah 9/11 memang sulit bagi muslim. Semua yang berjenggot, berhijab, memiliki nama Muhammad atau bau Arab lainnya akan diteriaki sebagai teroris. Terlalu banyak kecurigaan konyol yang ditujukan kepada muslim Amerika di pasar, sekolah, bandara, dan jalanan sehingga masyarakat muslim hampir-hampir tidak menemukan cara untuk membela diri.
Di tengah situasi sulit itulah Amerika memunculkan Dean Obeidallah, Hasan Minhaj, dan kawan-kawan mereka yang memutuskan untuk melawan keadaan dengan menertawakannya. Ya, Dean akhirnya mengajak muslim Amerika bersama-sama menertawakan kondisi mereka lewat stand up comedy. Show pertama mereka bisa dibilang sebagai sebuah revolusi!
Menertawakan kesedihan sepertinya memang manuver penting untuk bertahan.
Itu mirip yang dilakukan Marjane Satrapi, feminis Iran berkewarganegaraan Prancis lewat Persepolis dan karya-karyanya yang lain. Satrapi merdeka mengantar ide perlawanan lewat satire.
Saya sendiri mencoba melakukan hal yang sama—menulis kritik lewat seni bercanda—di situs Mojok.co. Ya, tidak semua penulis Mojok punya motivasi yang sama memang. Tiap penulis punya identitasnya masing-masing.
Sebelum pertunjukan #PerempuanBerHAK, di ruang make-up saya mewawancarai Ligwina Hananto. Ligwina bilang, “Aku adalah ibu untuk anak-anakku. Aku juga istri dari suamiku. Tapi, ada saat-saat tertentu di mana aku adalah seorang Ligwina. Aku memiliki profesi dan pandangan politik pribadi yang berbeda dari suami. Di Indonesia, kadang-kadang hal ini belum begitu diperhatikan. (Bahwa) Seorang Ligwina boleh berbeda pendapat dengan suaminya.”
Materi Ligwina malam itu cair sekali. Misalnya, ia curiga semua pengarang dongeng putri-putrian di dunia adalah laki-laki. Sebab, kalau perempuan, ketika Cinderella buru-buru pergi pukul 12 malam, sepatunya nggak bakalan ketinggalan. Perempuan mana yang rela sepatunya hilang?
Sementara Alison yang memiliki sebuah sekolah di Bandung sempat curhat. “Aku tinggal di Bandung sudah belasan tahun. (Aku) Biasa saja dengan identitas buleku ini. Tapi, akhir-akhir ini aku merasa Bandung sudah berubah. Sering ketika aku lewat, orang-orang berani memandang sambil berbisik-bisik soal pakaianku. Padahal aku masih memakai t-shirt dan celana pendek biasa. Ya, aku harus pakai apa? Aku kan kafir,” kelakarnya.
Pertunjukan malam itu betul-betul mendebarkan. Beberapa kali saya, yang duduk di antara Arie Kriting dan Hannah Al Rashid, berpandang-pandangan dan geleng-geleng kepala.
“Justru yang harus dipertanyakan, laki-laki yang ML sama gue selama 13 tahun ke belakang ini, mereka ngerti nggak agama mereka? Gue fucking mereka nggak ada batas, sah-sah aja dari sisi gue. Tapi, kalau mereka, perasaan nggak boleh deh fucking sama gue.”
Kalimat nakal, menggelitik, dan bikin sensi itu benar-benar dinyatakan Alison di panggung! Saya jadi ingat cerita seorang teman yang murtad dari Islam dengan alasan jadi muslim itu sulit. Kewajibannya salat lima kali sehari, aturan fikihnya banyak, sumber dosanya banyak. Benar-benar alasan yang polos tapi nyata.
“Pacarmu kan bule, kamu pasti berbuat hal-hal yang tidak kita lakukan,” kata Fathia, menirukan seorang kawannya. “Sama saja kok dengan kalian,” lanjut Fathia yang pada malam itu berbicara dalam bahasa Inggris. Ketika temannya tidak percaya, Fathia memberi skakmat walau lebih sering dalam batin, “Anggaplah aku matre seperti anggapan kalian. Aku lebih bermanfaat karena morotin pacarku buat mengembangkan desaku. Kamu berbuat apa dengan pacarmu?”
Saya memberi standing aplause berkali-kali untuk materi janda yang dibawakan Alison, atau materi soal perawan tua yang dibawakan Fathia.
Materi Jessica yang penuh istilah perkelaminan malam itu sialnya semua benar. Soal lelaki berpoligami pakai alasan istrinya gagal memberinya keturunan laki-laki (ya ampun, saya baru-baru ini dapat cerita bahwa peristiwa seperti itu sering terjadi di kalangan bos perusahaan besar, kiai terkenal, ataupun keluarga ningrat, persis di film-film). Padahal, secara biologis, sperma ayahlah yang menentukan jenis kelamin janin. Kemudian soal keperawanan yang dianggap simbol moral dan keberhargaan perempuan, padahal ketebalan selaput dara bervariasi dari orang ke orang.
Para comic perempuan ini memang keterlaluan beraninya. Semua satire dan sarkasme yang mereka lempar di panggung adalah materi yang “berbahaya” jika didengar telinga-telinga yang tidak siap. Tapi, di gedung teater itu, semua orang sekaligus bisa tertawa. Entah tawa solidaritas atau ketawa bareng buat hidup yang sialan.
“Bagiku, komedi almost relijius. Jika boleh me-ranking, mungkin Louis C. K. adalah tokoh idolaku setelah Nabi Muhammad,” kata Sakdiyah suatu kali kepada saya.
Selain Ligwina, para penampil malam itu memang bisa disebut perempuan marjinal dalam komunitas mereka masing-masing. Sakdiyah yang keturunan Arab, Jessica yang Tionghoa, Fathia yang terbebani stigma “perawan tua” bekerja sebagai karyawan sebuah hotel bintang lima, dan Alison Thackray yang sudah bule, kafir, janda lagi!
Saya kemudian paham bagaimana komedi sebagai seni kritik ini bekerja. Saya jadi paham kenapa ketika menonton Indonesia Lawak Klub orang bisa terhibur. Saya juga paham mengapa banyak orang menikmati membaca Mojok. Tetapi, tentu saja setiap hal di dunia ini tidak bisa diterima semua orang, apalagi seni, salah satu wilayah yang menurut Jakob Sumardjo punya filsafatnya sendiri.
Banyak orang yang tidak bisa memahami komedi. Banyak orang yang tidak merasa nikmat dalam bercanda. Sebagaimana banyak pula orang yang salah paham dengan kalimat-kalimat Gus Dur sebelum berhasil menelannya secara utuh.