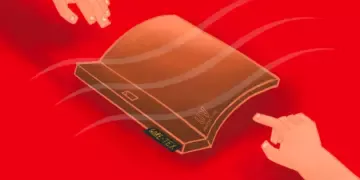MOJOK.CO – Kejahatan bisa datang dari kesalehan. Seperti aksi teroris yang terjadi di Sigi, di mana pemerintah kelewat lama mengabaikan benihnya.
Semua tahu bahwa peristiwa pemenggalan kepala dan pembakaran gereja di Sigi pada 27 November lalu dilakukan oleh teroris. Semua juga sepakat bahwa teroris ini harus ditindak tegas.
Selesai. Tak ada perkara. Aparat pun kabarnya juga sudah turun tangan. Tim telah diterjunkan untuk memburu penjahatnya.
Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menjadi tersangka utama. Saksi kunci mengidentifikasi sejumlah nama ketika ditunjukkan foto-foto, dan mengonfirmasikan hal tersebut.
Sisa-sisa tanzhim jihadi yang berbaiat kepada ISIS tersebut rupanya masih mampu melancarkan serangan sporadis. Operasi Tinombala selama lima tahun terakhir ini masih belum mampu melenyapkannya.
Mereka memang punya ideologi seperti itu. Mereka menamakan dirinya sebagai salafi jihadi –aliran yang sama yang dianut oleh kelompok-kelompok teroris global.
Bolehlah masyarakat menyebut teroris tak punya agama, tapi dalam konteks untuk mengidentifikasi mereka, ya harus dipelajari betul ideologi mereka. Apa yang menggerakkan mereka, dan memampukan mereka melakukan kekejian seperti itu.
Mengutip penulis Umberto Eco, kejahatan itu bisa datang dari kesalehan. Dan ini mau tidak mau harus diakui bersama. Semua agama mempunyai sisi kelamnya masing-masing.
***
Peristiwa teror di Sigi ini sebenarnya juga merefleksikan hal lain. Yakni, buruknya tata beragama di Indonesia. Untuk sisi ini, rapot pemerintahan Jokowi sama nilainya dengan soal revisi UU KPK, penanganan Covid-19, dan Omnibus Law: sangat buruk.
Hingga beberapa hari berselang, Presiden Jokowi masih saja diam membisu tak mengeluarkan statement atau perubahan kebijakan yang intinya lebih melindungi kehidupan beragama di Indonesia. Baru tiga hari kemudian, pada Senin (30/11) malam, Jokowi berpidato mengutuk aksi tersebut.
Meski begitu, pidato tersebut masih tetap saja tak memuat janji atau strategi tentang tata beragama di Indonesia. Tidak ada road map yang ditawarkan menuju tatanan beragama di mana semua pemeluk agama bisa menjalankan ibadahnya dengan baik.
Batasan dan guidelines yang jelas soal pembangunan tempat ibadah. Atau bagaimana strategi untuk melawan persekusi agama dari “orang-orang saleh” yang sering terjadi selama ini.
Sebelumnya yang muncul hanya pernyataan normatif dari Menko Polhukam saja. Bandingkan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Yang meski kontroversial, dia langsung tampil mengeluarkan pernyataan.
Atau contoh yang tidak kontroversial, yakni PM Selandia Baru Jacinda Ardern ketika terjadi aksi terorisme di Christchurch. Dia langsung mengenakan kerudung dan menemui keluarga korban.
Kenapa respons pemerintah terhadap peristiwa di Sigi perlu dibandingkan?
Karena akhir Oktober lalu, Presiden Jokowi didampingi pengurus MUI menggelar konferensi pers mengecam pernyataan Macron. Lengkap dengan bumbu yang menyebutkan MUI siap mengajari Perancis soal toleransi beragama.
***
Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling parah terpapar paham radikal. Celakanya, pengelolaan tata beragama di Indonesia, justru memperburuk situasinya.
Ada banyak contoh kasus untuk itu. Pengusiran penganut Ahmadiyah yang diselesaikan dengan SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung yang isinya justru “menyalahkan” penganut Ahmadiyah.
Pembubaran misa tak terhitung berapa kali. Persekusi kelompok mayoritas terhadap agama minoritas juga kerap didengar. Pelarangan pendirian tempat ibadah. Coba saja mengurus izin pendirian gereja di Bogor atau di Bekasi. Sangat sulit sekarang ini.
Alih-alih berupaya menegakkan aturan yang tegas dan adil untuk semua agama, pemerintah cenderung mengakomodasi kelompok Islam “intoleran”. Akomodasi ini bahkan dilakukan secara terang-terangan.
Perhitungan yang dipakai adalah perhitungan khas utilitarianis fanatis dengan kalkulus kebahagiaannya. “Memberi manfaat yang terbesar untuk kepentingan kelompok yang terbanyak.” Sebuah pilihan yang jelas-jelas tidak berpihak ke kelompok minoritas.
Bahkan, bukan hanya sekadar tidak berpihak, tapi juga sampai membahayakan nyawa. Saya, Anda, atau siapa pun, yang nanti kebetulan menjadi minoritas, akan sulit mendapatkan perlindungan di negeri ini.
Yang lebih menyakitkan lagi, bahwa akomodasi terhadap “orang saleh” di kelompok-kelompok Islam ini ditengarai dilakukan hanya karena kepentingan politik. Untuk dukungan politik dan tambah-tambah suara.
Kadang juga digunakan sebagai pion politik. Bisa untuk pengisruh suasana, bisa untuk pemecah perhatian, bisa untuk membuat gaduh dan menenggelamkan isu yang lebih gawat. Tergantung.
Kebijakan ini justru menyuburkan dan memberi ruang bagi kelompok-kelompok seperti ini untuk tampil. Pada gilirannya, kelompok ini berkembang sendiri, lalu bisa mandiri secara finansial, dan belakangan menjadi sulit diatur dan berubah menjadi lembaga vigilante.
Tapi, yang paling berbahaya dari sudut pandang terorisme, menguatnya arah ke kanan dalam pendulum politik ini membuat ideologi para pelaku ini makin sulit dideteksi.
Seorang perwira Densus 88 pernah mengeluh kepada saya. Bahwa ruang gerak mereka menjadi terbatas ketika melakukan penindakan.
“Nanti, bisa disebut memerangi Islam dan sebagainya. Harusnya yang lebih penting adalah deradikalisasi di tingkatan masyarakat. Ibaratnya, kami hanya membasmi kecoanya saja. Jika rumahnya tak pernah akan dibersihkan, ya kecoanya nggak habis-habis,” urainya panjang lebar.
Yang dimaksudkan perwira itu jelas. Membiarkan organisasi intoleran berkembang, setidaknya akan memberikan lahan subur bagi tanzhim jihadi aka organisasi teroris untuk berkembang pula.
Dan itu buahnya, teror mengerikan yang terjadi seperti di Sigi.
***
Setiap pemimpin pasti ingin berakhir dengan baik. Termasuk pula Jokowi. Memang tak selamanya apa yang dilakukannya buruk. Tapi, periode kedua ini menuai lebih banyak kontroversi. Daftarnya sangat panjang.
Memberikan false sense of security terkait Covid-19, komitmen soal hukum dan penindakan korupsi, beleid-beleid yang dikeluarkan lebih berpihak kepada oligarkhi (seperti Omnibus Law, ekspor benur, UU Minerba, dsb), dan ketidaksensitifan terkait tata beragama di Indonesia, membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya menurun drastis.
David Hume, filsuf Skotlandia, dalam buku Principles of Government, bilang bahwa, “Kekuasaan akan selalu berada pada rakyat banyak. Pada orang-orang yang diperintah. Maka Penguasa tidak memiliki dukungan bagi mereka sendiri, kecuali melalui opini.”
Artinya, Hume bilang soal legitimasi kekuasaan itu selalu berada di tangan rakyat. Bisa diambil kapan saja oleh yang punya (rakyat). Hanya pemerintah tampaknya juga tahu betul ini, dan memainkan opini melalui buzzerp. Tapi pertanyaannya sampai kapan?
Buzzerp mungkin bisa memoles atau menahan, tapi ekses kebijakan buruk akan terjadi terus dan terus.
Dan ketika itu terjadi terlalu banyak, dan rakyat makin banyak yang protes, maka Jokowi akan dikenang sebagai presiden dengan catatan yang sangat buruk sekali.
Membuat malu yang mencoblosnya dua kali dalam pilpres, di antaranya saya. Iya, saya. Haaadehhh.
Semua buah reformasi sudah nyaris hilang semua di masa kepemimpinannya. Desentralisasi kembali ke resentralisasi dengan Omnibus Law. Pemberantasan korupsi yang terlihat makin pesimistis. Oligarki yang ada justru makin menguat.
Ditambah dengan kegagalan merespons Covid-19, mengelola persoalan intoleransi beragama, dan kini dihadapkan pada urusan ektremis “orang-orang saleh” di Sigi.
Hm. Coba mana, sini pengen lihat, mana itu orang-orang yang kemarin bilang katanya mau ngajarin Perancis soal toleransi agama.
Pfft.
BACA JUGA Kepala Orang Dipenggal di Sigi dan Citra Islam yang Dibajak Lagi dan tulisan Cak Kardono lainnya.