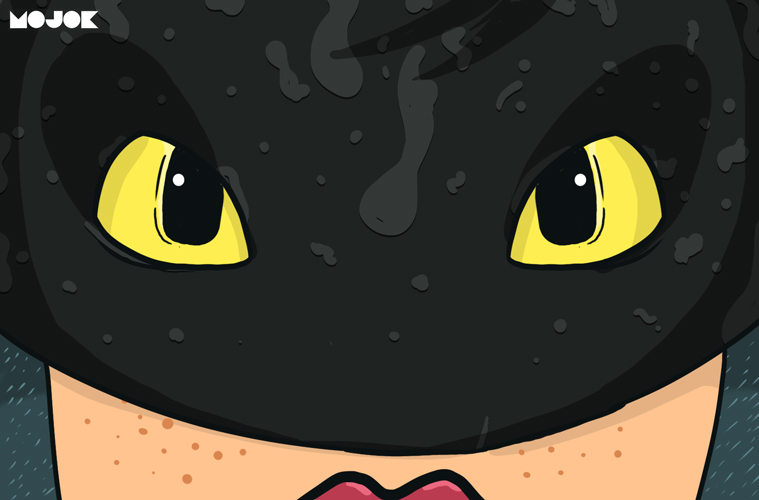MOJOK.CO – Ini adalah kisah saya sendiri di tengah kehidupan malam kota Semarang. Ketahuilah, sesungguhnya ada banyak dimensi kehidupan di sekitar kita yang tak perlu dihakimi.
Malam mulai naik ketika kami tiba di penginapan. Aku tidak tahu bagaimana menyebut tempat ini; motel atau hotel—yang bahkan dibilang kelas Melati pun belum bisa. Meski begitu, tempat ini cukup ramai dengan pengunjung muda yang hanya beberapa tahun sedikit lebih tua dibanding kami.
Aku mengekor dua teman lain yang mengatur pemesanan menuju kamar kami. Sempit dan menyesakkan. Tidak ada jendela, apalagi AC. Hanya kipas angin kecil yang kalah telak melawan udara panas Semarang. Kalau tidak terpaksa, aku pasti memilih kembali ke Solo saat itu juga. Tapi mengabari Ibu kalau anaknya berada dalam perjalanan menjelang tengah malam tampaknya bukan ide yang bagus. Lebih baik akbermalam di sini sebelum besok kembali pagi-pagi sekali.
Jam delapan malam, kedua temanku menawari makan ke luar. “Sekalian cari udara,” kata mereka. Keduanya pasti cukup frustasi karena tidak bisa merokok di sekitar kamar yang 3S: sempit, sumpek, dan sumuk. Daripada harus turun ke lobi untuk sebats, lebih baik sekalian jalan-jalan menikmati angin malam Semarang.
Aku yang menolak gabut sendirian di kamar 3S itu memilih bergabung dengan mereka, meskipun tahu konsekuensinya akan pulang larut malam. Lagi pula kapan lagi bisa jalan malam begini? Kalau di Solo, bisa-bisa aku disidang pengurus kos muslimahku! Hehe.
Malam semakin tinggi ketika kami memasuki kawasan Kota Lama. Sepertinya, saat itu hampir jam 12 malam ketika kami melewati deretan tenda di pinggir jalan. Kalau di Solo, warung seperti itu biasa kukenali sebagai hik, tempat nongkrong mahasiswa minimalis sambil berdiskusi macam-macam. Atau kalau buat ukhti sepertiku, tempat beli nasi kucing dan teman-temannya ketika esok hari mau puasa dan malas memasak buat sahur.
Tapi tenda-tenda yang mirip hik itu tidak menjual nasi kucing. Tenda-tenda di hadapan kami begitu riuh menyuarakan musik karena ternyata itu tempat karaoke. Aneh juga, pikirku. Bagaimana kita bisa syahdu menyanyi kalau “kamar karaoke” berdempetan tanpa kedap suara begitu?
“Itu karaoke plus plus,” kata temanku, mengurai kerut di balik jilbabku.
“Oh, I see.”
Pantas saja hawa di sini agak beda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan hawa yang berbeda itu. Tapi jujur, bagi muslimah yang sangat asing dengan kehidupan malam, berada sedekat itu dengan kawasan plus-plus membuatku merasa insecure. Untungnya, kedua temanku berbaik hati mempersilakanku berjalan di tengah, alias diapit keduanya. Hehe.
Pengelola karaoke tenda itu mayoritas sudah lanjut usia—mungkin hanya beberapa tahun lebih muda dari ibuku yang saat itu berusia lima puluhan. “Tapi kenapa mereka masih bekerja seperti itu? Di mana anak mereka?” pikirku naif. Toh ibuku juga masih harus bekerja untuk menambah biaya hidup kami setelah meninggalnya Bapak.
“Yang jajan di sini biasanya anak sekolah. Bayarnya juga seadanya,” kata temanku lagi, sekaligus menjelaskan berhentinya sebuah motor di salah satu tenda. Dilihat dari tampilannya, pengendara yang mulai bercakap dengan ibu pengelola karaoke itu jauh lebih muda dariku. SMA, atau mungkin masih SMP.
“Padahal kalau yang jajan anak sekolah begitu bikin rugi. Duit nggak seberapa, masih nawar, nggak mesti aman juga.”
Teman-temanku masih mengobrol tapi suara mereka hilang di rimba pemikiranku. Seperti ada sesak di dada yang melebihi sesak kamar penginapan kami melihat dua manusia di tenda karaoke bernegosiasi.
Kalau mau selow melihat mereka dari kacamata bisnis, pemandangan itu biasa saja: seorang konsumen yang sedang nego harga dengan produsen. Kalau oke, deal, proses jual beli jasa terlaksana.
Sayangnya, aku yang baperan melihat mereka dalam peran-peran sosial yang lain. Seorang ibu yang sedang bekerja untuk keluarganya, dan seorang anak yang entah bagaimana memilih menyelesaikan hajatnya pada perempuan yang lebih pantas menjadi ibunya.
Aku mencoba tampak woles dengan terus melanjutkan perjalanan. Di sekitar jembatan (atau di mana tepatnya aku lupa), beberapa ratus meter dari kawasan karaoke plus-plus, kami menjumpai banyak anak muda nongkrong.
“Semarang memang nggak ada matinya,” batinku, teringat tempat tinggalku di desa yang sudah pasti senyap di jam segini.
“Mikir a! Arek jilbaban ngene ditawari!” kata temanku berteriak dalam logat jawa timurannya, sambil menarikku kembali berjalan di tengah.
“Eh?” Aku yang tadi sibuk melamun jelas bingung dan bertanya pada teman satunya.
“Tadi kamu ditawari ‘jajan’ sama mas-mas yang di dekat motor itu.”
“Astaghfirullah!” aku auto-istighfar. Hanya karena berjalan-jalan di malam hari, mereka pikir aku bebas ditawari hal semacam itu. Padahal pakaianku masih utuh dengan jilbab lebar, rok panjang, plus kaos kaki tebal!
Aku merasa direndahkan. Pelecehan memang tidak mengenal tampilan yang dikenakan. Toh mbak-mbak di sekitarku, yang nongkrong di atas motor masing-masing, juga berpenampilan cenderung menutup. Nggak provokatif, kalau kata orang-orang.
“Mereka jualan juga?” tanyaku merujuk pada para perempuan pengendara matic yang tersebar di sepanjang jalan. Temanku mengangguk, lalu menjelaskan cara kerja pasar di sini.
Tidak seperti tenda karaoke, konsumen perempuan matic ini kebanyakan bermobil dan tampak lebih matang. Mereka akan mendekati salah satu mbak incarannya, mengobrol sebentar, lalu pergi diikuti perempuan yang terpilih. Produsen di pasar ini juga lebih muda dan berpenampilan menarik.
Kalau menurut prinsip “ana rega ana rupa”, tentu tarif mereka juga lebih tinggi. Mungkin pilihan tempat kerja mereka juga jauh lebih baik daripada kotak sempit tenda karaoke. Bisa jadi, para pelanggan mereka juga mau lebih bermodal dengan beli pengaman. Meski begitu, rasa sesak tadi yang mestinya hilang dengan angin segar di sepanjang jalan tidak juga berkurang.
Kami masih berjalan ketika beberapa meter kemudian kujumpai sekelompok laki-laki berbaju koko lengkap dengan sarung dan pecinya keluar dari mobil. Aneka asumsi memenuhi kepalaku sebelum lelaki terakhir (kecuali supir) keluar dengan sekotak nasi bungkus dan membagikan kardus lain dengan isian sama pada teman-temannya. Mereka mulai bergerak membagikan makanan pada tunawisma yang sepanjang jalan memang banyak kutemui tidur di emperan bangunan.
Ada rasa sesak baru yang menyeruak masuk ke dadaku. Rombongan putih-putih ini datang dengan makanan, bukannya pentungan. Mereka bahkan tidak berceramah atau mencekal “pasar manusia” yang hanya beberapa meter dari tempat mereka bersedekah. Mereka kerja berdampingan tanpa gontok-gontokan. Aneh sekali bagiku yang anak LDK saat itu.
Kenapa para akhi itu tidak mendakwahi saudara-saudara mereka yang bekerja penuh kemaksiatan? Kenapa mereka diam saja dengan praktik prostitusi yang hanya beberapa meter darinya, dan justru dengan tenang membagikan nasi bungkus untuk tunawisma? Apakah mereka pikir perbuatan baik dari sedekah itu cukup sebagai hujjah untuk tidak mencegah kemungkaran?
Aku hampir berprasangka lebih jauh sebelum temanku menepuk pundakku dan mengajak putar balik menuju penginapan.
Sepanjang malam aku sulit tidur. Bukan hanya karena kamar yang sumpek-sempit-sumuk, tapi juga karena pemandangan kehidupan yang kulihat sepanjang jalan tadi. Rasanya sedih dan sesak sekali, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya tahu kalau banyak sekali yang belum kuketahui. Selama ini aku hanya mengecam hal-hal yang kusebut kemaksiatan dalam diam, tetapi ketika berpapasan langsung dengannya, aku mendadak bungkam.
Bukan, ini bukan karena aku tidak lagi meyakini standar kebenaranku, tapi karena paham bahwa sekalipun keyakinanku benar, ada banyak dimensi kehidupan yang lebih membutuhkan uluran tangan sebagai bantuan, bukan tamparan.