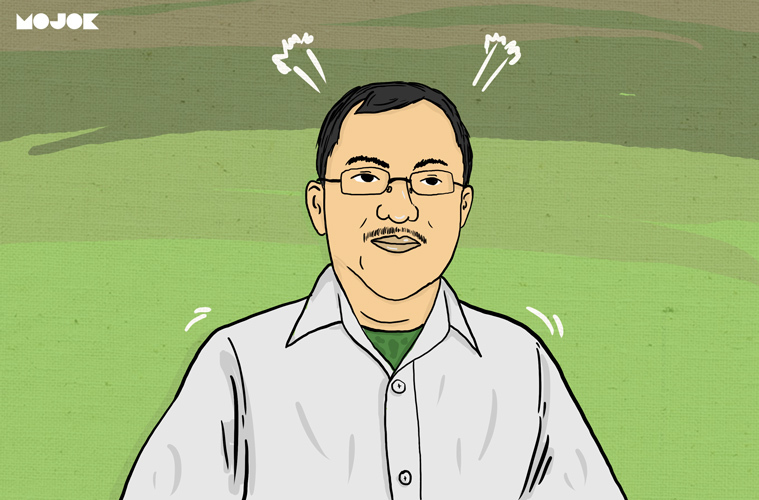MOJOK.CO – Kasus Dokter Terawan adalah kasus kesehatan kesekian yang menimbulkan kehebohan, tetapi lebih banyak berkisar pada rumor daripada kebenaran.
Pemecatan sementara dr. Terawan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat banyak pihak angkat bicara. Butet Kertaradjasa, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, anggota DPR, hingga pasien-pasiennya dikabarkan membela dr. Terawan. Rektor dan guru besar Universitas Hasanuddin, kampus tempat dr. Terawan mengambil S-3 mengenai metode “cuci otak” juga mempertanyakan pemecatan itu. Satu benang merah pendapat mereka: Banyak yang sembuh kok dipecat?
Pada saat yang sama juga terjadi persinggungan antar-institusi: IDI dan TNI Angkatan Darat. Dokter Terawan adalah perwira yang sekaligus kepala rumah sakit militer. Ketika dipecat sebagai dokter, apakah status direktur rumah sakit yang mensyaratkan status dokter itu menjadi illegitimate? Posisi dr. Terawan sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan menyebabkan masalah makin pelik.
Oke, itu tadi masalah institusi. Buat masyarakat, yang lebih relevan adalah benarkah metode cuci otak nggak ilmiah? Tapi, kenapa banyak yang sembuh? Wajar masyarakat bertanya demikian, lha wong memang tidak ada informasi, seperti berapa pasien dr. Terawan yang tidak sembuh, berapa pasien yang setelah di-“cuci otak” tetap tidak ngaruh apa-apa, dan berapa yang mengalami komplikasi merugikan.
Di media, informasi soal-soal itu sangat terbatas. Dokter Terawan dipecat dari IDI atas rekomendasi Majelis Kode Etik Kedokteran setelah proses sidang yang panjang. Tapi, materi sidang kode etik yang membahas hal ini secara mendalam tidak boleh dibuka secara luas.
Ini persoalan pelik. Teknik cuci otak hanya dipahami secara mendalam oleh para ilmuwan kedokteran papan atas. Dokter spesialis saja belum tentu memahami, apalagi dokter umum dan lebih lagi masyarakat. Masyarakat ya tahunya, ada teknik cuci otak di RSPAD yang bisa menyembuhkan atau mencegah penyakit. Titik. Soal ilmiah atau tidak, valid atau tidak, evidance-based atau tidak, jelas tidak masuk dalam pemikiran, toh yang melakukan adalah dokter.
Pada intinya, kasus dokter Terawan dan metode cuci otaknya sebenarnya cuma mengulang sejumlah kasus kesehatan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Kasus-kasus itu punya pola: bikin heboh media, beritanya tersebar di sana-sini, tapi pada dasarnya tidak mendapat informasi apa-apa. Masyarakat dibiarkan meraba dalam gelap tanpa ada pihak yang menjelaskan secara gamblang, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi?
Sebagai contoh, kita ambil kasus difteri, plastik dalam air, dan cacing dalam ikan.
Menurut info dari salah seorang rekan dokter spesialis anak, kasus difteri itu sebenarnya telah diwanti-wanti oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sekitar setahun sebelum menjadi wabah. Namun, informasi edukatif tidak sampai ke masyarakat dengan baik sampai kemudian masalahnya booming di media. Medialah yang memberi informasi, sedangkan gaung suara pemerintah tidak juga sampai ke telinga masyarakat secara luas sehingga masyarakat panik karena tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana memproteksi diri. Bahkan untuk melakukan vaksinasi pun masyarakat masih ragu karena kasus vaksin palsu dan efek samping vaksinasi tak kunjung clear.
Soal kasus plastik dalam air mineral juga demikian. Awalnya kasus dibuka oleh media, lalu masyarakat seperti dibiarkan mencari-cari sendiri jawaban melalui media. Setelah sekian lama, BPOM baru mengeluarkan info. Itu pun tenggelam dengan informasi-informasi yang tersiar di media sosial yang bejibun. Artinya, penjelasan kepada masyarakat tidak efektif.
Yang terbaru soal cacing dalam ikan. Setelah mengetahui dari media, teman saya yang sedang sekolah doktor kedua kalinya langsung gelisah… beli obat cacing untuk seluruh keluarganya karena agak sering konsumsi ikan kalengan sambil maki-maki di wall-nya tentang proteksi konsumsi masyarakat. Beberapa teman lain juga melakukan hal yang sama. Tidak juga segera mendapat penjelasan yang baik, masyarakat malah disuguhi pernyataan Bu Menteri soal cacing mengandung protein.
Tiga kasus tersebut memberi gambaran bahwa informasi sampai ke masyarakat dengan cara tidak efektif. Jangankan berharap informasi awal untuk pencegahan, bahkan saat kejadian pun, informasinya simpang siur. Artinya, pemerintah dan pihak pemegang otoritas keilmuan seperti tidak memiliki public relation yang baik. Jadi, siapa sebenarnya penanggung jawab informasi kesehatan untuk masyarakat?
Bukan berarti saya sebagai dokter merasa kerepotan untuk selalu menjawab pertanyaan dari keluarga besar saya mengenai kasus-kasus itu. Itu juga sudah tugas saya. Tapi, kalau pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, memiliki penyebar informasi yang efektif, masyarakat menjadi lebih teredukasi dan merasa aman. Mungkin Menkes perlu juru bicara atau mengoptimalkan Pusat Komunikasi Publik Kemenkes atau mengoptimalkan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat agar lebih mublik. Semua itu untuk menjamin informasi disiarkan dengan jelas dan mendidik. “Cacing mengandung protein” itu benar, tapi tidak memiliki nilai edukasi yang kontekstual, bahkan menimbulkan polemik dan keresahan.
Komunitas keilmuan dan profesional medis seperti IDI juga harus berperan. Penjelasan ilmiah populer patut dicoba agar masyarakat lebih mudah memahami hal-hal yang sebenarnya pelik, namun penting. Jangan biarkan masyarakat menduga-duga secara tidak proporsional seperti dalam kasus helm anti-kanker yang konon ampuh, tapi akhirnya dipatenkan di luar negeri. Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) sebagai wadah non-formal para dokter yang sering menyuarakan soal kesehatan juga bisa ikut berperan secara lebih membumi ke masyarakat.
Kita tahu, daya kritis masyarakat meningkat. Masyarakat akan mencari-cari informasi ke mana pun, pada siapa pun. Ini bagus sekaligus menantang. Tantangannya adalah, khususnya soal kesehatan, bagaimana menyediakan informasi yang benar dan tepat.
Sebaiknya masyarakat mencari informasi dari pihak berwenang sembari menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada ahlinya, baik dalam hal etik, hukum, maupun keilmuan. Masyarakat perlu cerdas membaca berita dengan landasan logika yang baik, membiarkan rumor tetaplah sebagai rumor, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kebenaran.
Soal metode cuci otak tak akan berhenti sampai di sini, apalagi dr. Terawan mendasari metodenya itu dengan hasil studi S-3. Komunitas ilmiah medis pasti akan menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas mendapatkan kebenaran. Menjaga persoalan ini tetap berada dalam koridor ilmiah adalah jalan terbaik untuk saat ini.