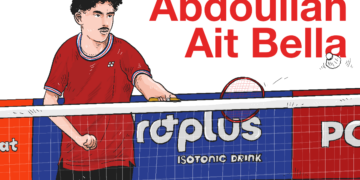MOJOK.CO – Karena poliglot tak pernah menyebut jumlah bahasa yang dikuasai, harusnya orang Indonesia itu poliglot semua, soalnya minimal bisa dua bahasa.
Menjadi poliglot tak melulu soal bakat dan kemauan belajar. Ada kemungkinan menjadi poliglot adalah semata mekanisme bertahan hidup mendasar untuk orang tertentu.
Anda mungkin pernah mendengar nama Wouter Corduwener. Kalau belum, bisa dicari videonya di YouTube. Pria berkebangsaan Belanda ini mengaku bisa berkomunikasi dalam 29 bahasa. Hal ini menjadikannya sebagai seorang poliglot, atau hiperpoliglot, tergantung definisi mana yang dirujuk.
Poliglot, dari bahasa Yunani yang berarti “berlidah banyak”, merujuk pada orang yang fasih dalam banyak bahasa. Tidak ada definisi yang universal yang menyebutkan berapa jumlah bahasa yang mesti dikuasai untuk seseorang bisa disebut poliglot. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang lima.
Lalu, untuk disebut sebagai hiperpoliglot ada yang bilang seseorang mesti menguasai lima, tujuh, sebelas, atau lebih bahasa.
Sebagai orang yang cuma bisa berkomunikasi dalam tiga bahasa, saya kagum benar dengan orang seperti ini. Sebab, dalam pengalaman saya belajar bahasa asing itu bukan soal mudah.
Saya pernah dua semester ambil kelas Bahasa Jerman dengan cukup berdarah-darah, dan kalimat yang kini tertinggal di otak monokotil saya cuman “Ich spreche Deutsch nicht”. Ini ekspresi yang ganjil sebenarnya. Lha wong niatnya ngasih tahu kalau saya nggak bisa ngomong Jerman tapi ngomongnya malah pakai bahasa Jerman.
Balik ke soal poliglot tadi, konon, salah satu sebab seseorang bisa menjadi begitu adalah kuasa alam, yakni terlahir dengan satu kualitas neurologis tertentu yang memungkinkan seseorang bisa mempelajari banyak bahasa dengan mudah dan menggunakannya dengan fasih.
Ada orang-orang yang memang istimewa seperti Wouter Corduwener, John Bowring dan Kenneth Hale. Nama terakhir, poliglot sekaligus linguis kenamaan dari Amerika Serikat, menguasai lebih dari 50 bahasa, termasuk bahasa-bahasa yang hampir atau sudah punah di Amerika dan Australia.
Kata salah satu muridnya, Kenneth Hale bahkan bisa “menyerap” bahasa baru hanya dalam waktu sepuluh menit duduk dengan orang yang berbahasa sama sekali asing baginya. Ngawu-awu, tenan!
Tapi apa bakat alam saja cukup? Ya tentu saja tidak toh bwoss!
Sejauh penelusuran saya yang tidak begitu ekstensif, mereka ini punya ketertarikan yang besar terhadap bahasa. Ketertarikan terhadap bahasa di luar bahasa ibu dipicu salah satunya oleh lingkungan multikultural. Selain ketertarikan terhadap bahasa, mereka ini punya privilese, punya kesempatan, punya daya dukung.
Kenneth Hale pergi ke Australia pada tahun 1959 dan 1960 untuk mempelajari bahasa Lardil dan Darmin. Darmin adalah satu-satunya bahasa decak (click language seperti dalam film The Gods Must Be Crazy) di luar benua Afrika.
Bayangkan, untuk bisa ke Australia dari Amerika pada tahun-tahun segitu berapa besar ongkosnya?
Dan melakukan penelitian dan belajar langsung dari suku pribumi di tempat mereka tidak bisa dilakukan sembarang orang. Perlu jadi orang “terdidik” dan ditopang sumberdaya yang lebih dari memadai. Kalau orangnya yang model internetan masih ngandelin wifi gratisan ya kayaknya tangeh lamun, impossible.
Apakah dengan demikian, menjadi poliglot itu melulu privilesenya mereka yang berdaya?
Tidak selalu. Kondisi “alamiah” tertentu memungkinkan orang menjadi poliglot.
Di negara semultikultural Indonesia, misalnya, keterpaparan seseorang atas banyak bahasa adalah mungkin belaka, kalau bukan niscaya. Tak heran jika ada laporan bahwa lebih dari 17 persen penduduk Indonesia fasih dalam tribahasa, rasio tertinggi di dunia.
Proses akuisisi bahasa untuk menjadi poliglot rupanya tidak selalu proses sukarela (voluntary) seperti dua konteks di atas. Baru-baru ini saya temukan, orang menjadi poliglot bisa juga karena terpaksa alias kepepet, sebagai sarana bertahan hidup.
Beberapa bulan lalu saya berkenalan dengan seorang mahasiswi dari Eritrea, sebuah negara kecil di timur laut Afrika. Mahasiswi berkerudung ini, sebut saja Sarah, memerlukan bantuan untuk menyelesaikan materi video presentasi. Itu memang salah satu tugas saya sebagai pegawai casual di perpustakaan kampus tempat saya kuliah.
Di sela-sela membantunya, kami bercakap-cakap sedikit. Dia bilang dia bisa berkomunikasi dalam delapan bahasa. Selain tiga bahasa daerah dari tempat asalnya yakni Tigre, Tigrinya dan Saho, dia lancar berbahasa Arab, Jerman, Turki, Perancis, dan Inggris.
Tiga bahasa daerah dia dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Dia sempat belajar di madrasah sehingga ia cukup lancar berbahasa Arab.
Empat bahasa sisanya dia pelajari saat dia dilabeli pengungsi. Konflik dalam negeri berkepanjangan mendorong orang tua Sarah memboyong keluarganya keluar dari Eritrea. Mereka tersaruk-saruk dari satu negara ke negara lainnya.
Sarah sekeluarga tanpa daya tinggal di negara asing sebagai paria. Tanpa kemampuan bahasa, dia tak akan bertahan di negeri orang. Terpaksalah dia belajar bahasa Turki demi bisa survive selama beberapa tahun di sana. Saat harus menggelandang di Jerman beberapa lama, dia mesti belajar juga bahasa Jerman.
Sarah tidak menyebutkan apakah dia pernah mengungsi ke Perancis di antara perjalanan sengsaranya itu. Yang jelas, dia baru mendapatkan visa untuk masuk ke Australia, sekitar tujuh tahun lalu.
Sekarang, dia sudah resmi menjadi warga negara dan harus menggunakan bahasa Inggris untuk bisa melanjutkan hidup di Australia—negara benua yang meskipun tak punya bahasa resmi, semua juga sudah paham secara de facto Inggrislah yang dipakai sebagai bahasa nasionalnya.
Waktu ngobrol sama Sarah saya terpikir untuk mengenalkan satu bahasa lain untuk membangun kedekatan, yakni bahasa kalbu. Tapi saya urungkan niat itu.
Saya teringat istri. Kalau dia sampai tahu, bisa-bisa saya dihapus dari muka bumi ini, persis seperti dihapusnya mural-mural curahan hati rakyat sengsara oleh deraan pandemi dan kebijakan penanganannya yang kita semua tahu seperti apa.
BACA JUGA Merasa Kualat Belajar Bahasa Prancis yang Mbulet dari Penutur Aslinya dan tulisan Sugiyanto lainnya.