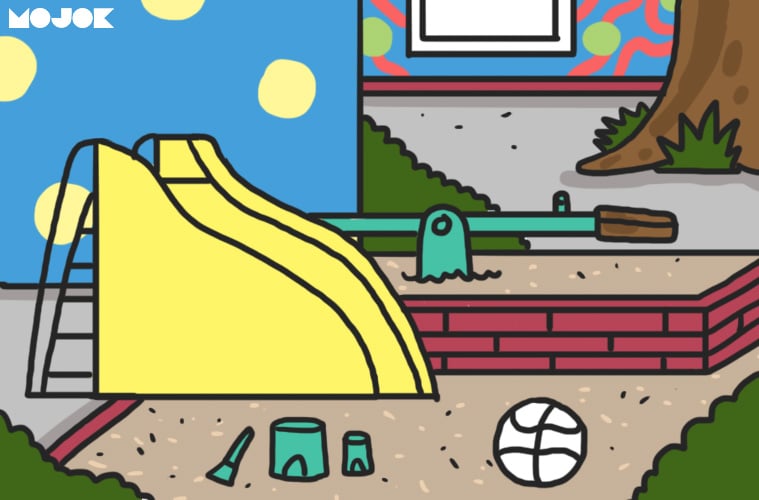Indomaret Pasteur, tempat singgah barang sejenak
Menjelang sore, datang para pekerja berseragam biru dongker. Tukang bangunan, kurir paket, teknisi kabel, sopir angkot dari penjuru Bandung juga merapat.
Mereka membeli nasi bungkus dan teh botol di Indomaret Pasteur. Lalu, mereka makan di trotoar dengan cepat. Tak banyak bicara. Gerak mereka efisien, seperti waktu yang mereka punya: singkat dan mahal.
Saya melihat kelelahan yang menumpuk di wajah-wajah mereka. Bukan hanya dari kerja fisik, tapi dari hidup yang ditentukan oleh upah harian dan harga bensin. Tapi, meski begitu, mereka tetap makan dengan tenang, kadang sambil bercanda pelan. Ada sesuatu yang lembut di sana. Ya, sejenis ketabahan yang tak perlu diumumkan.
Sumber kebahagiaan kecil
Kadang, datang ibu muda dengan anak kecilnya ke Indomaret Pasteur. Si anak langsung berlari ke rak permen, dan ibunya, setelah pura-pura menolak, akhirnya luluh juga.
“Satu aja, ya.”
Lalu mereka keluar sambil tersenyum. Anaknya menggenggam es krim yang meleleh di tangan.
Pemandangan sederhana itu, entah kenapa selalu membuat dada saya hangat sekaligus perih. Di dunia yang keras ini, kasih sayang pun diukur lewat kemampuan membeli.
Bagi banyak keluarga, konsumsi bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga bentuk cinta, cara bertahan. Kapitalisme paham betul di mana letak hati manusia: di anak-anak yang senang kalau dibelikan sesuatu.
Kehidupan driver ojol di depan layar gawai
Di Indomaret Pasteur juga, driver ojek online sering duduk di bangku besi. Mereka sibuk menatap ponsel masing-masing.
Kadang mereka bercanda soal pelanggan yang cerewet, kadang mengeluh tentang order yang sepi. Mereka tampak bebas, tapi di balik layar itu, algoritma sedang menentukan segalanya: ke mana mereka pergi, berapa lama mereka harus menunggu, bahkan seberapa banyak mereka bisa makan hari itu.
Mereka tertawa, tapi ada rasa lelah yang dalam di baliknya. Dunia digital ternyata juga punya cara halus untuk memperbudak.
Kisah pekerja Indomaret Pasteur
Dan di dalam Indomaret Pasteur, kasir berdiri tegak di balik meja. Wajahnya muda tapi matanya lelah.
Dia tersenyum setiap 15 detik, menyebut harga, menawarkan promo. “Sekalian top up, Kak?” atau “Ada promo dua ribuan, loh.”
Saya kadang berpikir, betapa luar biasanya manusia bisa berpura-pura ceria di tengah kerja monoton seperti itu. Tapi di situlah ideologi bekerja. Di wajah yang harus tetap ramah, bahkan ketika gaji tak cukup untuk menabung. Dalam dunia ini, bahkan senyum bisa dijual, dan keramah-tamahan menjadi komoditas.
Di dalam Indomaret Pasteur, (seharusnya) semua setara
Kalau melihat dari luar, semua orang di Indomaret Pasteur itu tampak setara. Semua antre di kasir yang sama, memegang uang yang sama, dan membawa pulang kantong plastik yang juga sama.
Tapi, sebenarnya, tidak ada yang setara di sana. Yang satu datang dengan motor cicilan, yang lain berjalan kaki. Lain lagi membeli karena bosan, yang lain karena lapar.
Di balik keseragaman itu, ada struktur besar yang bekerja diam-diam. Kapitalisme yang mengatur ritme hidup manusia sampai ke hal paling kecil. Kapan harus makan, apa yang harus dibeli, bahkan bagaimana cara tersenyum.
Saya menatap logo Indomaret Pasteur di atas kepala saya dan tiba-tiba merasa aneh. Tempat sekecil ini ternyata memantulkan wajah dunia yang besar.
Indomaret bukan cuma toko. Ia adalah dunia dalam versi mini.
Apa yang terjadi di sini—hubungan antar manusia, cara bekerja, cara mencintai, cara bertahan—juga terjadi di mana saja: di pasar modern, mall, platform daring, hingga ruang kerja. Semuanya mengikuti logika yang sama: logika uang, efisiensi, dan citra kebahagiaan yang dijual lewat kemasan.
Bias kenyataan dan kebiasaan
Kita semua, tanpa sadar, sedang memainkan peran yang sudah disiapkan: pembeli, pekerja, pengguna, pelanggan. Kita mendapat ilusi bahwa kita bebas memilih, padahal pilihan itu sudah ditentukan.
Mau Indomaret atau Alfamart, Shopee atau Tokopedia. Semuanya hanya nama berbeda dari sistem yang sama. Dan sistem itu sudah begitu rapi sehingga kita bahkan merasa nyaman di dalamnya.
Malam makin turun, tapi lampu Indomaret Pasteur tak pernah padam. Saya masih duduk di kursi itu, roti saya sudah habis, kopi kaleng sudah dingin.
Dari balik pintu otomatis Indomaret Pasteur, udara dingin AC terus keluar, seperti napas panjang dunia yang tak pernah berhenti bekerja. Saya melihat orang-orang datang dan pergi, dan entah kenapa, saya merasa sedang menatap kehidupan dalam bentuk paling jujurnya: sederhana, berisik, tapi menyimpan paradoks yang dalam.
Di bawah cahaya putih yang dingin itu, saya paham satu hal: dunia tak selalu berubah lewat revolusi besar atau pidato lantang. Kadang ia memperlihatkan dirinya lewat hal-hal kecil. Ya seperti yang saya jelaskan: senyum kasir, tangan anak kecil yang menggenggam permen, atau para buruh dan pekerja di Bandung.
Dan ketika saya berdiri, membuang bungkus roti ke tempat sampah, saya merasa seolah sedang meninggalkan panggung kecil. Sebuah panggung di mana kapitalisme tampil begitu halus, begitu manusiawi, sampai kita tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan kebiasaan.
Penulis: Muhammad Ifan Fadillah
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Rekomendasi 4 Camilan Gluten Free yang Bisa Dibeli di Indomaret dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.