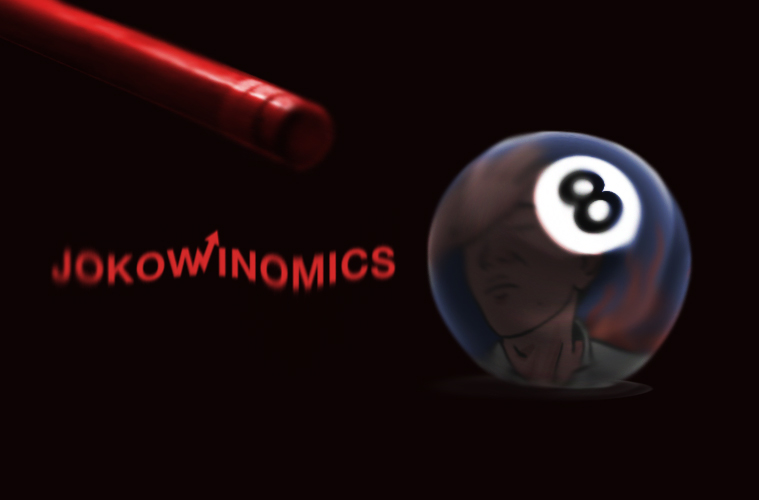MOJOK.CO – Selama delapan tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi, dengan Jokowinomics-nya, ternyata tidak memberi dampak signifikan.
Terhitung sejak 20 Oktober 2022 lalu, delapan tahun sudah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sewindu sudah platform Jokowinomics berjibaku dengan segala persoalan ekonomi di negeri ini selepas masa kemepimpinan Presiden SBY.
Perpaduan agresivitas belanja infrastruktur dengan kebijakan fiskal ekspansif (termasuk ekspansi utang publik) yang digadang-gadang sebagai keyword platform Jokowinomics diharapkan bisa menjadi pembeda dengan pemerintahan sebelumnya. Platform ini juga diharapkan menjadi obat untuk perekonomian nasional yang sudah mulai melandai di penghujung pemerintahan SBY
8 tahun yang biasa saja
Namun, selama delapan tahun pemerintahan Jokowi, menurut hemat saya, ekonomi kita masih berjalan as usual. Belum terlihat perbedaan fundamental dibanding pemerintahan sebelumnya. Jika ada, nampaknya sekadar perbedaan-perbedaan teknis. Pasalnya, di era SBY, bahkan di era Soeharto, infrastruktur tetap menjadi prioritas. Di era Orde Baru, bahkan diberikan diskresi kepada presiden (instruksi presiden) untuk melakukan terobosan pembangunan fisik, terutama di desa-desa. Jika mau dipaksakan perbedaanya, rasanya hanya terletak pada proporsi alokasi anggaran.
Oleh karena itu, infrastruktur bukan sebuah kebaruan dan bukan pembeda fundamental Jokowi dengan pemerintah sebelumnya. Jadi tak heran, di penghujung pemerintahan SBY, di mana pertumbuhan ekonomi mulai melandai, lalu saat disambung oleh Jokowi, justru tidak terjadi pembalikan arah pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan semakin menurun, lalu stagnan dalam jangka waktu yang lama (zona lima persen). Setidaknya hal itu menjadi pertanda bahwa pemerintahan Jokowi memang belum membawa pembeda signifikan.
Konsumsi rumah tangga stagnan karena pendapatan juga cenderung stagnan, bahkan pada kuartal-kuartal tertentu menurun. Investasi juga demikian. Investor nampaknya belum berani untuk berharap banyak karena nyatanya raihan pertumbuhan ekonomi memang kurang prospektif untuk melakukan ekspansi investasi.
Sementara itu, di sisi lain, ekspor berjalan dalam napas serupa. Ekonomi global yang dihantui stagnasi selepas krisis finansial 2008 memang tak banyak menjanjikan peluang kepada Indonesia, selain ekspor bahan mentah dan aneka rupa produk UMKM. Walhasil, pertumbuhan menjadi sangat bergantung kepada belanja pemerintah. Bahkan boleh jadi peningkatan porsi belanja infrastruktur telah menyelamatkan pemerintahan Jokowi dari penurunan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.
Dengan lain perkataan, secara prinsipil boleh jadi ada benarnya juga tudingan AHY yang menggunakan istilah “gunting pita” tersebut, tapi tentunya dalam makna simbolik. Artinya, bukan proyek di era SBY yang diresmikan oleh Jokowi, tapi memang Jokowi secara prinsipil hanya meneruskan platform ekonomi SBY. Apalagi Menkeunya adalah sosok yang pernah bekerja di era SBY. Jadi secara ideologis, platform fiskalnya tentu tak akan jauh berbeda.
Baca halaman selanjutnya….
Kekhawatiran yang terasa
Lantas, di mana letak persoalannya, terutama terkait dengan persoalan perekonomian nasional? Dalam hemat saya, kekhawatiran utama ada pada sisi output atau pertumbuhan ekonomi. Jokowi dan tim ekonominya, nampaknya, sangat memahami bahwa di penghujung era SBY, sudah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara gradual karena era commodities booming mulai mereda sebagai imbas dari stagnasi ekonomi global. Tapi Jokowi dan tim ekonominya kurang berhasil menemukan sumber pertumbuhan baru yang lebih sustainable sebagai pendamping proyek-proyek infrastruktur, meskipun berhasil menetapkan target tujuh persen dalam janji kampanyenya.
Nah, karena kurang berhasil dalam mendorong lahirnya sumber pertumbuhan baru, walhasil pertumbuhan ekonomi di era Jokowi cenderung meneruskan tren yang sudah terjadi di penghujung pemerintahan SBY alias pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding dengan era SBY. Risiko logisnya, serapan tenaga kerja baru tentu akan lebih rendah dan pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih lambat.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi
Masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja tentu terkait erat dengan performa pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan semakin baik kualitas pertumbuhan tersebut di sisi lain, semakin besar daya serapnya terhadap angkatan kerja yang ada dan akan semakin besar pula peluang untuk menekan angka pengangguran di satu sisi dan angka kemiskinan di sisi lain.
Faktor lainya adalah semakin memburuknya kualitas Incremental Labour Output Ratio (ILOR) atau daya serap tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Pelemahan ILOR ini bisa terjadi karena beberapa hal.
Pertama, investasi baru lebih cenderung terjadi di pasar finansial (bukan investasi fisik dan foreign direct investment) untuk menghindari risiko dan sewaktu-waktu bisa out. Kedua, penerapan teknologi di banyak lini. Dan ketiga, boleh jadi karena bertambahnya jumlah tenaga kerja asing yang dipakai dalam investasi baru di dalam negeri karena konsesi-konsesi tertentu dengan negara-negara asal investasi.
Nah, kembali ke pertumbuhan ekonomi, sejak lima tahun lalu, apalagi setelah datangnya pandemik, performa pertumbuhan ekonomi kita masih sangat standar, bahkan sempat minus dan soft recession saat pandemik. Pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibanding pertumbuhan angkatan kerja baru. Sementara setelah pandemi datang, angka angkatan kerja yang tidak bekerja bertambah karena sebagian tenaga kerja lama keluar dari pekerjaan atau terkena lay off.
Ceritanya tentu akan sangat berbeda jika Jokowi berhasil menunaikan janjinya saat kampanye delapan tahun lalu untuk menorehkan pertumbuhan ekonomi sekitar tujuh persen. Jika itu terjadi, tentu pembalikan akan terjadi secara gradual. Hasilnya, daya serap tenaga kerja baru akan jauh lebih besar, pengangguran akan lebih cepat ditekan, dan akhirnya kemiskinan akan lebih cepat dikurangi.
Di sisi lain, dengan pertumbuhan yang terbilang sangat standar (sebagian menyebutnya “kutukan lima persen”), wajar inflasi pun kemudian akan ikut melandai (sebelum pandemik tentunya). Tingkat aggregate demand yang standar, disertai limpahan impor dari negara yang memiliki efisiensi lebih tinggi (terutama Cina), angka inflasi yang rendah adalah hal yang masuk akal alias bukan prestasi yang perlu dibesar-besarkan.
Celakanya, semua upaya itu sudah disertai dengan rezim budget defisit yang cukup besar. Masalahnya, pertumbuhan utang yang tinggi kemudian kurang berhasil mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Artinya, semua utang yang telah dipungut oleh pemerintah belum mampu dijadikan sebagai instrumen fiskal produktif untuk mendongkrak output ekonomi. Walhasil, rasio utang terhadap PDP terus meningkat di satu sisi, tapi tanpa diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang ideal di sisi lain.
Dengan kata lain, Jokowi belum berhasil menggunakan segala instrumen yang bisa digunakan, baik instrumen politik, fiskal, dan moneter, untuk bermanuver meningkatkan output ekonomi. Imbas akhirnya melebar kemana-mana, terutama ke tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rasio utang terhadap PDB (pertumbuhan ekonomi).
Tidak ada perubahan berarti
Secara personal, saya setuju dengan rezim deficit fiscal, terutama saat terjadi ganjalan dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan jika diperlukan, deficit budget-nya lebih dari tiga persen APBN sehingga terdapat ruang fiskal yang cukup luas untuk bermanuver. Bukan karena lebih memilih Keynes ketimbang Hayek plus Milton Friedman, tapi karena status emerging market yang kita sandang yang mengharuskan Indonesia untuk catch up dengan negara besar lainnya di satu sisi dan karena platform ideologi ekonomi Pancasila yang memungkinan itu untuk dilakukan oleh pemerintah.
Meski begitu, tentu harus ada syarat ketatnya. Utang sebagai akibat dari rezim deficit budget harus digunakan secara maksimal dan prudensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yakni untuk menyiapkan ekosistem ekonomi yang produktif yang bisa dinikmati oleh semua pihak.
Belanja produktif tersebut merentang mulai dari peningkatan daya saing SDM, pembiayaan inovasi-inovasi yang akan menstimulasi perbaikan produktivitas ekonomi nasional, pembangunan dan penataan infrastruktur dasar dan infrastruktur komersial, pembenahan regulasi, peningkatan pelayanan dasar dan komersial, stimulan-stimulan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan seterusnya.
Dengan kata lain, jika produktivitas dan output ekonomi memang bisa digenjot dengan tambahan belanja produktif, imbas logisnya, rasio utang terhadap PDB akan tetap terjaga di bawah 30 persen dengan nominal utang yang diterima tetap besar dan terus membesar selama output ekonomi tumbuh di level yang diharapkan. Dan itu semua bisa digunakan secara berkelanjutan untuk belanja produktif yang manfaatnya bisa dirasakan secara lintas generasi.
Pendek kata, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia bersama platform Jokowinomics nyatanya tidak berubah. Masih sama dengan pemerintahan sebelumnya. Oleh sebab itu, mau tak mau, pemerintah harus ikut menuai dan meneruskan tren pertumbuhan dari pemerintahan sebelumnya yang memang sedang melandai.
Jadi, delapan tahun eksistensi Jokowinomics di Indonesia, pertumbuhan ekonomi masih cenderung bergerak secara natural dengan sokongan utang yang cukup ekspansif di satu sisi namun penggunaanya belum terlalu produktif di sisi lain. Catat itu, Pak Jokowi.
BACA JUGA Jokowi Senang, Sri Mulyani Semringah: Hobi Gali Utang, Bikin Rakyat Terengah-engah dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Ronny P. Sasmita
Editor: Yamadipati Seno