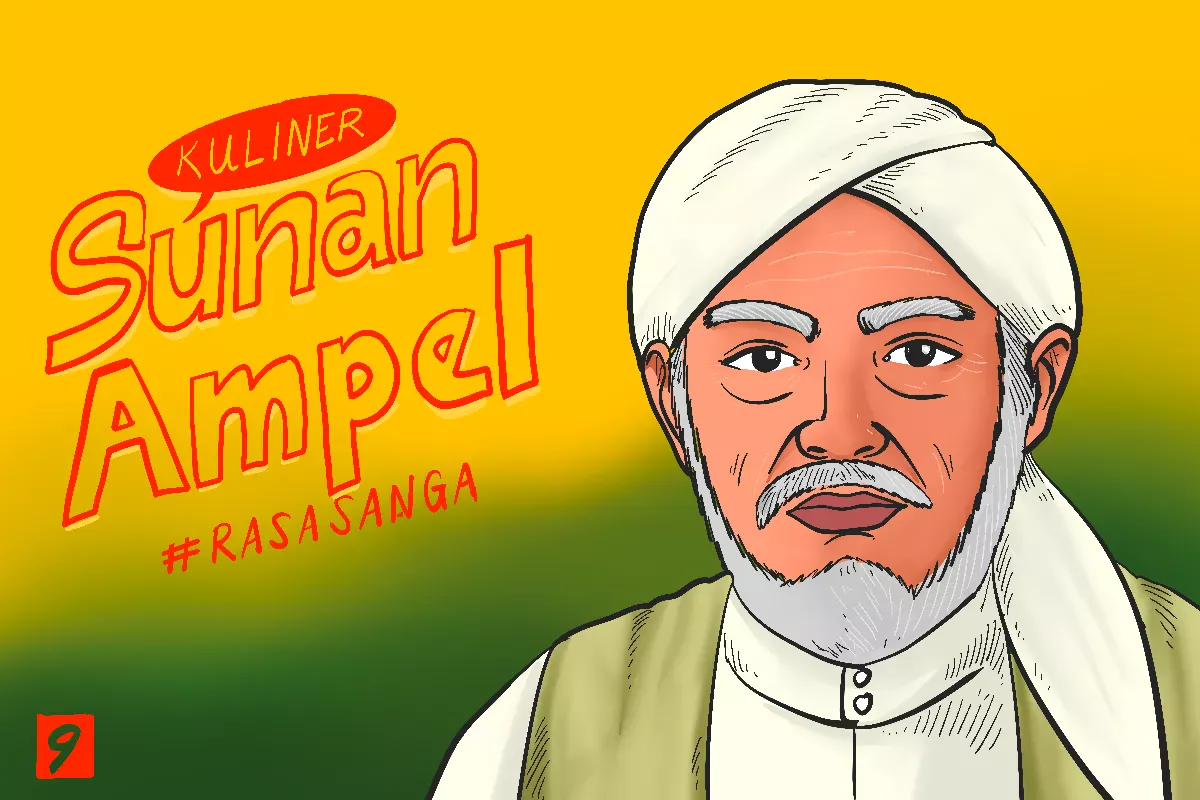Akhir pekan lalu, saya membaca artikel mbak Mercy Lucia Alesty tentang organisasi mahasiswa yang dia sebut sering bikin anggotanya boncos. Bukan cuma boncos uang, tapi juga boncos waktu, tenaga, dan ekspektasi. Dari situ, saya jadi paham kenapa hari ini semakin banyak mahasiswa yang memilih menjauh dari organisasi kampus, atau setidaknya ogah-ogahan ketika diajak bergabung.
Fenomena ini sering disederhanakan sebagai gejala kemalasan generasi sekarang. Mahasiswa dianggap kurang daya juang, terlalu pragmatis, dan maunya yang instan-instan. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, sikap menjauh dari organisasi mahasiswa justru lahir dari kesadaran yang cukup rasional. Mahasiswa hari ini tidak serta-merta menolak pengalaman, mereka hanya lebih selektif menentukan pengalaman mana yang layak diperjuangkan.
Organisasi mahasiswa masih kerap dijual sebagai ruang belajar paling ideal. Katanya, di sanalah mahasiswa ditempa kepemimpinan, manajemen konflik, dan kemampuan bekerja dalam tim. Masalahnya, praktik di lapangan sering tidak seindah teori pengkaderan. Banyak organisasi terjebak pada rutinitas yang melelahkan tanpa hasil yang jelas. Rapat berjam-jam hanya untuk membahas hal teknis yang bisa selesai lewat grup WhatsApp. Program kerja disusun demi laporan pertanggungjawaban, bukan dampak nyata. Di titik ini, mahasiswa mulai menghitung untung-rugi.
Hitungan ekonomi mulai masuk
Perhitungan itu semakin masuk akal ketika realitas ekonomi ikut menekan. Tidak semua mahasiswa punya privilese untuk sekadar sibuk tanpa memikirkan biaya hidup. Bagi sebagian orang, waktu malam lebih berguna untuk bekerja paruh waktu, mengerjakan proyek lepas, atau sekadar menjaga kesehatan mental setelah seharian kuliah. Organisasi mahasiswa, dengan segala tuntutan kehadiran dan iuran, sering kali terasa sebagai kemewahan yang mahal.
Belum lagi budaya di dalamnya yang kerap tidak ramah. Senioritas masih dianggap lumrah. Kritik sering dibungkam atas nama solidaritas. Mereka yang berbeda pilihan dicap tidak loyal, setidaknya itu di organisasi saya. Dalam iklim seperti itu, organisasi kehilangan fungsinya sebagai ruang belajar demokrasi. Ia berubah menjadi ruang kepatuhan. Mahasiswa yang kritis tentu akan berpikir dua kali sebelum masuk ke dalamnya.
Di sisi lain, dunia di luar kampus bergerak jauh lebih cepat dibanding ritme organisasi mahasiswa. Perusahaan, lembaga riset, dan komunitas profesional menuntut portofolio konkret, bukan sekadar jabatan ketua divisi atau sekretaris umum. Mahasiswa pun mulai mengalihkan fokus ke hal-hal yang lebih nyata. Magang, riset independen, kerja sukarela berbasis keahlian, atau bahkan membangun usaha kecil-kecilan terasa lebih relevan untuk masa depan mereka.
Baca halaman selanjutnya