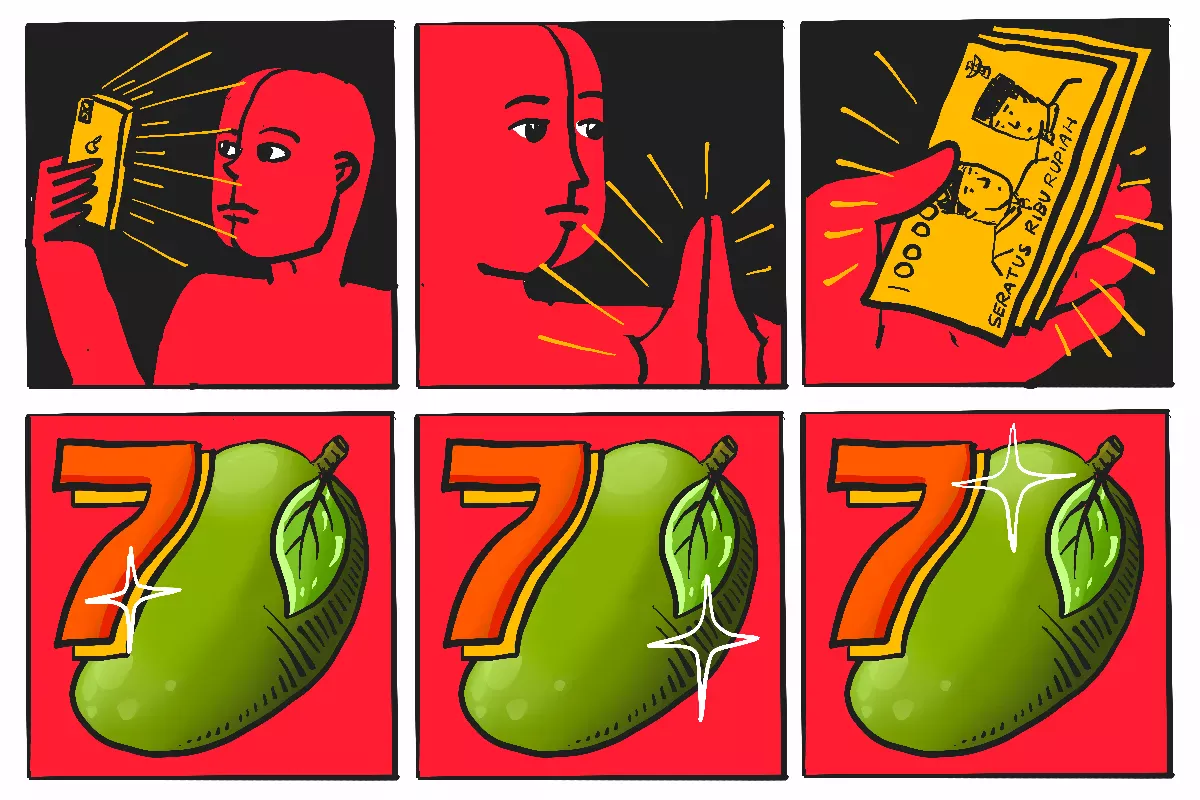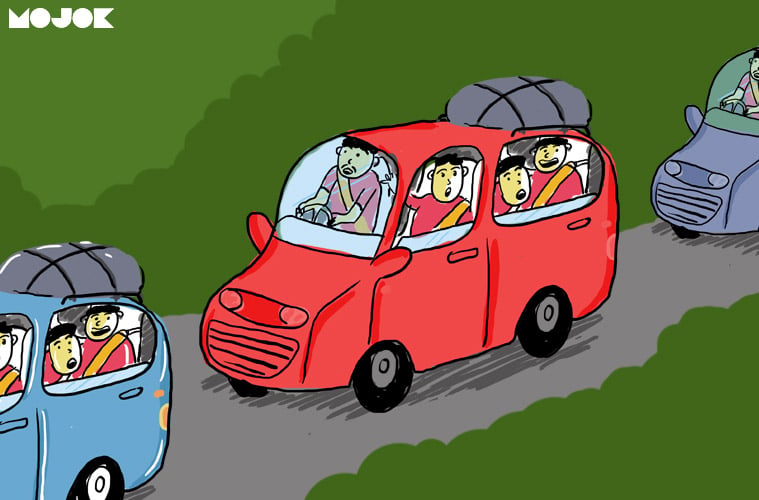Saya nggak habis pikir tentang orang-orang yang suka mencemooh diri saya gara-gara keputusan saya hengkang dari pekerjaan sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah daerah. Mulai dari tetangga, teman, bahkan para pelanggan toko saya menyalahkan saya gara-gara keputusan resign dari kerja di instansi pemerintah. Mereka seolah-olah menggoblok-goblokan diri saya gara-gara lebih milih usaha percetakan daripada kerja di balik meja kantor.
Maksud saya, kalian tuh yang merendahkan saya emangnya tau apa, tentang kehidupan saya? Tau apa tentang kerja di pemerintah? Kok bisa-bisanya menyayangkan pekerjaan di kantor pemerintah. Kalian tuh hanya tau permukaannya doang tentang status sosial saya kalau setiap hari bersepatu pantofel, berkemeja rapi, naik mobil plat merah, kalau kunjungan kerja selalu dijamu warga. Tapi dibelakang itu semua? Blas, kalian nggak tau apa-apa.
Melalui tulisan ini, sedikit saya memberikan beberapa alasan saya untuk memutuskan angkat kaki dan sedikit menginfokan sisi gelap kerja di instansi pemerintah. Semoga melalui tulisan ini kalian yang nyinyir dengan orang-orang seperti saya sadar, betapa tidak idealnya kerja di balik meja pemerintahan.
Menjadi tenaga honorer
Alasan paling utama saya hengkang adalah status saya sebagai tenaga honorer. Awalnya saya menerima menjadi honorer karena memang ada wacana bahwa suatu saat bakal diangkat menjadi PNS. Okelah, saya terima. Namun, hari demi hari telah berlalu, obrolan dengan beberapa honorer lain telah terdengar. Dan salah satu yang membuat saya kaget adalah, banyak honorer yang sudah bekerja 10-15 tahun tapi nggak diangkat jadi PNS di instansi saya.
Ada memang dari honorer kemudian diangkat PNS. Tapi ia diangkat jadi PNS ketika berusia kisaran 60 tahun, alias udah punya cucu baru diangkat jadi PNS. Coba bayangin betapa tidak adanya jenjang karier yang jelas dalam menjadi honorer di instansi pemerintah.
Namun, saat itu saya masih bertahan, karena ada program penerimaan PPPK, yang barangkali membawa angin segar. Tapi, angin segar itu berubah menjadi api panas semenjak saya dijegal oleh petinggi kantor.
Wait, what?
Jadi begini, saya sebenarnya sudah memiliki surat pengalaman kerja di kantor itu bertanda tangan kepala kantor sebagai syarat seleksi PPPK. Sebab, saya ajudan beliau jadi cukup mudah bagi saya mendapatkannya. Namun, surat itu tiba-tiba ditarik oleh pejabat tinggi lain gara-gara saya belum dua tahun bekerja, sehingga saya tidak dapat mengikuti seleksi PPPK.
Melalui tragedi itu, saya menyimpulkan bahwa saya harus menderita dahulu selama dua tahun baru kemudian dapat menjadi PPPK. Itu pun harus melalui seleksi terlebih dahulu, nggak langsung diterima. Padahal seharusnya kalau memang mau mensejahterakan honorer, ya udah bolehkan mereka mendaftar seleksi tanpa ada syarat yang membuat mereka harus menahan penderitaan.
Status tinggi tapi gaji hanya sekuku jari
Karena saya tenaga honorer, gaji saya pun tak setinggi PNS yang bisa berjuta-juta sekaligus tunjangannya. Saya hanya digaji satu juta perbulan. Kalaupun naik, itupun hanya naik menjadi satu juta setengah, itu pun harus bekerja bertahun-tahun dulu. Tenaga honorer lain di luar sana malah banyak yang lebih menjijikkan gajinya.
Ya, memang ketika saya bekerja, saya memiliki status sosial yang cukup tinggi. Pakaian saya tak beda dengan pejabat dan pegawai PNS lainnya. Karena saya sebagai ajudan, saya pun riwa-riwi menggunakan mobil plat merah dan dijamu layaknya raja. Kalau kunjungan makannya enak-enak, disambut, disediain tempat khusus dan lain sebagainya.
Namun, apalah status sosial yang tinggi kalau gaji hanya sekuku jari? Bensin saya, uang makan saya, bahkan uang untuk perkuliahan saya tidak dibayar dengan status sosial, tapi dibayar dengan uang.
Uang bensin saya aja untuk bolak balik kantor habis 400.000 jika per hari habis bensin 20.000. Sudah hampir separoh gaji saya untuk bolak balik kantor. Belum untuk keperluan lainnya. Nggak heran kalau honorer lain punya sampingan seperti istrinya bekerja jualan atau lainnya. Lah kalau saya yang masih belum beristri pemasukan dari mana?
Jika boleh dibandingkan dengan penghasilan saya di toko percetakan saya, menjadi honorer nggak ada apa-apanya. Hanya menang status sosial doang tapi gajinya kalah dengan pengusaha percetakan.
Kerja dari gelap ketemu gelap
Salah satu alasan saya menerima kerja di instansi pemerintah adalah saya kira saya hanya bekerja sampai pukul empat sore, atau mentok jam lima sore. Pasalnya, memang demikian yang dilakukan oleh para pekerja di instansi saya baik PNS maupun honorer. Jadi, dengan jam pulang seperti itu, harapan saya, saya bisa mengoperasikan toko fotocopy saya pada malam hari, atau saya dapat berkuliah yang memang kebanyakan jadwal kuliah malam.
Namun, apa yang saya bayangkan tidak demikian. Karena saya adalah ajudan kepala kantor, akhirnya membuat saya sangat sibuk, bahkan sesibuk jabatan kepala kantor. Pasalnya, saya harus mengikuti aktivitasnya mulai matahari belum terbit, hingga matahari tenggelam, dari gelap hingga gelap.
Saya sudah stay di kantor mulai pukul setengah enam, berarti saya dari rumah berangkat subuh. Kemudian saya pulang kerja jam sembilan, sepuluh bahkan pernah pulang jam sebelas malam. Kenapa kok saya sampai larut? Ya karena kepala kantor ada kunjungan kerja hingga keluar kota yang perjalanannya hingga larut malam. Bahkan sempat kesel saya sampai diinapkan tidur di rumah kepala kantor karena disuruh ikut kegiatan tahlil ayah ibunya di luar kota. Campur aduk antara pekerjaan kantor dan pekerjaan pribadi kepala kantor yang membuat saya semakin… arghhhh begitulah.
Bayangin jam kerja saya lebih daripada kuli yang jam lima sudah berhenti. Kehidupan saya sudah seperti mengabdi pada raja yang tunduk dan patuh atas perintah penguasa, apa pun titahnya.
Ya, saya ikhlas sih asalkan gajinya nggak sejuta juga. Atau seenggaknya UMR daerah saya yang sekitar empat jutaan. Lah tapi yang terjadi adalah saya sudah disuruh kerja serius, tapi gaji becanda.
Bagi tenaga honorer, libur adalah ilusi
Alasan terakhir, sebagai latar belakang saya akhirnya memutuskan secara tegas untuk hengkang adalah saya diriwehin ketika hari libur kerja. Saya tidak pernah mengenal hari Sabtu dan Minggu, semua hari bagi saya adalah hari Senin, full kerja tanpa leha-leha.
Sabtu-Minggu yang seharusnya saya dedikasikan penuh untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang terbengkalai, atau mengerjakan garapan percetakan, akhirnya tak dapat dikerjakan sama sekali. Jadi, selama saya bekerja beberapa bulan di instansi pemerintah, antara toko dan kuliah saya benar-benar terbengkalai. Sudah gaji nggak mencukupi untuk bayar UKT eh kuliahnya nggak diurus. Jadi sudah seperti beban ganda yang menyiksa.
Ya memang di tempat kerja lain diriwehi bos di hari libur adalah hal yang biasa. Namun, bagaimana jika keriwehan itu terjadi setiap akhir pekan, setiap saat bahkan serasa tak pernah memiliki hari libur kecuali jam 12 malam hingga subuh pagi. Ya, itulah yang terjadi pada saya hingga memutuskan angkat kaki.
Jadi, kalian masih mau menghakimi tenaga honorer yang cabut dari kantor pemerintah? Kalau masih ya, artinya memang ada kerikil yang menyumbat syaraf di kepala kalian.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Guru Honorer Tetap Mengajar dengan Gaji Kecil Bukanlah Pengabdian, Itu Terjebak Keadaan