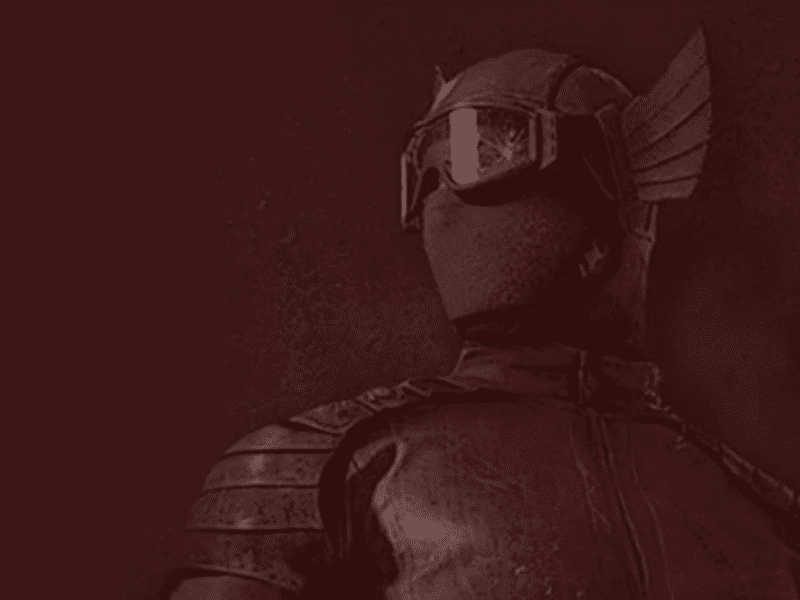Akhir pekan ini untuk mengubah sebuah quantity time agar menjadi quality time, saya mengajak istri jalan berdua. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, saya merasa seperti sepasang kekasih anak SMA. Jadi, ada semacam pacaran sudah halal, gitu. Cie pacaran halal~
Tidak. Tidak… Saya tidak sedang berkampanye agar teman-teman menikah muda, kok. Tidak juga sedang berkampanye kalau pacaran setelah halal itu asyik. Sumpah, itu hanya sebuah delusi. Saya Cuma mau pamer saja kalau saya dan istri sebetulnya sudah tua tapi merasa masih baby face. Halahhh baby face. Pede banget, Mz~
Kebetulan sekali film Gundala sedang hype banget. Akhirnya kami berdua membeli tiket untuk menyaksikannya. Kami juga ingin merasakan euforia setelah menonton film ini. Sekaligus dalam rangka perayaan kecil atas honorarium pertama saya dari Terminal Mojok. Ya lumayan lah, bisa mengajak istri nonton bisokop. Pulangnya bisa makan di restoran yang cukup elit.
Jujur saja, saya tidak tahu banyak ihwal pahlawan super dari Indonesia. Sewaktu duduk di bangku SMP saya pernah mendengar nama-nama pahlawan super Indonesia dari majalah anak-anak. Salah satunya Gundala Putra Petir ini. Tapi sampai sekarang, sampai saya sudah dewasa—untuk tidak menyebut sudah tua—belum pernah membaca ceritanya atau komiknya. Ya, cuma sekadar mendengar namanya saja.
Maka dari itu ketika lampu sudah mulai dipadamkan, ketika suara Dolby: “All arround you…” terdengar sayup-sayup di telinga, dan ketika film akan dimulai, saat itu saya mulai fokus. Fokus kepada Sancaka dan konflik-konflik lingkungan yang sudah ia lewati dari kecil.
Saya tidak menyangka kalau Sancaka lahir dari keluarga buruh. Lahir dari orangtua yang memperjuangkan hak buruh. Dan Sancaka itu sendiri juga bekerja sebagai security pabrik. Termasuk buruh juga, kan?
Pantas saja kalau si Sancaka punya panggilan jiwa yang kuat untuk memperjuangkan keadilan. Di awal film saya cukup optimis, pahlawan yang lahir dari latar belakang buruh akan menjadi pahlawan yang tangguh. Sebab menjadi buruh saja merupakan pahlawan. Khususnya untuk kehidupan keluarga dan perusahaan.
Ada hal yang mengejutkan saya. Wah, ternyata Gundala ini sosok yang pintar. Tak hanya pintar bela diri saja, tapi juga pintar dalam hal lain: memperbaiki lampu di rumahnya, memperbaiki mesin di pabrik tempatnya bekerja, dan ilmu pengetahuannya juga cukup mumpuni.
Dalam adegan demi adegan, cukup memberi kesan kalau Sancaka sudah pintar dari kecil. Memang untuk menjadi pahlawan nggak cukup sekadar kuat dan memiliki kemampuan ajib, tapi juga harus pintar. Berkat pengetahuannya, Gundala memiliki langkah cerdik untuk menghancurkan botol-botol obat yang berisi serum amoral dengan cara menyalurkan gelombang petir melalui botol kaca yang dia pegang. Secara otomatis botol kaca di tempat lainnya juga ikut pecah.
Lagi pula bagaimana Sancaka nggak pintar? Coba perhatikan saat adegan di tempat tinggal Sancaka—yang terlihat seperti rumah susun itu. Kamera akan menyorot buku-buku koleksi Sancaka. Meskipun hanya sebagai latar belakang saja. Ada satu adegan saat Sancaka menjelaskan tentang petir, lalu Teddy (adiknya Wulan) berseru: “Kok tahu?”. Dengan singkat, padat, dan jelas Sancaka menjawab: “Baca”.
Kemudian saya sempat heran ketika ada adegan Sancaka—sambil memegang buku—ngobrol dengan Pak Agung. Batin saya bertanya-tanya: Kenapa ada buku di tangannya, gitu?
Eh, ternyata tidak hanya di rumah, di loker tempat kerja Sancaka juga tersimpan buku-buku koleksinya. Ini cukup jelas untuk menggambarkan bahwa Sancaka adalah tokoh yang suka membaca. Pahlawan yang melek literasi.
Dalam film ini saya melihat tidak hanya sekadar literasi keberaksaraan—buku-buku bacaan— saja yang ditunjukan. Saya kira lebih jauh dari itu. Lebih dari sekadar ajakan membaca. Melainkan literasi yang menyangkut kemelekan atas lingkungan sosial. Di setiap adegan atau konflik dalam film ini, kita bisa belajar membaca isu-isu lingkungan. Mencermati untuk bisa bersikap kritis dalam melihat sesuatu yang terkecil dalam ruang lingkup kita.
Film Gundala ini memiliki rating 13+. Agak berat rasanya jika dikonsumsi anak-anak yang konfliknya politik banget. Seharusnya memang tidak ada anak-anak dibawah usia 13 tahun yang menonton. Tapi tetap saja pihak bioskop akan membolehkan anak-anak untuk masuk. Mau gimana lagi? Demi omzet, Bray~
Loh, kalau rating-nya 13+, lalu pesan Sancaka—secara tersirat—agar suka membaca, untuk siapa kalau bukan untuk anak kecil?
Ya sangat jelas, untuk kita—orang dewasa—yang menontonya agar tidak mudah terprovokasi gerakan masa. Agar tidak mudah termakan berita bohong. Agar tidak lagi membaca berita hanya dari judulnya saja. Agar lebih mendalam untuk memahami keadaan suatu lingkungan.
Ada misteri X—atau apalah namanya—yang saya dapatkan di sini. Tidak menutup kemungkinan, Joko Anwar melalui Sancaka sedang menyebarkan virus literasi kepada khalayak ramai. Bahkan untuk lebih topnya lagi, Sancaka bisa didhapuk sebagai duta literasi nasional dari Jagat Sinema Bumi Langit ini.
Melihat potensi Sancaka, ia tidak akan menjadi duta literasi yang hanya menggaungkan minat baca. Ia akan mengajak kita untuk naik level, dari yang hanya sekadar suka membaca buku menjadi membaca lingkungan dan sosial. Sebab dengan begitu kita akan menjadi manusia yang menjunjung tinggi kebenaran. Melawan Pengkor-Pengkor dunia nyata.
Mungkin, kalau Sancaka punya akun media sosial, dia tidak segan mengunggah buku-buku yang sudah dibacanya. Tak lupa juga foto yang Instagramable lengkap dengan resensinya. Eh, tapi kalau sedang update status jangan lupa dimatiin lokasinya yah. Takut lokasinya ketahuan haters musuh yang sedang mencari dirimu, Mz.
Oh iya, anyway, kalau punya Instagram ada niatan untuk menjadi seorang bookstagram nggak, Mz Sancaka? (*)
BACA JUGA Perjuangan Ibu Hamil Di KRL atau tulisan Allan Maullana lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
—