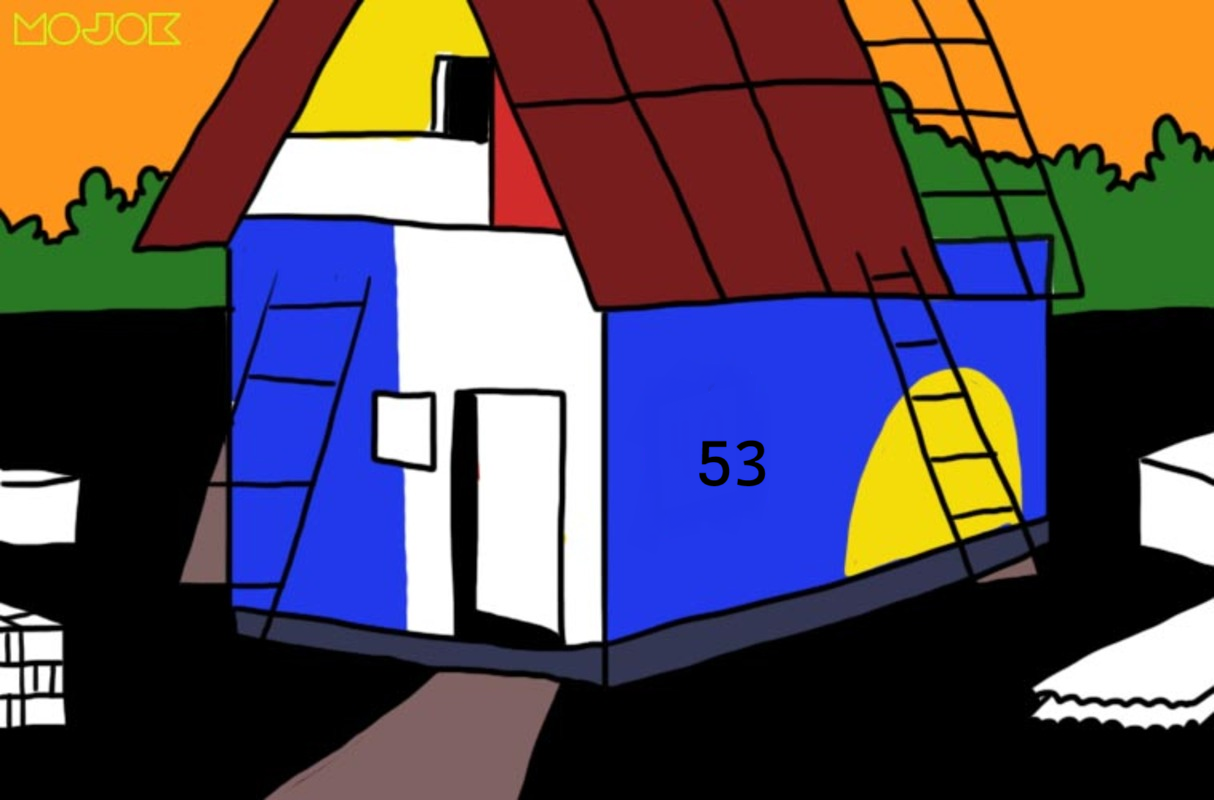Pukul 04:30 WIB Surabaya adalah waktu di mana kota ini mulai menyapa matahari. Langit yang mulai terang dan gemuruh bising kendaraan bermotor di jalan, menandakan kota ini sudah terjaga sejak beberapa waktu sebelumnya. Potret ramai tentu terlihat dari titik-titik ekonomi seperti pasar, tidak terkecuali Pasar Dupak Magersari.
Suara manusia yang saling bersahut, tawar-menawar barang, sesekali di sela-sela proses berunding harga itu, tawa terdengar. Tapi, di tengah semua itu, suara peluit melengking bersamaan dengan terdengarnya bunyi sirine palang Kereta.
Terdengar lantang seruan, “Awas, sepure lewat,” dari sosok paruh baya. Beberapa pedagang juga berseru: “Mingger, mingger, awas diseruduk.”
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Pasar Dupak Magersari memang jadi pasar tumpah yang letaknya berdampingan (bahkan bisa disebut di tengah-tengah) dengan rel kereta yang masih aktif.
Selang beberapa saat kemudian, kereta dari Pasar Turi Surabaya melintasi pasar tersebut. Memecah kerumunan yang sebelumnya terjadi. Setelah kereta lewat, kerumunan yang pecah itu kembali menyatu.
Setidaknya, selama beberapa minggu terakhir, Pasar Dupak Megarsari jadi destinasi belanja saya. Sehingga, fenomena tersebut yang awalnya tampak memprihatinkan, menjadi sesuatu yang berangsung-angsur saya maklumi.
Pasar Dupak Magersari, wujud konsensus masyarakat Surabaya
Pasar Dupak Magersari buka sejak dini hari. Tampak pedagang menggelar dagangan dengan gerakan yang tegas tapi tak kaku, seperti orang yang sudah berkali-kali mengulang adegan yang sama.
Pedagang sayur, lauk, plastik, timbangan, uang kembalian, semua bergerak tanpa skenario yang diatur. Hentakan dan gesekan barang dagangan menghasilkan bunyi seperti orkestra yang dinikmati semua orang yang ada di pasar tersebut.
Pasar ini adalah wujud bagaimana sebuah konsensus dari masyarakat Surabaya bertahan melintasi waktu. Beberapa catatan mengungkapkan bahwa pasar ini sudah ada sejak tahun 70-an. Dan itu dibenarkan oleh pedagang setempat. Pasar ini tidak tumbuh sekadar dari ide liar, tapi tumbuh dari sebuah kesepakatan karena beberapa pertimbangan.
Beberapa pertimbangan masyarakat Surabaya
Pertama, karena pasar yang berlokasi di Kecamatan Bubutan, Surabaya, ini adalah ruang kosong yang dekat dengan permukiman warga. Hal ini membuatnya jadi pilihan strategis bagi masyarakat kala itu untuk membuka titik ekonomi yang menghidupi lingkungan sekitar.
Kedua, lokasi Pasar Dupak Magersari dekat dengan simpul ekonomi, yaitu Pasar Turi. Sehingga para pedagang bisa ikut menikmati arus masuk pembeli dan barang dari pusat grosir tersebut. Pasar yang menempel pada pusat keramaian menjadi keuntungan tersendiri bagi para pedagang.
Ketiga adalah tradisi warga Surabaya di bantaran rel yang sejak lama berhadapan dengan status ruang yang “abu-abu” (lalu ia mengeras jadi kebiasaan lintas generasi). Lokasi ini menjadi saksi terciptanya konflik-legal dan keseharian negosiasi yang bikin ruang di pinggir rel terasa seperti wilayah yang bukan sepenuhnya resmi, tapi juga bukan kosong. Sebab statusnya yang sudah dihuni, dipakai, dan dihidupi puluhan tahun.
Isu dengan PT KAI
Warga Pasar Dupak Magersari sempat punya isu dengan PT KAI. Saat itu, PT KAI punya rencana untuk membangun jalur double track. Oleh sebab itu, PT KAI ingin mensterilkan lahan pinggir rel dari bangunan. Warga yang sudah lama menempati area itu selama puluhan tahun mempersoalkan rencana PT KAI.
Terutama karena, dalam pandangan warga, PT KAI tidak menunjukkan bukti kepemilikan lahan dan lebih merujuk pada Undang-Undang Perkeretaapian. Situasi ini terekam dalam penelitian Universitas Airlangga yang dimuat di Jurnal Politik Muda (Vol. 2 No. 3, 2013).
Riset itu menjelaskan bagaimana ketegangan antara proyek double track dan klaim ruang hidup warga kemudian memicu lahirnya Komunitas Warga Pinggir Rel (KWPR). Ini sebagai gerakan perlawanan untuk mempertahankan lahan, termasuk melalui upaya-upaya yang berujung pada tertundanya pembongkaran serta terbukanya jalur bantuan/dukungan dari Pemkot (proses sertifikasi tanah) dan respons DPRD (dorongan judicial review atas UU No. 23/2007).
Warga Pasar Dupak Magersari dan kewaspadaan
Konflik ini berlangsung lama. Sebuah kondisi yang membuat orang di sekitar Pasar Dupak Magersari jadi terbiasa hidup dengan kemungkinan ditertibkan sewaktu-waktu. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang di Pasar Dupak Magersari yang statusnya adalah generasi penerus orang tua mereka dulu. Di sisi lain, pembeli juga ada yang sudah jadi pelanggan puluhan tahun.
Dari sisi KAI, keberadaan pasar tersebut dianggap membahayakan dan dilarang (ruang manfaat jalur KA), tetapi di lapangan pasar tetap berjalan. Oleh karena itu, sebagai mitigasi, KAI mengimbau masinis untuk membunyikan klakson peringatan dan menurunkan kecepatan di area itu terbatas (disebut maksimal sekitar 30 km/jam) karena ada tikungan/lengkung jalur.
Tapi sekali lagi, tuntutan kebutuhan dan konsensus kolektif membuat risiko besar itu seperti sudah jadi latar. Mereka menyadari bahaya yang ada, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan pasar. Mereka pun mengklaim, sejauh ini tidak terjadi insiden selama berpuluh-tahun pasar berdiri.
Boleh jadi karena warga sudah memahami dan terbiasa dengan ritme bunyi dan jadwal kereta. Ada semacam hafalan kolektif yang tertanam, yaitu kapan harus mulai, memadatkan transaksi, dan berhenti.
Pagi-pagi sekali ramai, lalu perlahan mereda sebelum siang. Seolah-olah semua orang sepakat bahwa hidup di sini harus selesai cepat, karena di atas rel, waktu bukan milik pedagang. Waktu milik kereta.
Tapi yang paling penting, mereka juga paham satu hal yang lebih krusial dari urusan nafkah, yaitu nyawa. Sirene itu bukan sekadar bunyi, melainkan perintah paling masuk akal untuk berhenti dulu. Sebab, mereka tidak ingin pulang membawa uang belanja, tapi rumah menyambutnya dengan tangis hanya karena satu momen lengah.
Sejarah Surabaya yang terabaikan
Pasar Dupak Megarsari ini terasa seperti sejarah yang terabaikan dari dokumen perencanaan Kota Surabaya. Ia lahir bukan karena Surabaya menyiapkan ruang, tetapi karena hidup yang menuntut mereka menciptakan ruang.
Sebab, ketika tempat yang resmi terlalu mahal, jauh, dan penuh dengan aturan, warga pinggiran harus memutar otak untuk menemukan celah ruang yang tersisa. Sekalipun celah itu berupa bantaran rel yang tiap pagi bisa berubah dari pasar menjadi lintasan tragedi. Di pasar itulah mereka membangun ruangan ekonominya sendiri.
Pasar Dupak Magersari adalah gambaran bagaimana kota besar seperti Surabaya membiarkan sebagian orang mengais ekonomi di ruang yang tersisa. Pemerintah tentu tidak salah untuk menuntut kerapian dan keselamatan, tapi seharusnya itu dibarengi dengan kesadaran penuh soal sebab kekacauan.
Pada akhirnya, di kepala saya, Pasar Dupak Magersari bukan tentang pasar yang ada di rel, melainkan tentang manusia yang selalu menemukan cara untuk hidup. Bahkan ketika hidupnya bukan tempat yang disiapkan untuk hidup.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.