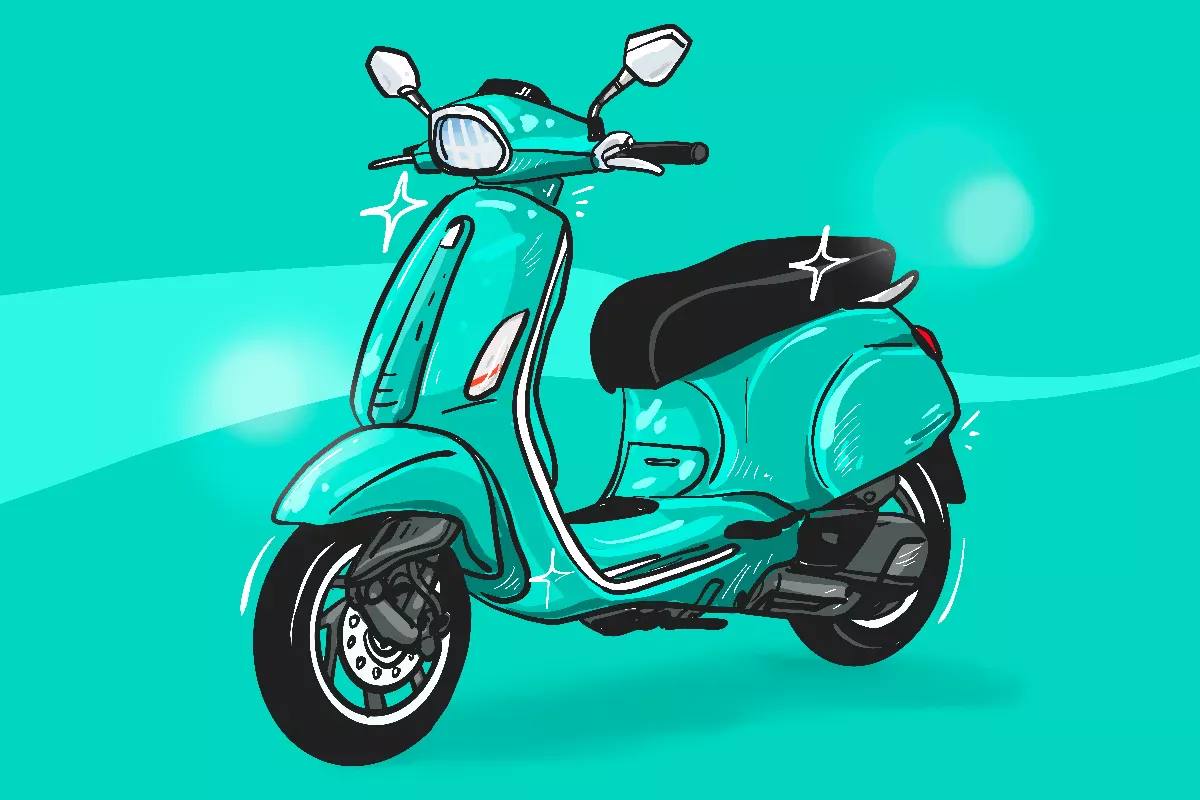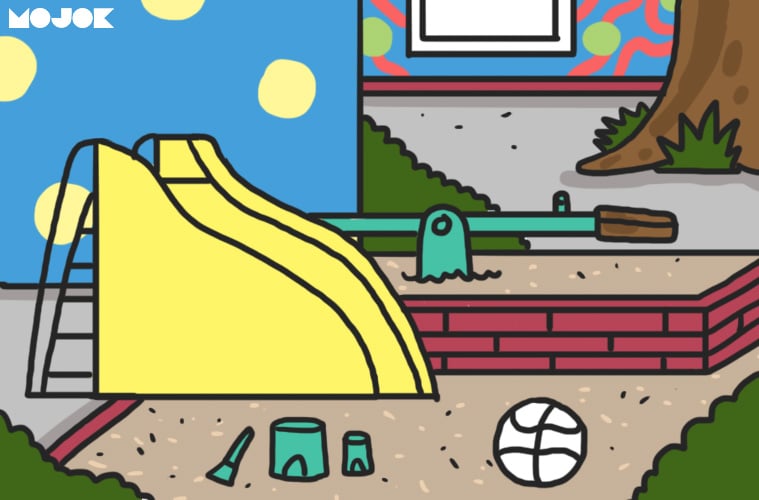Malang sudah overrated soal slow living. Mending ke Mojokerto aja.
Dalam beberapa tahun terakhir, nama Kota Malang hampir selalu terdengar di telinga saya setiap kali orang-orang sedang bergerombol di laman media sosial membicarakan soal narasi slow living. Malang kerap disebut sebagai kota yang paling pas buat menurunkan ritme hidup bagi siapa saja yang ingin pensiun dengan menghirup udara sejuk tiap hari, tetap bisa nongkrong di kopi kalcer, dan melepaskan pandangan pada hamparan sawah dan kebun yang sering dilihat di kiri kanan.
Namun semakin sering kota ini dibicarakan, semakin terasa pula banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, beberapa waktu yang lalu saya pernah lewat Jalan Soekarno Hatta Malang. Jalan yang pada tahun 2019 terasa lengang itu kini kerap padat di jam-jam tertentu. Belum lagi banyaknya bangunan villa dan perumahan yang kian menjamur di area perkotaan. Perhalan-lahan fenomena ini menggerus area resapan air dan membuat banjir Malang bukan lagi dongeng belaka.
Di titik itu, saya mulai bertanya dalam hati, di mana lagi kota di Provinsi Jawa Timur yang masih layak dihuni untuk menghabiskan masa tua, tapi namanya jarang terdengar oleh banyak orang? Ingatan saya kemudian jatuh pada Kota Mojokerto yang tak lain adalah tanah kelahiran suami saya.
Mojokerto tidak memaksamu berubah total menjadi manusia udik
Meskipun tampak sepele, adanya transisi budaya dari orang yang awalnya lahir dan besar di tengah hiruk pikuk kota menjadi orang yang tinggal di desa tentu saja tidak membuat semua orang langsung siap. Mulai dari penyesuaian dengan pilihan makanan yang itu-itu saja atau nggak banyak tempat nongkrong kece bisa jadi pemicu seseorang menjadi burn out. Dan Mojokerto cukup bijak soal ini.
Di sini masih banyak menyisakan titik-titik nyaman versi kota besar tapi dengan ritme kehidupan yang pelan. Beberapa gerai makanan cepat saji yang sering ditemui di kota besar nyatanya masih tersisa di sini seperti Solaria, Marugame Udon, hingga Ramen Master. Mungkin terdengar receh, tapi buat orang yang baru saja pindah, hal-hal kecil seperti ini bisa jadi poin utama.
Gaji yang masih masuk akal dan jalanan yang tak pernah menguji kesabaran
Untuk ukuran kabupaten, gaji di Mojokerto masih tergolong kompetitif. Memang nominalnya tidak fantastis, tapi itu semua akan cukup jika ditambah dengan bumbu bersyukur di setiap harinya. Belum lagi kalau ditambah dengan bonus yang sering nggak didapatkan orang yang tinggal di kota-kota besar: pemandangan sawah atau ladang tebu yang masih sering ditemui. Kurang enak apalagi coba.
Kalau soal ritme jalanan, di Mojokerto jarang sekali macet. Jadi, kalau kamu mau berangkat kerja nggak perlu dikalkulasi pakai jadwal commuter line. Pulang kerja juga nggak akan diiringi dengan rasa dendam pada lampu merah. Karena ada beberapa orang pemusik yang masih memukul kolintang untuk menyenandungkan lagu mengusir penatnya hari setelah bekerja.
Harga makanan masuk kategori waras dan rasanya tetap bintang lima
Kata waras yang saya pakai di sini, bukan sekadar murah, tapi juga nggak bikin pembeli merasa ditipu. Di Mojokerto tidak ada porsi “hemat” yang ujung-ujungnya cuma mengenyangkan perasaan saja. Mie ayam dengan isian lengkap masih bisa kamu temukan seharga Rp7.000. Bahkan di beberapa tempat yang agak nyelempit, ada juga yang menjualnya dengan harga Rp5.000. Meski harganya murah meriah, cita rasanya sungguh ada, toppingnya niat, dan bumbunya juga nggak malu-malu.
Untuk ukuran kota besar, harga segitu mungkin cuma cukup untuk nambah kerupuk atau es teh kalau sedang makan siang di warteg. Itupun es tehnya tanpa gula. Sementara di Mojokerto, uang yang dianggap receh itu masih punya kehormatan dan tidak perlu ada acara negosiasi panjang dengan dompet ataupun rasa bersalah karena mampir jajan dan tidak makan masakan istri di rumah.
Jadi, Mojokerto mungkin bukan kota yang sering disebutkan dalam pembicaraan orang jika menyatut soal slow living. Tapi, justru di situlah letak nyaman dan istimewanya. Entah sampai kapan kondisi ini akan bertahan. Yang pasti, Mojokerto akan selalu menjadi sebuah kota yang tidak menjanjikan apa-apa selain kesempatan untuk mengirup udara sedikit lebih lega.
Penulis: Firda Fortuna Nasich
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Saya Sepakat kalau Mojokerto Dianggap Kota Layak untuk Hidup Bahagia sampai Tua, asalkan…
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.