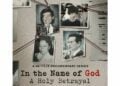Netflix belakangan ini tampak sangat bersemangat memproduksi film berkualitas. Beberapa film bahkan mendapat banyak pujian baik dari audiens maupun kritikus, misalnya Do Revenge dan Athena—tentu saja film Blonde tidak masuk ke dalam daftar ini. Kali ini Netflix menggaet sutradara asal Inggris, Mike Barker (Moby Dick, To Kill a King), untuk menyutradarai film Luckiest Girl Alive.
Betul. Luckiest Girl Alive adalah seperti apa yang kamu pikirkan. Film ini memang diadaptasi dari novel Best Seller New York Times berjudul sama karya Jessica Knoll. Jika kamu penggemar Jessica dan novelnya, kamu tidak akan kecewa karena sang penulis ikut berpartisipasi dalam penulisan naskah skenario film ini.
Luckiest Girl Alive mengisahkan kehidupan sempurna Ani Fanelli (Mila Kunis), seorang penulis di majalah wanita populer, yang bertunangan dengan Luke Harrison (Finn Wittrock), seorang pria dari kalangan terhormat dan sayang padanya. Namun, seiring waktu berjalan, kita akhirnya mengetahui bahwa ada masa lalu yang menghantui Ani. Dia memilih untuk tidak membahas kejadian kelam itu.
Kehidupan Ani yang sempurna lalu terguncang ketika seorang pembuat film dokumenter ingin mewawancarainya tentang tragedi school shooting yang dialaminya. Kejadian yang akan selalu melekat dengan dirinya, dan orang-orang selalu mengira bahwa Ani terlibat dalam peristiwa tersebut.
Film Netflix berdurasi hampir dua jam ini memiliki banyak hal untuk diceritakan. Penuturannya tidak semulus versi novel, tetapi sebagai kritik sosial, film ini selalu tepat sasaran. Jessica Knoll paham betul cara mengolah materi adaptasinya menjadi rangkaian plot yang koheren. Tidak semua hal dalam buku dituangkan ke film, tetapi poin utamanya tetap sama, bahwa trauma akan tinggal dalam waktu yang sangat lama dan tidak mudah untuk menghadapinya.
Awalnya saya mengira Luckiest Girl Alive akan menjadi film misteri seperti bagaimana Netflix menjualnya. Saya pikir Jessica Knoll memang ingin membuat adaptasi bukunya menjadi seperti Gone Girl karya David Fincher yang misterius dan menegangkan. Nyatanya, film ini menawarkan drama yang reflektif.
Tapi, memangnya ada kesamaan antara Luckiest Girl Alive dengan Gone Girl? Ya ada. Kedua film ini cukup provokatif dan brutal. Luckiest Girl Alive memuat adegan pemerkosaan dan penembakan dengan cukup gamblang. Namun, porsi adegan-adegan tersebut masih terbilang wajar. Kecuali jika kamu memiliki pengalaman serupa, film ini mungkin akan sulit untuk ditonton.
Luckiest Girl Alive bertransformasi dari 15 menit yang cukup “cerah” menjadi kisah korban pemerkosaan yang dituduh terlibat dalam penembakan massal di sekolah 15 tahun lalu. Saya suka bagaimana Mike Barker dan Jessica Knoll merusak ekspektasi penonton (dalam hal yang baik). Sebab kalau film ini tidak bertransformasi, ini hanya akan jadi film tentang perempuan yang berharap bisa melakukan apa yang dia pikirkan—seperti membunuh calon suaminya sendiri, misalnya. Selain itu, film ini akan sangat menyebalkan. Saya bersyukur film Netflix ini menjadi lebih thoughtful dan bertindak adil pada semua karakternya.
Film ini cukup berhasil menjelaskan sulitnya move on dari trauma. Beranjak dari trauma tidak semudah nasehat sabar dan sok bijak dari orang-orang. Film ini menjelaskan dengan panjang lebar sesulit apa untuk mengungkapkan rasa sakit yang diderita akibat trauma masa lalu.
Menggambarkan trauma dan penderitaan korban pemerkosaan
Luckiest Girl Alive juga menggambarkan bagaimana penderitaan korban pemerkosaan (tanpa mengeksploitasi penderitaannya) dan bagaimana trauma membangun dan merusak banyak hal dalam hidup. Ani yang selalu didikte oleh ibunya, suatu hari sadar bahwa mimpinya penting, begitu juga mimpi semua perempuan. Ani dihadapkan pada pilihan dilematis seperti pindah ke London bersama Luke dan hidup sebagai istrinya atau bekerja di New York Times seperti keinginannya. Dia akhirnya mampu memutuskan pilihan berdasarkan dirinya, bukan ibunya.
Jessica Knoll dalam buku dan naskah filmnya juga memperlakukan korban pemerkosaan seperti Ani dengan bijak. Film ini tidak menghakimi, tetapi berusaha memahami perasaan dan pikiran Ani. Film ini juga percaya bahwa semua orang bisa bangkit dari keterpurukan, seburuk apa pun itu. Ending film ini sangat powerful dan savage, merealisasikan semua racauan yang sebelumnya hanya ada di pikiran Ani. Film ini berakhir tanpa meninggalkan teka-teki atau pertanyaan. Semua hal yang ada di film ini disimpulkan dengan baik di akhir.
Satu hal penting selain trauma yang perlu disorot di film ini adalah tamparan untuk masyarakat dan media soal jarangnya pemerkosaan disebut pemerkosaan. Kita lebih sering membaca kata “cabul”, “disetubuhi”, “rudapaksa”, dan seterusnya pada tajuk berita daripada secara gamblang menyebut “pemerkosaan”. Hal tersebut terdengar seperti melindungi pelaku pemerkosaan, masyarakat dan media bahkan lebih sering membahas dan menggunjing korban.
Setelah menonton Luckiest Girl Alive, saya mengingat kembali versi novel yang saya baca sewaktu SMA. Kemudian saya menyadari bahwa meski bersifat fiktif, beberapa kejadian di film ini diambil dari kejadian nyata yang menimpa penulisnya, Jessica Knoll saat remaja, termasuk pemerkosaan (gang rape) dan kejadian school shooting. Saya juga kembali mengunjungi esai What I Know yang ditulis Jessica Knoll, yang secara gamblang menuliskan pengalaman mengerikan yang dialaminya. Saya akhirnya memahami mengapa film ini begitu kuat secara naratif dan sangat reflektif.
Luckiest Girl Alive adalah film tentang berdamai dengan trauma yang “brutal”, tetapi juga reflektif. Terlepas dari kekurangan teknis seperti editing yang tidak konsisten, film ini layak dinobatkan sebagai salah satu rilisan Netflix terbaik tahun ini. Saya ingin sekali merekomendasikan film ini kepada semua orang, tetapi karena mengandung banyak adegan yang mengganggu, sebaiknya kamu membaca informasi tentang film ini dahulu sebelum menonton.
Penulis: Rizal Nurhadiansyah
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Film Semi Terbaik di Netflix yang Nggak Cuma Jual Adegan Seks.