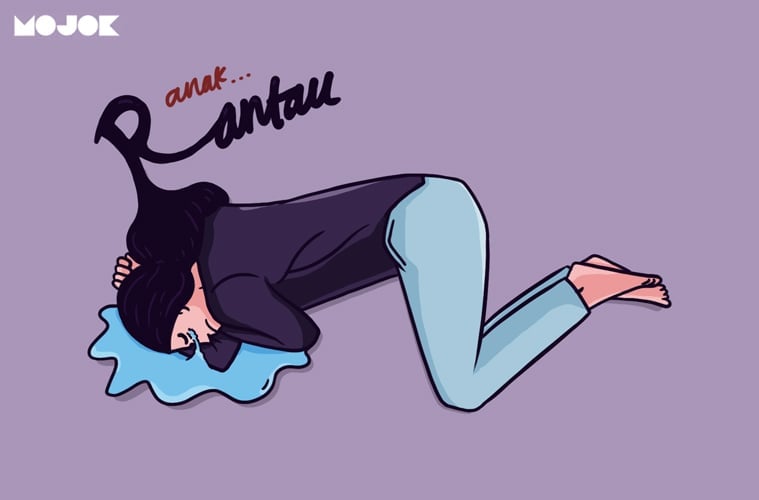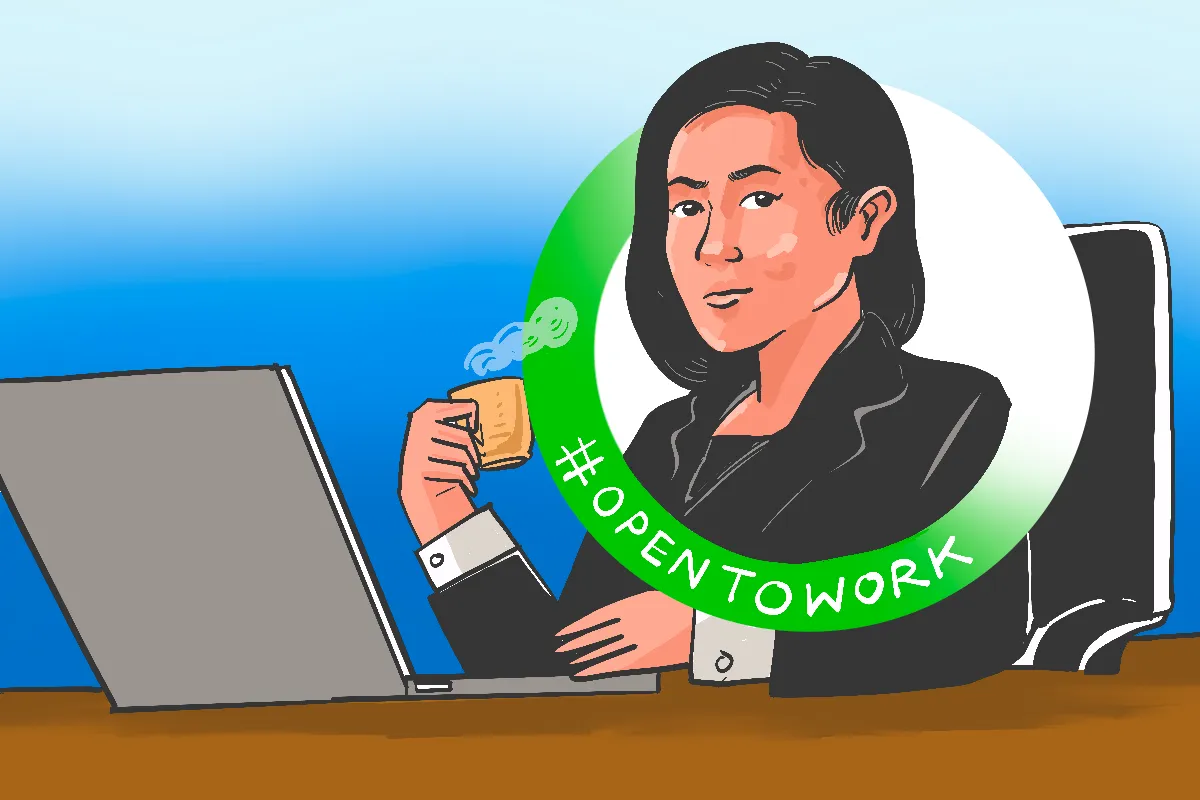Saya tidak pernah sekalipun mencari tahu kapan Mojok muncul atau dilahirkan. Pun, tidak pernah mencari tahu bagaimana awal mula pertemuan Puthut EA dengan Agusmul. Bukannya apa-apa, saya lebih suka dengan istilah yang lalu adalah untuk yang dulu, sedang yang sekarang adalah perayaan untuk diperjuangkan.
Romantika Mojok dan saya sudah berlangsung sejak saya awal masuk kuliah. Media ini banyak menjadi omongan karena sang ketua suku, Puthut EA, adalah kakak tingkat jauh saya di Fakultas Filsafat. Dan yang menjadi sumber inspirasi bahwa bahasan rumit tidak harus dilawan dengan berat. Maka, jargon “sedikit nakal banyak akal” seakan menjadi antitesis sempurna dalam menambah bahan bacaan untuk saya di balik ndakiknya buku-buku kuliah yang njimet dan bikin mumet.
Hubungan saya dan Mojok tidaklah selamanya langgeng, menengok sebuah hubungan ada pasang-surut hingga perpisahan. Kejadiannya kurang lebih sebelum Mojok evolusi besar-besaran dan menutup situsnya (kalau nggak salah ingat).
Sebelum Mojok tutup akun, saya sempat merasakan bosan membaca saja. Rasa penasaran itu berevolusi menjadi rasa ingin menulis ala Mojok. Pernah suatu ketika saya misuhi Mojok karena tulisan saya tak satupun dinaikan. Mungkin bahasa kerennya adalah keblinger, merasa paling mojok padahal tidak ada sama sekali mojok-mojoknya. Setelah saya baca lagi tulisan saya yang dulu—3 tahun lalu—isinya cuma nakal-nya tok, akal-nya entah hilang kemana. Saya pun menjadi malu kepada diri sendiri dan berjanji untuk kembali meriuhkan kolom emailnya, namun tidak untuk saat itu.
Hingga pada 2019 (kalau nggak salah ingat (2)), semesta sepertinya mengijinkan saya kembali dalam pangkuan Mojok. Namun, Mojok yang ini ada embel-embel Terminal di depannya. Mojok saja filosofinya saja saya tidak tahu, apa lagi kini ada terminal di depannya. Yang jelas, Terminal Mojok kini menjadi “tempat bermain” yang menyenangkan bagi saya dalam banyak hal yang meliputinya. Dan seringnya saya (walau tidak sesering penulis lain) menulis untuk Terminal, acap kali mendapatkan stigma yang unik selain stigma nama Adit yang sering dikira fakboi.
Pertama, satu tulisan yang lolos maka satu perayaan wajib di burjonan. Entah stigma ini datangnya dari mana. Sering salah kaprah kala banyak yang mengira menulis itu banyak uangnya. Padahal, menulis itu sebenarnya murni proses kreatif, kan? Datangnya dari kepala dan digerakkan oleh indera. Nah, ini adalah salah satu jawaban diplomatis yang paling saya hindari. Padahal, nulis di Terminal, adalah tujuan terselubung saya beli stok mie instan di indekos.
Sedih tapi realitanya seperti itu, wahai teman-teman yang suka minta dijajain tiap tulisan saya dimuat. Hitungannya begini, deh, semisal pendapatan maksimal perbulan di Terminal Mojok adalah 400 ribu. Sedang satu dos mie instan goreng isi 40 seharga 99 ribu rupiah di toko online. Dengan 40 mie instan, saya bisa bertahan hidup selama satu bulan dengan catatan lambung saya bermasalah setelahnya. Atau bisa saya bagi-bagikan ke rekan indekos dengan catatan saya menanggung biaya obat pencernaan teman-teman saya setelahnya.
Nah, 300 ribu sisanya tidak saya pergunakan secara sia-sia. Tujuannya tentu saja angkringan yang tersedia di setiap sudut gang tempat kos saya. Dengan uang segitu, maka saya bisa menggunakan 10 ribu rupiah per hari untuk bebas memilih nasi kucing dan es tehnya. Namun menjadi perdebatan kala saya diberi kesempatan untuk memilih antara sate usus atau sate telor puyuh. Duh.
Kedua, saya sering dianggap menjadi gila gara-gara menulis di Terminal Mojok. Bukan berarti saya memukul rata semua penulis di Terminal Mojok mendapat stigma ini, ya. Dan munculnya stigma itu sangatlah beralasan. Pertama, tulisan saya sering merecoki keuangan orang lain seperti contohnya dari mana Patrick Star yang gaweannya cuma baringan mendapatkan uang untuk beli krabby patty. “Ngapain sih ngurusin yang nggak penting?” Wah, tunggu dulu, kata siapa tidak penting? Bahkan saya waktu kecil sempat tidak bisa tidur gara-gara memikirkan hal ini.
Bukan hanya gila saja, saya bahkan pernah dikira konsumsi ganja karena pernah melakukan wawancara imajiner dengan Kojiro Hyuga di Pasar Dengung. Padahal kan susah, ya, mencari waktu yang tepat untuk mewawancara Kojiro Hyuga, dan kebetulannya malah ketemu ketika dia sedang belanja kebutuhannya di mess. Dari tulisan itu pun saya menulis tentang wawancara saya dengan pagar dekat bunderan soshum UGM yang membuat saya pribadi merenungi arti dari sebuah keabadian.
Ketiga, sebenarnya ini bukan stigma, sih. Melainkan sebuah ketakutan dari pembaca Terminal Mojok di kolom komentar yang terkadang ganas-ganas. Tapi, selama berjalannya waktu, rasa takut tersebut malah berbalik menjadi rasa semangat. Dan berikut adalah kumpulan komentar yang membuat saya semakin giat menulis. “Saya tidak suka dengan kata “laknat” yg Ada di tulisan ini .. seketika langsung saya hentikan aktifitas membaca saya. Dan pergi ke kolam komentar .. untuk meluapkan ketidak setujuan saya. Pada penulis dengan pemilihan kata .. yang .. kurang pantas menurut saya.. kata itu sangat kasar……..”
Atau ketika saya membahas tentang komentator sepak bola dengan panjang lebar dan memberi penjelasan baiknya bagaimana, lalu ada yang berkomentar “Lhaaa qta mo nonton bola atw host?” iyaaaa juga yhaaa. Kebanyakan orang itu melihat bola bahkan cuek dengan komentatornya, tapi ya bagaimana pun kedua aspek itu harus saling bergantung secara mutualisme. Dan penonton di rumah harus mendapatkan feedback yang bermanfaat.
Keempat, sering dikira wibu dan diajak ngobrol hal-hal berbau anime. Begini, iya saya suka sama kultur pop Jepang mulai dari game King of Fighter, bahkan The King of Fighters XIV di konsol PS 4 pun saya masih njajal, sampai manga Haikyuu yang saya sukai karena saya memang suka olahraga voli. Tapi, tidak semua kultur pop jepang seperti issekai-issekai-an saya hapal satu-satu. Bahkan saya pernah ditanya, “waifu-mu sopo?” oleh teman saya. Saya jawab saja dengan enteng, “Buttercup!”
Juga ada yang tiba-tiba ngajak ke event jejepangan berkat tulisan-tulisan saya di Terminal Mojok yang membahas sisi kewibuan. Dari sana, lingkup pertemanan saya bertambah, saya bisa melihat sisi lain kehidupan seorang wibu yang mengasyikan. Apakah saya ingin dianggap menjadi salah satu bagian dari mereka? Ah, biarkan posisi saya sebagai pengamat saja. Yang jelas, tulisan saya yang naik di Terminal Mojok, membuka cakrawala baru saya terhadap dunia yang sebelumnya tak pernah saya tapaki.
Bukan, bukan saya malu menjadi salah satu bagian dari teman-teman wibu. Saya itu paling tidak sanggup maraton film, apa lagi anime. Mata saya ini sering kecapekan. Lebih enak baca buku atau manga, serius. Tapi saya ini menyukai apa yang menurut otak saya suka. Band-band Jepang pun saya sukai, mulai dari Mas Hyde yang bikin saya geleng-geleng karena sudah tua saja masih keren. Masih ada Crossfaith, Fear and Loathing in Las Vegas sampai kini One Ok Rock yang seakan band asal Jepang tidak ada habisnya.
Setidaknya itu romantika saya ketika menulis di Terminal Mojok yang melahirkan banyak stigma yang merubah tataran kehidupan saya di bumi. Ketika bernapas hanya sekadar bernapas, kini napas yang saya keluarkan ini harus memiliki sebuah nilai tersendiri. Begitukan prinsip dari Terminal Mojok? Apa saja bisa jadi ide tulisan. Lha wong gajinya Tsubasa saja saya pikirkan, apa lagi kualitas tulisan untuk dibaca oleh jamaah Mojokiyah yang diciptakan oleh Tuhan untuk bersenang-senang dengan sebuah tujuan.
BACA JUGA Alasan Saya Menulis 248 Tulisan dan Mengirim Lebih dari 1 Naskah per Hari di Terminal Mojok atau tulisan Gusti Aditya lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pengin gabung grup WhatsApp Terminal Mojok? Kamu bisa klik link-nya di sini.