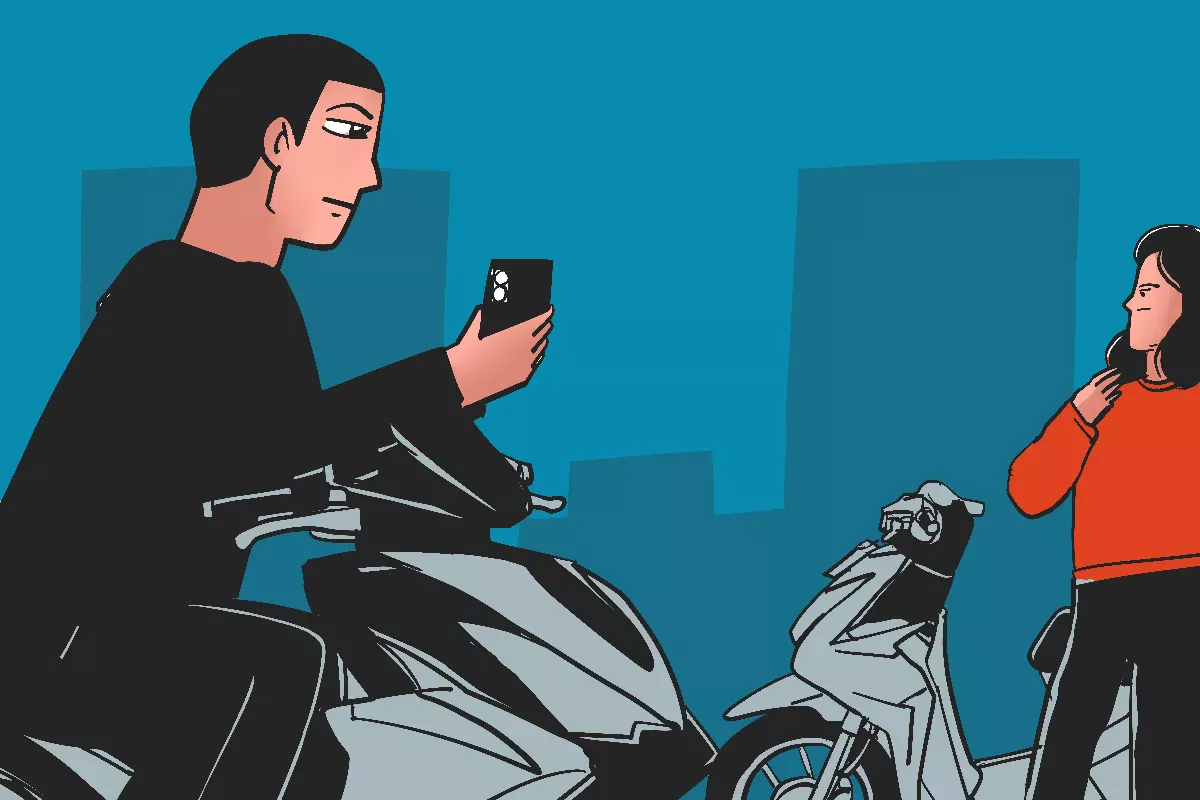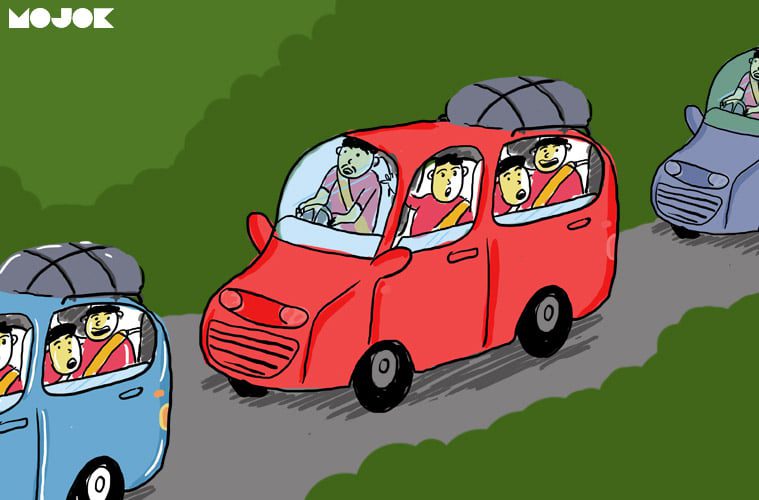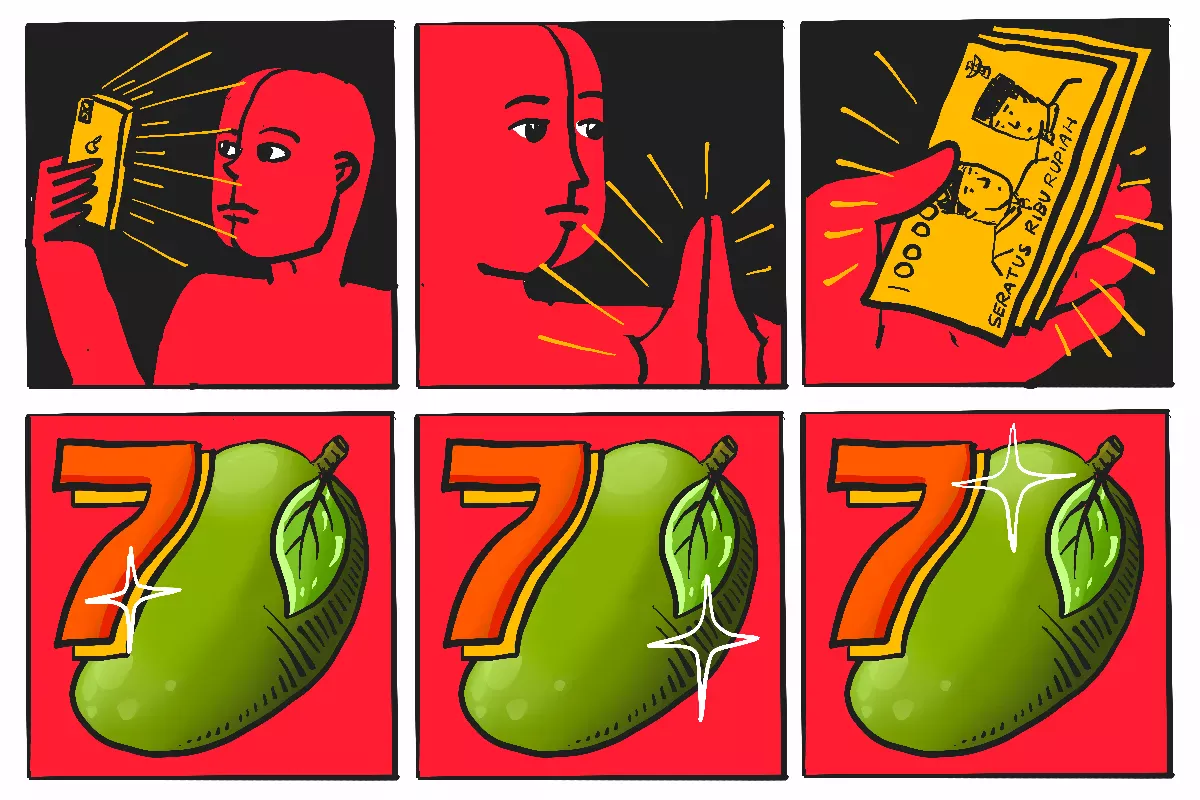#2 Nggak mengajari cara membaca yang benar
Ketika S1, jarang sekali dosen memberi bacaan spesifik yang realistis. Dosen S1 saya cenderung memberi banyak pilihan buku bacaan tanpa strategi membaca yang realistis. Pokoknya dipaparkan saja judul-judulnya, pilih sendiri, baca sendiri, dan simpulkan sendiri. Di kelas, ya presentasi tanpa arah lagi.
Sedangkan ketika S2, saya diajarkan cara membaca jurnal ilmiah dan bagian buku yang benar. Misalnya, dosen memberi satu jurnal untuk dibaca seminggu dan dipresentasikan. Tetapi dosen juga tidak membatasi jika mahasiswa ingin membaca referensi tambahan yang sesuai. Satu jurnal menjadi realistis dan akan benar benar dibaca mahasiswa dibanding banyak rekomendasi nggak jelas yang berujung nggak ada yang dibaca sama sekali.
Lebih dari itu, ketika kelasnya dimulai, dosennya keliatan sekali kalau juga ikut membaca bacaan yang akan dibahas. Nah, hal ini yang jarang saya temui dari dosen-dosen S1 saya dulu. Huft.
#3 Nggak mengajari software praktis keilmuan
Lantaran saya dari ilmu sosial, maka ada software populer yang namanya SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). Software ini fungsinya digunakan untuk mengolah data statistik untuk penelitian kuantitatif. Harusnya diajarkan secara bertahap dan serius ketika S1.
Akan tetapi hal itu nggak terjadi. Kelas metode kuantitatif dan statistik seakan hanya formalitas yang lebih sering dianggap candaan. Dosennya pun ngawur dan keseringan bercanda tanpa ilmu praktis yang berarti.
Alhasil ketika S2, saya keteteran. Beberapa mahasiswa dari kampus top justru sudah mahir menggunakan SPSS bahkan sudah di level penguasaan software lain seperti Stata dan R-Studio. Duh, di situ saya mengumpat dalam hati dan memaki tipis dosen statistik saya waktu S1. Hadeeeh.
Syukurnya, dosen S2 saya masih rela mengajar SPSS dari awal untuk alumni kampus medioker seperti saya ini. Pengajaran yang seharusnya dilakukan oleh dosen S1. Saya curiga, dosen S1 saya juga nggak ngerti SPSS. Hmmm.
Problem kampus medioker menjadi makin pelik kalau kualitas dosennya saja begitu, ya kan? Segera perbaiki lah. Tingkatkan lagi skill dosennya. Kasihan mahasiswa dan alumninya, lho.
#4 Nggak memberi penjelasan materi dengan porsi yang cukup
Ada beberapa mata kuliah ketika S1 yang dosennya nggak pernah masuk. Alasannya macem-macem, mulai dari studi S3 sampe ke naik haji. Tapi mahasiswa nggak ada yang protes, karena nilai akhir semua mahasiswanya rata, pasti A.
Jangka pendeknya, enak. Nilai bagus tanpa belajar. Tapi jangka panjangnya, bikin nyesel ketika sekarang memutuskan lanjut S2. Soalnya saya jadi merasa ketinggalan dari mahasiswa lulusan kampus top yang dapet materi utuh tentang mata kuliah yang sama. Sebut saja Kajian Gender.
Saya belajar sendiri, baca sendiri. Sedikit banyak akhirnya saya mengerti dari membaca buku dan jurnal. Tetapi pasti akan lebih menarik dan banyak pengetahuan baru kalau ada kelasnya. Potensi diskusi lebih luas dan penjelasan teoritis dan pengalaman dosen juga akan memperkaya pengetahuan. Cuma begitulah kampus medioker.
Nah, syukurnya dosen dosen ghosting begini nggak saya temui di S2. Dosennya profesional dan kalau nggak bisa ngajar pasti ada kelas pengganti. Katanya, mengajar mahasiswa itu tanggung jawab intelektual dan moral mereka. Jadi di luar penugasan mandiri mahasiswa, mereka sadar tetap perlu memberi penjelasan yang serius sesuai porsinya.
#5 Kampus medioker membuat mahasiswa terbiasa mengarang bebas
Ketika S1 di kampus medioker, setiap mahasiswa dituntut menulis penelitian di setiap mata kuliah. Kalau ambil 8 mata kuliah, berarti harus ada 8 penelitian dalam satu semester. Ini jelas nggak realistis kalau penelitian sosial yang membutuhkan pengumpulan data wawancara mendalam.
Sialnya, tugas penelitian adalah wajib sebagai syarat lulus mata kuliah. Mau nggak mau, ya harus selesai semua. Konsekuensi terburuknya karena waktu nggak nutut, ya mengarang bebas. Hasilnya, tulisan riset mahasiswa nggak berkualitas. Niat bisa publikasi dan mendongkrak akreditasi, malah menghasilkan mahasiswa yang terbiasa menulis jelek. Kalau kata pepatah, jauh panggang dari api.
Itulah 5 dosa kampus medioker terhadap alumninya yang memutuskan lanjut S2 di kampus top. Ranking kampus memang bukan segalanya, tapi berdasar pengalaman saya justru nyaris menjadi representasi yang nyata. Paling tidak, kuliah di kampus top memberikan peluang lebih besar untuk dididik oleh pendidik yang oke. Dengan pendidik yang baik, belajar jadi nyaman dan khidmat. Barangkali dari situ justru kesuksesan bisa terlihat sedikit lebih jelas.
Untuk kampus medioker, kualitas pengajaran dosen perlu dibenahi. Jangan sampai mengorbankan mahasiswa dan alumninya karena kurang ilmu yang kalian berikan. Tetap semangat.
Penulis: Naufalul Ihya’ Ulumuddin
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Kampus Ruko Dipandang Aneh dan Disepelekan, tapi Saya Nggak Menyesal Kuliah di Sana.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.