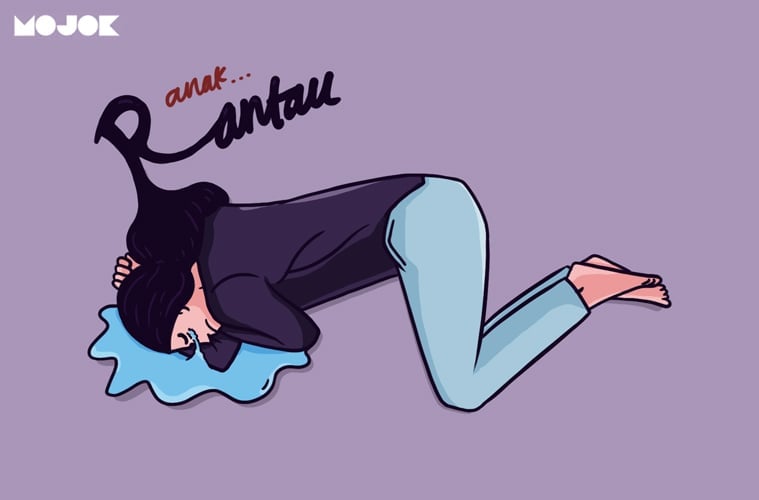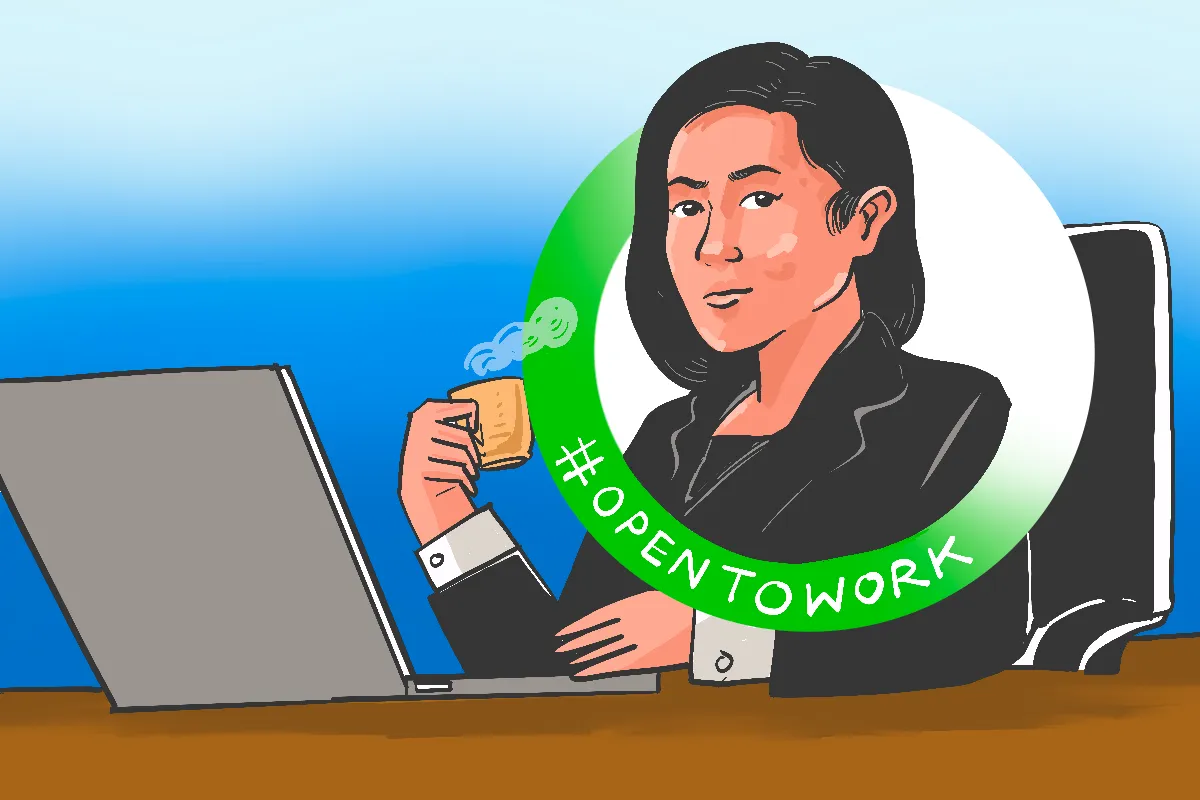Karya sutradara Yosep Anggi Noen memang memiliki sebuah benang merah yang jika dicermati selalu nakal dalam merepresentasikan kebungkaman. Kali ini film The Science of Fictions atau Hiruk-Pikuk Al-kisah hadir sebagai sebuah karya yang turut berusaha membebaskan diri dari sepinya kursi merah sinema. Bagaimana proses film ini sampai bioskop memang seolah memetaforakan ceritanya sendiri.
Saya tahu ini film “susah”, film yang mungkin cuma bisa dicerna oleh sinefil-sinefil edgy penggemar sinematografi yang rasanya kalau nggak pernah nonton filmnya Wong Kar-wai itu nggak mungkin. Merayakan film ini adalah dengan cara membedah konteks sejarah, politik, dan berusaha mengintip isi kepala Mas Anggi Noen. Film ini bakal jadi senjata orang-orang yang suka bilang, “Lu nggak tau film The Science of Fictions? Hadeeeh, katanya penyuka film?”
Tentu, tidak ada yang salah dengan itu. Film ini jelas layak mendapat penerimaan dengan sakral. Menyusunnya tidak mudah, proses olah pikirnya begitu panjang, bahkan menemukan ide untuk membuat sang aktor melakukan slow-mo sepanjang film itu jenius. Yosep Anggi Noen sendiri pernah jujur bahwa ide film ini dibuat hampir sepuluh tahun lalu ketika segala teknik perfilman belum mumpuni seperti sekarang. Kesabarannya telah lunas. Kritikus bakal standing applause sambil mengingat bayang-bayang Orde Lama, Soekarno dan G30S, genosida, dan pendaratan manusia di Bulan. Montase-montase itu hadir seperti kelap-kelip lampu disko.
Tapi, saya yakin orang bodoh seperti saya juga berhak merayakan film The Science of Fictions sebagai sebuah karya. Tanpa harus tahu apa yang sebenarnya pengin disampaikan sutradara, karya ini sangat mungkin dinikmati secara visual sebagai sebuah narasi yang juga menampilkan konflik dan penyelesaian. Bukankah pemaknaan itu milik penonton ketika film sudah naik ke layar?
Andai boleh saya sampaikan, Mas Anggi Noen selalu punya selera humor yang nyentrik banget. Siapa yang nggak akan geli melihat tokoh Siman minum gelas slow-mo layaknya Neil Amstrong yang sedang membuktikan teori Einstein di Bulan. Bahkan gerak tubuh Siman kalau dipercepat empat kali, dikasih latar musik “Thriller” udah bakal menyaingi jogetan Michael Jackson.
Siman adalah kita yang selalu lamban untuk tidak mengatakannya sabar. Siman punya dunia yang indah, keinginannya sangat jujur, yaitu jadi manusia Bulan.
Film ini tegas untuk memulai konfliknya di awal cerita. Membuat penonton setengah mati memikirkan kalimat sepanjang diputarnya film, “Iki sakjane Siman ngopo?” Bahkan ketika penonton sudah “akrab” dengan gerakan Siman yang begitu pelan, penonton dikagetkan dengan bagaimana dia begitu normal ketika emosi, lelah, kecewa, dan birahi. Ooh, jadi Siman lamban itu sandiwara? Kira-kira bisunya sandiwara juga nggak sih?
Tokoh yang tutur lakunya plek ketiplek seperti Siman memang hampir mustahil ada. Tapi, kerennya, karya ini membuat kita percaya kalau memang selalu ada orang-orang begini. Orang-orang yang punya dunianya sendiri, mereka yang selalu keras kepala dan konsisten dengan batasan yang mereka buat sendiri, batasan itu sering kita hakimi sebagai perilaku aneh. Mau ditertawakan seperti apa pun, Siman tetap slow-mo.
The Science of Fictions itu memang bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang, bukan cuma di tataran sejarah dan politik yang cuma bisa dicerna sinefil terpelajar. Kita yang ndah-ndoh juga akan membela Siman untuk mewujudkan mimpinya, mengumpulkan uang, dan entah bagaimana lah kalau bisa dia beneran pergi ke bulan. Tujuan ini tentu didaratkan dengan halus dalam penyelesaian cerita. Sebagai penonton, rasanya bangga banget menonton film dengan ending yang nggak bisa ditebak. Walau pertanyaan nyeleneh soal “Gimana caranya Siman mantap-mantap ya? Gimana caranya Siman makan ya?” dijawab dengan manis dalam adegan, pertanyaan jauh penonton jelas soal bagaimana cerita ini akan diakhiri.
Beberapa orang mungkin bakal merasa kalau film ini bikin ngantuk. Nungguin Siman naruh map merah di pabrik aja lamanya bukan main kok. Tapi, sebagian justru menikmati visual film ini yang begitu jujur. Kehidupan pasar, kehidupan buruh, cerita TKI Jepang, dan bapak-bapak menggosip sambil merokok-membahas tetangganya yang telah murtad.
Dibuat dengan dua format yang menunjukkan perbedaan waktu, saya sebenarnya sempat terganjal dengan motivasi film ini mengabaikan setting waktu. Yang satu ada di 1966, yang satu di masa kini. Keduanya masih dihadiri Siman yang sama seolah ia tokoh imortal.
Iya saya tahu, ada maksud dari semua itu, pasti. Namun, dalam narasi kebodohan pemikiran saya, alasan silogisme itu kurang believable untuk menggabungkan keduanya dalam kesatuan yang utuh. Alih-alih memahami bahwa kebenaran sejarah itu mengalami diversifikasi, saya justru meraba-raba di tahun berapa Siman mendarat pada frame film yang berwarna. Mau bilang kalau setting waktunya masa kini karena melihat ponsel Android dan tampilan uangnya kok ya nggak yakin. Tidak ada sekat yang tegas seperti planting info penyebutan tahun yang jelas muncul di format hitam putih. Otak saya terpaksa beranggapan bahwa format hitam putih sengaja dibuat untuk prolog, bukan bagian yang menyatu dengan cerita panjangnya.
Bagaimanapun, yang jelas The Science of Fictions berhasil bikin efek nyata di akhir cerita. Saya yang dari tadi nonton film kok bisa-bisanya di ending merasa lagi ditonton. Breaking 4th wall kali ini bener-bener “breaking” ya, Bund, sampai ngeri sendiri sambil cari-cari posisi CCTV bioskop. Saya jadi ingat film pendek Mas Anggi Noen yang lain, Ballad of Blood and Two White Buckets yang efeknya sukses bikin saya batuk-batuk walau sebelumnya nggak minum es.
Sumber gambar: YouTube International Film Festival Rotterdam
BACA JUGA Kebodohan Acara Televisi Indonesia Memang Sudah Semestinya Dirayakan dan artikel Ajeng Rizka lainnya.