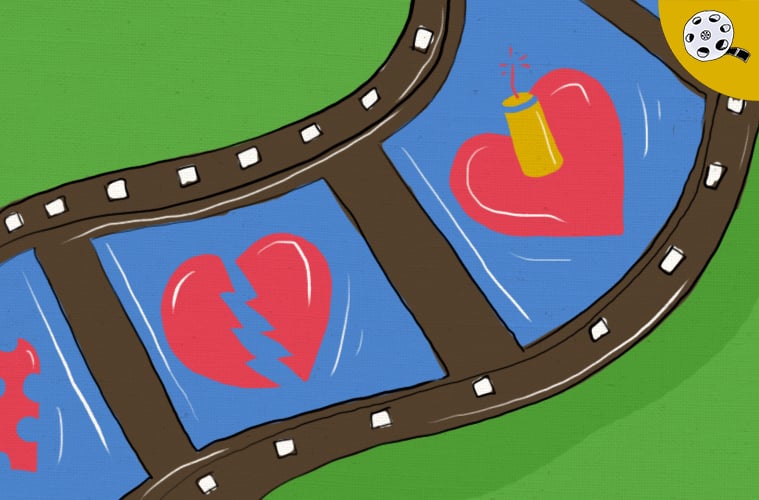Sebelum menyaksikan tangisan massal di aula pelatihan ESQ, pemandangan pertama saya tentang orang-orang berurai mata tanpa malu-malu di keramaian terjadi di depan layar kaca.
Itu ketika Kuch Kuch Hota Hai tengah diputar dari VCD player. Di hadapan tragedi cinta Bollywood itu, air mata turun tanpa pandang umur, lebih deras dari air mata Shah Rukh Khan, lebih keras sengguknya dari si pemeran Anjali kecil.
Belakangan saya menyadari hal yang sesungguhnya sudah terjadi lama dan merata: orang yang bersedih cenderung melarutkan diri pada film dan musik yang juga sedih. Terutama jika penyebab perasaan terluka itu adalah cinta.
Seorang teman pernah melempar pertanyaan, “Mana yang lebih dulu, orang menonton film sedih lalu bersedih, atau orang bersedih lalu menonton film sedih?”
Ia yakin, yang kedua lebih tepat.
Dalam kasus patah hati, disarikan dari pengalaman-pengalaman, saya putuskan untuk mengiyakan pendapatnya. Cinta memang bikin orang jadi masokis. Di mana-mana, aksi selalu akan ditimpali dengan reaksi, begitu kan kata Newton? Kalau lapar, makan; jika ngantuk, tidur; kalau kangen, bilang.
Pada orang patah hati, perlakuannya berkebalikan. Sedih dibuat semakin sedih, kangen didesak pada titik tertingginya, ingatan menyakitkan diimbuhi dengan ingatan lain yang membuat semua semakin menyakitkan.
Aneh memang. Masalahnya cinta itu bukan berdasar hukum fisika. Logika cinta adalah logika vaksin. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan dimasukkan ke tubuh agar imun ketika penyakit sebenarnya datang. Sedih disedih-sedihkan agar ketika sedih lagi kelak, sedihnya tidak sedih-sedih amat. “Murung itu sungguh indah. Melambatkan butir darah,” kata ERK.
Oke, kita sudah tahu hukumnya, bahkan mungkin kamu sudah mengalami juga dan mengangguk-angguk membenarkan. Jadi, tidak menimbulkan heran apabila orang pesimistis justru keranjingan lagu ultrapesimistis seperti “Asal Kau Bahagia”.
Manusia itu memang perlu sedih. Pahami dan nikmati saja, jangan dianggap penyakit. Dia cuma vaksin.
Di bulan vaksinasi campak dan rubela ini, saya berterima kasih pada diri sendiri sudah pernah melalui patah hati yang beratnya masyaallah keterlaluan sekali. Patah hati yang membuat diri tidak pernah sama lagi setelahnya. Waktu membuktikan, selepas kejadian sialan yang patut disyukuri itu, kesedihan-kesedihan sejenis bisa dihadapi dengan lebih kuat. Masih sedih kadang, tapi tidak sehisteris dulu.
Ada beberapa film yang menjadi bekal di fase itu. Sekarang, kalau menonton film-film itu lagi, perasaan melankolis masih naik turun. Tidak apa, hidup jadi lebih dinamis berkatnya.
Film pertama berjudul Chungking Express garapan sutradara Tiongkok Wong Kar Wai. Ceritanya berpusar di tengah piruknya Kota Hong Kong dengan dua orang polisi berkutat pada kenangan mantan pacar mereka melalui cara masing-masing.
Polisi pertama, He Zhiwu (Takeshi Kaneshiro), memantulkan kekecewaannya lewat obsesi pada nanas kalengan hampir kedaluwarsa. “Jika kenangan bisa dikalengkan, apa dia bakal punya tanggal kedaluwarsa juga?” tanyanya.
Kedua polisi itu ditinggalkan kekasih dan tidak mengerti apa alasan yang cukup kuat untuk berpisah, terlebih setelah semua kenangan yang mereka buat bersama. “Di mata May, aku tak berbeda dari sekaleng nanas,” kata He Zhiwu lagi.
Nanas kalengan yang jika sudah kedaluwarsa, bisa dibuang begitu saja.
He Zhiwu kemudian bertemu seorang perempuan yang membuatnya tertarik. Suatu kali perempuan itu bilang, “Sebenarnya, benar-benar mengenal seseorang itu tak ada artinya. Orang terus berubah. Hari ini dia bisa jadi nanas, besok dia akan jadi hal lain.”
Untuk orang yang pernah diputuskan oleh pacar atau ditinggal menikah begitu saja tanpa penjelasan yang cukup, menonton film ini serasa menyaksikan diri sendiri. Selain ceritanya, lagu “What a Difference a Day Makes” dari Dinah Washington benar-benar membuat ingin memperbarui blog dengan tulisan semicurhat yang mendayu-dayu lagi.
Norwegian Wood yang diangkat dari novel karangan Murakami Haruki punya nuansa yang mirip: perasaan kosong.
Persahabatan Toru, Kizuki, dan Naoko berantakan ketika suatu hari Kizuki ditemukan bunuh diri tanpa alasan pasti. Setelah itu, Toru tak pernah lagi bertemu dengan Naoko yang juga kekasih Kizuki, sampai pada satu ketika, di masa mahasiswanya, mereka berpapasan di jalan.
Hubungan mereka berubah dari nostalgia teman lama menjadi perasaan yang lebih intens, tapi Naoko kemudian menghilang kembali karena merasa bersalah pada cinta lamanya dengan Kizuki. Selama Naoko menghilang, Toru bertemu Midori.
Dua gadis itu menyiksa Toru karena di satu sisi, mereka membuka hubungan dengan Toru, di sisi lain mereka tak punya ruang di hati mereka untuk Toru. Sebagaimana lirik di lagu The Beatles yang dijadikan judul film ini, “I once had a girl or should I say, she once had me. […] She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn’t a chair.”
Jika kenangan cinta yang gagal begitu melumatmu, akankah kamu mau untuk memilih menghapus kenangan itu? Itulah yang dipilih Clementine (Kate Winslet) dalam Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Hubungan yang dimulai dari pertemuan tak sengaja antara Clementine dan Joel (Jim Carrey) berawal bahagia dan berakhir depresif. Tipikal. Tapi, Joel semakin terpuruk ketika tahu Clem telah datang ke klinik penghapus ingatannya untuk membuang semua kenangannya bersama Joel. Sejak itu, Clem tidak lagi mengenal Joel Barish dalam hidupnya. Joel pun lalu melakukan hal yang sama.
Lewat kilas balik ketika penghapusan kenangan terjadi, penonton disodori bagaimana proses sebuah hubungan tercipta, menegang, lalu berakhir. Film ini punya akhir cerita yang bajingan, tetapi penggambaran proses itu jauh lebih bajingan. Mungkin inilah film tentang putus hubungan terbaik dan paling depresif yang pernah dibuat manusia.
Namun, soal tranformasi hubungan, master dari segala masternya tentu tak lain adalah trilogi Before Sunrise, Before Sunshine, dan Before Midnight. Melihat cerita, karakter, dialog, dan rentang waktu pengerjaannya membuat tiga film ini, nyaris mustahil akan ada film seperti ini lagi. Penyuka film dengan transisi adegan yang cepat tentu tak suka dengan dialog panjang lebarnya, padahal di situlah kehebatan Trilogi Before.
Bagaimana ia bisa merepresentasikan fase-fase hidup membuat film ini sangat personal bagi saya. Cinta anak muda yang spontan tapi berkesan (“Can your greatest romance last only one night?”), cinta yang kecewa dan menuntut (“What if you had a second chance with the one that got away?”), ditutup dengan cinta yang kompromistis dan dewasa (“Everything’s better with maturity”).
Oke, Before Midnight memang berkisah tentang dinamika pernikahan, tetapi adegan pertengkaran Celine dan Jose cuma karena obrolan soal masa lalu, yang ternyata membuka banyak persoalan yang selama ini mereka pendam, saya rasa dialami oleh banyak pasangan.
Masih banyak film lain yang sama sedihnya. Kuch Kuch Hota Hai yang dibenci sekaligus dipuja itu. Artificial Intelligence yang bagi orang dengan masa kecil tanpa ibu akan sangat melankolis. Stand by Me dengan kisah persahabatan masa kecilnya. AADC 2 yang seandainya diakhiri kejam pasti lebih mengesankan. Vicky Cristina Barcelona yang cocok untuk orang-orang jaim. Atonement yang mendayu-dayu. Closer yang … ah sudahlah. Bahkan film animasi seperti The Wind Rises atau Grave of the Fireflies yang tidak, tidak akan pernah bisa dibuat Hollywood.
Daftar itu masih bisa kamu tambahi dengan film yang sebenarnya tidak sedih-sedih amat, tapi jadi melankolis karena, misalnya, ditonton saat kencan pertama dengan mantan. Tapi, keenam film tadi selain memancing sengguk, juga dapat membantu melewati fase terburuk setelah gagal bercinta. Apalagi jika kegagalan itu datang sebelum usia 27, angka rawan untuk mengidap quarter life syndrome. Jika sindrom itu saja sudah berat, apalagi ditambah dengan daya tahan yang lemah pada patah hati. Kombinasi maut. Kamu perlu bersiap.
Selamat menonton. Menangislah sebelum menangis dilarang.