Yogyakarta lekat dengan mahasiswa dan kuliner. Beragam kuliner khas mulai dari yang sederhana sampai mewah jadi santapan para mahasiswa, demikian pula para penjaja makanannya. Mereka menyimpan segudang cerita dan pengalaman, baik dengan pelanggan yang selintas lalu maupun yang setia hingga lulus kuliah.
Bu Heri Rutin Berbalas Pesan dengan Mahasiswa saat Lebaran
Sisa-sisa hujan yang mengguyur Sleman pada Selasa (21/9) malam membawa kami ke salah satu warung bakmi di daerah Condongcatur. Lokasi persisnya berada di Jalan Sambirejo, Gempol, Condongcatur. Sayangnya, titik lokasi warung ini tidak terdapat di Google Maps, padahal letaknya cukup terlihat karena berada di tepi jalan yang sering dilewati pengendara dari arah utara jika hendak menuju Jalan Affandi-Gejayan.
Ketika masuk ke warung, kami disambut Bu Heri (60), salah satu pemilik warung bakmi godog yang berdiri sejak 1996.
“Monggo, Mas mau pesan apa?” tanyanya sambil memasukkan potongan ayam dan sayuran ke wajan.
“Bakmi nyemek kecap satu, Bu.”
Mulanya, warung ini ia dirikan bersama kakak sepupunya, Bu Mul. Mereka adalah warga Jogja yang tinggal di daerah Minomartani, Ngaglik tak jauh dari lokasi warung.
Saat berjualan mereka selalu berbagi tugas. Bu Heri bertugas memasak semua pesanan pelanggan, sedangkan Bu Mul membuat minuman, mengemas piring, hingga membantu mengaduk masakan di wajan agar tak gosong.

Pada 1996 mereka mematok harga satu porsi bakmi godog, nasi goreng, dan menu lainnya seharga Rp3.500. Harga tersebut, kata mereka, berangsur naik seiring dengan naiknya harga bahan masakan seperti ayam kampung, beras, gula, dan sebagainya.
“Dulu aja beras cuma lima ribu, Mas. Sekarang paling enggak sepuluh ribu,” ucap Bu Mul agak keras karena suara motor berknalpot racing yang kerap lalu-lalang di depan warungnya.
Saat ini Bu Heri dan Bu Mul mematok harga satu porsi bakmi dan kawan-kawannya dengan harga Rp16.000: Hampir lima kali lipat dibanding harga pada 25 tahun lalu, padahal itu merupakan harga yang sama sejak empat tahun lalu.
“Malah beberapa ada yang tanya, ‘Kok, enggak naik, sih, Bu, harganya?’, lalu kata saya, ‘Ya, biar aja, nanti ada waktunya,’“ ujar Bu Heri terkekeh.
Kami yang duduk persis di belakang gerobak melihat para pembeli yang silih berganti selalu disapa oleh Bu Heri dengan ramah.
Selama tiga kali ke sana di hari yang berbeda, kebanyakan pembeli warung Bu Heri merupakan karyawan muda, keluarga anak satu, ibu-ibu, hingga bapak-bapak bermobil yang bunyi alarmnya sampai ke warung saat ia menguncinya.
Kami, yang saat ini masih menjadi mahasiswa, lantas bertanya, “Kalau mahasiswa juga sering ke sini, Bu?”
Ia mengatakan bahwa saat pandemi hanya sedikit mahasiswa yang jadi pelanggan di warungnya karena masih berada di kampung halamannya masing-masing. “Sisa satu orang yang dari Jambi itu, Mas. Itu pun sudah lulus kuliah dan kerja di sini,” sambungnya.
“Dulu ada empat mahasiswa Jambi selalu ke sini. Pesannya pasti magelangan, enggak tahu kenapa suka sekali,” kenang Bu Heri sambil senyum-senyum sendiri.
Meski kini tidak pernah bertemu lagi, Bu Heri masih berbalas pesan dengan salah satu dari mereka, bahkan di sela-sela memasak, ia menunjukkan SMS dari salah satu mahasiswa langganannya kepada kami. Isinya: “Assalamualaikum gimana kabarnya Bu? Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin. (Anak lanang Jambi)”
Ia mengaku masih kerap berbalas pesan dengan mahasiswa itu, entah sekadar bertanya kabar atau mengucapkan selamat lebaran. “Ini, Mas. Masih saya simpan sampai sekarang,” ujarnya sembari menyodorkan ponsel Nokia jadul berwarna biru.
Bu Heri mengatakan bahwa ia sudah biasa memanggil dan dipanggil dengan sapaan akrab. Katanya, para langganan yang sering ke sini punya panggilan masing-masing terhadapnya, mulai dari sapaan “Mbok” sampai “Bu Legend”.
“Mas, kalau saben minggu ke sini, paling nanti datang-datang langsung ngomong, ‘Mbok, madang!’. Yakin, deh, Mas,” kata Bu Mul. Kami tergelak.
Waktu menunjukkan pukul 22.45 WIB. Belum ada tanda-tanda kedatangan pembeli. Bu Mul yang biasanya bermobilitas tinggi, kini terduduk sambil menyandarkan kakinya ke dingklik. Baru ini kami punya waktu untuk berbincang langsung dengannya.
Ia bertanya, “Mas sebenarnya aslinya dari mana, to?” Belum kami sempat menjawab, Bu Heri menyambar dengan menjelaskan secara rinci asal orang tua kami dan pekerjaannya, kami lahir di mana, dan kini tinggal di mana.
Kami terkesiap. Pantas saja banyak pelanggan yang akrab dengannya. Ternyata Bu Heri cepat hafal dengan para pelanggannya, bahkan kami yang baru tiga kali mengobrol dengan mereka.

Malam itu kami berbincang puas sekali. Tak hanya kami yang penasaran dengan cerita mereka, namun Bu Heri dan Bu Mul juga mengorek informasi tentang kami. Kami saling berbagi cerita dan pengalaman masing-masing.
Meski harga yang dipatok relatif mahal bagi mahasiswa kos jika dibandingkan dengan angkringan atau burjo, setidaknya akan sepadan dengan pengalaman dan cerita yang didapat jika menjadi pelanggan di warung ini.
Misalnya, cerita yang dialami Septy, perempuan 28 tahun asal Kalimantan Barat yang kini menetap di Jogja. Ia merupakan salah satu pelanggan warung bakmi Bu Heri sejak 2012. Dahulu, ketika kuliah S1, ia sering makan di warung Bu Heri bersama pacarnya.
“Dulu favoritnya bakmi rebus, saya bakmi goreng,” ujarnya. Meski demikian, pacarnya saat itu kini sudah menjadi mantan dan berkeluarga dengan orang lain, demikian pula dengannya. Meski pengalaman yang lalu dengan mantannya tak mungkin hilang dari ingatan, setidaknya Septy tahu ia harus pergi ke mana bila ingin mencari bakmi godog.
Pak No Tetap Jaga Silaturahmi dengan Pelanggannya
Adalah Pak No (46) dan Bu Sri (39), pasangan suami-istri yang berjualan sejak delapan belas tahun silam. Malam itu (22/9) kami mendatangi warung makan yang terletak di Jalan Karangwuni, Caturtunggal, Sleman. Kami disambut oleh Pak No yang tengah mencuci piring dari pembeli sebelumnya.
Kami memesan nasi goreng bakso dan lanjut berbincang dengan Pak No dan Bu Sri.
“Awalnya, Pak No itu sopir pribadi, Mas,” kata Bu Sri. “Waktu itu bosnya Bapak wis pensiun, akhire pindah haluan, ya karena kebutuhan juga makin banyak, Mas,” pungkasnya.
“Terus nyicil bikin gerobak dulu. Nanti kalau sudah terkumpul uangnya, baru mulai jualan,” ujarnya.

Keduanya juga mengakui bahwa awalnya mereka enggan berjualan bakmi karena keuntungannya lebih sedikit dibanding berjualan yang lain.
“Keuntungannya lebih sedikit dibanding jualan soto,” kata Pak No, “tapi jualan soto, tuh, capek. Jadi, ganti jualan bakmi sama nasi goreng,” timpal Bu Sri.
Aroma nasi goreng yang sudah tercium membuat kami tak sabar mencobanya. Beberapa menit kemudian, pesanan kami diantar Bu Sri.
“Ini, Mas, pesanannya,” kata Bu Sri dengan ramah. Walaupun mengenakan masker, tarikan di kedua matanya tak bisa membohongi bahwa ia sedang tersenyum.
Pak No bercerita pelanggan yang paling sering makan di warungnya merupakan mahasiswa UGM dan UNY. Kebanyakan adalah mahasiswa yang ngekos karena harga yang cocok bagi mereka.
Daftar menu yang berada di meja mendorong rasa penasaran kami untuk menanyakan harga yang dipatok Pak No saat awal berjualan.
“Kami menyesuaikan dengan ‘harga mahasiswa’ dan harga bahan baku, Mas,” kata Pak No.
“Awalnya, harga untuk makanan 2.500 rupiah, Mas. Untuk minuman, semuanya lima ratus rupiah,” Bu Sri menimpali.
Berjualan sejak 2003, Pak No memiliki banyak pelanggan lintas generasi. Mulai dari yang dahulunya mahasiswa dan sekarang sudah berkeluarga, hingga dosen dan pegawai di UGM.
Pak No dan Bu Sri mengakui bahwa pelanggannya yang sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja biasanya akan kembali ke warungnya saat liburan ke Jogja.
“Kalau yang langganan sudah lama, biasanya balik ke sini pas mereka liburan, Mas. Coba tanya aja sama Mas Irfan ini,” kata Bu Sri sembari melayani pelanggannya dan memperkenalkan ke kami.
“Dari Tulungagung, Mas. Alumni Peternakan UGM,” kata Mas Irfan saat kami menanyakan asalnya.
Tidak hanya level mahasiswa dan dosen, Bakmi Pak No juga pernah didatangi oleh jajaran pejabat di masanya.
“Bahkan waktu itu, ya, Mas, pejabat juga pernah makan di sini,” Pak No bercerita dengan antusias. Kami juga sangat bersemangat mendengar ceritanya.
“Dulu pernah didatangi Pak Bambang Sudibyo waktu menjabat Menteri Pendidikan dan Pak Makarim Wibisono, mantan dubes Indonesia, Mas,” lanjutnya sambil menunjukkan kepada kami rumah Pak Bambang di sekitaran warungnya.
Selain itu, Pak No punya kebiasaan yang ia lakukan hingga saat ini yaitu menyimpan nomor ponsel pelanggannya. Sambil memeriksa ponselnya, ia menunjukkan kepada kami 711 kontak pelanggan yang ia simpan. Hal itu ia lakukan, selain untuk menerima pesanan, juga untuk menjaga silaturahmi dengan mereka.
Pak No bercerita bahwa biasanya pelanggan yang memesan lewat WhatsApp akan menanyakan kepadanya terlebih dahulu apakah hari itu ia berjualan atau tidak. Semisalnya sudah buka, pelanggan tersebut akan langsung memesan menunya via chat di WhatsApp.
“Biasanya pesanannya saya yang nyebutin, Bu Sri yang ngehafalin, Mas,” kata Pak No.
Bu Sri juga melanjutkan, “Pernah ada banyak yang pesan, kadang Pak No suka salah baca tulisannya, Mas, tapi saya tetap hafal pesanannya.”
Sementara itu, esok harinya kami berbincang dengan salah satu pelanggan tetap yang juga merupakan dosen kami, Mas Adi (38).
“Waktu itu keliling cari makanan. Terus, dari teman kos merekomendasikan ini. Ternyata murah dan rasanya juga enak bagi saya,” katanya.
“Enggak hanya soal harga dan rasa, Pak No bahkan hafal menu yang dipesan sama pelanggannya,” sambungnya.
Soal menu favoritnya, Mas Adi menyebut bahwa sejak awal hingga sekarang ia selalu memesan nasi goreng. “Nasi gorengnya enak, bro. Bintang lima, pokoknya,” katanya penuh semangat.
Ia juga bercerita tentang pengalaman uniknya selama menjadi pelanggan Bakmi Pak No. Dari cerita yang awalnya masih sendiri, punya pacar, hingga berkeluarga.
“Saat saya punya pacar saya ajak dia ke Bakmi Pak No. Sampai akhirnya saya sudah berkeluarga, masih ngajak dia ke sana. Terus lama enggak ke sana, saya bawa anak satu. Lama enggak ke sana, datang, terus anak saya sudah dua. Jadi, tiap datang ke sana, tambah anak satu,” katanya tergelak.
Meskipun sudah berkeluarga dan punya anak, Pak No selalu ingat dengan Mas Adi. Hal itu yang membuat Mas Adi sudah mengganggap Pak No seperti keluarganya sendiri.
“Saya merasakan jalinan emosional saat berkomunikasi dengan Pak No. Tiap baru datang, langsung ditanyakan kabar, terus bernostalgia, dan tetap ingat dengan menu yang selalu saya pesan biasanya,” tutupnya.
Kumpul-kumpul dan Nostalgia di Soto Mbah Marmo
Selain bakmi yang erat dengan kuliner khas Jogja, soto juga jadi salah satu menu andalan para mahasiswa. Harganya murah, banyak tambahan lauk, dan mengenyangkan, seperti warung soto Mbah Marmo yang kami kunjungi Rabu (22/9) lalu, di Jalan Bimosuko, Yogyakarta. Lokasinya diapit dua hotel berbintang: Grand Mercure dan New Saphir.
Ketika datang, kami disambut istri Mbah Marmo. “Monggo, Mas, pakai kol napa mboten?” tanyanya dengan setengah membungkuk. “Iya, Mbah, satu porsi, nggih.”
Kami izin berbincang dengan mereka. Mengetahui kami hendak meliput, Mbah Marmo berkelakar, “Boleh, silakan. Mbah Marmo istrinya lima, Mas!” kata laki-laki berusia 62 tahun ini. Kami semua terkekeh, gelak tawa pecah di warung seluas 5 x 8 meter itu. Istri Mbah Marmo hanya tersenyum kecil dan berkata, “Ngawur, mesakke anakmu.”
29 tahun lalu di lokasi tempat kami duduk saat itu Mbah Marmo dan istrinya mendirikan kios kecil untuk berjualan soto. Suasana bangunan tua langsung terasa tatkala kami memasuki warung. Cat dinding yang mengelupas, dinding dari papan kayu yang diolesi dengan minyak, hingga barang-barang yang usianya tak lagi muda. Contohnya yaitu kipas angin kotak yang warna aslinya pun sudah tak kelihatan lagi, diganti warna kuning kusam di seluruh body-nya. Peribahasa “hidup segan, mati tak mau” cocok dengan kipas angin ini. Sama dengan jam dinding merek Mirado yang tertancap di dinding belakang kami. Jam dinding produksi tahun ‘80-an dengan ciri khas yang berbunyi tiap jam itu sudah berwarna kuning kusam. Meski demikian, ia masih berdetak dengan baik.
Ketika kami datang pada pukul dua belas siang, pelanggan yang makan di sana hanya kami dan satu orang laki-laki, padahal menurut keterangan salah satu teman, biasanya pembeli soto Mbah Marmo harus mengantre hingga ke luar hanya untuk duduk.

Istri Mbah Marmo bercerita bahwa pandemi COVID-19 membuat warungnya sepi pembeli. Perempuan enam puluh tahun itu mengatakan bahwa sebelum pandemi warungnya bisa buka sampai pukul dua siang, sedangkan saat awal pandemi ia dan suami terpaksa menutup warung dan tak berpenghasilan selama empat bulan.
“Pas awal pandemi sepi sekali jalan ini, Mas, ndak ada orang lewat,” katanya.
Raut wajah yang semula murung kembali ceria tatkala ia bercerita bagaimana awal mula merintis usaha ini dari nol. Mbah Marmo yang saat itu berusia dua puluh tahun menikahi dirinya yang berusia delapan belas tahun. Dari kampung halamannya di Kecamatan Cawas, Klaten, mereka pindah ke Jogja untuk mengadu nasib.
Pada 1989 Mbah Marmo berkeliling menjajakan soto dengan gerobak di permukiman penduduk tak jauh dari lokasi warung sekarang. Tiga tahun mengumpulkan pelanggan, Mbah Marmo akhirnya membangun sendiri kios itu.
Lebih dari seperempat abad mereka berjualan soto, para pelanggan selalu datang dan pergi. Kata istri Mbah Marmo, orang yang langganan di warungnya sudah tak terhitung jumlahnya. Asal daerahnya bermacam-macam: Kebanyakan berasal dari Medan, Batam, Bangka Belitung, Makassar, hingga Manado.
Kami berbincang dengan Elyas, pemuda 29 tahun asal Sragen yang sejak 2010 menjadi pelanggan tetap warung soto Mbah Marmo. Ia bercerita bahwa saat ia baru menjadi pelanggan harga soto Mbah Marmo masih Rp6.000, gorengan Rp500, dan es teh Rp2.500. Semua harga tersebut hanya berbeda seribu rupiah jika dibandingkan dengan harga saat ini.
Menurutnya, dengan harga semurah itu ia sudah bisa mendapat porsi yang besar, kuah soto yang banyak, dan mengenyangkan. “Namanya mahasiswa pengin hemat. ‘Kan biasa, makan pagi sama siang digabung. Jadi, harus kenyang,” katanya sambil terkekeh.
Baginya, harga yang dipatok Mbah Marmo dari dahulu hingga sekarang sangat terjangkau bagi semua kalangan, tak terkecuali kantong mahasiswa. Mbah Marmo melihat pelanggan yang makan di tempatnya berasal dari latar belakang yang sangat beragam, mulai dari mahasiswa, mantan mahasiswa, dosen, karyawan, buruh, hingga pensiunan.
Semasa kuliah Elyas bersama tiga orang temannya makan di sana tiap dua sampai tiga hari sekali. Sembari berbincang, ia mengingat-ingat kembali kebiasaan dengan teman-temannya ketika makan di warung ini.
“Dulu tiap pulang ngampus, terus ke sana, mbahnya tau saya, selalu tanya kabar kami dan gimana kuliahnya,” ujarnya.
Saat sudah lulus rutinitas tersebut hilang seiring ketiga temannya yang bekerja di luar Jogja. Ia mengatakan bahwa mereka sama seperti para langganan warung soto Mbah Marmo lainnya.
“Karena enggak sesering dulu, akhirnya ya sama dengan pelanggan lainnya juga,” ujarnya.
Meski demikian, mereka selalu menyisihkan waktu untuk makan di warung soto Mbah Marmo tatkala semuanya sedang berada di Jogja. “Biasanya kita nge-list dulu, mana warung yang sering dikunjungi pas kuliah, salah satunya Mbah Marmo,” ujarnya. Menurutnya, makan di warung soto Mbah Marmo saat ini jadi tempat kumpul-kumpul dan nostalgia masa kuliah.
Pada akhirnya, Mbah Marmo dan istrinya tetap menjadi bagian dalam hidup para pelanggannya. Mereka mengisi sirat-sirat hidup seseorang, serta menyaksikan seseorang berkembang, jatuh, bangkit lagi, hingga sukses.
Reporter: Muhammad Fadhil Pramudya Putra dan Yogama Wisnu Oktyandito






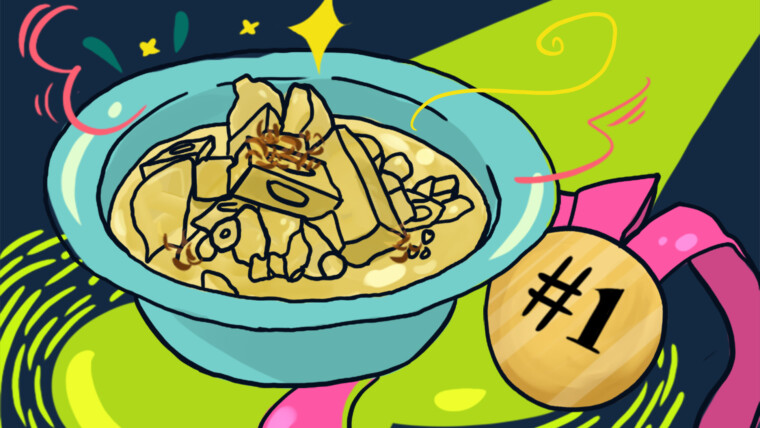

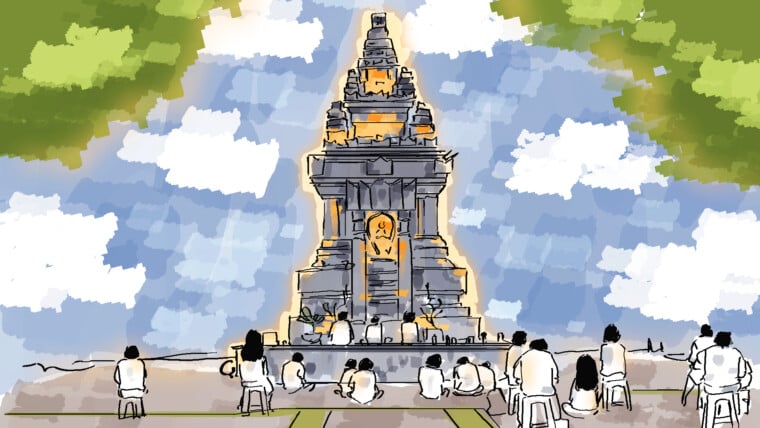
Getirnya Mahasiswa Kedokteran Hewan yang Menghilangkan Peliharaan Klien
Generasi Permen Karet Menyebalkan di Organisasi Kampus
Bukan LSM atau Start-up, Kerja di Pemerintahan yang Paling Enak
Balada Dinda-Dinda yang Punya Resting Bitch Face
Ingatan Sembrono dan Ikan Kurisi
Berdamai dengan Air Mata untuk Merawat Kenangan
Dua Hari untuk Selamanya: Menjajal Jadi Kuli karena Kehabisan Duit di Akhir Bulan
Blue Jeans milik Gangga Kusuma dengan Blue Jacket pada Cinta Pertama