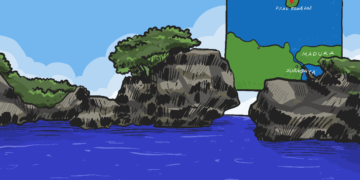Kabupaten Ponorogo yang identik dengan kesenian reog, tak lepas dari sosok Bathoro Katong atau Batara Katong. Anak Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V ini adalah pendiri daerah tersebut setelah mengalahkan Ki Ageng Kutu.
***
Alkisah, Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, setelah masuk agama Islam, menugaskan Tumenggung Seloaji dan Ki Ageng Mirah untuk meminta salah satu demangnya, Ki Ageng Kutu datang menghadap. Tujuannya agar Ki Ageng Kutu tersebut masuk Islam.
Saat kedua utusan tersebut sampai di tujuan dan menyampaikan pesan junjungan mereka, Ki Ageng Kutu marah. “He Seloaji! Kowe wong anyar katon, lagi iki ketemu. Apa ora kulak warta adol prungon, yen Demang Kutu itu orang keno digegabah. Apa ora neling-nelingake yen Demang Kutu itu wong kuwoso, wong sekti mandraguna!”
Wajar, Ki Ageng Kutu kecewa dan kaget atas kedatangan Tumenggung Seloaji dan Ki Ageng Mirah. Isi ajakannya pun supaya beliau segera sowan ke Raja Majapahit dan berkenan mengikuti agama Islam.
Walaupun sebelumnya Ki Ageng Mirah sudah dengan baik menanyakan kesehatan dan menghaturkan salam dari Raden Bathoro Katong, anak dari Prabu Brawijaya V. Akibat Ki Ageng Kutu yang marah, Ki Ageng Mirah pun langsung meminta maaf dengan santun. Namun, amarah Ki Ageng Kutu sudah memuncak.
Beliau lantas menyuruh Ki Honggolono untuk menangkap dan membunuh Ki Ageng Mirah. Cekatan, Patih Seloaji menggagalkan serangan tersebut dengan tombaknya, hingga Ki Honggolono terbunuh.
Kemudian hari, tepat pada Jumat Wage, Ki Ageng Kutu dan pengikutnya dari Kademangan Surukubeng, Jetis, menyerang Raden Bathoro Katong di Ponorogo yang saat itu masih bernama Wengker. Pertempuran dimenangkan Ki Ageng Kutu setelah beliau mengeluarkan keris pusakanya Kyai Condhong Rawe. Begitu yang tertulis di buku Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo karya M. Fajar Pramono (2006).
Raden Bathoro Katong, Ki Ageng Mirah, dan Tumenggung Seloaji
Raden Bathoro Katong merupakan putra Prabu Brawijaya V, Kerthabumi dari istri kelima, putri Bagelen. Nama Bathoro Katong ketika kecil adalah Raden Lembu Kanigoro atau Raden Katong. Beliau juga merupakan saudara beda ibu dengan Raden Patah yang merupakan anak Prabu Brawijaya V dengan istri ketiga, Putri Campa.
Kedatangan Raden Bathoro Katong ke Wengker sendiri, menurut versi Moelyadi (1986) dalam buku Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog, merupakan suruhan Prabu Brawijaya V, versi lain menurut Purwowijoyo (1986) dalam buku Babad Ponorogo merupakan suruhan dari Raden Patah.
Penasaran dengan cerita tersebut, saya mencoba bertanya kepada juru kunci Situs Makam Bathoro Katong, Mbah Sunardi (69). Menurut beliau, versi berangkatnya Raden Bathoro Katong ke Wengker, adalah permintaan dari saudaranya, Raden Patah. Beliau tidak berangkat dari Majapahit, melainkan dari Demak bersama Tumenggung Seloaji. Sedangkan Ki Ageng Mirah, beliau sudah berada di Wengker terlebih dahulu, mencoba menyebarkan agama Islam.
Ki Ageng Mirah dan Ki Honggolono yang terbunuh oleh tumenggung Seloaji tadi merupakan saudara seperguruan Ki Ageng Kutu, sekaligus pengikut atau punggawa dari Ki Ageng Kutu dalam menata Kademangan Surukubeng.

Menurut silsilah, Ki Ageng Mirah merupakan putra dari Raden Jaka Dholog, anak Prabu Brawijaya V. Sehingga masih merupakan keponakan Raden Bathoro Katong.
Ki Ageng Kutu sendiri, sebenarnya merupakan penggawa Majapahit yang setia, berwibawa dan memiliki pengaruh yang luas. Pembangkangan yang dilakukan beliau kepada Majapahit, memiliki dua dasar. Pertama, karena penyebaran agama Islam oleh wali sanga tidak sesuai dengan konstitusi kerajaan dan malah difasilitasi dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak. Kedua, Ki Ageng Kutu menganggap wali sanga dan Kerajaan Islam Demak mengganggu keyakinan beliau.
Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan kesenian barongan atau reog sebagai kritik kepada raja Majapahit yang ditundukan oleh perempuan atau Putri Campa. Dalam seni tersebut, raja Majapahit disimbolkan dengan kepala harimau, sedang Putri Campa dalam sosok, dadak merak.
Laku prihatin mengalahkan Ki Ageng Kutu
Setelah kalah, Raden Bathoro Katong melakukan beberapa upaya, salah satunya menyepi di daerah Ngebel. “Ketika Bathoro Katong kesulitan mencari air, beliau lantas menancapkan tongkatnya di tanah. Bekas tancapan tongkat tersebut keluar air. Sampai sekarang mata air tersebut masih ada dan dinamai Kucur Bathoro,” Ujar Mbah Sunardi. Versi lain, dalam buku Melihat Ponorogo Lebih Dekat karya Soemarto (2010), mata air tersebut ditemukan oleh Bathoro Katong ketika berkunjung ke daerah Ngebel .
Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Raden Bathoro Katong untuk menaklukan Kademangan Surukubeng. Termasuk menata pasukan dan memetakan kelemahan Ki Ageng Kutu. Konon nama “Bathoro” yang digunakan beliau adalah pemberian dari Bhre Pandan Alas, Prabu Brawijaya IV Kerajaan Majapahit ketika ditemuinya di Telaga Ngebel (Moelyadi, 1986). Versi lain, nama “Bathoro” diberikan oleh Sunan Kalijaga (Purwowijoyo, 1986).
Yang menarik, dalam upaya strategis menaklukan Kademangan Surukubeng yang dipimpin Ki Ageng Kutu, Ki Ageng Mirah memiliki ide untuk mengirim pasangan suami istri bernama Singosari dan Nawangsari untuk menjadi abdi dalem di sana. Singosari menjadi tukang kebun dan Nawangsari menjadi pamong Niken Gandhini, putri Ki Ageng Kutu.
Lewat Nawangsari, Raden Bathoro Katong berhasil mendapatkan Kyai Condhong Rawe yang dipercayakan Ki Ageng Kutu kepada putrinya, Niken Gandhini (Purwowijoyo, 1986). Melalui laku prihatin tersebut, akhirnya dilakukan penaklukan dan pengejaran hingga Ki Ageng Kutu diceritakan moksa atau menghilang.
Usai kemenangan, Raden Bathoro Katong kemudian babat alas dengan menamakan kawasan yang dipimpinnya Prana Raga yang kemudian menjadi Ponorogo seperti penyebutan sekarang ini. Ia memerintah Kadipaten Ponorogo sejak tahun 1496, selanjutnya ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Surukubeng ke Kadipaten, tepatnya di Dukuh Tinggen sebelah barat pesarean.
Niken Gandhini kemudian dinikahi dan diboyong. Anak Ki Ageng Kutu lainnya atau adik Niken Gandhini, R. Suryolono diangkat menjadi panglima tentara bergelar Suromenggolo. Sedangkan anak pertama Ki Ageng Kutu, R. Suryodoko dijadikan demang di Surukubeng menggantikan ayahnya.
Atas keberhasilan ini, tiga tokoh sentral tadi disebut sebagai tiga kekuatan yang membangun Ponorogo, seperti kata Mbah Sunardi: “Raden Bathoro Katong sebagai umara, Tumenggung Seloaji sebagai patih yang bisa diartikan menjadi wakil atau panglima, dan Ki Ageng Mirah sebagai ulama.”
Kompleks makam Raden Bathoro Katong kini
Penasaran dengan pesarean atau makam Bathoro Katong, Mojok datang ke kompleks makam Raden Bathoro Katong sekaligus berziarah. Beruntung, ada rombongan peziarah dari Nganjuk yang juga ingin mengantarkan doa ke beliau.
Terdapat beberapa gerbang sebelum sampai ke makam beliau. Setelah masuk gerbang ketiga dari pintu masuk depan, tampak pendopo dan Masjid Bathoro Katong, satu gerbang terkunci yang dibuka jika ada peziarah, dan satu gerbang lagi menuju pemakaman kampung.
Kami harus menunggu beberapa saat di pendopo sebelum Mbah Sunardi membukakan pintu. Setelah masuk gerbang yang terkunci, didalamnya terdapat satu gerbang lagi dan dua buah batu, salah satunya bernama sengkalan memet yang terukir gambar orang bertapa, pohon beringin, burung garuda, dan gambar gajah, yang jika diterjemahkan bertuliskan angka 1408 tahun saka, atau 1486 masehi.

Sengkalan memet merupakan pengingat selesainya pembabatan hutan oleh Raden Bathoro Katong. Pahatan lain, menunjukan angka dalam huruf Jawa kuno bertuliskan 1418 atau 1496 masehi, tahun yang menunjukan dimulainya pemerintahan Kadipaten Ponorogo dan kekalahan Ki Ageng Kutu.
Setelah gerbang terakhir, muncul jalan setapak yang langsung mengarah ke makam Raden Bathoro Katong. Selesai menghantar doa-doa bersama rombongan dari Nganjuk. Saya mencoba berkeliling sejenak. Tampak banyak makam lain yang ada di sekitar makam Bathoro Katong.
Makam Bathara Katong terdapat di tengah, di dalam bangunan pendek bergenteng sekitar 4-5 meter persegi. Patok nisan beliau berbalut kain kuning dengan tirai-tirai hijau putih di pintu masuknya.
Sebelah kiri, atau sebelah barat dari makam beliau, terdapat makam dengan bangunan pendek lebih kecil bertuliskan Ki Ageng Mirah. Tepat sebelah baratnya lagi, saya baru menyadari bahwa di sana terbaring Tumenggung Seloaji. Dari ketiganya, hanya makam Tumenggung Seloaji yang tidak diberi genteng, diceritakan dalam Soemarto (2010) makam beliau dari dulu tidak diberi peneduh karena setiap dibangun, tidak lama kemudian roboh karena disambar petir.
Hari itu, tepat di Jumat Kliwon, bunga kamboja yang tumbuh bertebaran di bawah langit sore menjelang magrib, ditambah hawa teduh setelah hujan, membuat momen berziarah semakin nyaman. Dilihat dari manapun, tempat tersebut memang cocok untuk beristirahat beliau bertiga.
Di luar gerbang makam, tepat di sebelah barat, terdapat pendopo yang menjadi tempat para peziarah beristirahat. Sebelah baratnya lagi terdapat masjid Bathoro Katong yang menjadi langgar dari pusat pemerintahan beliau.
Kini, makam Bathara Katong hanya dibuka ketika ada yang datang untuk berziarah saja. Kata Mbah Sunardi, kompleks makam biasanya sedikit lebih ramai ketika menjelang pemilihan pejabat. “Mungkin mereka sedang meminta izin atau ngalap berkah Mas.”
Salat magrib pun dimulai, warga sekitar sudah ramai berduyun-duyun ke masjid. Saya mengucap salam sebelum meninggalkan makam: “Mbah Bathoro Katong, wargamu rukun-rukun, sukses Mbah anggene riyen nyebaraken agama Islam.”
Masjid Kauman dan Alun-alun Kota Lama
Kini, keraton dan alun-alun dari Kadipaten yang diperintah Bathoro Katong sudah tidak ada. Walaupun begitu, masih ada dua saksi pemerintahan beliau, Masjid Kauman Kota Lama, dan Pasar Pon Ponorogo. Jauh setelah berdirinya keraton di sini, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke kota baru oleh Bupati Ponorogo ke-14, Raden Adipati Martohadinegoro pada tahun 1837.
Sekitar 70 meter ke utara dari Bundaran Pasar Pon Ponorogo, sebelah kiri jalan lurus sekitar 100 meter, terdapat Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Sembari menunggu salat ashar, terlihat beberapa anak sedang lalu lalang bersiap mengaji di sana. Mungkin begini juga suasana Masjid Jami ini ratusan tahun silam, para pemuda dari berbagai wilayah berduyun-duyun datang meramaikan pengajian.
Selesai salat ashar, saya berkesempatan berdiskusi dengan Mbah Maher (67), Mbah Mahmud (70), dan Mbah Badrun (77), mencoba membahas sejarah Masjid Jami ini.
“Untuk bangunan masjid, yang masih benar-benar asli itu tiang sama cungkupnya saja Mas, tiangnya ada 16 yang asli sejak awal berdiri. Kalau sampean hitung ini ada 20, empat sisanya yang ada di serambi luar sebelah utara itu tambahan Mas,” ujar Mbah Maher.
Sisi bangunan sebelah utara juga merupakan pemekaran dari bangunan utama, empat tiang tambahan tadi merupakan penyeimbang bangunan yang bertambah luas ke utara.
Ketika melihat-lihat tiang masjid yang terbuat dari kayu itu, saya masih terperangah dengan kondisinya yang masih bagus dan kokoh. “Itu cara halusin tiangnya masih pakai tatah Mas, hasilnya masih kasar, belum ada mesin penghalus seperti sekarang,” Mbah Badrun menimpali.

“Lha kalau bedug itu Mbah?” Saya menunjuk bedug di sisi utara masjid.
“Kayu bedugnya itu masih asli Mas, kalau sampean lihat, itu satu batang kayu utuh Mas, mengingat kalau dulu memang pohonnya besar-besar. Nggak seperti bedug sekarang yang kayunya sambungan.” Mbah Mahmud ikut menimpal.
Mbah Badrun yang dulu merupakan marbot masjid menceritakan bahwa dulu sebelum memakai keramik seperti sekarang, lantai masjid masih pakai mlester bata berwarna merah. “Kalau digosok nggak kalah gilap sama sekarang, Mas.”
Masjid Jami ini, sepengetahuan Mbah Mahmud terakhir direnovasi pada tahun 1965. Konon ketika tiang utamanya mau digali supaya bisa ditinggikan, alat berat yang dipakai tidak kuat dan malah terangkat. Jendela-jendela kecil estetik di sisi selatan ruang utama juga merupakan hasil renovasi.
Mbah Maher menambah: “Dulu tembok masjid sebelah selatan tebalnya sampai satu meter, Mas. Kini sudah jauh berkurang.”
Jika Anda masuk ke dalam masjid, atapnya terasa lumayan pendek jika dibandingkan dengan masjid lain di jaman sekarang. Walaupun begitu, hawa di dalam masjid tetap terasa sejuk dan menenangkan, mungkin merupakan berkah dari ratusan tahun masjid ini menampung doa masyarakat.
Perihal kegiatan mengaji di sore hari. Mbah Maher mengatakan jika hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Sejak beliau kecil pun sudah ada. “Dulu ketika tahun 1965 sampai sekitar 1975, orang ngaji subuh itu bisa sampai pintu gerbang depan.” Saya ikut membayangkan, jika sampai pintu gerbang depan, berarti jamaah bisa tembus 100 meter ke arah timur.
“Yang ngajar Kyai Maghfur, Mas. Keturunan dari Mbah Mesir, Durenan, Trenggalek. Waktu itu belum ramai ngaji subuh bulan ramadhan seperti sekarang, tetapi beliau berani mengawali. Di sore hari juga ada pengajian, santrinya kalau dihitung juga banyak, dari Jetis, dari Jenangan, kadang ada dari luar Ponorogo,” tambah Mbah Mahmud.
“Kalau berdirinya, sejak tahun berapa Mbah?” Saya bertanya sambil mengarahkan muka bergantian ke mereka berdua.
“Kalau menurut catatan, sejak tahun 1400, Mas. Buktinya ada di pigura situ Mas.” Ujar Mbah Mahmud. Setelah saya lihat, piagam berpigura itu dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Masjid Ponorogo dengan catatan masjid berdiri pada tahun 1400. “Di depan masjid juga ada batu semen bertuliskan masjid ini berdiri 1560, Mas. Di atasnya ada lagi simbol-simbol yang dipahat Mas, mungkin itu ada artinya, tetapi saya tidak tahu,” Mbah Maher menambahkan.
Mengenai tata kota di Kadipaten, Mbah Mahmud mengatakan jika pada masa lalu mungkin tata ruangnya sudah seperti tatanan bangunan Kota Mataram Islam pada umumnya. Di sebelah selatan ada pasar, di sebelah barat ada masjid, di sebelah timur ada keraton yang sekarang menjadi Kompleks Makam Bathoro Katong.

Untuk alun alun. Mbah Mahmud masih ingat jika dulu ada lapangan luas di antara masjid dan kompleks pemakaman, “Mungkin dulunya itu alun-alun, Mas. Sekitar tahun 1975, perlahan lapangan tersebut dipenuhi rumah-rumah hingga tampak padat seperti sekarang,” hal ini diakui juga oleh Mbah Maher.
Untuk Pasar Pon sendiri, dulu juga ramai utamanya di tahun 1950-an sampai 1960-an. Waktu itu kegiatan perekonomian juga masih ditunjang larisnya produksi batik khas Ponorogo di wilayah Kertosari. Dalam hal ini Mbah Maher, Mbah Mahmud, dan Mbah Badrun sama-sama setuju.
Keesokan pagi, saya mencoba pergi ke Pasar Pon. Trenyuh. Pasar terlihat sepi dengan beberapa pedagang yang menempati meja dagangnya. Dengan langkah tertatih, saya mundur beberapa langkah dan lekas menyalakan sepeda motor.
“Ngapunten Mbah, saya hanya berniat memfoto, belum ada niatan untuk beli, semoga Njenengan rejekinya lancar, anak cucu dapat penghidupan layak semua. Amin,” ucap saya dalam hati.
Reporter : Prima Ardiansah
Editor : Agung Purwandono
BACA JUGA Di Puncak Bibis: Sarapan Bubur Biker, Makan di Angkringan Kandang Sapi
dan liputan menarik lainnya di Susul.