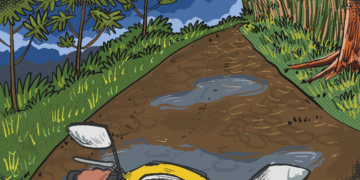Sosok muslim Tionghoa bernama Koh Hin (72) ini unik. Ia menyelesaikan pendidikan dokter, tapi bukannya buka praktik, malah jualan obat tradisional. Saat masih remaja di tahun ‘60-an, ia memilih aktif di Pelajar Islam Indonesia, berkebalikan dengan orang-orang Tionghoa di Temanggung waktu itu.
***
Rabu 11 Mei 2022, saya kembali menemui Koh Hin (72), seorang Tionghoa di Parakan Temanggung. Hampir setahun lalu, saya berbincang lama dengannya. Saya membuat catatan tentang sosoknya. Kali ini saya datang untuk silahturahmi Lebaran sekaligus mengambil fotonya sekaligus meminta izin untuk mengirimkan kisahnya ke Mojok.co. Saya juga berbincang untuk melengkapi percakapan dengannya waktu itu.
Suatu pagi pada akhir Juni 2021, cuaca Kota Parakan sedang tidak menentu. Bulan yang seharusnya jadi harapan masyarakat Temanggung dengan cuaca hangat demi kelancaran musim tembakau. Kecamatan Parakan dengan luas 2.223 hektar di kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi dua wilayah yaitu kelurahan Parakan Kulon (Kauman) dan Parakan Wetan (Pecinan).
Pusat perdagangan Parakan berjajar terlihat di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Aip Mungkar, Jalan Brigjen Katamso dan sekitarnya. Masyarakat Tionghoa cukup menguasai jantung perekonomian di Parakan.
Kota yang tumbuh dan menjadi besar pada abad 19 ini menurut saya sangat menarik. Parakan memiliki sejumlah kisah lokal mulai dari asal-usul Kota Tembakau, perjuangan warga Jawa-Tionghoa melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda.
Sekaligus kota kecil yang menjadi saksi hidup berdampingannya etnis Tionghoa dan Jawa sejak akhir abad ke-18. Hingga saat ini telah terjadi banyak perkawinan campuran Tionghoa dan Jawa. Bahkan menyimpan kisah persahabatan antar etnis yang masih terekam dalam kehidupan sehari-hari dan masih bisa saya temui.
Salah satunya adalah Hindro Pramono atau Bing Hiedi, pemilik toko lawas jamu tradisional China di Parakan. Namun Bapak saya akrab memanggilnya Koh Hin. Begitupun saya. Bapak mengenal Koh Hin sejak belia, pertemuannya dengan Koh Hin bermula ketika Bapak yang tinggal di area bekas Stasiun Parakan, tidak jauh dari rumah Koh Hin sering bermain dengan Bing Liong, sepupu Koh Hin.
Terlebih lagi Bapak dan Koh Hin berada dalam sebuah organisasi yang sama, Pelajar Islam Indonesia (PII) meskipun terpaut satu generasi.
Koh Hin muslim Tionghoa yang memilih jadi anggota PII
Menjelang siang, Bapak dan saya pergi ke toko jamu Koh Hin di Jalan Diponegoro. Rumah yang difungsikan sekaligus sebagai toko ini, bangunannya terlihat sangat lawas bergerbang hijau, masih sepi. Berderet rapi banyak jenis obat-obatan China dalam rak kaca berlapis kayu. Di usia 71 tahun, Koh Hin masih terlihat bugar, meramu berbagai obat-obatan dari penyakit ringan sampai berat.

Saya duduk berhadapan terpisah dengan rak kaca, sementara Bapak saya pergi membeli beras di desa lain. Diiringi bising kendaraan bermotor dari jalan raya, Koh Hin menceritakan pengalaman masa mudanya ketika menjadi aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), organisasi yang pada awal pendiriannya memiliki kedekatan dengan Partai Masyumi. Salah satunya berbasis di Kauman, Parakan.
“Waktu itu sedikit sekali orang Muhammadiyah, rata-rata yang masuk PII kan orang-orang Muhammadiyah,” ceritanya dengan suara yang tak begitu jelas, saya pelan-pelan menangkap cerita dari Koh Hin. Koh Hin sudah masuk Islam sebelum tahun 1965—kira-kira ketika beliau masih usia SMP.
Saya lantas bertanya, “Kenapa Koh Hin masuk PII? Dulu siapa yang mengajak?” Koh Hin menjawab, keikutsertaannya dengan PII betul-betul dari keinginan dirinya sendiri, di usia negara Indonesia yang masih sangat muda dengan situasi politik perubahan Orde Lama menuju Orde Baru yang begitu tegang, Koh Hin tidak sepakat dengan gerakan-gerakan Partai Komunis Indonesia.
Kehadiran PII sebagai salah satu antitesis PKI. Sedangkan saat itu di Parakan, sebagai Muslim Tionghoa cukup sulit bertahan dengan identitas dan pilihan politik yang berbeda.
“Saya dulu bahkan sudah bisa memilih saat pemilu pertama masa Orde Baru di tahun 1971, sedangkan Tionghoa lain di Parakan nggak bisa,” kata Koh Bin.
Bertahan sebagai minoritas
Masa-masa itu negosiasi lokal dengan masyarakat Tionghoa, sebagai seorang muslim masih sulit terjadi namun sekarang semua terasa sama saja. “Dulu kan memang dipecah-pecah oleh Belanda. Islam dan Tionghoa dipecah belah. Coba dulu kalau Islam dan Tionghoa bersatu mungkin kita lebih cepat merdeka,” pendapat Koh Hin mengingat masa-masa perjuangan pascakemerdekaan.
Dalam prosesnya menjadi seorang muslim, Koh Hin juga turut berpartisipasi dalam pendirian Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) untuk Jawa Tengah di Semarang saat beliau masih berkuliah kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
Saya kemudian penasaran, bagaimana hubungan Koh Hin saat itu dengan Tionghoa lainnya, “Koh Hin dulu gimana sama masyarakat Tionghoa yang lain,” tanya saya.
Koh Hin menjawab dengan santai, “Wah jangan ditanya 95% orang Tionghoa itu benci saya. Hampir rata-rata dari mereka masuk ke IPI (Ikatan Pelajar Indonesia), organisasi underbow PKI. Rutin itu baris-berbaris di jalanan Parakan, apalagi pas Agustusan,” tukas Koh Hin. Pergolakan satu sama lain amat kencang pada masa itu.
Kedekatan Koh Hin dengan Hasan Basri
Bergabungnya Koh Hin dengan PII sejak belia membuatnya lebih sering bermain di area Kampung Kauman, Parakan. Bahkan saat merantau ke Semarang sampai kuliah di UNISSULA Koh Hin sering berkunjung di markas PII di Jalan Borang. Koh Hin sering datang dari pengajian ke pengajian sampai bertemu dengan Ustadz Hasan Basri, salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki.
Menurut penuturan Koh Hin, Hasan Basri memiliki keturunan 25% Tionghoa bercampur dengan Banjar Kalimantan. “Saya dulu diangkat anak sama Pak Hasan Basri karena bertemu di pengajiannya beliau,” cerita Koh Hin.

Koh Hin mengikuti dan menemani aktivitas Hasan Basri setiap hari, sejak subuh mengisi kajian dan aktivitas mengajarnya di Yayasan Al-Irsyad, tempat di mana Abu Bakar Ba’asyir juga mengajar saat usianya masih 30 tahun-an di penghujung tahun 1960-an menjelang 1970-an. “Saya biasanya kalau ada libur dua minggu, seminggu di Parakan lalu seminggu di Surakarta di tempat Hasan Basri bapak angkat saya,” tuturnya perlahan.
Dekat dengan aktivis Islam
Setelah kuliah di Semarang, ia merantau kembali ke Jakarta dan kuliah dengan jurusan serupa, di Universitas Trisakti. Di ibu kota, Koh Hin juga sembari belajar ilmu pengobatan China. Selain itu, aktivitas Koh Hin banyak bergelut dengan Yayasan Haji Karim Oei di Jakarta.
Koh Hin juga dekat dengan pendirinya, Abdul Karim Oei — ia adalah seorang figur Persyarikatan Muhammadiyah, lelaki yang lahir dengan nama Oei Tjeng Hien itu turut mendirikan organisasi PITI. Sampai akhirnya ia mendapatkan mandat langsung dari Abdul Karim Oei untuk mendirikan PITI di Jawa Tengah.
Dalam pendirian PITI di Jawa Tengah, Koh Hin banyak dibantu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, ‘Aisyiyah, dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah. Komunitas muslim yang banyak membantu pembentukan komunitas Muslim Tionghoa adalah orang-orang Muhammadiyah, begitu pun di Yogyakarta dan Jakarta.
Koh Hin juga menyampaikan bahwa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah A. R. Fachruddin di masa kepemimpinannya saat Orde Baru banyak mendukung dalam pembentukan PITI dan majelis-majelis Islam yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa di Yogyakarta.
Dari cerita-cerita Koh Hin, terlihat bahwa dalam pengokohan komunitas Muslim Tionghoa banyak bersinggungan dan dekat dengan organisasi Muhammadiyah, organisasi yang banyak membantu proses pembentukan dan asimilasi para Muslim Tionghoa dengan komunitas Islam lainnya. Bahkan aktivitas PITI di Yogyakarta banyak dibantu oleh Suara Muhammadiyah.
“Waktu itu banyak dibantu sama sahabat saya Bakti Nur, keponakan dari Hasan Basri yang menjadi pimpinan redaksi di Suara Muhammadiyah.” Sayangnya, menurut Koh Hin di Parakan cukup sulit dalam membentuk komunitas Muslim Tionghoa serta hanya sedikit yang memeluk Islam.
Kehidupan yang dijalani Koh Hin dari muda hingga saat ini banyak beririsan dengan banyak ruang dan berbagai irisan. Saya mendapatkan kisah-kisah yang tidak ditemukan dalam buku sejarah lewat Koh Hin. Begitupun perspektifnya saat gejolak politik pasca-1965. Pilihannya menjadi seorang Muslim membawanya pada banyak petualangan di beberapa kota.
Koh Hin ini berasal dari keluarga dokter di Temanggung. Saudara-saudaranya banyak yang menekuni profesi ini. Begitu juga dengan dua anaknya yang juga menjadi dokter. Ia sendiri, meski memiliki ijazah kedokteran, ia memilih untuk tidak membuka praktik. Ia justru membuka toko obat tradisional Tionghoa.
Ingatannya masih kuat, saya merasa beruntung dan betah duduk lama-lama di toko Koh Hin. Rasanya seperti didongengi seorang kakek dengan pribadi yang hangat dan terbuka.
Reporter:
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Toko Kecil dari Poris yang Menjaga Peradaban Tembakau dan liputan menarik lainnya di Susul.