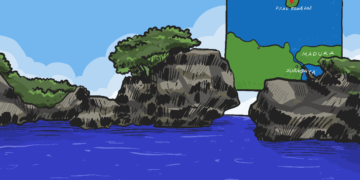MOJOK.CO – Selamat ulang tahun Tragedi Kanjuruhan. Sebuah tragedi di mana pemerintah dan aparat ingin kita melupakannya. Sungguh menyedihkan negara ini.
Dalam Tragedi Kanjuruhan, pemerintah dan aparat bisa saja merekayasa pengadilan dengan menggunakan kekuasaannya. Misalnya, menyalahkan angin atau fenomena alam atas terbunuhnya ratusan nyawa. Ada lagi, usaha memanipulasi barang bukti, memecah belah gerakan, dan menggunakan harta untuk menutupi kesalahan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya mereka lakukan, yakni menghapus ingatan kita.
Silakan datang ke Malang sekarang. Cobalah mengelilingi kota, menikmati berbagai hiburan, mencicipi aneka kuliner, dan berkunjung ke taman. Kalian tidak akan merasakan bahwa di kota ini, 1 tahun yang lalu, bunga-bunga tersebar di segala penjuru, lilin-lilin menyala sepanjang malam, lagu haru tak berhenti berkumandang, dan ratusan orang tua memenuhi jalan membawa foto anaknya. Di kota ini, puluhan keranda mayat pernah memenuhi balai kota. Bendera dan poster tuntutan memadati kota, bahkan polisi hadir di jalan raya selama beberapa bulan.
Namun, Malang yang penuh duka itu, hari ini, sudah mulai kembali seperti semula. Bendera dan poster tuntutan perlahan menghilang. Keranda yang memenuhi balai kota tak lagi nampak wujudnya. Lalu, foto-foto korban Tragedi Kanjuruhan yang memadati kota perlahan berganti menjadi foto-foto kampanye pejabat dengan segudang janjinya.
Satu tahun berlalu, alih-alih penuntasan proses hukum Tragedi Kanjuruhan yang diprioritaskan, pemerintah justru merenovasi stadion sebagai barang bukti terbesar dari sebuah tragedi. Kami menyebutnya sebagai “politik pelupaan”, suatu upaya yang dilakukan pemerintah agar kita tidak lagi bergairah untuk mengingat kejahatan mereka.
Melawan politik pelupaan di Tragedi Kanjuruhan
Untuk melawan politik pelupaan, pada 25 September sampai 29 September 2023, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya mengadakan pameran 2 dimensi. Mereka mengadakan acara ini untuk mengingat 1 tahun Tragedi Kanjuruhan. Di pameran itu, terdengar suara orang tua yang ditinggalkan anaknya dalam puisi karya Anggita, “Tanpa belas kasihan, belum sempat kau ucap selamat tinggal. Susah payah aku, Hidup di masa penghabisan”.
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya juga mengadakan diskusi di ujung pameran. Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan dan Pak Midun yang menggowes sepeda dari Malang ke Jakarta turut hadir sebagai narasumber.
Pak Hatib Abdul Kadir, dosen Antropologi yang menjadi salah satu narasumber, berkata “Negara kita ini mirip dengan apa yang dikatakan Clifford Geertz sebagai “negara teater”. Jadi, cara untuk membuat warganya senang itu diberi hiburan terus, kalau ada yang terluka atau meninggal yah dikasih hiburan. Coba perhatikan, setelah Tragedi Kanjuruhan, yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah mengubur ingatan masyarakat dengan menciptakan banyak hiburan, mulai dari menaikkan sepak bola dari U20, U21, U Balita, dan semacamnya. Ini semata untuk membuat kita terlena akan kejahatan negara.”
Selain membuat kita terlena dengan berbagai hiburan, cara lain untuk membuat kita lupa akan kejahatan negara beserta aparatusnya di Kanjuruhan, adalah dengan menghilangkan situs kekerasan. Kita dapat melihatnya dalam ketergesaan pemerintah merenovasi Stadion Kanjuruhan.
“Hal serupa terjadi ketika pemerintahan Jokowi meminta maaf dan membongkar salah 1 rumah panggung yang digunakan untuk melakukan interogasi dan penyiksaan warga sipil di Aceh, lalu dialih fungsikan menjadi masjid. Untuk apa itu? Jadi, jika di sana ada pembantaian, cara untuk melupakan ingatan warga dan korban adalah dibongkar dan diganti bangunannya. Kita harus waspada jika hal ini terjadi pada Kanjuruhan”, lanjut Pak Hatib. Saat situs kekerasan dihilangkan, ingatan masyarakat tentangnya bisa perlahan sirna.
Akankah usut tuntas hanya menjadi janji di atas ambang kerinduan?
Pak Nuri, salah satu keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang menjadi narasumber, menceritakan kejadian selepas tragedi. Katanya, pemerintah memberi berbagai macam tawaran kepada keluarga korban agar mengikhlaskan jasad anaknya yang terbunuh karena gas air mata. Tawaran-tawaran itu berupa rekrutmen untuk menjadi Polisi/TNI/PNS, mendapatkan modal usaha, mempermudah proses membuat SIM, dan semacamnya.
Menanggapi kejadian itu, Pak Hatib menegaskan bahwa Indonesia makin lama makin mirip Israel.
“Yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina setelah mereka dibom, dibunuh, dan dikasih gas air mata adalah mempercepat berita tentangnya. Jika tragedinya telah terjadi selama sehari, maka berita tentangnya ditutup dan diganti berita-berita lain, seperti ekspor-impor, inflasi, dan sebagainya. Jadi warga sipil Palestina itu tidak mempunyai hak untuk berduka,” kata Pak Hatib.
“Nah, korban Tragedi Kanjuruhan saat ini juga demikian. Hak dukanya diambil dengan cara diberi hal-hal yang lain seperti modal usaha, direkrut menjadi PNS, dan sebagainya. Padahal, hak untuk berduka itu sama seperti hak untuk makan, hak untuk berpakaian, bahkan hak untuk hidup. Kita dapat lihat bahwa di Indonesia, hak asasi keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, yakni hak untuk berduka telah direnggut oleh pemerintah,” tegasnya.
Meski hak dukanya dicabut, keluarga korban tidak gentar dan terus menuntut keadilan bagi anaknya. Barangkali, salah satu puisi di pameran 1 tahun Tragedi Kanjuruhan bisa mewakili. Puisi ini karya Olivia. Bunyinya: “Akankah usut tuntas hanya menjadi janji di atas ambang kerinduan? Nyawa-nyawa pencari keadilan masih berdiri tegak, meski penegakkan hukum di negeri ini masih membengkak”.
Bagaimana usut tuntas yang seharusnya?
Sudah berjalan 1 tahun, upaya menyelesaikan proses hukum Tragedi Kanjuruhan masih mengalami dilema. Siapa yang salah? Suporter yang terlebih dulu turun ke lapangan atau aparat yang menembakkan gas air mata? Inilah dilema yang melekat pada benak banyak orang. Namun, banyak orang lalai, persoalan Kanjuruhan bagi kita semua yang mengamini bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan soal “siapa yang salah” tetapi “siapa yang berhak memutuskan”.
Bila memang menemukan fakta bahwa suporter yang turun ke lapangan adalah pihak yang paling bersalah, kita yang tak punya wewenang bisa apa? Saat diselidiki lebih lanjut dan bahkan saat suporter memang bersalah, apakah aparat sungguh pantas menembakkan gas air mata?
Mana yang lebih mungkin menyebabkan kematian? Gas air mata atau turun ke lapangan? Lalu, saat aparat penembak gas air mata menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, pertanyaannya masih sama, kita bisa apa?
Tidakkah kita sudah terlampau lelah dengan dengan dilema ini? Tidakkah kita merasa iba kepada mereka yang ditinggal mati oleh keluarganya? Sudah saatnya menyudahi semua ini!
Kita perlu bersama-sama mencatat bahwa adalah pengadilan yang berhak memutuskan. Ya, pengadilan yang paling berhak berbicara.
Namun, apa yang bisa kita harapkan dari pengadilan yang menyalahkan angin atas terbunuhnya ratusan nyawa? Tidak ada pengadilan sebrengsek ini dalam sejarah umat manusia.
Oleh karena itu, perjuangan usut tuntas yang sesungguhnya bukan lagi berdebat tentang siapa yang paling bersalah. Perjuangan sesungguhnya adalah mengawal Tragedi Kanjuruhan sampai pengadilan dibuka lagi, memastikan pengadilan tidak lagi mengkhianati kita, dan menghantam segala tipu daya yang menghalanginya.
Bersama merawat ingat dan menolak lupa!
Tidak tuntasnya kasus Kanjuruhan telah memberi pelajaran berharga bagi kita tentang pengkhianatan pemerintah. Khususnya, pada mandat untuk melindungi rakyat dan menciptakan keadilan sosial. Kemudian, dengan melihat tembakan gas air mata ke kampung di Dago Elos dan ke sekolah di Rempang, membuat kita sadar bahwa pemerintah dan aparatnya tidak belajar apa-apa dari Tragedi Kanjuruhan.
Setelah merenungkan hal ini, tidakkah kita merasa bahwa saling menyalahkan antar-golongan dan sesama masyarakat itu tidak diperlukan? Karena sesungguhnya, hari ini masyarakat Indonesia telah mengalami darurat solidaritas.
Kita, masyarakat sipil, perlu bersatu untuk saling menguatkan di tengah kekerasan aparat negara yang semakin tak terelakkan. Kekuatan terbesar yang kita miliki adalah suara dan ingatan. Jangan sampai kita membiarkan suara itu hilang karena tertelan politik pelupaan. Apabila jalan-jalan sudah dipenuhi foto kampanye, kita perlu lebih memenuhinya dengan foto korban. Jika pemerintah punya ratusan cara untuk membuat kita lupa, kita harus punya ribuan cara untuk terus mengingat.
Tentang tragedi ini, kita bisa saja tidak sepakat dengan Nelson Mandela yang mengatakan, “Kita memaafkan, tapi tidak melupakan,” sebab kita tidak akan memaafkan para pembunuh di Kanjuruhan sampai kasusnya tuntas dan menemui keadilan!
Penulis: Mohammad Rafi Azzamy
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Tragedi Kanjuruhan: Menormalisasi Hal yang Tidak Normal Adalah Mula Malapetaka dan seruan menarik di rubrik ESAI.