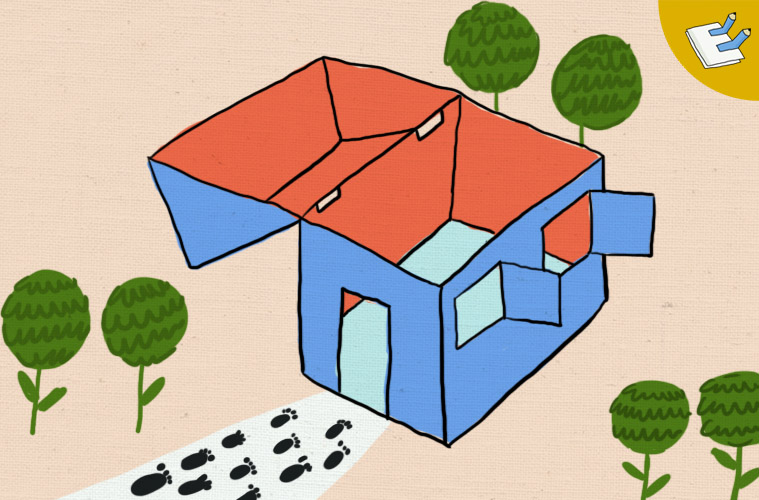Hari pertama Lebaran. Usai berkunjung ke rumah seorang sahabat, saya menaiki bus PPD ke arah Cililitan dari arah Pulo Gadung. Seperti orang yang sedang menuju masjid untuk tarawih, bus berjalan gontai. Sekira 30 tahun lalu itu, jalan tol di atas Jalan By Pass belum maujud. Di dekat jembatan Jatinegara, dua motor bersinggungan, Vespa dan Yamaha, lalu menggelinding ke bahu jalan. Dari dalam bus, saya melihat kedua pengendara itu berguling-guling di atas tanah.
Saya deg-degan menanti adegan selanjutnya. Bayangan saya, yang agak dikuasai film action, pastilah akan terjadi percekcokan bahkan mungkin perkelahian di antara mereka. Tiba-tiba, nyess …hati saya seperti diguyur air es di panas yang terik. Kedua orang itu saling mengampiri lalu bersalaman dan saling memegang bahu. Dari seberang jalan saya masih bisa melihat keduanya saling lempar senyum, dan mengguncang-guncangkan tangan dalam salam yang hangat.
Dalam hati saya berujar pelan: “Id mubarak ….”
Motor mereka tentu mengalami rusak-rusak kecil. Juga tubuh mereka, sangat mungkin ada luka-luka ringan. Tapi Lebaran, Idul Fitri ini, telah menjadi obat penyembuh paling manjur yang tidak dijual di apotek atau bengkel mana pun.
Peristiwa spontan itu melekat kuat dalam memori saya. Seperti prangko pos yang ditempel dengan lem Aibon. Gambar-gambarnya masih jelas sekali. Mungkin bagus juga kalau adegan itu direproduksi kru Mojok untuk Movi, dengan pemeran utama si kembar identik Prima Sulistya dan Agus Mulyadi.
Sekarang mari kita lihat tentang mewabahnya open house ketika Lebaran. Dari para elite kuasa di pusat hingga daerah, wabah menular itu merayap ke mana-mana, tanpa ada satu pun Puskesmas yang melakukan pemberantasan atau mengembangkan sistem peringatan dini.
Saya membandingkan dua hal itu seperti membandingkan FC Barcelona (peristiwa di atas) dengan Persikabo (open house). Sungguh sebuah usaha pembandingan yang bikin capek, dan berpotensi membatalkan puasa.
Peristiwa di atas, sumpah mampus, pasti tanpa rekayasa yang diurus oleh Event Organizer. Sementara sebuah open house, sering dicurigai pekat dan berlumur kepentingan. Coba kita lakukan penyidikan lebih jauh lagi, ya.
Di dalam open house, pada dasarnya, si elite: pertama, sedang mengakumulasikan kekuasaannya dengan menerima bejibunnya permintaan maaf dari rakyatnya. Rakyat yang harus datang dan minta maaf. Dan sang pemberi maaf, si penguasa itu, membuka senyum lebar-lebar sampai barisan giginya kering beberapa kali sambil menyodorkan tangannya, seolah memberi maaf dan ampun.
Dalam drama ini, yang salah adalah rakyat. Makanya saya gatel banget pengin ngusulin ke Fahri Hamzah agar memelopori pembentukan Hak Angket untuk memblejeti upacara-upacara open house kayak gini. Open house bisa jadi sarana pengukuhan anggapan bahwa penguasa tidak mungkin salah. The king can do no wrong! Ini menyayat-nyayat dan mendurjanakan akal sehat namanya.
Kedua, kenapa bukan si elite saja sih yang turba, blusukan, datang ke kampung-kampung minta maaf ke rakyatnya? Selain elitisme kekuasaan itu akan cair, dan insya Allah langsung longsor, saya jamin rakyat akan menyambut sambil sorak-sorak.
Dengan begitu, sebagai petugas partai, Ente nggak akan dianggap menyalahi mandat partai, bahkan akan semakin mendapat legitimasi sosial. Partai mana yang nggak ngeces ngiler sama dukungan populer, coba? Kecuali partai ganda campuran.
Ketiga, memberi maaf itu lebih mudah daripada meminta maaf. Ibaratnya, ya, Ente baru beli rokok sebungkus, terus tahu-tahu ada yang minta sebatang. Mudah, kan, untuk nyabut sebatang dan memberikannya? Bisa dilakukan sambil nerima tilpun atau balas pesan WA. Tapi coba Ente bayangin berada di posisi peminta. Pasti kagak mudah. Peminta bakal berada di antara sejumlah persoalan: mulut asem karena sudah pengin ngudud, mau beli rokok jauh atau pas lagi gak bawa duit. Mau minta ragu, bakal dikasih nggak ya? Jangan-jangan yang mau diminta bakal bilang: “Wah, rokok ana kebetulan tinggal sebatang, Gan.” Bisa malu, kan? Belum lagi, meminta itu sendiri kan bukan perkara gacel. Ada beban psikologis yang hanya bisa dilewati oleh pemudik nekad motor bebek, jalur Bekasi-Lamongan.
Jadi, menyadari diri salah, mengakuinya, dan dengan tulus minta maaf dan ampunan atas kesalahan itu, buat orang di posisi singgasana seperti Ente, mungkin bisa seperti akan melewati jembatan shirothul mustaqim. Semua bayangan kengerian ada di sana.
Pengakuan akan kesalahan, buat yang susah menerimanya, mungkin akan dianggap bisa menjatuhkan harga diri dan wibawa. Padahal dengan melakukannya, Ente akan segera merasa plong, dan Ente akan benar-benar dianggap sebagai manusia beneran, bukan jurig atau jejadian lainnya.
Sementara bertahan menganggap diri tidak pernah melakukan kesalahan, atau bahkan menutup-nutupi kesalahan, sungguh akan menimbulkan kesan bahwa kadar keimanan Ente berada di level terendah, dan harga diri ente cuma di kisaran harga seribu tiga! Percaya deh, ana bisa ngomong begini setelah melewati 18 kali sesi konsultasi dengan psikolog selama hampir 2 tahun!
Tidak mau mengakui kesalahan mungkin bisa merupakan keputusan rasional, demi tidak goyahnya wibawa dan kuasa tadi. Masuk akal. Tapi, di situlah juga soalnya. Karena mata dan telinga jiwa bisa melihat, mendengar, dan memahami apa yang otak Ente tidak bisa lakukan. Otak Ente membangun beton-beton tinggi yang mengangkangi diri Ente. Beton-beton tinggi penghalang itulah yang diterabas oleh mata jiwamu, dan lalu mengajakmu untuk melihat dengan hati nurani. Kecuali kalo Ente anggap diri seperti payo-payo (memeden/orang-orangan di sawah).
Mendiang Bang Ben mungkin bercanda ketika bilang “Lu bikin salah di Betawi, kok minta maapnye di kampung lu?” Tapi menurut saya, ada hikmah di situ yang mengajak kita agar fokus pada kesalahan yang kita buat dan meminta maaf di tempat di mana kita melakukannya, dan kepada orang yang mengalami akibatnya secara langsung. Jangan ada tabir manipulasi di sana, hatta antum bungkus dengan argumen demi kesatuan nasional sekalipun.
Lalu apa artinya Idul Fitri? Itu artinya bukan balikan ke si Fitri yang udah ente mantanin itu. Bukan. Secara bahasa memang berarti “kembali ke keadaan fitri”, keadaan tanpa salah dan dosa. Mirip orok yang baru lahir. Tapi buat kita-kita yang sudah bangkotan ini, kembali jadi orok ya jelas ajaib dan mungkar dari kenyataan. Kalo mungkarnya kelamaan, bisa kena sweefing Ente.
Kembali ke keadaan fitri adalah membebaskan diri dari peran-peran akal yang sering dikacaukan oleh muslihat penepuk dada itu. Kembali ke jiwa yang rendah hati, tapi juga merdeka.
Yang kita perlukan adalah open heart atau open soul. Bukan open house yang berorientasi matre itu.