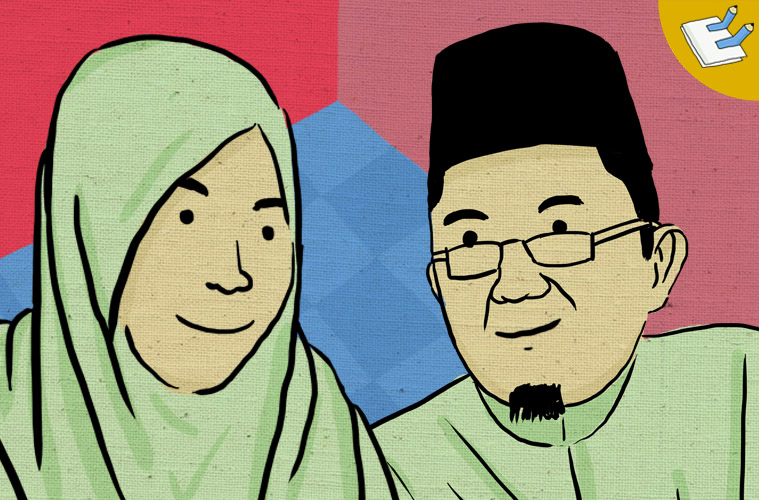Ada dua ceramah yang rutin kita dengar. Amanat pembina upacara dan khotbah keagamaan. Yang pertama hanya ada di sekolahan. Sedangkan yang kedua, yang saya ingat, terakhir kali jumatan saya malah nge-tweet, karena si khotib teriak-teriak: “Ini bukan masalah SARA, ini adalah perkataan Allah.”
Ngeri, memang. Parahnya lagi, budaya ceramah macam itu malah diturunkan ke anak-anak kecil. Tahu acara Dai Cilik? Nah, itu. Pernah saya tak sengaja menontonnya di televisi. Meniru ustadz-ustadz ‘senior’, salah seorang peserta menutup tiap pernyataan dengan: “Betul apa betul?”
Tapi di sini saya tidak ingin berkomentar lebih jauh soal ajang pencarian dai cilik. Urusan itu terlalu serius untuk sekadar ditanggapi tulisan iseng ini. Saya berharap ada psikolog anak atau pemerhati media yang berminat turun tangan.
Saya mau membicarakan mimbar. Mimbar yang bukan melulu ada di masjid atau lapangan upacara, melainkan juga tempat-tempat lain yang memungkinkan seseorang mengemukakan pendapat.
Persoalan mimbar ini jadi penting belakangan ini. Pasalnya, makin sering saja kita temui ujaran kebencian, sains oplosan, hingga spekulasi ajaib tak ternalar, yang muncul dari berbagai panggung. Mulai dari panggung Rizieq Shihab, Zakir Naik, hingga yang tengah hangat, Alfian Tanjung.
Lucunya, pada saat yang kurang lebih bersamaan, ada sejumlah orang yang menyayangkan Afi Nihaya Faradisa mengisi acara Talk Show Kebangsaan di UGM. Salah seorang yang statusnya saya temui di Facebook bilang, mengundang anak yang baru lulus SMA adalah aib buat para mahasiswa. Seharusnya justru mahasiswa yang mengisi acara di sekolah-sekolah.
Cara pikir macam ini membuktikan satu hal: masih ada orang yang tak tahu cara memahami mimbar. Memangnya hanya pakar (atau yang lebih tua) saja yang layak didengar? Jelas tidak. Sebab, selama ada kerangka yang jelas, siapa pun layak didengar—mau itu anak SMA, tukang ojek, penjual minyak wangi, atau fans Awkarin.
Tentu, penyelenggara bisa dikritik. Tapi itu baru bisa terjadi kalau memang pada acara diskusi, pembicara yang mereka pilih terbukti tidak sesuai. Misalnya, ketika jelas-jelas tajuk acaranya adalah menguak sisi buruk kapitalisme, tapi si pembicara malah mengajak audiens menyanyikan Mars Perindo.
Memilih pembicara memanglah harus teliti. Tak jauh berbeda dengan memilih karya seni untuk dipamerkan. Semuanya harus didahului dengan pertanyaan: apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikannya, seperti apa karakteristik audiensnya, dalam rangka apa itu disampaikan, dan seterusnya.
Memilih pembicara juga tidak harus terpaku dengan figur-figur yang disebut pakar. Dalam konteks diskusi, pandangan pakar hanyalah suatu elemen, yang bisa jadi tidak selalu dibutuhkan. Dan tak jarang, definisi “pakar” amat bisa diperdebatkan. Ingat, banyak orang yang menyebut Alfian Tanjung itu pakar komunisme.
Sementara dari sisi (calon) audiens, meledek pembicara yang bukan pakar tanpa sebelumnya mengetahui alasan dipilihnya si pembicara, menurut saya, sama ngaconya dengan mengejek lukisan impresionisme karena rupanya ‘jelek’.
Pikiran macam ini adalah pikiran yang hanya memiliki satu jenis standar, tapi menerapkannya buat segala hal. Berpikir “Gue juga bisa kalau begini doang,” tanpa sebelumnya mengetahui apa itu “begini” yang mereka sebut.
Di situ kemudian saya tak terlalu heran melihat banyak orang memuja Rizieq Shihab, Zakir Naik, dan Alfian Tanjung. Dengan embel-embel ustadz, (bekas) dosen, dokter, ulama, habib, dan lain-lainnya, mereka menjadi sosok yang kredibel.
Tak jadi soal bila Alfian Tanjung berkata bahwa Kolor Ijo adalah akal-akalan antek PKI untuk menghina umat Islam (hijau adalah warna yang identik dengan Islam). Itu sudah pasti benar, karena ia pakar.
Saya jadi penasaran. Andaikata Drs. Alfian Tanjung, M.Pd.yang mengisi Talk Show Kebangsaan di UGM, bukan Afi Nihaya Faradisa, akankah ada penolakan?
Ngomong-ngomong, Afi sebetulnya tidak butuh mimbar lho. Ia sudah punya. Ia membuktikan bahwa, ketika media sosial merajalela, mimbar sesungguhnya ada di smartphone kita. Kita bisa berpendapat kapan saja, di mana saja, dan lewat media sosial apa saja.
Bedanya, dengan menggunakan Facebook, Afi menjadi penanggungjawab tunggal terkait apa pun yang ia nyatakan dalam tulisannya. Tak ada penyuntingan, tak ada sangkut pautnya dengan Mark Zuckerberg. Dan feedback bisa datang dari kalangan yang sama sekali tak terduga; mulai yang hanya ingin menghujat, sampai yang iseng menaruh iklan peninggi badan.
Satu yang kemudian cukup menyita perhatian: ada yang merespons status Afi dengan cara mencari tahu otentisitas tulisannya.
Entah siapa yang memulai, setahu saya sih dari tulisan di Kompasiana, beredar kabar bahwa Afi melakukan tindak plagiarisme dalam statusnya yang berjudul “Belas Kasih dalam Agama Kita”. Status Afi, katanya, meniru status Mita Handayani.
Afi kemudian menyangkal tuduhan itu, dan berkata bahwa, dari 2012, dia sudah menulis. Tapi tulisan itu ada di akun lamanya yang sudah tidak aktif.
Saya tidak berminat membela siapa pun di sini. Tapi saya agak heran saja: Memangnya tulisan Afi selama ini dianggap istimewa karena otentisitas gagasannya?
Afi penting bukan karena pemikirannya otentik. Ia penting karena mampu menuangkan berbagai gagasan, semisal “agama itu terberi”, lewat bahasa yang sederhana bagi sasaran pembacanya.
Kesederhanaannya inilah yang membuat Afi bisa menjangkau khalayak seluas-luasnya. Afi bahkan tidak menggunakan secuil pun bahasa Inggris (ataupun Arab) dalam tulisan berjudul Warisan. Beda dengan Alfian Tanjung yang mengatakan kebangkitan PKI itu “the real is come back”.
Saat tulisan ini dibuat, akun Facebook Afi tidak bisa diakses lagi. Entah apa alasannya apa. Mungkin ia tengah tertekan isu plagiarisme, atau mungkin sesederhana tak tahan dengan perhatian khalayak yang begitu besar, yang mulai membebani kesehariannya.
Apapun yang terjadi, di tengah beredarnya berbagai konten mengerikan—semacam video bocah teriak bunuh Ahok, rasanya wajar bila banyak orang yang merayakan kehadiran Afi. Ia adalah bukti bahwa masih ada anak muda yang bisa melihat kondisi sekitarnya dengan jernih, dan menyampaikannya dengan bahasa yang jernih pula.