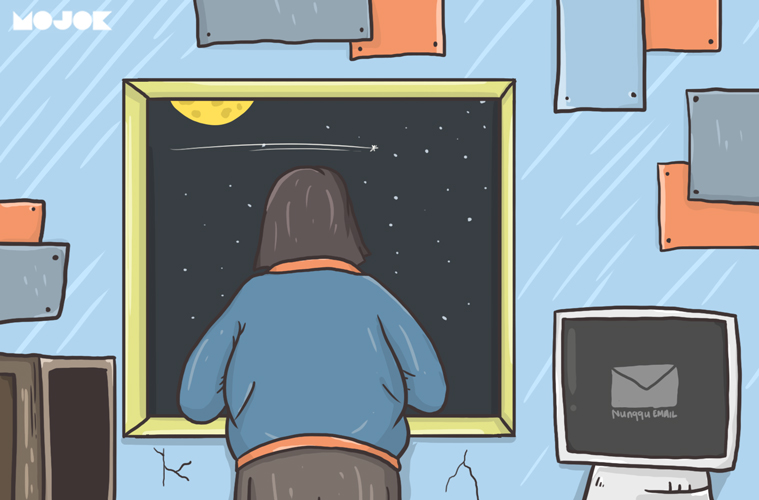Baca cerita sebelumnya di sini.
Kumohon jangan bertindak IMPULSIF! From: Andangsaki Kalasan <as.kalasan@gmail.com> Date: data system errors (configuration doesn’t show absolute time) To: Witfana Aulia <fanawit.aulia@gmail.com>
Fana,
Aku tergeragap. Napasku tersengal. Aku terbangun sebab sepotong mimpi yang meluncur bagai longsoran es dari tebing putih rapuh di kutub selatan. Keringat dingin mengucur dari pelipisku. Segera aku terbangun dan mengambil air minum dari lemari es.
Mimpi tadi begitu samar sekaligus begitu terang. Sebuah lorong rumah sakit, aroma pembersih lantai antiseptik, sekumpulan tenaga medis yang berjalan cepat, para penunggu pasien yang bermuka lelah, dan ibuku terbaring tak berdaya. Menjalani masa kritisnya, menghabiskan sisa waktunya.
Ini bukan mimpi yang terbentuk oleh sesuatu yang bersifat fantasi. Ini memoriku. Ingatan yang terpanggil ulang. Di alam bawah sadar, ia tertimbun berlapis-lapis kenangan baik maupun buruk. Ia muncul tiba-tiba seperti longsoran es. Kenapa ingatan ini baru sekarang muncul ke permukaan?
Karena kehadiranmu ke Jogja.
Karena rencanamu yang luar biasa impulsif, nekat, dan sembrono!
Kamu boleh balik marah padaku. Tunggu. Akan kujelaskan padamu.
Ingatan itu adalah hari di mana ibuku kalah. Virus mematikan memenangkan pertarungan setelah sekian tahun lamanya. Aku duduk di samping ranjang, memegang tangannya yang kering-kurus bagai ranting pohon. Sebentar kemudian, tangannya akan mendingin. Kehidupanku rasanya membeku saat itu. Dokter di sebelahku hanya menepuk bahu seorang bocah lelaki 12 tahun. Aku tidak bisa menangis.
Sudah berkali-kali kubayangkan momen itu akan datang: sebuah kemungkinan terburuk. Tapi, rasanya tetap luar biasa mengguncang. Aku menahan tangisku karena merasa asing dengan dunia sekitar: tabung oksigen, kabel-kabel, para medis berpakaian putih, dan mayat perempuan yang telah melahirkanku.
Bapakku belum tampak. Ia pamit padaku lima jam lalu bahwa ia perlu ke kantor untuk mengurusi satu-dua masalah. Tiga jam yang lalu aku sudah mengiriminya pesan bahwa ibu kembali kritis. Dokter dan perawat mencarinya. Dua jam lalu, aku terus mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Ia membiarkanku menghadapi momen terburuk ini sendirian. Kami hanya bertiga di rumah. Aku anak tunggal yang dididik mandiri sejak kecil. Namun, menghadapi kematian ibu seorang diri? Apakah aku setegar itu?
Bapak akhirnya datang dengan napas memburu. Ia masuk ke ruangan ICU dan mendapati tubuh ibu telah tertutup selimut rumah sakit sepenuhnya. Refleks aku menghambur padanya. Tangisku pecah.
Kami, dua lelaki, menangis bersamaan. Aku bisa merasakan dekapan bapakku yang erat sekaligus bergetar. Kami saling membasahi baju bagian pundak dengan air mata dan ingus. Kami membutuhkan sekian menit untuk mengakui kehilangan. Saat itu, samar-samar kulihat seorang gadis berdiri di ambang pintu. Ia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Lama, mematung di sana.
Aku terbangun dan siluet gadis itu tiba-tiba terasa sangat familiar.
Setelah diriku agak tenang karena ingatan tadi, kutelepon Bapak di Panama. Aku berbasa-basi sekenanya, lalu bertanya apakah ia masih ingat dengan seorang gadis yang datang bersamanya di hari kematian ibu. Ia keheranan, mengapa tiba-tiba aku bertanya demikian. Aku hanya bilang, penasaran. Jauh dari lubuk hatiku, rasa cemas itu perlahan muncul.
“Dia yang membuat Bapak terlambat datang saat ibumu sakaratul maut. Bapak tak sengaja menabraknya di depan Tugu. Di antara berpuluh-puluh turis yang asyik ambil foto selfie, gadis itu yang paling sembrono—tidak sadar kalau lampu merah dari utara telah berganti hijau. Untung ia tidak kenapa-napa. Hanya lecet-lecet sedikit. Tapi aku tetap perlu membawanya ke rumah sakit.”
Bapak lupa nama gadis itu. Katanya mirip nama artis zaman Bapak masih muda. “Kalau tidak salah… Nafa… Nafa Urbach?” Lalu kudengar suara tawa keras jauh di seberang benua sana. Bapak pasti sedang dalam pengaruh alkohol. Ia mabuk dan mulai melantur.
Aku buru-buru pamit dan hendak menutup telepon, saat Bapak tiba-tiba berkata, “Seingat Bapak dia dari Jakarta. Masih SMA saat itu. Mungkin minggat dari rumah. Sendirian main ke Jogja. Di Jakarta banyak, kan, anak broken home? Sepertinya dia merasa bersalah karena membuatku terlambat menghadiri kematian istriku sendiri. Dia memberiku sapu tangan berbordir kupu-kupu sebelum berpamitan pergi. Ada apa Kala? Kamu membencinya? Kamu mendadak perlu membencinya seperti semua orang di sekitarmu yang kamu benci? Ngomong-ngomong bagaimana kabar Raisa—?”
Kuputus sambungan telepon ketika mendengar nama mantan kekasihku disebut. Aku benci Bapak masih mengingatnya di saat aku bahkan lupa pernah ada seorang “Raisa” dalam hidupku.
Fana, apa yang kamu pikirkan saat sudah sampai di Jogja?
Kamu hendak mencari seorang anak bernama Andangsaki Kalasan berusia 12 tahun dan memberinya permen? Kamu hendak bilang padanya bahwa sepuluh tahun ke depan ia akan berteman dengan seorang gadis SMA dari masa itu karena tak sengaja bertemu di app lintas waktu? Bagaimana caramu meyakinkan Kala, yang masih seorang anak SD?
Aku, saat itu, bisa saja berpikir bahwa kamu adalah remaja sinting yang hendak berbuat jahat. Aku bisa saja melaporkanmu ke polisi seperti petunjuk teknis yang selalu diwanti-wanti orang tua sedunia: “Jika ada orang asing yang memberimu makanan, jangan diterima. Jika ada orang asing yang tampak ingin sekali mengajakmu mengobrol, waspadalah! Jika ada orang asing yang mencurigakan, segera lapor ke polisi!”
Apa kamu tidak memperhitungkan risiko di masa depan yang akan menimpa kita jika kamu secara impulsif datang menemuiku di masa lalu dan menceritakan banyak hal? Oke, aku juga melakukan itu padamu belakangan. Aku bercerita banyak tentang 2029 yang bisa membuatmu menjadi seorang peramal sakti di 2019. Tapi poinku adalah: posisi kita setara. Kita bisa mengobrolkan banyak hal dengan rasional.
Sementara itu, kamu akan menemuiku—Kala, bocah 12 tahun—dan membuat pertemuan yang justru berpotensi mengubah skenario. Kamu pasti paham maksudku. Kita semua hidup dalam satu skenario besar.
Sial! Kalimatku barusan membuatku tersadar: gara-gara kamu, aku jadi memikirkan kembali kuasa Tuhan!
Kamu tahu, saat aku membayangkan bertemu denganmu di apartemen berlantai 78, aku tidak akan mengatakan apa pun mengenai pertemanan kita, hubungan kita yang dipisah oleh ruang dan waktu. Aku hanya ingin menyapamu seperti orang asing yang sesungguhnya. Bahkan, bisa mengamatimu beraktivitas dari jarak jauh sudah membuatku bahagia!
Kenapa kamu musti ke Jogja, sih?
Apa yang kamu katakan pada orang tuamu karena tiba-tiba saja kamu berangkat ke Jogja? Seminggu pula! Berbohong ada study tour? Bagaimana kamu mengatur jadwal sekolah dan les-les-les-lesmu? Kenapa kamu senekat ini? Bagaimana jika kamu mengalami hal buruk dan bertemu orang yang mempunyai niatan buruk padamu? Bikin janji denganku bertemu setiap jam lima sore di Tugu? Bagaimana caraku—Kala-22-tahun—memberitahu Kala-12-tahun agar tiap sore ke Tugu?
Astaga, Fana, aku bukan seorang turis! Kala-12-tahun pasti tidak mungkin dan tidak mau main ke Tugu saat itu. Februari 2019, selama dua minggu, hidupku hanya berkutat di rumah, sekolah, rumah sakit. Dari buku, game, buku, game, sembari menunggui ibu.
Fakta bahwa kamu hampir saja mengalami kecelakaan fatal di Tugu hanya gara-gara SELFIE membuatku ingin sekali menjitakmu. Aku masih ingat ceritamu bahwa kamu paling susah membaca peta, kamu sering terjatuh dan menabrak benda-benda di sekitarmu, dan sekarang kamu di Jogja sendirian!
Pulanglah, orang tuamu pasti khawatir. Mungkin melebihi kekhawatiranku padamu.
Aku akan mencari cara bagaimana kita bisa bertemu dengan aman. Satu-satunya solusi yang bisa kupikirkan sekarang adalah menemui kumpulan mahasiswa geek di laboratorium IT. Aku perlu berdiskusi dengan mereka. Dan tolong jangan impulsif lagi.
Salam,
Kala
Delapan hari kemudian.
Fana, kamu di mana? Are you okay? From: Andangsaki Kalasan <as.kalasan@gmail.com> Date: data system errors (configuration doesn’t show absolute time) To: Witfana Aulia <fanawit.aulia@gmail.com>
Kamu tidak membalas surelku. Ini sudah sembilan hari lamanya sejak surel terakhirmu, delapan hari sejak surel terakhirku. Kamu di mana? Apakah kamu marah padaku? Apa yang telah terjadi?
Aku mencoba menelusuri identitasmu kembali di masaku, 2029. Seorang kawan geek mengingatkanku bahwa lima tahun yang lalu, sejak negara ini berganti sistem khilafah, berbondong-bondong orang berganti nama. Ratusan ribu orang mengurus pergantian nama ke Disdukcapil. Banyak motivasi yang menimbulkan tren seperti itu. Apakah kamu termasuk dari mereka yang berganti nama?
Karena aku semakin tak tenang, aku pun iseng menelusuri berita-berita dari arsip mesin pencari di 2019. Siapa tahu aku menemukan jejakmu. Aku berharap mendapati berita berjudul “Seorang Remaja SMA Ngotot Tak Mau Balik ke Jakarta karena Telah Bertekad menjadi Abdi Dalem Keraton” atau “Ditemukan: Seorang Turis Jatuh Cinta dengan Warga Lokal dan Memutuskan Hidup Selamanya di Jogja”.
Tidak ada berita-berita konyol seperti itu.
Aku justru menemukan berita bahwa sebuah penerbangan pendek Yogyakarta (Bandara Adi Sutjipto) – Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) mengalami kecelakaan. Pesawat mengalami kendala karena masuk ke kemelut cumulonimbus dan jatuh di perairan Laut Jawa. Semua penumpangnya tewas. Kabar buruk ini terarsip tidak jauh dari rentang waktu rencanamu di Jogja. Aku tidak berani membuka daftar nama para korban.
Aku berharap belum menemukanmu hingga sekarang sebab hal-hal norak semacam tren pergantian nama. Kita belum ngopi bersama, Witfana. Aku sudah janji akan mentraktirmu. Kalau perlu, aku akan mentraktirmu bergelas-gelas kopi. Atau semua minuman dan makanan yang ada dalam buku menu, silakan pesan semua.
Namun, kumohon jangan pergi dulu. Jangan lenyap.
Marahlah padaku, Fana. Aku akan menerimanya dengan senang hati.
Salam,
Kala
P.S: Aku merindukan kalimat-kalimat bawelmu.
Baca cerita berikutnya di sini.