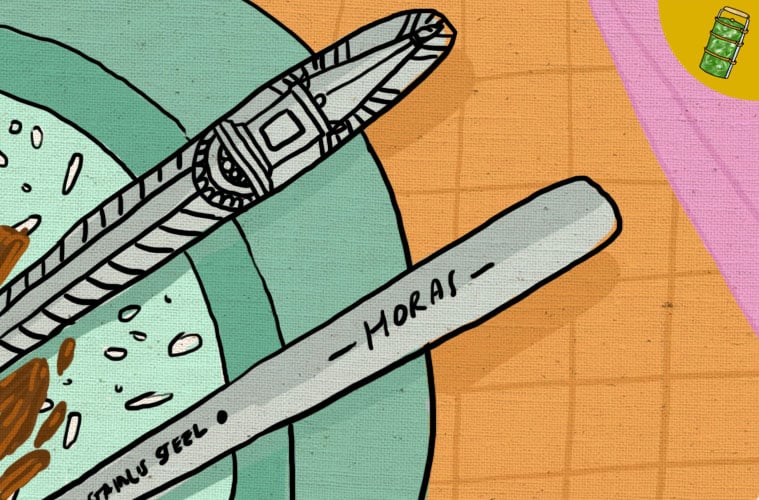Beberapa bulan belakangan saya hidup berpindah-pindah. Tuntutan pekerjaan membuat saya hanya bisa menetap di satu tempat tak lebih dari sepuluh hari dan harus pindah ke tempat lain setelah itu. Mulai dari Pulau Timor, Sumbawa, Sumba, hingga Yogyakarta. Sungguh mengasyikkan dan memberi banyak pelajaran. Berinteraksi dengan orang-orang baru, hidup dengan kultur yang berbeda-beda. Dan tentu saja, merasakan pengalaman kuliner khas di tempat-tempat yang saya sempat tinggali.
Tempat yang pertama saya tinggali adalah sebuah desa bernama Oeleon di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Awal-awal perjalanan terasa sangat melelahkan bagi pejalan amatir seperti saya. Belum lagi gegar budaya yang harus dihadapi. Di tengah kelelahan dan kebingungan tersebut, mama asuh saya, Mama Serfina, menyodorkan sepiring terong goreng dan sambal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sebagai penggila sambal, jiwa saya terpanggil untuk mencoba sambal ini.
Terong goreng yang masih panas tersebut langsung saya cocol ke dalam sambal. Tak sampai tiga puluh detik berselang, saya sudah panik mencari air minum ke sana kemari. Amagoiamang, tak pernah rasanya saya makan sambal sepedas dan segurih ini. Ditambah rasa getir yang dihasilkan jeruk nipis sebagai bahan utama sambal ini. Sungguh surga bagi para pecinta sambal-sambalan seperti saya.
Belakangan saya ketahui bahwa sambal tersebut bernama lu’at. Sambal ini berbahan utama cabai dan jeruk nipis, lazim dijumpai di seluruh penjuru Pulau Timor. Jika Anda seperti saya yang hobi uji nyali dengan makan sambal-sambal superpedas sampai mencret, Anda akan rugi dunia wal akhirat jika tidak pernah makan dengan sambal lu’at.
Sambal lu’at ini sendiri sukses membuat saya jatuh cinta dan kerasan di Pulau Timor. Ke mana pun saya melangkah selama di Pulau Timor, lu’at selalu menjadi hal pertama yang saya cari. Ketika saya berkesempatan untuk mengunjungi desa adat Boti, orang-orang Boti sampai geleng-geleng kepala melihat kegandrungan saya akan pedas dan gurihnya sambal lu’at.
Bahkan orang-orang Boti ini, dari tataran Raja, para tuan putri, hingga rakyatnya, terang-terangan menertawakan muka saya yang sudah memerah karena tak henti-hentinya menambahkan sambal lu’at ke dalam piring. Tak apalah, bagus juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan. Bagi mereka, saya akan dikenang sebagai perempuan aneh yang suaranya terlalu kencang dan makan sambal terlalu banyak.
Perjalanan pun terus berlanjut dan tempat demi tempat saya singgahi. Setelah lu’at, berbagai varian kuliner baru lainnya juga saya coba dan gandrungi satu demi satu. Namun, tanpa dinyana, saya tiba pada satu titik di mana saya ngidam masakan kampung saya sendiri alias masakan orang-orang Batak selatan; Angkola dan Mandailing.
Tentu saja mustahil menemukan makanan khas Batak selatan di gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Namun, rasa ini tidak tertahankan lagi. Akhirnya, di suatu pagi saya memutuskan untuk mencoba saja memasak salah satu masakan kampung saya yang paling khas, daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk adalah sayuran dengan bahan daun singkong yang ditumbuk lalu dimasak dengan santan. Sering kali ditambah dengan rimbang alias cepokak dan kincung a.k.a. kecombrang sebagai penambah aroma dan cita rasa gurih.
Resep sambal lu’at: Iris jeruk nipis, ulek dengan cabai rawit, aduk dengan irisan daun kemangidan daun siba, beri garam. Simpan racikan sambal itu di toples selama dua hari, setelah itu baru siap disantap.
Saya tidak bisa masak. Dan level ketidakbisaan saya dalam memasak ada pada tingkat D alias dreadful. Mengerikan. Proses memasak daun ubi tumbuk yang biasanya memakan waktu tidak sampai sejam saya eksekusi dalam waktu hampir lima jam. Namun, tak pernah rasanya saya menikmati proses memasak seperti memasak daun ubi tumbuk kemarin itu.
Ketika saya mulai menumbuk daun singkong dengan lesung kecil, memori masa kecil melintas di pikiran. Siluet tubuh bagian belakang mama saya yang terlihat berjibaku menumbuk daun ubi dengan lesung padi. Tangannya bergerak naik turun. Punggungnya berpeluh keringat. Tuk, tuk, tuk, suara lesung tersebut. Sesekali beliau menyenandungkan irama lagu favoritnya. Saya yang masih kecil dibiarkan bermain dan membaca di sampingnya. Tak dipaksakannya saya membantu pekerjaannya.
Perlahan air mata saya menetes. Ternyata saya tidak ngidam daun ubi tumbuk semata karena lapar. Atau karena bosan dengan makanan khas Timor yang menjadi konsumsi keseharian saya kala itu. Saya hanya rindu mama saya yang berjarak ribuan kilometer dan hanya sesekali bisa saya hubungi karena ketiadaan jaringan komunikasi yang layak di tempat saya tinggal.
Akhirnya, setelah lima jam penuh pergulatan dan kenangan, masakan daun ubi tumbuk saya siap untuk disajikan. Dan seperti sudah saya perkirakan sebelumnya, daun ubi tumbuk tersebut sama sekali tidak ada enak-enaknya. Terlihat dari ekspresi keluarga asuh saya yang ogah-ogahan ketika mencicipi daun ubi tumbuk tersebut.
Keluarga baru saya ini dengan baik hati tetap memuji masakan tersebut untuk menghargai kerja keras saya. Namun, selera tidak pernah bisa ditipu dan menipu. Orang Batak memiliki sebuah idiom, dai te, alias makanan yang memiliki rasa layaknya tahi. Bukan berarti orang Batak pemakan tahi sehingga tahu rasanya tahi bagaimana, ah masak ini harus dijelaskan sih. Ini cuma simbolisasi betapa menjijikkan dan tidak enaknya rasa sebuah makanan. Ya, seperti hasil masakan saya itu misalnya.
Namun, saya tetap bangga dengan daun ubi tumbuk saya, meski anjing kampung juga tidak sudi memakannya. Mengolah dan memakan daun ubi tersebut membuat rindu saya pada Mama sedikit terobati. Juga rindu saya pada kampung halaman. Bahwa sejauh mana pun saya pergi, pada akhirnya saya hanyalah perempuan dari kampung yang menyukai daun ubi tumbuk, meski makanan ini dicap kampungan dan dapat menyebabkan kolesterol.
Mungkin, pengalaman saya terkait beberapa ragam kuliner di atas menjadi bukti akan satu hal. Indra pengecap ternyata sama sensitifnya dengan indra lainnya. Bahwa rasa yang disampaikan lidah menjadi manifestasi dari rasa yang dirasakan oleh hati dan pikiran kita. Di mana rasa asin, manis, gurih, dan asam mewakili keinginan-keinginan dan ide kita sebagai manusia, beserta kenangan-kenangan yang terselip di dalamnya.
Sebagian orang akan berpendapat bahwa ini hanya dramatisasi dari efek lezatnya sebuah makanan. Toh itu hanya makanan. Dimakan jadi tahi juga. Mungkin saya yang terlalu baperan sampai makanan pun dibaperin.
Tak apa. Pada akhirnya pengalaman tersebut menjadikan saya semakin yakin atas apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini. Bahwa cinta memang datang lewat perut.
Dan bangsat, ternyata rindu juga bisa datang lewat perut.