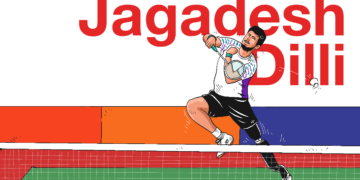Seusai menonton Mann (1999), tahulah saya bahwa Aamir Khan adalah aktor dengan kualitas akting yang baik. Di tahun 1990-an ia banyak membintangi drama-drama percintaan, tetapi orientasinya beralih ke film-film serius sejak tahun 2000-an, dan saat itu saya tahu, ia aktor yang baik, sutradara cerdas, sekaligus aktor-sutradara yang punya idealisme.
Saya tertarik menyoroti beberapa film yang dibintangi Aamir Khan dalam perspektif studi poskolonialisme, mazhab yang dianut cendekiawan kritis India Gayatri Chakravorty Spivak. Perempuan kelahiran Kolkata, India, ini turut mengembangkan wacana poskolonial bersama Homi K. Bhaba, cendekiawan Harvard keturunan India. Berangkat dari sini, kita bisa menikmati film-film yang dibintangi Aamir Khan dari perspektif lain.
Dalam pemikiran Spivak, kolonialisme Barat tidak luntur begitu saja. Sebab, struktur politik, budaya, ekonomi, dan sosial di bekas negara koloninya masih tetap berkiblat kepada penjajahnya. Struktur yang menindas ini akan membuat objek jajahan tidak dapat bersuara dan tidak bisa menyuarakan gagasannya secara leluasa. Di sinilah Spivak yang mengusung mazhab Subaltern Studies di India berusaha melakukan dekonstruksi agar pihak yang tertindas ini bisa bersuara.
Sebutan subaltern, menurut Spivak, lebih pas daripada istilah klasik proletar yang berlandaskan logika kapital. Jadi, sejarah proletar berkait dengan sejarah kapital, sementara sejarah subaltern adalah sejarah orang-orang yang terpinggirkan dari latar mana saja: perempuan Timur, komunitas adat, kelompok tarekat, petani, buruh, dan masyarakat tradisional.
Subaltern, kata penganut mazhab ini, merujuk pada orang-orang maupun kelompok yang terpotong dari garis mobilitas sosial kelompok elit. Mereka ini pula yang terdesak ke pinggir oleh garis-garis kultural dan pengetahuan yang memproduksi subjek kolonial. Mereka, kata Mas Ahmad Baso dalam Islam Pasca-kolonial, hanya diatasnamakan dan tidak pernah menyatakan sendiri nama dan suaranya.
Inilah yang coba diusung Aamir Khan: menyuarakan kaum yang selama ini (di)bungkam. Dia menyuarakan petani miskin yang terjerat upeti mencekik di tengah kolonialisme dalam Lagaan, menyuarakan penderita disleksia dalam Taare Zameen Par, menggemakan ironi petani fakir dalam Peepli [Live], dan terakhir, menyuarakan keperkasaan seorang pegulat perempuan di tengah kultur misoginis India melalui Dangal.
Dalam Lagaan (‘pajak tanah’), Aamir Khan mengajak kita bertamasya ke era tatkala kolonialisme Inggris mencengkeram India. Dia menghadirkan suasana sebuah desa miskin yang penduduknya kompak dan ceria di tengah himpitan upeti yang mencekik. Kebengisan kolonialisme tidak dia hadirkan di layar dengan brutal dan berdarah-darah, melainkan dengan cara yang khas: kemiskinan di sebuah desa yang kering di satu sisi, keglamoran para penjajah di sisi lain.
Dengan caranya, Aamir Khan menampilkan kaum subaltern, para petani, yang melakukan perlawanan bukan dengan senjata, melainkan dengan olahraga kriket. Kriket adalah olahraga yang menjadi alat tawar penduduk desa miskin—yang tak tahu bagaimana cara memainkannya—melawan penindasan Inggris. Jika para petani miskin ini kalah, pajak dinaikkan tiga kali lipat, apabila mereka menang, mereka bebas dari kewajiban membayar upeti selama tiga tahun.
Aamir Khan kembali bermanuver dengan mengangkat kisah para petani, kaum subaltern di India dan tentu saja di Indonesia, melalui Peepli [Live] (2010). Petani adalah kaum penyangga pangan negeri yang justru paling rentan dihajar para mafia. Petani adalah kaum (di)pinggir(k)an dengan beragam problemnya; bualan pemerintah, jeratan rentenir, mafia pupuk, sindikat yang menghancurkan harga panen, hingga penggusuran tanah semena-mena atas nama pembangunan.
Peepli [Live] yang diproduseri Aamir Khan bersama istrinya, Kiran Rao, secara satiris mengangkat kehidupan para petani miskin India. Natha, petani miskin, dan kawan-kawannya ditipu aparat desa yang membual bahwa negara bagian akan memberi tanah secara cuma-cuma bagi petani yang bunuh diri.
Ada juga petani kurus kering bernama Hori Mahato yang menjual tanahnya. Dia bukan menjual tanah dengan cara meteran, hektare, maupun satuan luas tertentu sebagaimana lazimnya, melainkan benar-benar menggali tanah sempit yang dia miliki, mewadahinya dalam karung, mengangkatnya ke atas sepeda, lalu dengan tubuh cekingnya mengendarai sepedanya. Ke mana? Menjual tanah!
Inilah gambaran kemiskinan dan ketidakberdayaan yang fatal. Kulit legam, tatapan nanar, tubuh kurus, dan nafas yang terengah saat mencangkul dan mengayuh sepeda adalah gambaran nestapa seorang petani yang ketika menggali tanah seolah sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Sebuah satire sarkastis yang diusung Aamir Khan sebagai produser dengan tetap mengandalkan ciri khasnya: komikal dan menonjok, sebagimana pula dalam 3 Idiots dan PK.
Film-film yang dibintangi, disutradarai, maupun digarap Aamir Khan memang tidak seartistik dan seanggun gaya produksi Sanjay Leela Banshali, tidak seglamor produksi Yash Raj Chopra, tidak semeriah film-film Karan Johar, juga tidak semewah garapan Rohit Shetty. Film-film Aamir Khan masih membumi dengan tetap menampilkan (dan bangga) dengan identitas keindiaannya seperti ciri khas film-film bikinan Ashutosh Gowariker.
Melalui beberapa film yang dia bintangi, dia sutradarai, dan juga dia produseri bersama istrinya, Kiran Rao, Aamir Khan melakukan (semacam) penyuaraan kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan, maupun tidak didengar jeritannya. Dia tidak melakukan, dalam istilah Homi Babha, mimikri, dengan meniru-niru gaya Hollywood dan kaum Barat dalam tampilan, plot, gaya, hingga latar film.
Dia menghindari apa yang disebut oleh Spivak sebagai The Big Other (‘yang lain yang besar’): yakni manakala Barat menampilkan diri sebagai objek hasrat ideal bagi pribumi terjajah. Dalam relasi ini, sang pribumi terjajah tidak pede dengan gambaran dirinya sendiri, tapi butuh gambaran orang lain (yaitu sang penjajah) untuk memberikan penilaian “modern”, “maju”, “progresif”, dan “kekinian”.
Dalam relasi ini, banyak film Bollywood akhirnya melangit dan sama sekali terasing dari kenyataan, sebab dunia yang diusung dalam filmnya sama sekali bukan Delhi dengan kesemrawutannya, Mumbai yang kosmopolit namun menyisakan kekumuhan di pinggirannya, maupun Agra yang eksotis. Yang kita temui malah film-film Bollywood berlatar New York, London, Amsterdam, hingga Zurich. Inilah yang coba Aamir Khan hindari.
Pada akhirnya, gaya kebarat-baratan dalam Kites (Hrithik Roshan), Roy (Arjun Rampal), Don dan Dilwale (Shah Rukh Khan) nyaris tidak kita temui dalam film yang digarap Aamir Khan satu dasawarsa terakhir. Kecuali Dhoom 3, Aamir Khan tetap bergerak dalam aras Hindustan beserta kehidupan kesehariannya. Amerika dan Hollywood yang dianggap sebagai rujukan sahih dalam banyak hal justru dia hindari. Pada titik ini, kita ingat gaya sutradara Abbas Kiarostami yang tetap bangga dengan corak sinematrografi tradisional Iran dan Akira Kurosawa yang mengusung sentuhan teatrikal Kabuki Jepang dalam berbagai karyanya.