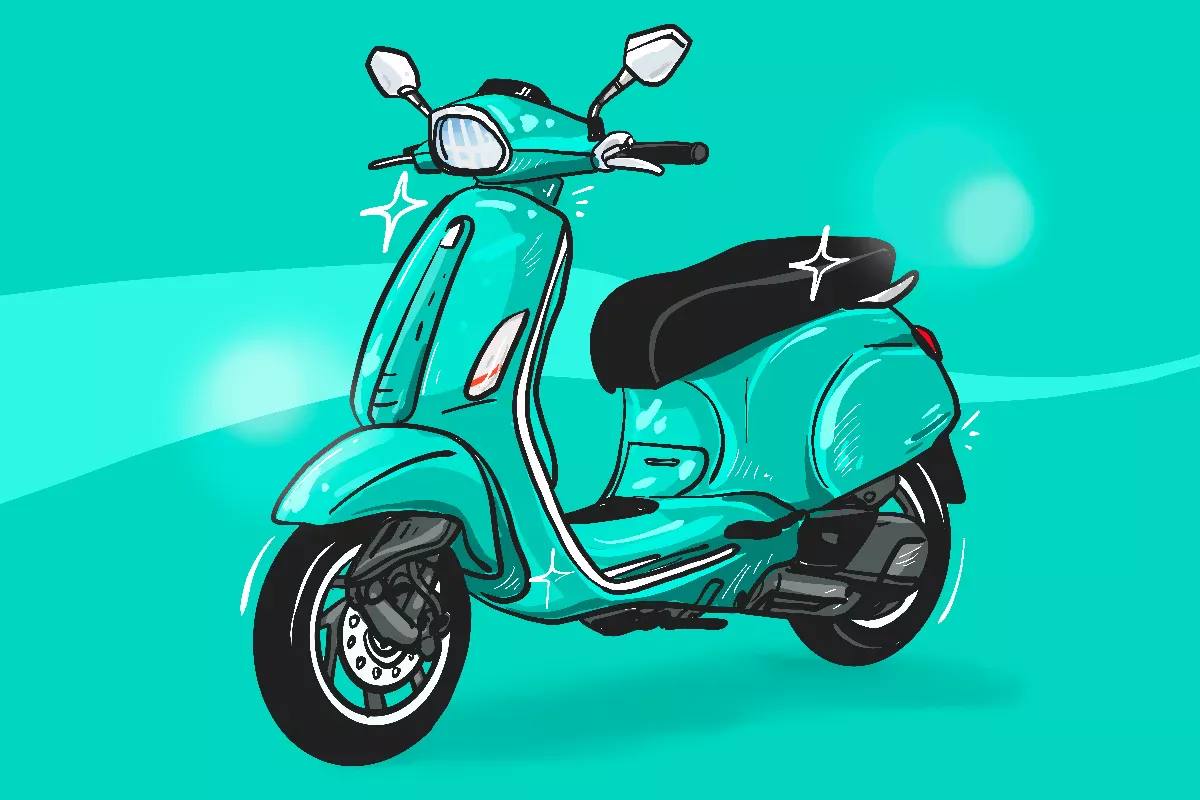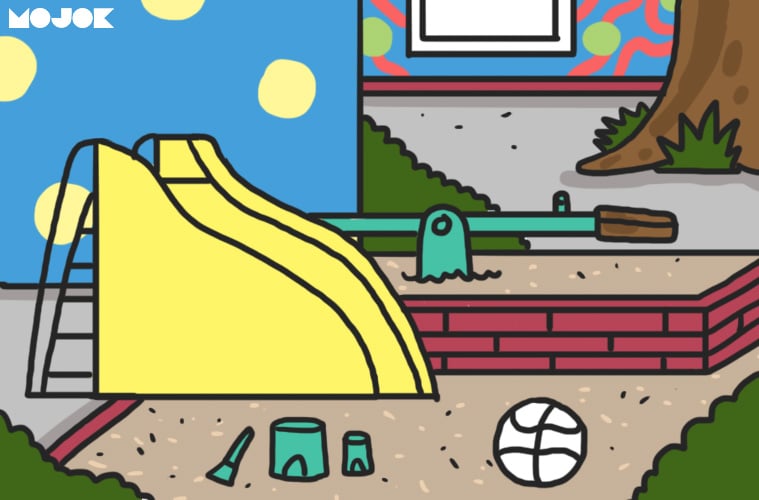Jogja selama ini dikenal sebagai kota pelajar yang murah, ramah, dan bersahaja. Julukan itu seolah diwariskan dari generasi ke generasi, diceritakan dari mulut ke mulut, dan diperkuat oleh pengalaman orang-orang yang pernah tinggal di sana bertahun-tahun lalu.
Bagi banyak orang termasuk saya, Jogja adalah simbol kota impian, tempat belajar, hidup sederhana, dan bertahan dengan biaya pas-pasan. Tapi, pengalaman singkat saya tinggal di sana justru membuat saya mempertanyakan kembali mitos “Jogja kota murah” yang selama ini dipercaya.
Perjalanan ini bermula ketika sepupu saya yang kuliah di Universitas Gadjah Mada akan melaksanakan wisuda. Saya diajak oleh bude untuk ikut ke Jogja. Selain ingin menghadiri momen wisuda, saya juga sangat antusias karena akhirnya bisa melihat langsung kampus yang dulu pernah menjadi impian saya.
Sekalian, tentu saja, saya ingin merasakan bagaimana rasanya tinggal meski hanya sebentar di kota yang sering disebut sebagai rumah kedua bagi mahasiswa dari berbagai daerah.
Kosan biasa aja harganya 800 ribu per bulan? 800 ribu?
Sesampainya di Jogja, saya menginap di kosan sepupu. Kosannya tergolong standar, seperti kos mahasiswa pada umumnya. Ukurannya sekitar 3×4 meter, cukup untuk satu orang tidur, belajar, dan menyimpan barang-barang seadanya. Tidak ada AC, tidak ada fasilitas mewah, dan suasananya pun sederhana.
Namun, keterkejutan saya datang saat mengetahui harga kos tersebut mencapai Rp800.000 per bulan. Bagi saya, ini bukan angka yang kecil. Di daerah asal saya, Lampung, dengan Rp600.000 per bulan, seseorang sudah bisa mendapatkan kosan dengan ukuran dan fasilitas yang relatif lebih baik. Dari sini, saya mulai merasa bahwa gambaran Jogja sebagai kota dengan biaya hunian murah tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang saya temui.
Ekspektasi saya kembali diuji ketika berbicara soal makanan. Selama ini, Jogja identik dengan makanan murah angkringan, nasi kucing, dan berbagai menu kaki lima yang sering disebut ramah kantong. Saya datang dengan bayangan bahwa makan Rp10.000–Rp15.000 per porsi masih sangat mungkin. Tapi, kenyataan berkata lain.
Saat saya membeli pecel lele di dekat kosan sepupu, harganya mencapai Rp25.000, itu pun tanpa minum. Untuk ukuran makanan kaki lima, harga tersebut terasa cukup mahal bagi saya. Mungkin ini bukan sesuatu yang luar biasa bagi warga lokal atau pendatang yang sudah lama tinggal, tetapi bagi saya yang datang dengan ekspektasi tertentu, angka itu cukup mengagetkan.
Saya mulai bertanya-tanya. Apakah mahalnya biaya hidup ini karena lokasi kosan yang berada di tengah kota? Bisa jadi. Kawasan sekitar kampus besar tentu memiliki permintaan tinggi, sehingga harga kos dan makanan ikut terkerek naik.
Apalagi Jogja merupakan kota yang sangat terkenal dan selalu ramai. Saat saya datang, kebetulan sedang musim wisuda dan liburan. Jalanan padat, penginapan penuh, dan tempat makan ramai oleh pendatang, wisatawan, serta keluarga wisudawan. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga seolah menjadi hal yang “wajar”, meskipun tetap memberatkan.
BACA JUGA: Jogja Memang Benar-benar Istimewa, Tanpa Syarat, Tanpa Ketentuan
UMR Jogja ternyata… segitu?
Kebingungan saya semakin memuncak ketika saya sempat menanyakan besaran UMR Jogja. Jawabannya membuat saya benar-benar terdiam. UMR Jogja hanya berada di kisaran Rp2 jutaan. Mendengar angka itu, saya langsung terbelalak.
Dengan harga kos Rp800.000, makan yang tidak lagi murah, dan kebutuhan harian lainnya, rasanya sangat tidak mungkin hidup dengan layak jika hanya mengandalkan upah minimum. Di sini, saya mulai melihat adanya ketimpangan yang cukup serius antara pendapatan dan biaya hidup.
Jogja mungkin murah bagi mereka yang datang dengan sokongan keluarga, beasiswa, atau penghasilan di atas rata-rata, tetapi bagi pekerja dengan upah minimum, hidup di kota ini tampaknya penuh kompromi.
Pengalaman saya semakin diperkuat saat berjalan-jalan ke Malioboro. Kawasan yang selama ini menjadi ikon wisata Jogja itu ternyata menyimpan cerita lain. Di sana, saya merasa seperti “diketok harga” secara tidak masuk akal. Harga barang dan makanan terasa jauh lebih mahal dibandingkan tempat lain. Padahal, saya sudah mencoba menggunakan bahasa Jawa saat berinteraksi.
Mungkin karena logat saya tidak terlalu seJogja itu, saya tetap dianggap pendatang. Dari sini saya belajar bahwa di kawasan wisata, harga sering kali tidak lagi berbicara soal nilai barang, melainkan tentang siapa pembelinya.
BACA JUGA: Jogja Itu Nggak Istimewa dan Tidak Lagi Sama karena yang Istimewa Itu Orang-orangnya
Mungkin sudah berubah, mungkin?
Pengalaman-pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa Jogja hari ini mungkin sudah sangat berbeda dengan Jogja yang diceritakan orang-orang dahulu. Kota ini tumbuh, berkembang, dan menjadi magnet bagi mahasiswa, wisatawan, serta pendatang dari berbagai daerah. Pertumbuhan itu membawa dampak ekonomi, tetapi juga menghadirkan persoalan baru, biaya hidup yang semakin sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah.
Saya rasa pengalaman singkat saya di Jogja menunjukkan bahwa label “kota murah” tidak lagi bisa digunakan secara umum. Jogja mungkin masih ramah secara budaya dan hangat secara sosial, tetapi dari sisi ekonomi, kota ini menuntut lebih dari sekadar mimpi dan harapan. Bagi pendatang seperti saya, realitas Jogja terasa jauh berbeda dari cerita manis yang selama ini digembar-gemborkan.
Penulis: Intan Permata Putri
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jogja Itu Aslinya Murah, tapi Jadi Mahal Gara-gara (Gaya Hidup) Pendatang
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.