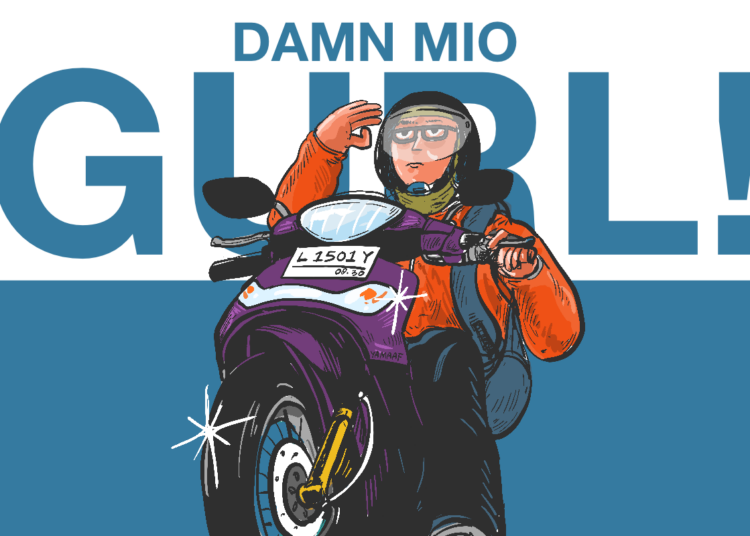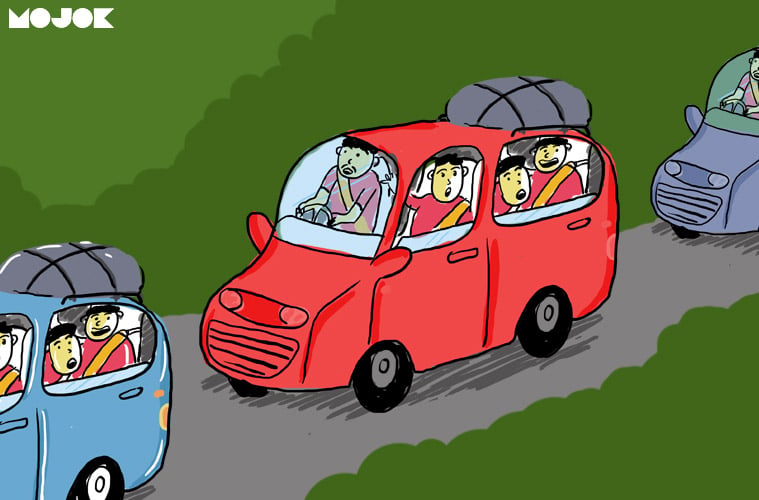Dalam salah satu sajaknya, Sapardi Djoko Damono pernah menulis bahwa tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Sebagai mahasiswa Sastra Indonesia, saya tentu mengakui bahwa penggalan puisi tersebut sangatlah puitis. Namun, dalam konteks kehidupan sehari-hari, saya rasa Pak Sapardi sedikit keliru. Pasalnya, bagi saya, pernyataan yang lebih tepat adalah “Tak ada yang lebih tabah dari pejuang KRL”.
Teruntuk kalian yang menetap di wilayah Jabodetabek, kalian pasti tahu bahwa banyak sekali orang yang mengandalkan Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai moda transportasi sehari-hari. Harap diingat bahwa tak semua orang memiliki kendaraan pribadi, sehingga satu-satunya solusi jika hendak bepergian adalah dengan memanfaatkan kendaraan umum. Kebetulan, saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terhitung ke dalam golongan tersebut.
Tabah menjadikannya sebagai rutinitas
Jika hanya dilakukan sekali-dua kali, menaiki kendaraan umum di Jabodetabek mungkin akan dipandang sebagai bentuk refreshing. Mungkin ada saja orang di luar sana yang bosan melalui hari-harinya dengan mengendarai mobil atau motor pribadi, lantas bermaksud untuk menggunakan KRL, MRT, Transjakarta, atau transportasi umum apa pun saat hendak menuju suatu tempat. Bagi kelompok tersebut, tampaknya mereka tidak akan begitu relate dengan isi artikel ini.
Ketika membuat tulisan ini, perspektif yang saya gunakan adalah orang-orang yang menjadikan kendaraan umum sebagai bagian dari rutinitas mereka. Orang-orang yang setiap harinya berangkat ke sekolah, ke kantor, atau ke mana pun dengan menaiki KRL dan pulang dengan menggunakan moda yang sama pula. Jujur saja, bagi saya, mereka yang kerap disebut sebagai “pejuang KRL” tersebut adalah definisi paling valid dari ketabahan; contoh paling konkret dari kesabaran.
Meskipun saya juga merupakan seorang pejuang KRL, tetapi boleh dibilang saya masih newbie dalam menyandang julukan tersebut. Saya baru menyematnya dalam waktu kurang lebih setahun, tepatnya sejak saya pertama kali menetap di Depok. Dalam periode tersebut, saya selalu memanfaatkan KRL setiap kali akan berangkat ke lokasi magang, ke kantor di mana saya bekerja paruh waktu, ataupun ketika saya sekadar ingin berjalan-jalan bersama teman-teman.
Oleh karena itu, saya telah melihat banyak sekali “kisah” di dalam KRL, kisah dari mereka yang menjadikan KRL sebagai bagian dari rutinitas. Mereka yang rela berangkat ketika subuh baru menetas demi tidak berdesak-desakan di dalam kereta. Mereka yang harus pulang lebih awal ataupun lebih larut agar tidak harus “berjumpa” dengan jam-jam sibuk kereta di sore hari.
Sejujurnya, saya selalu kagum oleh mereka yang sanggup menjadikan itu sebagai “makanan” sehari-hari. Saya yang belum sampai setahun saja sudah dibuat lelah dan terkadang tak tahan akan semua itu. Lantas, bagaimana dengan mereka yang mungkin telah melaluinya dari waktu ke waktu?
Naik KRL berarti harus tabah dan sabar
Menurut saya, jika dibandingkan dengan teman-temannya sesama transportasi umum, KRL memang transportasi yang paling menuntut ketabahan. Jika ketabahan yang dimaksud dalam sajak Sapardi adalah tabah menunggu sesuatu yang tidak ada (hujan di bulan Juni), tabah dalam menaiki KRL maksudnya adalah tabah dalam menunggu datangnya kereta yang terkadang cepat terkadang (agak) lama.
Tak berhenti sampai di situ, naik KRL berarti harus tabah pula berdesak-desakan dengan penumpang lain di jam sibuk. Kita juga harus berpegal ria karena tak mendapatkan tempat duduk meski stasiun yang dituju berjarak sangat jauh seperti hubungan kamu dengan gebetan.
Sementara apabila dibandingkan dengan transportasi umum lain, misalnya, Transjakarta, situasinya memang terkadang cukup serupa. Akan tetapi, entah mengapa bagi saya keadaan di Transjakarta tidak se-“menyiksa” seperti di dalam KRL. Saya tidak tahu penyebab pastinya, tetapi kalau boleh menduga-duga, mungkin ada saja faktor psikologis yang berperan.
Sebagai contoh, ketika menaiki Transjakarta, penumpang bisa melakukannya sembari menikmati pemandangan jalanan kota. Bagi indra penglihatan, hal ini cukup menghibur dan sejenak dapat membuat saya melupakan fakta bahwa saya tengah berada dalam situasi terhimpit penumpang lainnya.
Nah, di dalam KRL, kemampuan saya untuk dapat menikmati panorama kota jadi lebih terbatas karena kecepatan kereta yang cukup menyulitkan pandangan saya untuk “melihat-lihat”. Ngerti, kan, maksud saya? Pokoknya andai saya memilliki refleks super cepat seperti The Flash, saya pasti tidak akan membahas permasalahan yang satu ini.
Kemudian, kalau berbicara mengenai JakLingko, saya telah cukup banyak berbicara mengenai transportasi tersebut dalam artikel yang pernah saya tuliskan di sini. Akan tetapi secara keseluruhan, saya tetap menyimpulkan bahwa level ketabahan pejuang KRL masih lebih tinggi daripada penumpang JakLingko.
Tempat berkumpulnya orang tabah
Setelah menjadi warga Jabodetabek selama kurang lebih satu tahun, saya dapat mengatakan bahwa Jakarta (dan wilayah sekitarnya) adalah tempat berkumpulnya orang-orang tabah. Kalau boleh meminjam ungkapan seorang teman saya, maka Jakarta adalah tempat bagi mereka yang menjunjung tinggi istilah “perintis, bukan pewaris”.
Para pejuang KRL adalah mereka yang saya maksud. Demi menciptakan kehidupan yang lebih baik, atau setidaknya, dapat terus bekerja, mencari uang, dan “bertahan hidup”, mereka harus berdesak-desakan di dalam sebuah kendaraan bermesin yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka sehari-hari.
Memang hal semacam ini tidak akan terasa relate bagi semua orang. Ini adalah semacam curhatan berisi uneg-uneg yang baru bisa dipahami sepenuhnya oleh mereka yang benar-benar merasakannya. Ya, siapa lagi kalau bukan para pejuang KRL, sang orang-orang tabah di tengah kerasnya kehidupan ibu kota.
Jadi, mana yang lebih tabah? Hujan bulan Juni atau para pejuang KRL?
Penulis: Bintang Ramadhana Andyanto
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Merasakan Tua di Jalan: Naik KRL Transit Manggarai Harus Bayar Pakai Mental Health.